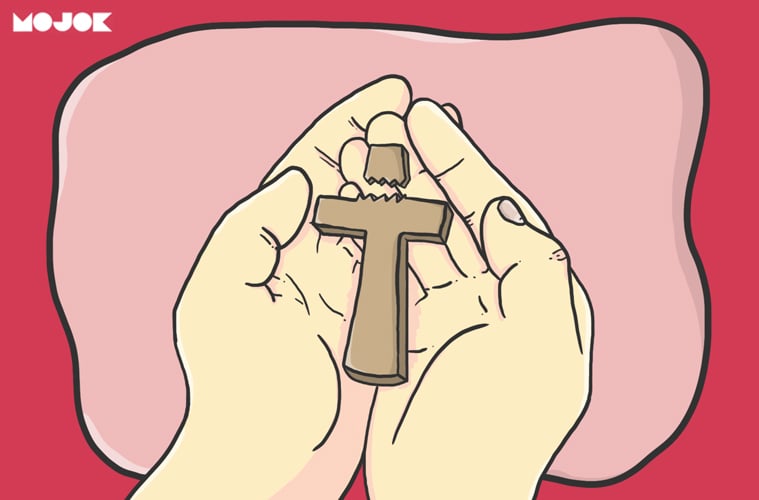MOJOK.CO – Menghakimi masyarakat dalam kasus pemotongan nisan salib dengan local wisdom-nya sama seperti pandangan kolonial klasik memandang dunia yang ditaklukkannya.
Selama kuliah di filsafat dulu, saya mengenal bahwa kebenaran ternyata mempunyai banyak jenis. Tidak bersifat tunggal. Kebenaran lebih dari sekedar benar mana: bumi itu bulat atau bumi itu berbentuk donat.
Dalam kehidupan sebenarnya, ternyata ada beberapa jenis kebenaran. Bahkan, ada kebenaran sebuah preposisi yang jika disebutkan kebalikannya, tetap benar juga. Contohnya, jika saya mengucapkan hidup itu singkat. Jika disebutkan kebalikannya, hidup itu lama, maka itu juga benar.
Masalahnya, hal ini yang terjadi dengan kontroversi pemakaman Albertus Selamet Sugihardi di TPU Purbayan, Kotagede, Jogja. Gara-garanya sederhana, nisan makam almarhum yang berbentuk salib harus dipotong oleh warga.
Tema, yang sebenarnya sudah ditulis dan diulas oleh esais pilih tanding Iqbal Aji Daryono. Sampai jadi balas-membalas yang panas dengan Arman Dhani. Yang bangsatnya, membuat saya bingung harus masuk darimana. Lha yang menarik-menarik sudah dihabiskan oleh argumentasi dua orang itu.
Tapi, baiklah. Saya numpang argumentasinya Iqbal dulu. Pak Selamet meninggal dan dimakamkan di makam kampungnya di Purbayan. Pak Selamet beragama Nasrani, dan keluarga sempat hendak memakamkannya dengan simbol Nasrani pula. Tapi, mayoritas penduduk kampung di sana adalah muslim. Dan tidak setuju dengan adanya simbol Nasrani pada makam itu.
Maka, nisan kayu yang berbentuk salib dipotong bagian atasnya, dan hanya menjadi seperti huruf T. Kemudian, si keluarga hendak melakukan doa perkabungan di rumahnya, masyarakat menolaknya. Akhirnya, doa dipanjatkan di Gereja Santo Paulus Pringgolayan.
Lalu, entah bagaimana, kasus ini menjadi viral. Netizen mengecam. Intoleransi terjadi. Kemudian, muncul pula surat pernyataan yang ditandatangani tujuh orang. Termasuk Maria Sutris Winarni, istri pak Selamet. Isinya berupa pernyataan bahwa Maria tak mempermasalahkan adanya pemotongan nisan berbentuk salib tersebut. Bahwa hal itu dilakukan demi kebaikan bersama, dan keluarga tidak ada masalah sama sekali.
Apakah kasusnya selesai? Bagi Iqbal sih iya.
Dia punya landasan kuat untuk itu. Dia melakukan analisis bahwa Kotagede sebenarnya sama dengan komunitas adat. Sama seperti dengan dominannya kaum Nasrani di Pulau Mentawai, atau umat Hindu di Bali.
Sehingga, sah-sah saja jika ada konsensus dalam masyarakat tersebut, termasuk dalam pemakaman. Apalagi, keluarga pak Selamet pun tidak mempermasalahkan. Dibuktikan dengan surat pernyataan tersebut. Baginya, netizen yang mempermasalahkan tak lebih dari pluralis fundamentalis SJW yang tak paham konteks lokalitas.
Argumen ini benar. Dalam etika, argumentasi ini mirip dengan etika utilitarianisme. Aliran yang diperkenalkan oleh filsuf jenius eksentrik Jeremy Bentham ini berprinsip bahwa “kebahagiaan itu bisa dikuantifikasi”. Karena kebahagiaan ala Deontologis Immanuel Kant itu subjektif dan sulit diukur. Bentham memperkenalkan apa yang namanya “kalkulus kebahagiaan”.
Kebahagiaan adalah kebaikan komunal untuk jumlah yang lebih besar. Hitung sejauh mana satu keputusan itu mendatangkan kebaikan terbesar untuk lebih banyak orang. Maka keputusan warga Purbayan sangat bisa dipahami.
Lagipula, menghakimi sebuah masyarakat adat dengan local wisdom-nya sama seperti pandangan kolonial klasik memandang dunia yang ditaklukkannya. Barbar, tidak maju, dan sebaiknya diarahkan ke yang benar. Sama seperti Inggris, Prancis, Belanda melihat negara-negara dunia ketiga.
Namun, masalahnya, kebenaran dalam kehidupan tidak bekerja seperti itu. Ada satu hal yang bisa sekaligus benar dan salah. Termasuk halnya kasus pemakaman Pak Selamet ini.
Pertama adalah pengabaian terhadap perasaan keluarga Pak Selamet. Bayangkan Anda menjadi keluarga Pak Selamet. Menjadi kelompok minoritas dari masyarakat. Di mana Anda tak punya rumah lagi selain di sana. Tak punya pilihan untuk berganti lingkungan.
Jika lingkungan meminta Anda untuk menghilangkan simbol keagamaan Anda, dan kemudian menyodori surat pernyataan untuk ditandatangani, apakah Anda punya pilihan lain? Adakah pilihan lain untuk Maria Sutris? Menolak semua itu? Yang benar saja.
Siapa pun akan realistis untuk menerima. Menolak berarti sama dengan menyatakan perang dengan lingkungan. Setidaknya, temuan dari Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutusan Ciptaan (KKPKC), komisi gabungan dari Kevikepan Jogjakarta dan Keuskupan Semarang menunjukkan adanya intimidasi dari sekelompok pendatang dengan dukungan dari luar terhadap keluarga Selamet.
Jelas, Maria dan keluarganya tak mempunyai pilihan lain untuk sukarela bertanda tangan. Mereka tentu lebih memilih untuk harmoni dengan lingkungan.
Yang kedua, peristiwa ini memberikan pesan yang buruk. Yakni, tidak ada perlindungan untuk minoritas. Sesuatu yang kini makin langka di Indonesia. Memang benar apa yang dikatakan Iqbal. Banyak dari netizen yang mengecam itu berlebihan. Argumentasi yang dibangun pun mirip-mirip fundamentalis. Tapi, pesan yang mereka terima benar juga. Yakni, tidak ada perlindungan untuk minoritas.
Situasi ini menimbulkan dilema yang menjengkelkan. Mengecam keputusan masyarakat Purbayan itu terasa seperti kolonial, namun membenarkan keputusan itu mengirim pesan buruk: pemakluman tirani mayoritas ke minoritas.
Beberapa saat usai polemik pemotongan nisan di Kotagede, Jogja ini, seorang kawan beragama Nasrani menulis di statusnya seperti ini:
“Ya ndak papa, ndak boleh pasang salib di makam, makam Yesus mula-mula juga nggak pake simbol salib. Simbol itu untuk yang hidup, mereka yang butuh yang meninggal lebih butuh belas kasihan Tuhan. Bukan belas kasihan manusia lagi.
Ya ndak papa, ndak boleh doa-doa di rumah. Kalau kemudian ada yang terganggu, tahu diri saja, doanya dalam hati. Bukankah akan lebih khusyuk? Suara hatimu yang akan didengar Tuhan. Cukup kau dan Tuhanmu yang tahu. Kalau kau peduli dan mendoakan benar-benar agar yang meninggal dimaafkan Tuhan, dan ada yang ditinggal benar-benar dimaafkan tetangga oleh jerit suara pilu dukamu.
Kalau doamu dianggap mengganggu, berarti memang ada yang terganggu. Sebagai minoritas, ya terima sajalah. Kau ini bisa apa.”
Begitu membaca itu saya jadi ingin berbalik bertanya ke sahabat-sahabat yang lain. Sebagai mayoritas, ya kita sih terima-terima saja. Justru kita yang malah nggak bisa apa-apa. Yang minoritas udah mencoba mengalah, masa yang mayoritas masih tetap tidak tergugah?