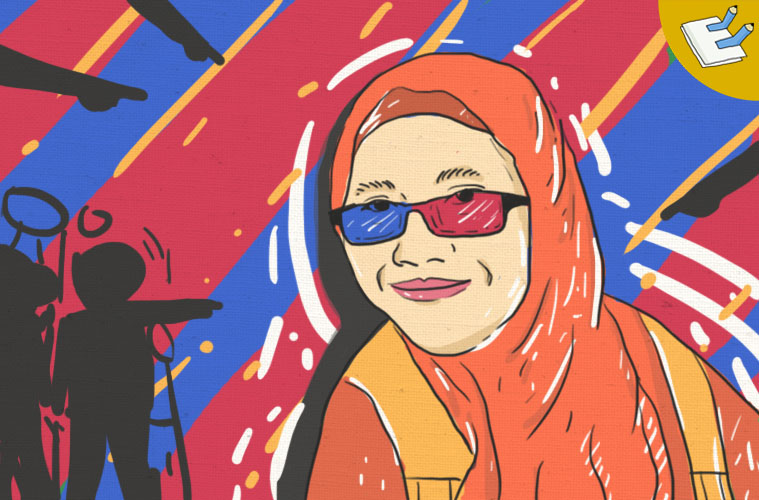“Bagaimana mungkin laki-laki dan perempuan bisa setara nilainya jika para perempuan masih menganggap bahwa apa yang biasa dikerjakan oleh para laki-laki dianggap lebih tinggi daripada apa yang biasa perempuan lakukan?”
Pertanyaan saya ini muncul dalam sebuah kelas.
Dosen saya sedikit terkejut saat mendengarnya. Mimik wajahnya berubah. Jawaban muncul, tapi saya tidak menangkap apa yang dimaksud, lebih ke berputar-putar ke arah nggak jelas. Baru pada kalimat terakhir saya menangkap apa jawabannya.
Jawaban yang kurang lebih sama seperti pelajaran dari cerita kawan saya, seorang laki-laki jomblo jelang 30 tahun saat minta doa kepada kiainya. Kurang lebih begini dialognya.
“Kiai, saya minta didoakan agar enteng jodoh,” kata kawan saya.
Si kiai menatap wajah kawan saya. Lalu bukannya menjawab, malah balik bertanya hal yang tidak nyambung, “Ibumu masih hidup?”
Keruan saja kawan saya kaget. “Eee, masih, Kiai,” kata kawan saya bingung.
“Masih sehat?”
“Masih, Kiai. Sehat walafiat,” kata kawan saya.
Kiai ini mengembuskan napasnya sambil tersenyum. “Sudah pernah minta doa sama ibumu biar enteng jodoh?”
Kawan saya celingukan bingung. “Heee, belum pernah, Kiai,” kata kawan saya.
“Kalau begitu kamu keliru minta doa ke aku. Doaku nggak ada seujung kukunya daripada mustajabnya doa ibumu. Apalagi kamu anak laki-laki,” kata si kiai.
Si kawan ini lalu pamit dan beberapa hari kemudian menceritakan pengalaman ini kepada saya.
Sepintas memang tidak ada yang aneh dari dialog ini. Doa ibu memang luar biasa dahsyat (konon kutukannya juga dahsyat). Tapi, ada pesan yang tersirat di dalamnya. Soal hubungan seorang ibu dengan anak laki-lakinya.
Begini sidang jemaat yang dirahmati Allah. Berbeda dengan hubungan seorang ibu kepada seorang anak perempuannya, seorang anak laki-laki punya kewajiban bakti yang tak lekang oleh waktu kepada ibunya. Bahkan ketika si anak laki-laki ini sudah punya anak sampai cucu, ikatan baktinya tidak akan putus. Ini jelas berbeda dengan anak perempuan yang akan terputus kewajiban yang sama saat sudah bersuami.
Hm, tunggu dulu, terlihat tidak adil ya?
Begini, dalam Islam, kedudukan perempuan itu sebenarnya sama tingginya dengan laki-laki. Bahkan tidak perlu tafsir njelimet untuk memahaminya. Ayolah, tentu saja situ juga pernah mendengar riwayat saat seorang sahabat bertanya siapa yang harus dihormati terlebih dahulu antara bapak dan ibu kepada Nabi Muhammad. Dan di jawaban Nabi, ibu disebut sampai tiga kali.
Oke, tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana jika seorang perempuan kebetulan tidak punya anak laki-laki?
Untuk menjawabnya, bagaimana jika perspektif pertanyaannya kita balik?
Setiap laki-laki—kecuali Adam tentu saja—dilahirkan dari siapa? Seorang perempuan. Seorang ibu.
Artinya, seorang laki-laki terikat beban bakti yang teramat tinggi kepada seorang perempuan. Ibu mereka masing-masing. Entah itu kepala suku, pemred mojok, sampai dengan akhi-akhi yang dibilang Kalis Mardiasih “cupet”. Semua punya kewajiban yang sama. Semua berkalang perempuan.
Termasuk juga seorang suami yang menjadi sebab putusnya hubungan bakti seorang anak perempuan kepada ibu dan bapaknya. Hal yang kemudian membuat hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam sebenarnya adalah sebuah lingkaran. Seharusnya, tidak ada yang lebih dominan di antara satu dengan yang lain. Istri bakti kepada suami, suami bakti kepada ibunya, begitu terus sampai kiamat.
Hal itulah yang sebenarnya masih membuat saya bingung dengan wacana umum soal “kesetaraan gender”. Tentu bukan soal kesetaraan di urusan hukum atau pendidikan, tapi kesetaraan nilai antara “maskulin” dengan “feminin”.
Dalam momen seperti Kartinian misalnya, kenapa yang dimunculkan justru perempuan yang menjadi kondektur bus, tukang ojek, atau seorang lurah—misalnya? Tidak ada yang salah dengan itu, tapi kenapa tidak memunculkan nilai bahwa menjadi ibu rumah tangga pun sama kerennya? Sama penting dan bernilainya seperti seorang bapak yang mencari nafkah?
Hal itulah yang kemudian membuat saya berpikir bahwa seorang perempuan tetap keren sekalipun ia hanya membesarkan anaknya, mengurus rumah tangga, melayani suaminya, bekerja di ranah-ranah—istilah yang para aktivis feminis sering gunakan—DOMESTIK.
Sebab, ranah semacam itu memang bukanlah ranah yang lebih rendah. Tidak lebih buruk menjadi seorang ibu rumah tangga daripada menjadi seorang wanita karier atau berpendidikan tinggi.
Ini bukan persoalan mana perempuan yang lebih hebat dan mana yang tidak. Ini hanyalah persoalan siapa lebih mampu untuk sekolah dan siapa yang tidak memiliki akses ke sana. Dan persoalan semacam itu tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi juga laki-laki. Artinya ini bukan masalah gender.
Jika kemudian muncul inferioritas kepada seorang perempuan yang bisa lebih melakukan lebih banyak hal daripada laki-laki, saya pikir itu masih dalam taraf wajar saja. Toh, bila saja saya punya kenalan perempuan yang punya selusin mobil Alphard. Dan kebetulan saya hanya seorang pemuda dusun yang cuma punya sepeda ontel. Apakah kemudian saya menjadi cupet jika saya menghapusnya dari daftar “perempuan yang berpeluang untuk saya nikahi”?
Ini memang bentuk inferioritas, tapi bukan sebatas karena dia perempuan dan saya laki-laki. Ini karena dia berada di kelas sosial yang berbeda dengan saya. Ibarat Arlian Buana ingin menikahi Agnes Monica, pandangan umum juga akan bersuara, “Lha kowe ki sopooooo?”
Lagi pula, yang namanya pernikahan bukan hanya penyatuan dua orang yang sedang dimabuk cinta, ini adalah persoalan menggabungkan dua keluarga menjadi satu keluarga. Jika secara level sosial dan kelas sosial berbeda, itu benar-benar akan sangat menyulitkan.
Bagi pasangan yang menikah sih mungkin enteng-enteng saja menjalani perbedaan ini, tapi bagi keluarga masing-masing yang punya cara pandang yang berbeda-beda, belum tentu. Ini pekerjaan besar.
Lalu apakah pernikahan semacam itu mustahil dilakukan? Tidak juga. Bisa saja sih, tapi perlu usaha lebih untuk melakukannya. Dan tentu saja, lebih banyak orang yang enggan mengambil tantangan seperti itu.
Dan harus saya akui, saya orang yang enggan mencari tantangan semacam itu. Hal yang saya lakukan saat mencari jodoh (dulu) sederhana saja. Saya seorang santri, mencari istri pun ya seorang santri, atau punya latar belakang santri. Karena bagi saya, kesamaan kelas sosial, latar belakang, dan pengalaman-pengalaman istri saya adalah representasi dari keluarganya. Sehingga akan jauh lebih mudah nyambung dengan keluarga saya.
Tidak njelimet, simpel, praktis.
Kesimpulannya, selera dan keputusan saya dalam memilih pasangan ternyata lebih banyak ditentukan oleh latar belakang, pendidikan, dan lingkungan tempat saya dibesarkan. Dan karena punya kesamaan kultur dan kemiripan model lingkungan, istri saya dan keluarganya punya cara berpikir yang juga sama soal itu, jadinya kita cocok. Nikah deh. Sekarang punya anak satu.
Hal yang tanpa disadari sebenarnya juga dilakukan oleh semua orang.
Memacari atau menikahi teman sekelas waktu SMA, teman kuliah, teman satu kampung, teman satu komunitas, atau bahkan teman sesama penulis Mojok. Ada latar yang sama sehingga jalan semacam itu dipilih karena lebih masuk akal dan tidak ribet. Seperti Kalis Mardiasih dan Agus Mulyadi atau “akhi-akhi cupet” dengan mbak-mbak non-S-3.
Yang setara-setara saja. Toh yang penting setia.