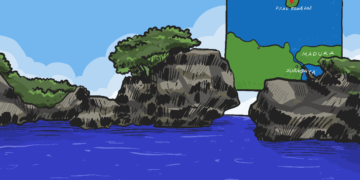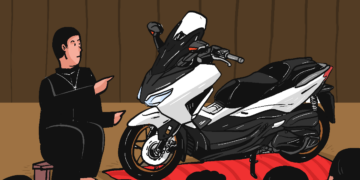“Dasar Batak blangkonan!” Mendengar ejekan itu dari salah seorang rekan kerja, saya cukup tersenyum tahu diri dan memaklumi.
Awal penyebabnya adalah muka dan nama saya yang punya embel-embel Marpaung di belakang, tetapi jangankan ngomong Batak, lah wong membedakan tulang sama amangboru saja saya masih harus buka RPUL. Sulit. Vokabulari bahasa Batak saya sama menyedihkannya, mentok di horas (halo) dan hepeng (duit). Di luar itu saya membutuhkan Google Translate.
Saya lahir dan besar di Magelang, kota yang terkenal sebagai kota sejuta bunga walau entah di mana bunga sebanyak itu ditempatkan. Saya sangat fasih berbahasa Jawa yang notabene bahasa ibu. Ini semua bermula dari ibu saya, seorang perempuan Jawa yang khilaf menikah dengan lelaki Batak perantau dari Pematang Siantar. Berkat mereka, balada hidup saya sebagai pejabat alias peranakan Jawa-Batak dimulai. Mungkin versi kebalikan dari diri saya adalah para pujasera, putra Jawa kelahiran Sumatra, yang lahir dari orang Jawa tapi lidahnya Melayu totok.
Menjadi pejabat membawa suka duka, terlebih dengan adanya marga yang menempel. Beberapa orang Batak mengejek saya dengan kata dalle, kata Batak yang artinya tidak sempurna, tersesat, dan semacamnya karena saya tidak bisa berbahasa Batak dan tidak mengerti adat Batak. Bagi sebagian orang Batak, panggilan tersebut menyakitkan karena memang ditujukan untuk merendahkan. Namun, saya tidak peduli dengan ejekan tersebut. Untuk menenang-nenangkan hati, saya yakini saja, orang Batak berbahasa Batak itu sudah berceceran di mana-mana, sementara orang Batak berbahasa Jawa itu unik.
Diejek memang, tapi status pejabat juga banyak membantu saya. Kombinasi muka dan nama Batak dengan bahasa Jawa yang fasih dan medhok yang sering menjadi bahan olok-olok itu malah memudahkan hidup saya ketika harus bekerja di luar Jawa. Saya jadi lebih mudah bergaul dan berbaur. Ketika harus merantau ke Kalimantan Timur, saya pikir saya harus belajar bahasa lokal agar mudah bergaul. Sampai di sana saya malah geli sendiri. Bahasa Jawa terdengar di mana-mana. Banyak sekali orang Jawa di Kallimantan, baik yang asli dari Jawa maupun yang sejak lahir sudah tinggal di sana—keturunan orang Jawa yang ikut transmigrasi puluhan tahun yang silam. Menurut data BPS tahun 2010, suku Jawa memang suku dengan populasi terbesar di Kalimantan Timur.
Hidup di pedalaman Kalimantan membuat saya sadar bahwa sebutan suku perantau bukan hanya monopoli suku di luar Jawa, seperti Batak, Padang, Bugis, dan lain-lain. Sebab, di Kalimantan orang Jawa hidup dan beranak-pinak dengan tenangnya. Bahkan di tepi jalan dalam hutan yang tidak ada peradaban sama sekali (tidak ada perkampungan, warung, atau apa pun kecuali pohon dan penunggunya) masih ada orang Jawa yang sempat-sempatnya jual rambutan. Saya kira level survival orang Jawa sudah mendekati amoeba ataupun kecoak. Mereka bisa hidup di mana saja dalam kondisi apa pun.
Saya dengan mudahnya bisa berkomunikasi dengan banyak orang Jawa di sana, baik ketika harus menyelesaikan masalah berkait pekerjaan maupun ketika butuh bantuan pribadi. Sama-sama bernasib jauh dari tanah Jawa membuat kami lebih dekat. Apa lagi kami bisa berkomunikasi dalam bahasa Jawa, percakapan menjadi lancar.
Di sisi lain, muka dan nama yang Batak banget membantu saya dengan suku Batak. Walaupun saya tidak bahasa Batak, mereka tetap menerima saya dengan senang hati. Bagi orang Batak, di perantauan sesama orang Batak adalah saudara. Walaupun hampir di setiap pertemuan dengan mereka, saya pasti dikhotbahi panjang lebar untuk ingat leluhur, belajar adat Batak yang jelimetnya nggak ketulungan dan belajar bahasa Batak. Dan tidak lupa: saya juga harus cari istri orang Batak. Semua saran itu terbukti di kemudian hari tidak satu pun menjadi kenyataaan. Dalam rumah keluarga Batak pulalah saya berlindung dan bersembunyi ketika ada orang yang mau menggorok leher saya.
Ketika sudah bisa bergaul dengan orang Batak, bergaul dengan suku lain pasti akan lebih mudah, semisal dengan orang Toraja, Manado, Timor, ataupun Dayak. Kalau ini karena disatukan oleh hobi yang sama, yaitu memakan hidangan dengan kode B1 dan B2. B1 untuk kambing balap alias kirik dan B2 untuk sapi pesek alias celeng. Tidak lupa tuak dan petikan gitar mengalun bersama nyanyian rindu akan tanah leluhur.
Saya tidak menyesal jadi anak peranakan. Meski harus jadi Marpaung yang blangkonan, status pejabat membantu saya bertahan hidup di pedalaman Kalimantan. Saya bisa berbaur dan berkomunikasi hampir dengan semua suku. Bekerja, berteman, dan menjalin tali persaudaraan yang tidak akan putus.
Alamak, serius pulak jadinya, tak mangkat tuku kopi sek.