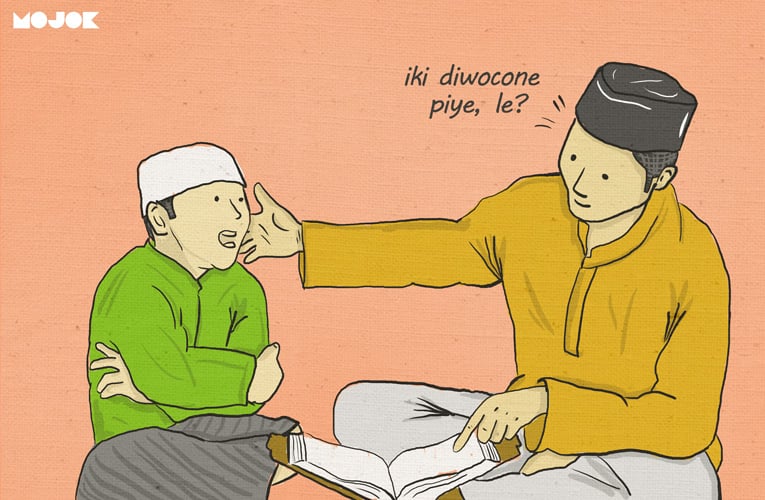[MOJOK.CO] “Akal sehat dan iman bisa berjalan berdampingan.”
Sejak berabad lalu, pulau Jawa merupakan kawasan rawan gempa sebab posisinya secara geografis berada di jalur subduksi yang merupakan pertemuan lempeng tektonik Hindia Australia dan Eurasia. Kondisi ini masih ditambah dengan banyaknya patahan (sesar) di daratan yang juga aktif bergerak. Teori tersebut kita pelajari di sekolah sejak SD, SMP dan SMA. Kita menerima itu sebagai kebenaran akal sehat ilmu pengetahuan.
Lalu, secara sporadis, seorang penceramah mengganti pemahaman ini dengan berujar bahwa Yogyakarta sering mendapat azab bencana alam berupa gempa dan gunung meletus akibat terbukti sebagai daerah dengan jumlah free sex tertinggi di Asia setelah Thailand menurut sebuah data survey. Meskipun pernyataan ini menyakiti nalar petugas BMKG atau kawan-kawan aktivis tanggap bencana, lebih-lebih juga korban bencana, tentu saja banyak jamaah pengajian yang akan tetap percaya. Maklum, Indonesia adalah negara yang sangat relijius. Suara ustaz, meskipun merendahkan akal sehat, harus diterima sebagai suara Tuhan.
Saya lalu teringat pemikiran bodoh yang sempat kuimani dan betul-betul tak ingin kuingat lagi. Entah siapa yang dulu memaksaku percaya bahwa tragedi bom Bali itu bisa dimaklumi. Sepertinya, pada tahun 2000-an itu sebuah stasiun televisi menyiarkan secara langsung berbagai siaran wawancara ekslusif dengan para tersangka yang merupakan kaum ekstremis beragama. Menurut mereka, Bali adalah pulau yang diizinkan oleh Allah untuk diazab, sebab lihatlah Bali, pulau yang hanya berisi maksiat serta pesta pora orang bule memakai bikini.
Jika di Bali ada jutaan pemeluk hindu yang taat, juga pemeluk Islam dari Jawa yang sejak dulu di perantauan mencari nafkah untuk keluarga, tentu tidak menjadi perhitungan. Bom diledakkan dua kali. Sekarang, ingin rasanya saya datang ke Monumen Bom Bali di Legian setiap tanggal 22 Oktober, semata untuk mengingat duka bersama warga yang pernah kehilangan 202 nyawa dan ratusan orang luka-luka.
Tak semua orang yang saklek dalam beragama mendukung tindakan ekstremis. Tetapi pola pikir ekslusif dalam beragama maupun perilaku ekslusif dalam subkultur lainnya sering memiliki bibit potensi untuk kekerasan.
Akal sehat kita dipaksa menerima hal yang bertentangan dengan nalar kita.Masih banyak orang yang memaklumi tragedi di Masjid Al Rawdhah, Mesir, dengan 300 lebih nyawa yang hilang karena pengeboman dan penembakan massal, sebab para korban diukur dengan satu indikator saja, yakni pelaku bid’ah. Sebelumnya pada Februari 2017, ekstremis mengebom sebuah masjid sufi di Pakistan dengan korban 80 jamaah yang tengah beribadah.
Ketika melangsungkan ego penuhanan diri itu, si ekstremis meneriakkan takbir. Ia menjustifikasi lafaz Allahu Akbar untuk melakukan kejahatan kemanusiaan. Dalam skala kecil, mereka yang memaklumi peristiwa penghilangan nyawa dengan alibi pembelaan kepada agama, mengawali pemikiran itu dengan gemar memboikot, meliyankan orang lain, dan menolak tata sosial kemanusiaan.
Itulah mengapa saya merasa aneh kepada sebagian Muslim yang protes kepada sebuah film anak yang dianggap menistakan nilai-nilai Islam karena salah seorang tokoh penjahat di dalam film gemar meneriakkan takbir. Persona teroris di berbagai belahan dunia jelas berkali lipat lebih seram dari musuh Naura atau Haji Muhidin yang dalam sebuah sinetron merupakan tokoh yang gemar berjamaah ke masjid tapi tetap mendengki kepada orang lain. Para ekstremis itu tak hanya meneriakkan takbir, tapi juga berbendera kalimat tahlil.
Persoalan sebenarnya bukan menistakan takbir. Mereka sesungguhnya sedang menistakan diri mereka sendiri karena gagal menafakuri makna takbir. Gus Mus pernah berpesan, menafakuri makna takbir dilatih ketika kita salat. Tepat ketika takbiratul ikram dan menyeru Allahu Akbar, kita seharusnya berada pada posisi nol untuk membuat diri kita merasa sangat kecil. Bukan sebaliknya, merasa jadi besar, apalagi memakai Maha Besar itu untuk mewakili ego paling benar.
Sayangnya, banyak dari mereka ini mengaku sebagai kaum salaf dan salah kaprah mendefinisikan makna salafiyah. Dalam peradaban Islam, kata salafiyah mengemban makna istilahi yang permanen, yaitu menunjuk pada tiga abad (generasi) pertama dalam usia umat Islam. definisi ini disimpulkan dari sebuah hadist, yakni,”Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, kemudian yang datang sesudah mereka, kemudian yang datang sesudah mereka…”
Dalam perkembangannya, istilah ini kemudian disalahpahami dan disalahgunakan. Sebagian dari mereka mengaku bahwa hanya mereka pewaris kaum salaf, sehingga tidak ada salafis selain mereka. Untuk berbagai kajian cabang agama yang kecil dan parsial, ia butuh berbagai macam dalil untuk mendukung keyakinannya.
Perbedaan pandangan dalam menanggapi sebuah amalan bisa membuatnya mengafirkan orang lain dengan landasan amalan tersebut tak ada dalil, ini menghina akal sehat kita, padahal kenyataannya justru ia sendiri yang belum menemukan dalil itu. Kalau perlu, mayoritas da’i dan ulama yang jujur dan tulus dari seluruh penjuru bumi dianggap tak lebih dari seorang pelaku bid’ah karena soalan ranah privat lagi parsial itu.
Anehnya, untuk persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti tanggap bencana yang sedarurat itu, ia hanya butuh mitos, rumor, dan desas desus. Dan tentu saja, untuk urusan ini, yang fasik atau kafir tetap orang lain, sebab keyakinan pribadinya kadang-kadang menutup segala peluang untuk terbukanya perspektif yang lebih luas.
Di masa lalu, ketika istilah salafiah muncul di Mesir bersama kepemimpinan Al Afghani dan Muhammad Abduh, ia adalah gerakan reformasi keagamaan yang bermisi membuang kejumudan yang bersumber dari segala pemberhalaan pemikiran yang menyebabkan masyarakat sulit maju. Salaf bukan sebuah gelar yang disematkan kepada sebuah mazhab yang para pengikutnya mengaku sebagai satu-satunya pengemban kebenaran.
Jika kaum salaf terdahulu boleh mengeluh, barangkali ia akan berpesan bahwa yang mesti ditiru dari mereka adalah apa-apa yang mereka gunakan untuk menghasilkan keputusan, seperti kaidah-kaidah penafsiran dan penakwilan teks, serta dasar-dasar ijtihad bil hikmah, bil mauizatil hasanah, dan mujadalah bil ahsan yang sangat mempromosikan nilai-nilai kesetaraan. Mereka juga pasti ingin sekali berpesan,”Tugas memikirkan peradaban adalah kewajiban tiap-tiap kaum Muslimin di segala zaman, bukan monopoli kaum salaf saja. Kreatiflah dalam menafsir zamanmu sendiri.”
Jadi, mengapa masih gemar menjustifikasi ego diri justru dengan mengorbankan nama baik para “salafush salih”?