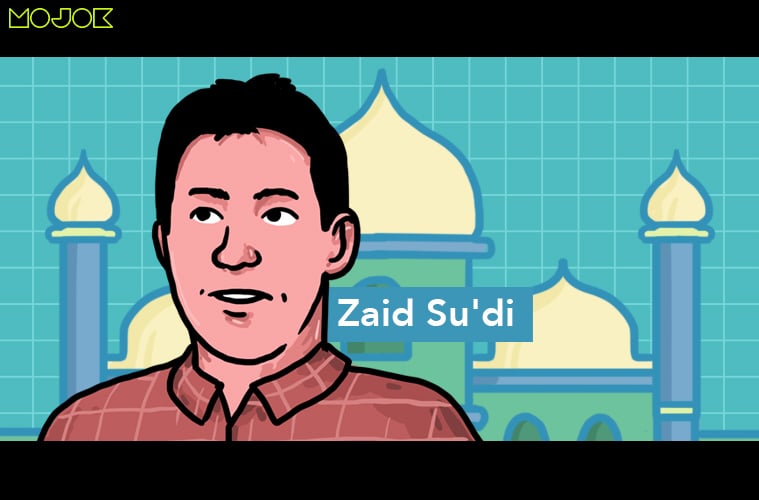MOJOK.CO – Apa sebenarnya dosa desainer yang sudah bikin sesat umat hingga mereka harus bertobat? Saya mencatat, setidaknya ada tiga hal.
Lebih seminggu sudah berlalu sejak diskusi akbar penuh takbir antara Ridwan Kamil dan Ustaz Baequni soal Masjid Al Safar yang kelihatan illuminati banget itu. Mojok sudah menurunkan enam atau lebih artikel terkait hal itu. When the dust has settled, pelajaran penting apa yang dapat kita petik dari bullying tabayun arsitektur itu?
Satu yang jelas: para desainer di negeri ini mestinya segera bertobat.
Tentu saja para desainer sudah tahu persis betapa penting dan mendesaknya agenda ini. Sayangnya, mereka memang keras kepala.
Betul, keras kepala adalah DNA desainer. Ya, desainer apa saja. Buktinya, sudah ada ribuan rancangan arsitektur masjid, masih juga para arsitek ingin bikin sesuatu yang beda.
Sudah tak terhitung banyaknya desain kursi, bahkan sampai ada museum kursi, masih juga desainer interior berjibaku bareng desainer produk untuk merancang kursi dengan pendekatan dan tampilan alternatif.
Desain sepeda motor? Selalu ada sentuhan anyar tiap rilis seri terkini. Desain penyajian makanan? Bermacam kreativitas kontemporer ditampilkan, hanya untuk dipandang beberapa kejap, disantap, lalu dilumat di lambung. Dan kita tahu, ke mana perginya sang makanan setelah itu esok harinya.
Begitulah. Dari merancang poster film, kebaya encim, interior pesawat terbang, sikat gigi, sampai interface aplikasi untuk mencari warung tenda yang pecel lelenya tidak gosong tapi parkirannya masih kosong, para desainer itu maunya selalu yang fresh, breakthrough, inovatif, inspiratif, mind blowing. Walah.
Hambok sudah, mendesain segala sesuatu itu woles saja. Tidak usah segitu-gitunya.
Ingatlah, semua upaya untuk inovasi selalu menghamburkan sumberdaya: waktu, biaya, tenaga, plus energi lainnya. Penghamburan menuju pada kemubaziran. Padahal sudah jelas kalau mubazir itu temannya syaitan.
Jadi, apa sebenarnya dosa desainer hingga mereka harus bertobat? Saya mencatat, ada setidaknya tiga hal.
Pertama: Desainer selalu cari masalah
Kalau kamu sedang belajar atau duduk di kantor saat ini, tengoklah ke sekeliling. Ada bolpoin, post-it, paper clip, stapler, atau mug kopi.
Ya, semua bebendaan itu adalah produk yang didesain serius. Tidak main-main. Ada observasi panjang sebelumnya. Ada letupan gagasan. Ada urak-urek sketsa awal entah berapa ribu biji. Lalu coba-coba bikin model dan menjajal beragam material.
Juga meraut purwarupa atau prototype-nya. Kemudian kalkulasi produksi, dan masih panjang lagi prosesnya hingga mereka ada di mejamu.
Untuk apa? Bikin hidup lebih mudah. Dan, hey, lihat, mereka juga indah.
Desain memang dimaksudkan untuk memberi solusi, atau setidaknya merespon, suatu masalah. Bahkan sesederhana sebuah safety pin alias peniti yang serbaguna itu. Atau sesimpel desain huruf “i” dilingkari yang bisa memberi tahu kita tempat mencari informasi.
Tapi justru di situlah persoalannya. Okelah, desain merupakan pemecahan masalah atau problem solving. Setidaknya, problem response.
Terus, bagaimana jika ternyata tak ada problem? Lha ya desainer dan komplotannya itulah yang cari-cari masalah atau bikin-bikin problem sendiri.
Dulu nenek buyut kita, misalnya, tak pernah bermasalah dengan rutinitas mengisikan tinta ke dalam pulpen. Lha wong mencelup pangkal bulu angsa ke botol tinta sebelum menulis pun mereka oke-oke saja.
Namun desainer, kadang bisa bersekutu dengan enjiner bahkan marketer, menganggap pulpen dan segala keribetannya sebagai masalah. Apa yang kemudian terjadi? Terciptalah ballpoint. Tinggal klak-klik, menulis bisa kapan saja di mana saja, sambil jungkir balik pun tetap aman dan praktis.
Kakek buyut kita sebetulnya juga tak masalah dengan rantang, baskom, atau peranti pecah-belah lain saat itu. Tapi di tahun 1950-an Earl S. Tupper mengintroduksikan Tupperware yang konon bukan hanya cantik tapi lebih awet, fleksibel, antitumpah, dan punya berbagai keajaiban plastik lainnya.
Bahkan The Museum of Modern Art (MoMA) pernah mengikutsertakan benda-benda itu dalam pameran What Was Good Design? -nya.
Atau, coba tanyakan pakde dan bude. Mungkin mereka juga tidak masalah dengan kancing celana atau jaket. Namun desainer dan para sekondannya memperkenalkan zipper lalu velcro.
Bahkan hari-hari ini, teman kita yang desainer grafis bisa menghabiskan waktu berjam-jam cuma untuk ngubek-ubek tipografi termasuk memilih font type.
Memangnya, apa beda Times New Roman dengan Helvetica atau Comic Sans? Toh semua itu sama-sama huruf, yang buat baca Iqra’ jilid satu pun tak bisa.
Lalu untuk segala ketidakjelasan ini, mereka akan bilang, “Itulah peradaban.”
Percaya? Jangan. Lantaran itu cuma pemberhalaan benda-benda. Sejak kapan memakai ritsleting ada ayat tuntunannya?
Akan tetapi, kalau mereka tetap bilang “itulah peradaban”, maka kita bisa bertanya: Peradaban yang mana, Akhi? Kalau bukan peradaban rabbani, ya, senyumin ajjah… (Kalimat terakhir mohon dibaca dengan intonasi manis sesantun-santunnya.)
Kedua: Obsesi kebaruan
Kekinian dan semangat zaman (atau zetgeist) adalah mantra para desainer. Untuk itu, mereka tak puas dengan hanya nitèni dan nirokké, tapi juga harus nambahi.
Masyaallah, orang kok sukanya menambah-nambahi. Bukankah lebih baik jujur, apa adanya, tak usah mengada-ada?
Bahkan anak kecil pun tahu bahaya obsesi akan kebaruan ini. Ingat dongeng The Emperor’s New Cloth? Raja yang tergila-gila akan tekstil baru tiada taranya itu pun akhirnya berjalan tanpa busana keluar istana. Na’udzubillahi min dzalik.
Makanya, jika harus mendesain masjid misalnya, ya, tidak usah neko-neko lah. Tinggal mencontoh saja bentuk paripurna masjid Nabawi. Tak perlu ribut soal perbedaan iklim atau besaran dan karakter pengguna.
Apalagi ngèyèl perkara proporsi, skala, dan semacamnya. Pokoknya fotokopi, sepersis mungkin. Kalau kegedean ya tinggal dikecilkan. Yang penting tak usah tanya-tanya usil, Masjid Nabawi yang zaman kapan. Soalnya, bentuk fisik masjid mulia di Madinah ini pun berevolusi dari masa ke masa.
Jangan lupa, lho, masjidnya pakai kubah—iya lah, mana ada masjid pakai kopiah.
Walaupun kubah Pantheon menaungi berhala-berhala kafir Romawi, kubah basilika St. Peter mengatapi gereja, dan kubah bawang nan cantik photogenic itu milik Saint Basil’s Cathedral di Moskow. Bahkan dulu sebelum bangkrut, kubahnya Donald Trump di Taj Mahal Atlantic City, nangkring di atas kasino.
Apapun alasannya, tidak bisa tidak: Atapnya pakai kubah, jamaahnya pakai jubah. Serasi dan syar’i sekali, bukan?
Tiga: Desainer itu plin-plan
Selain memiliki nilai fungsional, desain juga punya nilai simbolik. Sepatu misalnya, bukan hanya membuat kakimu aman dan nyaman serta tampilanmu makin tamvan. Tapi juga menunjukkan kevribadian. Dengan kata lain, desain adalah juga wahana komunikasi.
Di sini, bahasa visual menjadi sangat penting. Celakanya, dalam berbahasa visual itu desainer suka plin-plan. Misalnya, mereka bikin bulatan berwarna hijau. Dalam traffic lights, itu berarti: kendaraan harus jalan. Tapi pada kemasan obat, artinya: obat bebas. Sementara pada kemasan makanan: cocok untuk vegetarian. Terbukti seenak sendiri, kan? Cèn ramutu tenan.
Itulah setidaknya tiga hal yang membuktikan betapa pertobatan desainer sudah sangat mendesak. Akan tetapi, seperti terungkap di muka, mereka memang keras kepala. Bahkan, jangan-jangan, delusional.
Lihatlah desainer otomotif yang berkutat mati-matian menyelaraskan tampilan bentuk mobil dengan prinsip kerja mesin, ergonomi, keselamatan, dan efisiensi energi. Nyatanya, kalau kita mau masuk dari pintu sopir, tetap saja sulit mengutamakan kaki kanan terlebih dahulu. Desain begini, mana bisa islami?
Contoh lebih tragis, lagi-lagi terlihat di dunia arsitektur. Asal tahu saja, entah sudah berapa dekade para arsitek di negeri ini bekerja keras merumuskan what so called “arsitektur islami”. Padahal kita tahu, perumahan islami misalnya, sangat mudah membuatnya. Cukup dengan KTP.
Ya, seluruh penghuni perumahan itu wajib beragama Islam. Yang nonmuslim, out. Beres!
Jangan berburuk sangka dulu. Perumahan ini memang dirancang untuk mereguk rahmat Tuhan. Di dalam lingkungannya, salat berjamaah makin marak, kajian agama kian rutin, beribadah sunah lebih gairah, kegiatan sosial jadi gaya hidup.
Bahwa tak ada preseden semacam itu dari Rasulullah, bahwa urusan kemasyarakatan tak boleh disekat agama, bahwa Islam justru berkembang karena kesediaannya mempertimbangkan aneka ragam budaya, ah, itu kan propaganda sok rasional dari desainer dan orang-orang liberal.
Lagipula, tidak selayaknya kita memahami agama dengan menggunakan akal pikiran. Fahimtum?