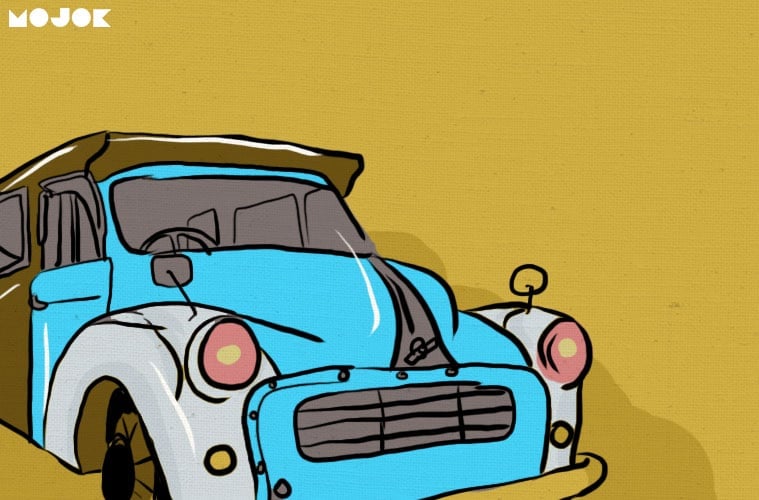[MOJOK.CO] “Tebak-tebakan kayak begini nih: kenapa suara soang alias angsa kenceng?”
Naik Oplet
Nama populernya oplet, biasanya berupa mobil Morris buatan Inggris. Merek yang beredar di jalan-jalan Jakarta pada masa digdayanya adalah Austin. Lidah orang Betawi yang memang cenderung ngegampangin menyebutnya Ostin. Lebih ringkes, pake “O”, lidah kagak bakal kesrimpung nyebut au.
Sudah ada di Jakarta sejak 1950-an, puncak kejayaannya pada periode 1960—1970. Pada tahun 1979, karena alasan modernisasi ditinjau dari berbagai aspek, mungkin termasuk klaksonnya yang khas berada di samping luar sopir dengan bola karet yang dipencet dan berbunyi tet-tot, Ostin dikandangkan dan diganti mikrolet.
Mungkin karena karena pabrik karoserinya dulu berada di Meester Cornelis (sekarang Mester), maka rute utama yang paling rame dilewati Ostin adalah Jatinegara—Kota. Ada juga di rute-rute lain kayak Tanah Abang, Kebayoran Lama, Tanjung Priok, dan lainnya. Tapi kisah historis radikal ini terjadi di rute Jatinegara—Kota.
Ah, ya, sebelumnya perlu gue jelasin bahwa di banyak mobil Ostin jaman dulu sering ada tulisan “ANAK-ANAK GRATIS. DEWASA Rp.25.” Tidak selalu, dan kadang ada juga sopir Ostin yang nagih ongkos ke anak-anak.
Sore itu, sekira pukul 5, seorang bapak bersama dua orang anaknya menyetop sebuah Ostin di bilangan Matraman arah Jatinegara. Ostin berhenti, si bapak dan dua anaknya tidak langsung masuk ke dalam Ostin. Ia memastikan dulu tulisan di atas itu, mungkin karena uangnya pas-pasan. Tulisan itu ade!
“Anak-anak gratis nih, Pir?”
“Iye, Be. Babe doang yang kena ongkos.”
“Bae deh. Umar, Jenab naik! Abah jalan kaki. Pir, turunin di Pasar Mester ye?”
“Lah, Babe kaga ikut?”
“Nggak, gue mo jalan kaki aje. Cuman 2 kiloan enih!”
“Buset dah. Semua diitung bener,” gerutu si sopir sambil menjalankan mobilnya. Sekilas ia menengok ke belakang melihat dua anak itu, yang dibalas oleh senyum mereka ke si sopir.
“Jangan nyengir lu pade!” si sopir masih aje ngedumel.
Bolot
Sebelumnya gue kaga tau kalo Bang Wawan bolot. Iye, budeg. Kami tinggal di Gang Mujaer, bilangan Tebet. Kadang di hari Minggu kami pergi mancing ikan. Biasanye sih kami patungan ngeborong empang. Lalu masing-masing mancing, yang dapet banyak, ya rejekinye. Minggu itu kami mancing di bilangan Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Sebuah empang yang berisi campuran ikan mas, nila, dan sedikit gurameh kami borong. Gue nongkrong di sisi barat bersebelahan dengan Mat Sani, Bang Wawan di depan kami di sisi timur.
Dari Mat Sani ini gue baru tau kalo Bang Wawan begitu. “Ntar dah, lu geroin die kalo die dapet ikan,” Mat Sani meyakinkan.
Setelah melempar beberapa umpan pancingnya ke kolam, Bang Wawan memakan Indomie yang ia pesan dari warung. Nggak lama sebuah umpannya dimakan ikan, Bang Wawan langsung menyentak joran pancingnya. Tak lama seekor ikan mas ia angkat. Mat Sani langsung kasih kode ke gue untuk segera membuktikan. Gue pun teriak.
“Wih, ikan mas gede. Umpannye ape, Bang Wawan?”
“Indomie, Leh. Tu banyak di warung. Enak, pake cabe ame daon kemangi.”
Mat Sani langsung meneblak (memukul) punggung gue, “Gue kate juga ape! Sekarang lu mau terus mancing ape pulang nih?”
Minggu depannya, hari masih pagi, gue nongkrong di bawah pohon jambu aer sambil makan nasi uduk. Tiba-tiba Bang Wawan keluar dari rumahnya menghampiri dan ngedeprok di sebelah gue sambil kebal-kebul asap rokok dan nenteng secangkir kopi. Kaga lama, Mat Sani lewat membawa joran pancing panjang. Keliatan dia mau mancing sendirian.
“Mo ke mane lu, Mat?” tanya Bang Wawan.
“Mancing. Mo nyari kocolan (ikan gabus), Wan.”
“Oh, kirain mo mancing,” Bang Wawan tersenyum elegan sambil nyeruput kopinya.
Tiba-tiba Mat Sani balik langkah ke arah rumahnya lagi.
“Kenape? Ade yang ketinggalan, Mat?” gue nanya.
“Kaga! Gue kaga jadi mancing, gara-gara ditanya orang sebelah lu tuh!”
Kuliah
Sudah 8 tahun Basit kuliah di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Basit berasal dari pinggiran selatan kota Jakarta. Betawi turun-temurun. Ketika akhirnya kuliahnya rampung, orang tuanya bangga banget. Basit pulang kampung langsung babenye mau buat selametan buat Basit. Basit sebetulnya ogah karena agak malu.
“Babe baru panen rambutan rapiah di kebon. Lumayan dapet lima karung mah. Alhamdulilah ade nyang langsung ngeborong. Besok Babe bikinin selametan buat lu ye, Sit?”
“Kaga usah repot-repot, Be. Tapi ya, terserah Babe deh.”
Usai Magrib para tetangga dan kerabat dekat berdatangan. Termasuk engkongnya Basit yang lansung ngedeprok di sebelah cucu kesayangannya itu.
“Jadi lu kuliah di mane, Tong?”
“Di IAIN, Kong.”
“Lah, Babe lu kate lu kuliah di Yogya?”
“Iye, IAIN Yogya.”
“Oh… IAIN Gajah Mada ye? Sohor tuh!”
Basit menunduk, berujar pelan, pelan banget, “Iyeee…” sambil mengurut-ngurut jempol kakinya.
Suara Soang
Satu kali dua mendiang maestro lawak Indonesia ini tampil satu panggung: Benyamin Sueb dan S. Bagio.
Bagio: “Ben, lu tau kenape suara soang (angsa) keras?”
Ben: “Ah, ade-ade aje, lu. Kaga tau gue. Ude dari sononye begitu.”
Bagio: “Payah lu! Itu karena leher soang panjang. Makanye suaranye keras.”
Ben: “Yo, lu tau uler kan? Badannye dari kepala sampe buntut leher semua. Suaranye keras kaga?”