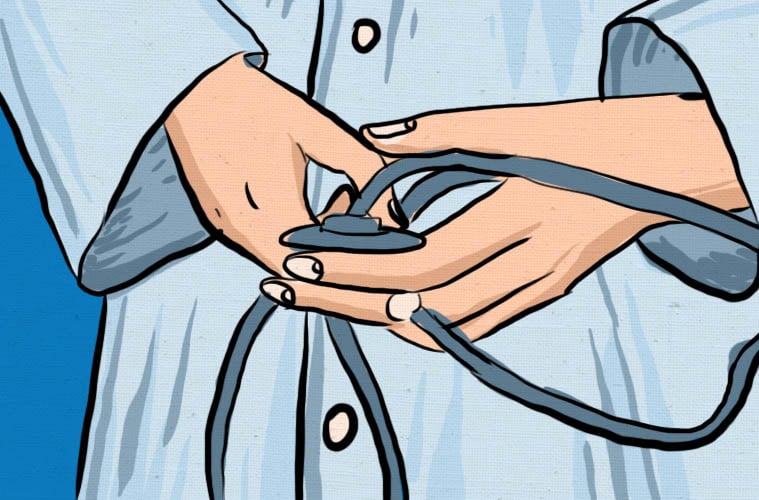Bayangkanlah pada suatu ketika otot-otot di tubuhmu lenyap seperti ditiup angin. Bayangkanlah pada suatu ketika dirimu kehilangan daya hanya untuk memegang kapas.
Malam itu kami tiba di rumah sakit tentara di Jakarta Pusat pukul 20.15 atau sekitar tiga jam dari rumah saya di Jakarta Selatan. Itu waktu yang cukup lama untuk jarak 23 kilometer dan untuk kondisi lalu lintas yang berlawanan dengan arus kendaraan (yang mengangkut) orang-orang pulang kerja. Tapi, lalu lintas di Jakarta sering sulit ditebak, sebagaimana nyeri di punggung saya.
Di mobil saya seperti koboi amatir sedang belajar menunggangi rodeo: duduk di punggung kuda liar dan harus mengendalikannya. Serbasalah saya berusaha meredamnya. Sebentar bersila. Sebentar berselonjor. Kadang menjadikan dua telapak tangan sebagai jok tambahan mengganjal bokong. Mujarab?
Hanya pada saat menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan sampai saya tertidur (10 menit), rasa nyeri ikut menguap. Bangun tidur, kembali saya menunggangi kuda liar. Begitu seterusnya hingga saya keluar gelanggang rodeo: tiba di rumah sakit, turun dari mobil, berjalan tertatih.
Saya memegangi pundak Voja, anak saya. Kami berjalan sangat pelan. Mirip siput. Mungkin siput terluka seperti yang pernah saya lihat di halaman rumah pada suatu pagi. Cangkangnya remuk sebagian entah karena apa.
Di depan kami dokter dan istri saya terlihat bergegas masuk ke ruang IGD, Instalasi Gawat Darurat, sebuah nama yang identik dengan instalasi listrik atau teknik, dan karena itu tak pernah saya pahami penggunaannya sebagai istilah di rumah sakit.
Kami terus berjalan mencari tempat duduk buat saya. Pada malam Jumat itu bangku di ruang tunggu penuh terisi. Beruntung Voja melihat sebuah brankar yang seperti teronggok di sudut ruangan. Kami berjalan ke sana. Saat kian mendekat saya tahu, itu adalah brankar besi model lama dan butut: catnya kusam, tempat tidurnya tak bisa ditinggikan atau direndahkan.
Tingginya hanya sepinggang saya walau saya tetap kesulitan untuk naik ke atasnya. Voja tak bisa membantu. Kedua tangannya menahan brankar agar roda-rodanya tak bergerak. Saya terus berusaha menaikkan kaki atau bokong. Berusaha lagi. Lagi, lagi, dan lagi. Tetap tak sanggup. Rasa nyeri di punggung yang luar biasa telah membuat otot tangan tak bertenaga bahkan sekadar untuk memegang sisi brankar sebagai pijakan tubuh agar saya bisa naik.
Sialnya fragmen kami malah menjadi tontonan. Tak ada yang membantu atau bertanya. Orang-orang di ruang tunggu hanya memandangi. Mungkin mereka juga sibuk dengan keruwetan masing-masing karena orang tua, anak, suami, istri, saudara, atau sahabat mereka malam itu juga masuk IGD. Mungkin pula mereka merasa heran melihat wajah saya yang terlihat tidak sakit, tapi bisa kesulitan hanya untuk naik ke brankar. Sebagian sibuk dengan gajet masing-masing. Ini sungguh malam Jumat 13 Juli yang menjengkelkan.
Sekali lagi saya berusaha naik dan dalam waktu sekian detik, saya menjerit. Voja telah mengangkat kaki dan mendorong tubuh saya. Kini saya sudah di atas brankar dan bisa rebahan. Voja yang menunggu di samping melihat saya. Saya melihatnya. Dia seperti merasa bersalah. Saya berusaha tersenyum, mencoba meyakinkan dia, saya baik-baik saja.
Sejauh ini saya memang berusaha terlihat tidak sakit. Saya tak mau siapa pun termasuk Voja melihat saya lemah bahkan pada saat saya sebetulnya sedang hancur sehancur-hancurnya. Kali pertama merasakan nyeri di punggung, saya setiap akhir pekan tetap rutin mengajak Voja lari pagi mengelilingi danau sejauh lima kilometer (yang kemudian olahraga itu saya tinggalkan karena kondisi punggung semakin parah). Hanya istri saya yang tahu betapa saya sebetulnya sedang sakit dan menderita meski wajah saya tampak seperti orang sehat walafiat.
Jauh-jauh hari sebelum kondisi saya semakin memburuk, istri sayalah yang tahu sejumlah perubahan pada tubuh saya. Suatu hari sewaktu mengompres benjolan di punggung, dia memberi tahu bahwa pundak saya miring, sudah tidak simetris dengan tulang punggung yang juga bengkok. Kali lain, saat memandikan saya, dia memberi tahu otot-otot di bokong saya nyaris tak ada.
Saya memang laki-laki dengan bokong tepos atau tidak menjulang, tapi yang dimaksud istri saya bukan bokong saya yang semakin tepos, melainkan kulit di bokong yang kian kendur karena tidak ada lagi otot-otot yang menempel. Kulitnya berkerut-kerut. Seperti keriput. Mirip balon kempes setelah beberapa hari menjadi hiasan pesta. Dia juga yang memberi tahu tentang otot di paha lalu di betis yang juga mulai berkurang.
Saya kemudian bukan hanya kesulitan berdiri dan berjalan, tapi berat badan saya melorot drastis dalam hitungan hari. Dari semula berat normal 45 kilogram turun menjadi 35 dalam waktu sebulan. Kulit di sekitar siku tampak kendur.
Setelah dirawat inap saya benar-benar tak mampu duduk tanpa dibantu untuk tegak dan tanpa sandaran, apalagi berdiri dan berjalan. Itu terjadi sejak hari-hari pertama. Perawat memasangkan gelang plastik berwarna telor asin sebagai tanda bahwa saya pasien terdaftar; di atas gelang ditempel stiker warna kuning sebagai tanda saya pasien yang harus diperlakukan ekstra hati-hati karena mudah “patah”—begitulah seorang perawat menerangkan arti warna-warna di gelang sewaktu dia selesai memasangkannya di pergelangan tangan saya. Kata dia, semua perawat tahu dan paham dengan tanda di gelang pasien. Saya tersenyum mendengar penjelasannya. Di rumah sakit ini saya merasa mirip barang pecah belah yang di kardusnya bertuliskan “Jangan Dibanting” atau “Fragile”.
Untuk hilir mudik dari ranjang ke kamar mandi saya harus dibopong oleh paling sedikit dua orang dengan kaki terseret-seret. Bersyukur banyak kawan yang rela menjaga saya, terutama dari Komunitas Kretek, beberapa mahasiswa, dan pesantren. Mereka rutin bergiliran menginap menemani saya. Setia memapah bahkan pada saat dini hari saat mereka sudah terlelap di sofa, dan mesti saya bangunkan dengan memanggil-manggil nama mereka. Keluarga pasien sebelah, keluarga dari seorang serdadu karier berpangkat letnan satu, sering juga membantu membangunkan kawan-kawan bila mendengar saya memanggil-manggil.
Di kamar mandi kawan-kawan itu mau memegangi badan saya agar tegak saat cuci muka dan menyikat gigi. Menyandarkan saya pada punggung kloset, membuka popok saat saya hendak kencing atau buang air besar, yang sering tidak jadi keluar atau kalaupun jadi keluar, hanya berupa cairan dan sedikit. Mereka juga orang-orang pertama yang melihat seluruh aurat saya. Mereka menyuapi saya. Mereka yang naik turun dari kamar perawatan di lantai empat ke lantai dasar untuk mengirim dan mengambil hasil uji darah, menebus resep, menyalin berbagai dokumen perawatan, membeli ini itu, dan sebagainya.
Pada suatu sore, di kamar mandi saya terjatuh. Mungkin karena rutin, istri saya dan seorang kawan kurang fokus memegang saya yang berdiri menghadap kloset. Bruuukkk …. Saya ndlosor di lantai. Istri saya menjerit. Kawan saya segera membopong agar saya kembali berdiri.
Anehnya, saya tak merasakan apa-apa. Tak ada luka. Tulang tak ada yang patah. Saya kemudian ingat tentang otot-otot di bokong dan kaki yang mulai tak ada dan tak berfungsi, seperti yang selalu diceritakan istri saya. Entah ke mana mereka semua pergi.
Sering saya mendengar suara, “Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan, wahai Rusdi? Menurutmu, kamu itu siapa?”
Itu suara dari ototkah? Suara hati? Suara kesadaran jiwa? Saya berhalunisasi?
Saya hanya tahu, saya selalu terlambat menyadari bahwa saya bukan siapa-siapa di hadapan semesta raya. Bahkan sebutir debu pun bukan. Kalau sudah demikian saya hanya bisa menarik napas panjang, menahannya di perut selama mungkin lalu melepaskanya lewat mulut sepelan mungkin.
Apakah saya lumpuh?
Belum. Belum sepenuhnya bila dibandingkan dengan kelumpuhan total setelah punggung saya dibedah.
Sekitar sejam saya dan Voja menunggu di ruang tunggu IGD. Sejak sebulan sebelumnya, di pekan terakhir Ramadan tahun ini dan kini di ruang tunggu IGD, dia tahu yang terjadi pada saya. Istri saya memberi tahu saya: Voja sempat shock, terpukul. Sempat murung sekian hari.
Dari atas brankar butut mata saya berkaca-kaca memandangi wajah Voja. Dia memalingkan muka. Tangannya erat menggenggam tangan saya.