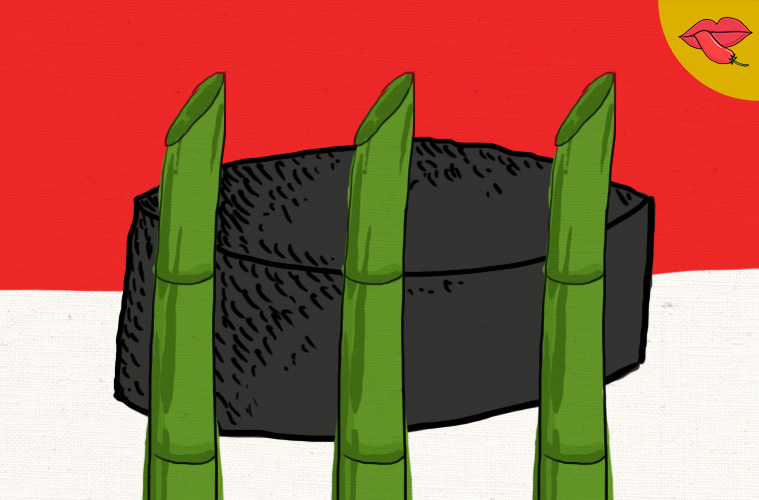Ini naskah terakhir untuk rubrik Nyinyir. Di Mojok yang baru, kami menyebut ini vox populi vox deui. Suara pembaca adalah suara jua. Kalau pembaca tak suka rubrik tertentu, apa boleh buat, kami harus mengeliminasinya tanpa banyak cingcong. Tanpa pembaca, apalah kami~
Karena ini naskah terakhir, dan minggu depan Anda tak akan menemui lagi rubrik ini, saya akan menulis tentang nasionalisme religius dengan pendekatan scholarship. Apakah ini pendekatan beasiswa? Apa lagi?
Mengapa saya menggeret-geret lagi “nasionalisme religius” ke dalam percakapan kita setelah dua tahun lebih kita lepas dari rezim yang menyebut dirinya “nasionalis religius”? Bukan, bukan karena Pak Beye, presiden keenam dan pendiri partai nasionalis religius itu sekonyong-konyong berkicau lagi. Kalau itu persoalannya, mana berani saya nulis di rubrik Nyinyir. Junjungan saya beliaunya, ucapan-ucapan beliaunya begitu mulia sehingga hanya akan cocok di rubrik Tokcer.
Ini karena banyak teman saya di Facebook membagikan status Chusnul Mar’iyah, dosen di Universitas Indonesia, mantan ketua program Pascasarjana Ilmu Politik dan HI di universitas yang sama, dan mantan komisioner KPU, berjudul “Re-reading Politik: Demokrasi dalam Bingkai Nasionalisme Religius”.
Berikut paragraf pertamanya.
Beberapa waktu ini, sejak gerakan 411 dan 212, saya dihadapkan beberapa pertanyaan yg menyangkut political Islam oleh kolega baik dalam maupun luar negeri, baik sebagai panelis maupun dlm FGD serta diskusi di warung kopi. Seperti terkaget2, Why Chusnul? did you go to 411, 212? you are part of FPI? Chusnul.,, you changed! Kemaren mendengarkan pidato Obama semakin memperkuat keyakinan saya bahwa kita perlu secara pendekatan scholarship untuk membahas bangunan demokrasi di Indonesia dengan konsep Nasionalisme religius.
You changed apa nih, Bu, kalo boleh tahu?
Lalu ibu dosen itu curhat alasan-alasannya mengikuti Aksi Bela Islam. Tak ada alasan baru, semuanya sudah pernah kita dengar, diikuti puja-puja oh betapa hebatnya oh betapa damainya oh betapa pentingnya. “Mengikuti demonstrasi 411 dan 212 menjadi sangat penting bagi seorang engage scholars,” tulis beliaunya yang ternyata seorang (((engage scholar))).
Apa itu engage scholar? Aduh, aing nga tega.
Apa saya berubah? tentu, yg abadi di dunia ini adalah perubahan sendiri. I am getting older and hopefully I am wiser.
Sedap. Memang tidak ada yang lebih indah di dunia ini kecuali menjadi tua dan menjadi bijaksana, Bu.
Jadi ada apa dengan political Islam? kenapa Islamophobia begitu kuat di kalangan kelompok terpelajar?
Saya tidak tahu ada apa dengan Islam Politik. Saya juga tidak tahu apakah islamofobia benar-benar telah menguasai orang kuliahan. Setahu saya, di kampus saya yang lama, banyak orang yang berjuang melawan islamofobia dengan beragam cara. Mulai dari menulis tentang kecocokan Islam dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi hingga turut serta dalam usaha-usaha dialog antaragama dan penyelesaian konflik.
Itu di mantan kampus saya sih. Mungkin keadaannya berbeda di kampus Ibu Chusnul. Sependengaran saya, di sana sedang marak Islamisme yang dalam banyak hal berlainan (atau bahkan bertentangan) dengan Islam.
Lalu Bu Chusnul bertanya,
“Kenapa kita menjadi muslim yg baik berjuang menuntut keadilan sosial, politik, ekonomi serta merta diperlawankan dengan anti kebhinekaan?”
Sudah betul itu, Bu. Sudah seharusnya demikian. Kita memang perlu melawan (dengan sengaja atau diperlawankan) yang antikebinekaan.
Menjadi muslim yg taat langsung diberi stigma anti universalisme?
Tidak apa-apa, Bu. Sebagaimana tidak semua film dari Universal Studio baik ditonton semua orang, tidak semua yang universal itu cocok dengan semua orang. Dalam banyak kasus, yang diklaim sebagai universalisme itu seringkali menginjak-injak harkat dan martabat orang.
Sepertinya ini tantangan bagi kita perlu membaca ulang Islamic teaching (valuenya by design Allah untuk semua manusia, universal, bukan untuk kaum tertentu, misal hanya untuk bani Israel)?
Dan,
Bagaimana menggabungkan the established theory dari Barat dengan pemikiran Islam atau dari Timur seperti Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldun, Al Mawardi, Al Farabi dan membaca juga Tarikh Ath-Thabari? Bagaimana membaca the second sex-nya Simone de Bavouar dengan kerangka Tarikh-Thabari pada bab Perempuan?
Nah ini, saya juga bingung bagaimana caranya, Bu. Mungkin perlu kita minta petunjuk Kak Jonru. Biasanya beliau punya solusi brilian.
Demokrasi dlm bingkai nasionalisme religius ini perlu dibahas dan dikonseptualisasikan menjadi teori modern.
Betul sekali, Bu. Untuk itu, saya kira Ibu Chusnul hanya perlu bertemu dengan Pak Beye dan mematangkan rencana tersbut. Kalau perlu, sekalian saja (((jihad struktural))) jadi kader Partai Demokrat.
Waktu saya semester 1, saya punya teman kuliah yang punya ambisi bikin teori Hubungan Internasional Islam. Menurutnya, hubungan internasional itu bermula jauh dari sebelum Perjanjian Westfalia, sejak pertemuan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Wah, benar juga, pikir saya.
Di satu kelas, dosen kami menerangkan teori-teori utama dalam Ilmu HI: Realisme dan Liberalisme. Realisme itu berangkat dari asumsi bahwa manusia itu pada dasarnya egois, selalu memikirkan keuntungan dirinya sendiri, dan pada akhirnya akan berkelahi atau saling makan dengan manusia lain. Begitu pula negara, begitu pula hubungan antar negara. Sementara Liberalisme berangkat dari asumsi bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain, dan mereka akan bekerja sama.
Teman saya menginterupsi, “Menurut Islam, semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi atau Kristen atau Majusi.” Dan dia berikrar, seperti Gaj Ahmada, akan mengembangkan teori HI berangkat dari asumsi dasar tersebut. Atau, kalau itu kurang mungkin, ia akan menggabungkannya dengan teori yang sudah mapan.
Bagaimana nasib teori itu? Entahlah. Ke mana ide kreatifnya? Tentu saja terbang bersama debu-debu Jakarta. Mungkin semakin dia banyak belajar semakin geli dia mengingat omongannya.
Teman saya adalah orang yang menulis artikel ini.