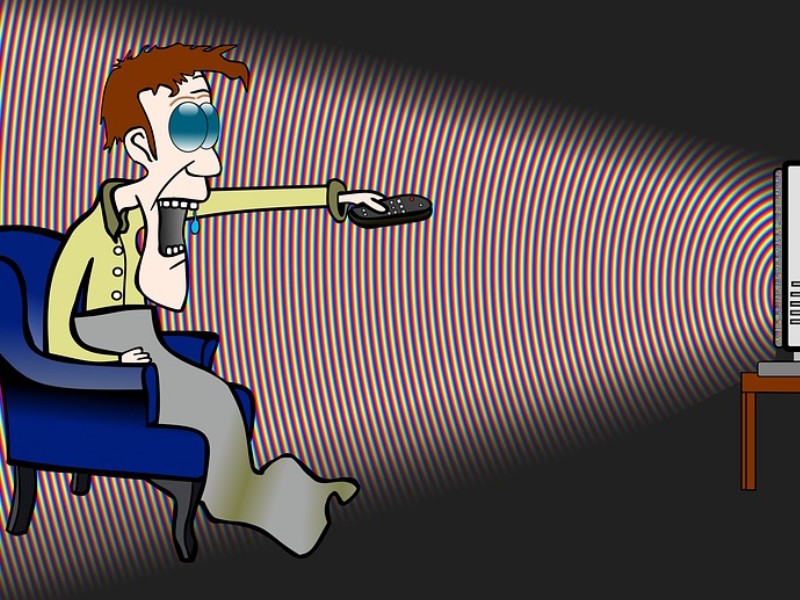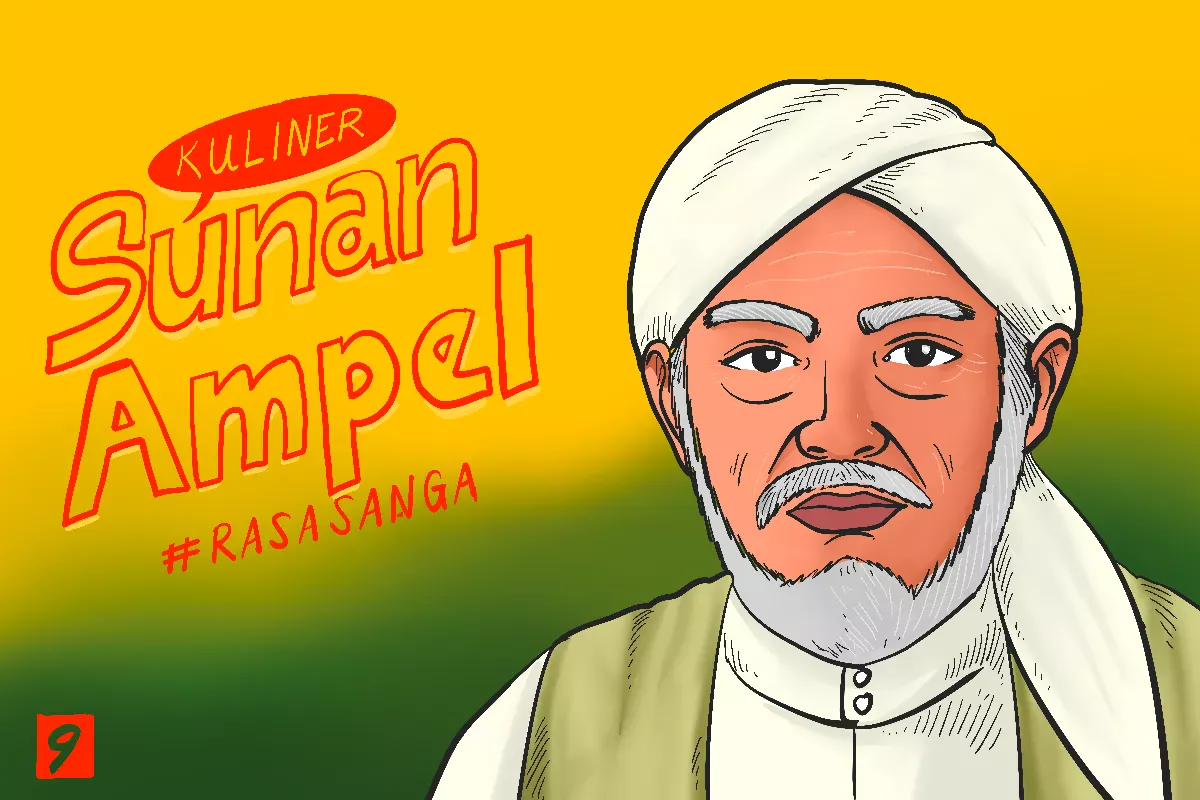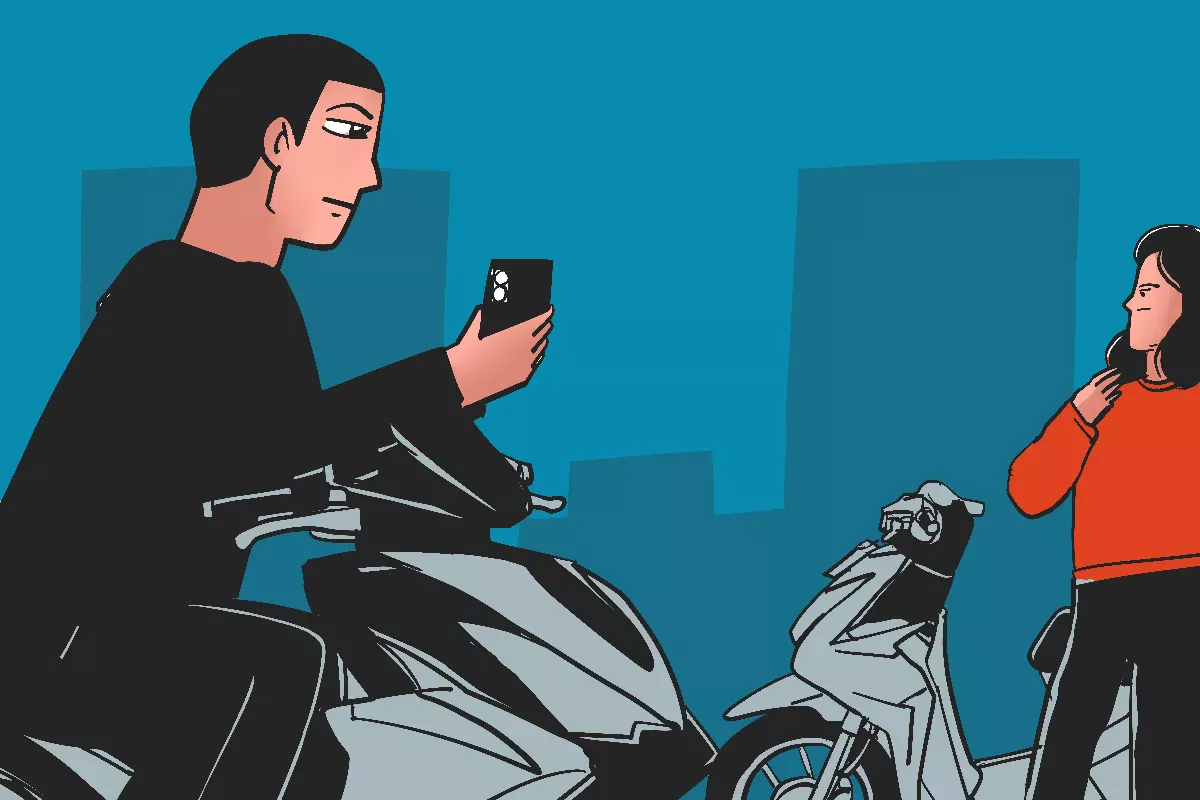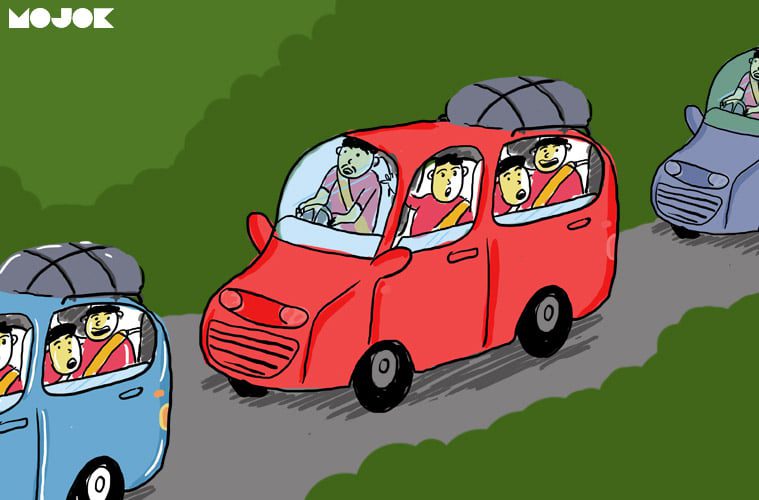Kecakapan apa, sih, yang jadi tolok ukur seseorang layak jadi pemimpin di negara demokrasi?
“Bahwa siapa-saja-bisa-jadi-apa-saja itu merupakan hakikat. Dan, itu sejenis berkah demokrasi, Cak. Semua ikan dalam kolam demokrasi punya hak yang sama,” ujar Solikin sambil menutup layar laptopnya. Mahasiswa cum aktivis itu, sedari magrib tadi menumpang wi-fi di emperan rumah Cak Narto. Revisi skripsi, katanya.
Semakin malam, udara dingin yang menyergap menambah riuh perdebatan mereka berdua.
“Tapi, kalau itu justru menunjukkan gelembung ketimpangan dan kemandekan bahkan kemunduran, lantas apa masih bisa disebut berkah? Kok, rasanya lebih tepat disebut musibah,” sergah Cak Narto.
“Sebentar! Apa maksudnya sampean tidak setuju dengan demokrasi, Cak?”
“Lho, ini bukan perkara setuju atau tidak setuju, Kin. Kalaupun aku tak setuju, bukan berarti lantas bangunan demokrasi kita runtuh begitu saja, kan? Aku cuma merasa ada yang salah dengan cara kita hidup berdemokrasi.”
“Tolong yang spesifik, Cak. Cara apa? Hidup apa?” Solikin mengejar.
“Oke. Kamu tadi memulai semua diskusi ini dengan sebuah gugatan, tho? Kamu bilang bahwa pandemi ini menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakcakapan para pemimpin dalam mengelola pemerintahan.”
“Iya. Betul, Cak. Lantas?”
“Yang tidak disadari banyak orang, termasuk kamu adalah bahwa semua tragedi selama pandemi ini merupakan lapisan terluar dari tumpukan kebobrokan sistem dari negara demokrasi kita. Sistem ini telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang melihat rakyatnya sebagai deretan angka dan statistik. Kita ngomel-ngomel atas situasi ini. Tetapi, kita lupa bahwa keberadaan mereka di atas sana adalah konsekuensi logis dari iklim demokrasi,” Cak Narto lugas kali ini.
“Tolong yang fokus, Cak. Konsekuensi apa?” tukas Solikin.
“Konsekuensi bahwa siapa saja bisa jadi apa saja, itu tadi. Tak peduli ia punya kecakapan atau tidak, punya sense of crisis apa tidak, punya kepekaan-kepekaan naluriah sebagai pemimpin atau tidak.”
“Kelewat jauh teropong sampean, Cak. Kecakapan, kepekaan, dan naluri itu kan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan meteran. Kalau seseorang sudah dilantik untuk menjadi pemimpin, berarti ia sudah mumpuni, Cak. Qualified!” Solikin menyanggah.
“Lho, berarti benar, tho. Ada yang salah dengan sistemnya. Kalau orang yang qualifed saja cuma sejauh ini kecakapannya,” Cak Narto menggeleng.
“Pemilu yang terakhir…” belum usai rupanya kalimatnya, “…telah memakan korban 800-an orang anggota KPPS, Kin. Kemudian ketika pemimpin sudah terpilih dan pesta sudah usai, puluhan ribu orang meninggal diterkam pandemi. Kalau memang demokrasi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang cakap dan kompeten, kematian-kematian ini sungguh suatu yang bisa dihindari,” asap dari mulut Cak Narto mengambang bagai halimun.
“Terus?”
“Aku cuma menduga, sekali lagi ya, menduga…” Cak Narto membentengi argumennya, “…bahwa mungkin ada yang salah dengan sistemnya. Ada bopeng dalam pelaksanaannya. Kalau siapa saja bisa jadi pemimpin, terlepas dari kecakapannya, yang kita pertaruhkan bukan hanya nyawa-nyawa rakyat tetapi juga masa depan bangsa.”
Cak Narto tampak hati-hati tapi juga berapi-api.
“Masih terlalu mengawang-awang, Cak. Analisis sampean kurang membumi!” tukas solikin meminta penjelasan.
“Gini, Kin. Untuk menjadi dokter, atau akuntan, atau profesional di bidang-bidang tertentu dibutuhkan kecakapan dan skill sets, bukan? Proses penguasaan ilmunya butuh waktu. Belum lagi serangkaian tes yang harus dilalui untuk akhirnya mendapatkan lisensi atau legitimasi atas profesinya itu. Lantas, kalau untuk menjadi presiden syaratnya hanya dua puluh biji itu, dan tak ada satu pun syarat kecakapan di sana. Apa ini namanya?”
Solikin bergeming. Ia menyimak.
“Padahal, sebagai presiden di negara demokrasi, kewenangannya luar biasa, Kin. Ia bisa menunjuk menteri untuk membantunya bekerja. Boleh siapa saja, asal memenuhi syarat administratif. Dan lucunya, juga tidak ada syarat kecakapan di sana. Ia juga boleh menunjuk komisaris-komisaris BUMN, dan tidak ada syarat kecakapan di sana.”
Suasana hening, tapi pikiran Solikin bergemuruh.
“Padahal, semua itu menyangkut kemaslahatan dan kesejahteraan bahkan hidup dan mati rakyatnya, tho? Dan ini yang terjadi sekarang, kan? Tidak tampak pemimpin yang punya kualifikasi kecakapan dalam mengelola pandemi.”
Solikin mengangguk.
“Legislatif pun begitu. Siapa saja bisa duduk menjadi anggota dewan yang terhormat. Meski tidak punya kecakapan dalam merumusukan undang-undang, misalnya. Asalkan diusung partai politik, maka sudah dianggap qualified, Kin.”
“Tapi, Cak…” solikin memotong, “…ada yang namanya visi misi, Cak? Itu kan semacam etalase kecakapan seorang calon pemimpin. Di sana rakyat diberikan kesempatan untuk menilai calon mana yang mempunyai visi misi yang paling relevan bagi kehidupan berbangsa.”
“Visi misi kan sesuatu yang belum terjadi, Kin. Bagaimana menguji akurasi visi misi? Paling banter di debat pilpres, tho? Lantas kalau visi misinya bagus apakah itu serta merta menunjukkan kapasitas, kompetensi, dan kecakapan seseorang untuk menjadi pemimpin?”
Solikin diam sejenak, kemudian… “Tapi, Cak, memang begitu konsep dan mekanisme memiliih pemimpin dalam negara demokrasi.”
“Gini, Kin. Kita kembali ke contoh sederhana tadi. Emangnya lisensi dan izin praktik seorang akuntan bisa diterima hanya dengan mengkampanyekan visi misi? Emangnya seorang dokter bisa praktik hanya bermodalkan visi misi?” Cak Narto menjeda, tersenyum.
“Tentu harus memenuhi standar kecakapan dulu, Kin. Lantas kalau untuk jabatan yang kewenangannya begitu luar biasa, presiden atau anggota legislatif misalnya, hanya dinilai dari visi misinya ketika kampanye, gitu?” Ia terkekeh.
“Apa maksud sampean lebih baik kita kembali ke zaman kerajaan, Cak? Sistem monarki gitu? Yang bisa menjadi pemimpin hanya trah para raja? Begitu?”
“Pertanyaannya bukan sistem mana yang lebih baik, Kin. Bukan monarki atau demokrasi. Melainkan, apakah sistem itu menghasilkan kepemimpinan yang tepat guna bagi kehidupan berbangsa. Apakah sistemnya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang cakap…”
“Terus bagaimana menurut sampean bagusnya, Cak?” tanya Solikin lemas.
“Yo, nggak tahu. Aku kan cuma sebatas menjawab pertanyaanmu itu tadi. Hehehe.”
***
Udara dingin menyergap seisi desa. Bulir embun mengembang di dedaunan. Entah dari mana asalnya, lamat terdengar suara gamelan mengalun pelan. Malam itu, Solikin gagal lagi menyelesaikan revisi skripsinya. Pikirannya diliputi pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak perlu ia pikirkan.
BACA JUGA Soal Negara Demokrasi, Semua Orang di Dunia Itu Norak! dan tulisan Suwatno lainnya.