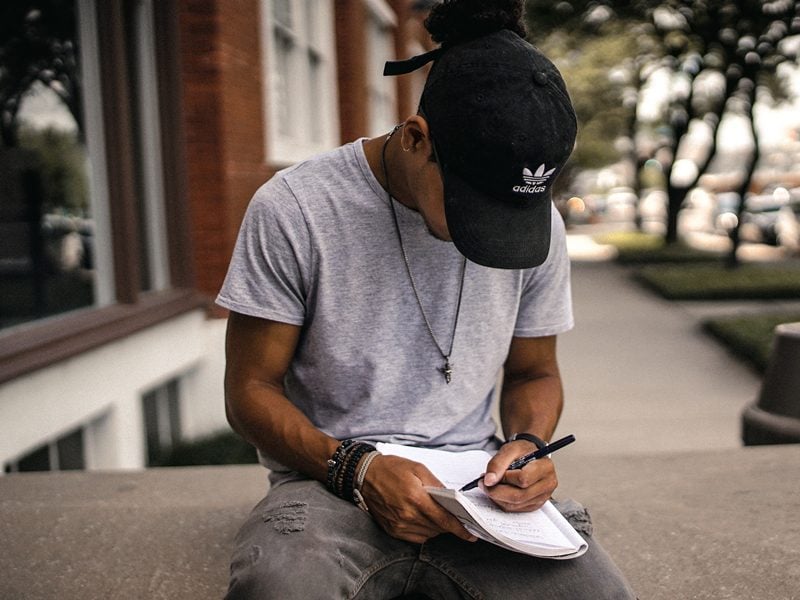Beberapa waktu yang lalu, ketika sedang membaca buku Sekolah Itu Candu, saya kembali mengingat perjalanan sekolah. Dari TK sampai kuliah. Saya berpikir ulang, apa alasan saya menghabiskan waktu begitu lama di dalam kelas yang begitu-begitu saja? Umur empat setengah tahun, saya diantar ibu masuk TK. Awalnya, guru saya menyuruh ibu menyetujui kalau saya di TK setahun saja. Langsung masuk SD, kan sudah gede. Akan tetapi, ibu menolak. Katanya, biarkan saya tetap melalui dua tahun di TK. Biar menikmati masa manja yang sama dengan teman-teman saya.
Saya melewati kelas TK dengan lagu-lagu yang dinyanyikan saban waktu. Saya menikmati permainan-permainan yang diajarkan. Kalau tidak salah ingat, saya juga diajari bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Sayangnya, di rumah saya dibiasakan berbahasa Jawa. Saya nyengir ketika membaca ulang catatan guru di raport TK. Ternyata saya bandel juga. Sering banyak salahnya dalam berbahasa.
Enam tahun berikutnya, saya disuruh belajar di kelas-kelas SD. Saya mulai diadu di dalam ring tinju. Guru memberi aba-aba. Saya dan teman-teman saling pukul dengan ilusi susunan angka-angka. Kalau saya ingat-ingat kembali, masa itu tujuan akhir kami cuma satu, menjadi kekasihmu rangking satu.
Untungnya, enam tahun tersebut tidak semuanya saya habiskan di dalam kelas. Saya masih bisa mencicipi bermain reog dengan teman-teman. Bahkan, kami sempat diundang untuk main di beberapa hajatan. Di tempat ini, kami nyuri belajar merokok ketika pura-pura kerasukan. Astaga… mengingat tingkah kami waktu itu, saya selalu terpingkal-pingkal. Betapa indahnya masa kanak.
Ketika masuk SMP, sepertinya saya mulai terfokus pada angka rapor. Tidak banyak yang bisa saya ingat di jenjang ini. Paling-paling, sekolah yang pulang-pergi jalan kaki dan berjualan jawaban ketika UAS. Dari bisnis inilah saya bisa mentraktir teman-teman, segelas es teh dan satu gorengan. Mengingat ini, saya merasa telah mencemari pendidikan Indonesia. Ya, tapi masalahnya, uang ibu saya sudah habis untuk membayar administrasinya. Selanjutnya, ketika di SMK, tujuan saya bukan agar setelah lulus langsung bekerja. Melainkan, agar ibu bisa pamer kepada tetangga memenuhi cita-cita, menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Ibu selalu mengulang-ulang kisahnya yang hanya tamat di sekolah dasar. Padahal keinginannya untuk melanjutkan sekolah sangat besar. Sayangnya, angka ekonomi orangtuanya sangat kecil. Sejak itu, cita-cita ibu diembankan kepada punggung kami, anak-anaknya yang menggemaskan ini.
Tiga tahun di SMK, waktu saya habis untuk petualangan cinta orientasi lapangan kerja. Saya mulai menyadari, selulusnya dari kelas kejuruan ini, saya akan bekerja di pabrik. Meskipun beberapa alumninya diterima kerja di luar negeri, tetap saja di pabrik. Sebenarnya tidak ada masalah bagi saya, tapi bagi ibu. Tujuan ibu menyekolahkan saya, tentu bukan untuk bekerja di pabrik. Teman saya yang lulus SD juga di pabrik. Gengsi dong… makan tuh gengsi!
Namanya juga orangtua, kebutuhannya kan anak yang kerja lebih baik dari yang lain untuk bahan menggunjing. Orangtua pasti kan pengin anaknya tidak menjalani nasib seburuk sama dengan dirinya. Berangkat dari kegengsian itulah ibu akhirnya membiayai kuliah saya. Sudah sekuat tenaga saya mengumpulkan angka terbaik dalam UN, tapi tidak terpakai. SNMPTN tidak lolos. SBMPTN tidak lolos. UMPTN lolos, tapi tidak nyambung sama sekali dengan jurusan waktu di SMK. Oh betapa~
Bayangan saya ketika sebelum dan sesudah kuliah pun sangat berbeda. Saya hanya punya referensi pada bayangan di televisi dan mbak-mbak yang sosialisasi di sekolah, menawarkan beasiswa dan kuliah murah. Semuanya rapi dan ramah-ramah. Setelah di kampus, mahasiswa yang saya temui, tidak ada rapi-rapinya sama sekali. Celana jeans pendek yang mungkin belum dicuci sekian hari. Kaos yang bersablonkan judul-judul acara. Semuanya serba seadanya. Bayangan awal saya tentang kuliah yang istimewa, di kampus ini segalanya biasa saja.
Untungnya, meskipun menyimpang jauh, saya menikmati perkuliahan itu. Saya melewati hari-hari yang habis dengan membaca buku, melembur tugas, mendengarkan diskusi, mengunjungi warung kopi, dan tidur di tempat-tempat free wifi. Lucunya, ibu tidak pernah peduli dengan perkuliahan saya. Maksud saya, peduli pada apa yang saya pelajari. Mungkin dalam pengertian ibu, sama seperti sekolah. Semua pelajaran diajarkan.
Jadi, selama empat tahun, ibu saya tidak pernah menanyakan nilai. Yang ditanyakan hanya, uang sakunya masih ada? Pacar sudah punya? Akhirnya, saya berusaha membuat surprise untuk ibu. Saya menyelesaikan kuliah di akhir semester delapan dengan nilai yang bisa dipamerkan. Ibu semakin percaya diri ketika bertandang ke hajatan dan reunian. Lalu dengan saya sendiri? Tidak ada yang tersisa selain kecemasan akan masa depan.
Saya sampai hari ini hanya berusaha menjaga nyala api doa dan cita-cita. Menebalkan telinga ketika ditanya kerja apa dan di mana. Meskipun sudah ada jawaban atas itu, saya tidak bisa yakin kalau tempat bekerja saya kelak bukan pabrik. Apalagi ketika selesai membaca pikirannya Roem Topatimasang dalam Sekolah Itu Candu. Roem melihat sekolah sebagai pabrik. Anak-anak bekerja dengan seragam dan pikiran yang sama. Lulus pun dengan tekad yang sama, rangking satu dan nilai sempurna. Saya sedikit sedih karena baru membaca buku tersebut baru-baru ini, padahal sudah ditulis sejak tahun 80-an. Tahu gitu kan, saya ndak perlu jadi guru seperti pekerjaan yang akan menjebak saya beberapa waktu ke depan. Kalau sudah begini, ya, saya cuma bisa tersenyum, nyengir, dan tertawa. Obat sakit hati seperti ini kan, ya, cuma haha-hihi.