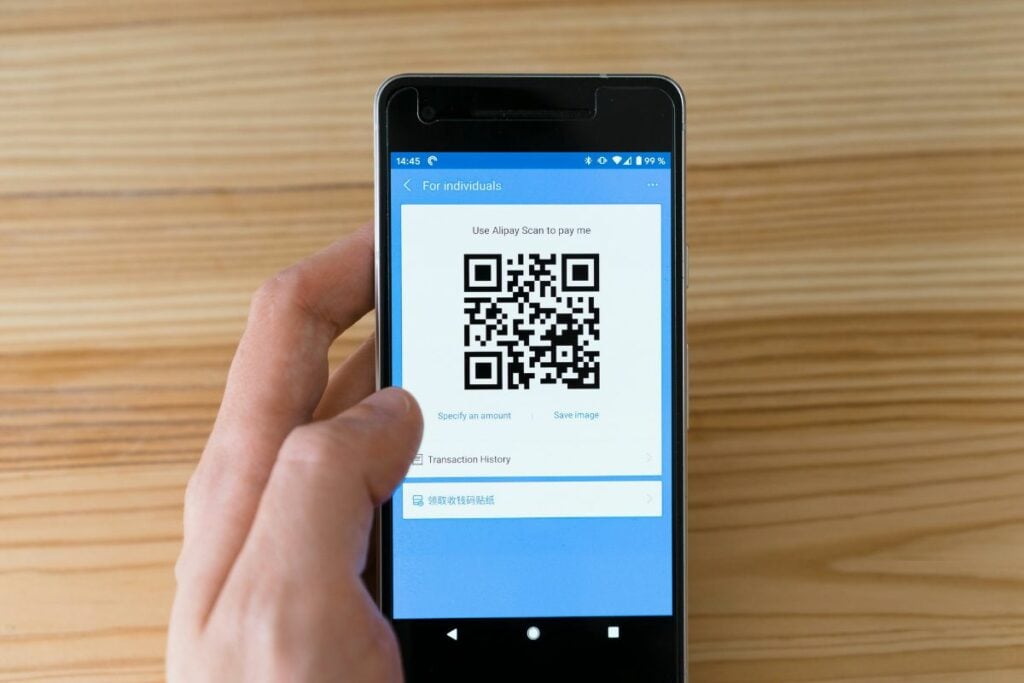Di satu sisi, penggunaan QRIS semakin masif di era sekarang karena praktis. Tetapi di sisi lain, pedagang kecil mengalami kebingungan.
Pernah nggak sih kalian berdiri di depan sebuah warung kelontong, atau mungkin kedai kopi hidden gem yang baru viral di TikTok, dengan sebotol minuman dingin di tangan, lalu ketika sampai di meja kasir, terjadi sebuah dialog yang paling menentukan nasib peradaban umat manusia modern.
Dialog itu biasanya dimulai dengan pertanyaan polos dari si pembeli yang notabene adalah Gen Z, “Bisa QRIS, Kak?”
Lalu dijawab oleh si penjual, biasanya dengan nada sedikit merasa bersalah tapi juga pasrah, “Maaf, Dek, cash aja.”
Hening.
Dalam keheningan sepersekian detik itu, kita bisa melihat sebuah proses loading yang intens di mata si Gen Z. Otaknya berputar cepat. Dia sedang menimbang-nimbang. Antara menaruh kembali minuman itu ke kulkas sambil bilang “Oh, ya udah Kak, nggak jadi,” atau dia harus melakukan sebuah aktivitas purbakala yang sangat merepotkan yang bernama… mencari mesin ATM terdekat.
Generasi cashless
Inilah potret generasi kita hari ini. Sebuah generasi yang menjadikan smartphone sebagai organ tubuh tambahan. Sebuah generasi yang dompetnya mungkin masih ada, tapi fungsinya lebih banyak buat nyimpen KTP, SIM, sama kartu member Kopi Kenangan yang udah nggak pernah dipakai lagi. Uang tunai bagi mereka adalah sebuah konsep yang merepotkan. Sesuatu yang kotor, penuh kuman, gampang hilang, dan yang paling parah dari semuanya, butuh kembalian.
Ya, Tuhanku. Kembalian. Nggak ada yang lebih bikin cemas seorang Gen Z selain bayar kopi harga Rp20 ribu pakai uang Rp100 ribu di pagi hari. Rasa bersalahnya mengalahkan rasa bersalah pas lupa matiin lampu kamar mandi. Mereka merasa telah membebani si Mas Barista, seolah meminta uang kembalian Rp80 ribu itu adalah sebuah dosa sosial yang tak terampuni.
Fenomena kemalasan kolektif inilah yang kemudian melahirkan sebuah tuntutan baru. Sebuah tekanan sosial yang halus, namun brutal bagi para pemilik usaha. Terutama mereka yang ada di segmen warung, toko kelontong, tukang bakso, atau ibu-ibu penjual gado-gado.
Siap-siap kehilangan pelanggan kalau tidak sedia opsi pembayaran dengan QRIS
Dulu, syarat buka warung itu gampang. Cukup punya tempat, punya barang dagangan, dan punya kalkulator buat menghitung. Sekarang? Nggak cukup. Konsumen baru yang didominasi oleh anak-anak muda ini punya syarat tambahan yang nggak bisa ditawar tawar. Warung Anda harus punya selembar kertas atau akrilik kecil bergambar kotak kotak hitam putih. Ya, QRIS.
Kalau warung Anda belum punya benda sakti itu, bersiaplah kehilangan pelanggan. Bersiaplah melihat calon pembeli yang udah di depan pintu, tiba-tiba memutar badan cuma karena mereka malas merogoh saku celana. Mereka lebih rela jalan kaki 500 meter lebih jauh ke Indomaret sebelah, yang harganya mungkin sedikit lebih mahal, cuma karena di Indomaret mereka bisa bayar pakai scan.
Ini bukan lagi soal efisiensi. Ini sudah jadi soal prinsip hidup. Prinsip hidup kaum rebahan yang menganggap segala sesuatu yang melibatkan aktivitas fisik lebih dari tiga klik adalah sebuah penderitaan.
Di satu sisi, kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Hidup di era digital memang memanjakan kita dengan kemudahan yang luar biasa. Mau makan tinggal pencet, mau transportasi tinggal geser, atau bayar tagihan tinggal tap. Semuanya serba instan. Uang tunai terasa seperti sebuah teknologi usang, seperti pager atau disket di zaman cloud storage.
Mencoba melihat fenomena “bayar pakai QRIS” dari kacamata pedagang kecil
Akan tetapi di sisi lain, coba kita lihat dari kacamata pedagang kecil. Sebut saja Ibu Valen yang sudah 20 tahun jualan pecel lele di pinggir jalan. Baginya, uang adalah lembaran kertas yang dia terima dari pelanggan, lalu detik itu juga dia pakai buat beli bahan baku ke pasar besok pagi. Uang adalah sesuatu yang berputar cepat, tunai, dan nyata.
Lalu datanglah teknologi QRIS ini. Ibu Valen mungkin tertarik, tapi dia bingung.
Pertama, dia harus punya smartphone. Oke, mungkin dia punya. Tapi smartphone itu harus terkoneksi internet. Kedua, dia harus daftar ke bank atau penyedia layanan. Itu butuh KTP, NPWP, dan serangkaian birokrasi yang mungkin bikin pusing. Ketiga, dan ini yang paling krusial, ada yang namanya MDR atau Merchant Discount Rate.
Bayangkan, Ibu Valen jual pecel lele Rp20 ribu. Kalau ada yang bayar pakai QRIS, uang yang masuk ke rekeningnya mungkin nggak utuh Rp20 ribu. Ada potongan sekian persen. Buat perusahaan besar, potongan itu receh. Tapi buat Ibu Valen yang untungnya mungkin cuma Rp3 ribu per porsi, potongan itu adalah harga bawang merah yang bisa dia beli.
Belum lagi soal pencairan dana. Uang yang di-scan hari ini, nggak selalu langsung masuk hari ini juga. Kadang butuh H+1. Lha, Ibu Valen mau belanja ke pasar subuh subuh pakai apa? Pakai screenshot transaksi berhasil? Tentu tidak, Ferguso. Tukang sayur di pasar maunya uang tunai yang bisa langsung dipakai beli bensin motor.
Maka, terjadilah perang batin. Warung warung dan toko toko kecil ini berada di persimpangan jalan yang dilematis. Mereka dipaksa beradaptasi oleh tuntutan Gen Z yang makin hari makin cashless. Tapi di saat yang sama, ekosistem digital ini belum sepenuhnya ramah sama model bisnis mereka yang butuh perputaran uang super cepat.
Tidak menyediakan opsi pembayaran QRIS = kuno
Gen Z menuntut kemudahan tanpa mau tahu keribetan di baliknya. Mereka cuma tahu scan, saldo terpotong, dan urusan selesai. Mereka nggak peduli soal MDR, soal H+1, soal Ibu Valen yang harus belajar internet banking di usia senja.
Akibatnya apa? Warung yang menolak menyediakan QRIS akan dicap kuno, ketinggalan zaman, dan nggak customer friendly. Mereka harus rela kehilangan segmen pasar yang paling konsumtif ini. Mereka harus pasrah ketika warung sebelah yang baru buka kemarin sore, yang jualannya biasa aja tapi udah pasang QRIS, tiba tiba lebih ramai.
Ini adalah sebuah evolusi paksa. Sebuah modernisasi yang didorong bukan oleh kesadaran si pemilik usaha, tapi oleh kemalasan kolektif konsumennya.
Pada akhirnya, suka atau tidak suka, uang tunai memang sedang menuju senjakalanya. Warung atau toko yang bersikeras hanya menerima cash mungkin masih bisa bertahan, tapi mereka akan berjuang sendirian di tengah gempuran zaman. Mereka harus menyediakan alternatif selain cash, bukan karena mereka mau, tapi karena mereka harus.
Karena di dunia yang serba digital ini, yang paling menakutkan bagi sebuah usaha bukanlah rugi. Yang paling menakutkan adalah menjadi tidak relevan. Dan paksaan untuk menyediakan QRIS, adalah cara paling brutal dari zaman ini untuk bilang, “Berubah, atau kamu selesai.”
Penulis: Rendi
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA 3 Hal Merepotkan di Balik Pembayaran QRIS yang Nggak Disadari Banyak Orang.