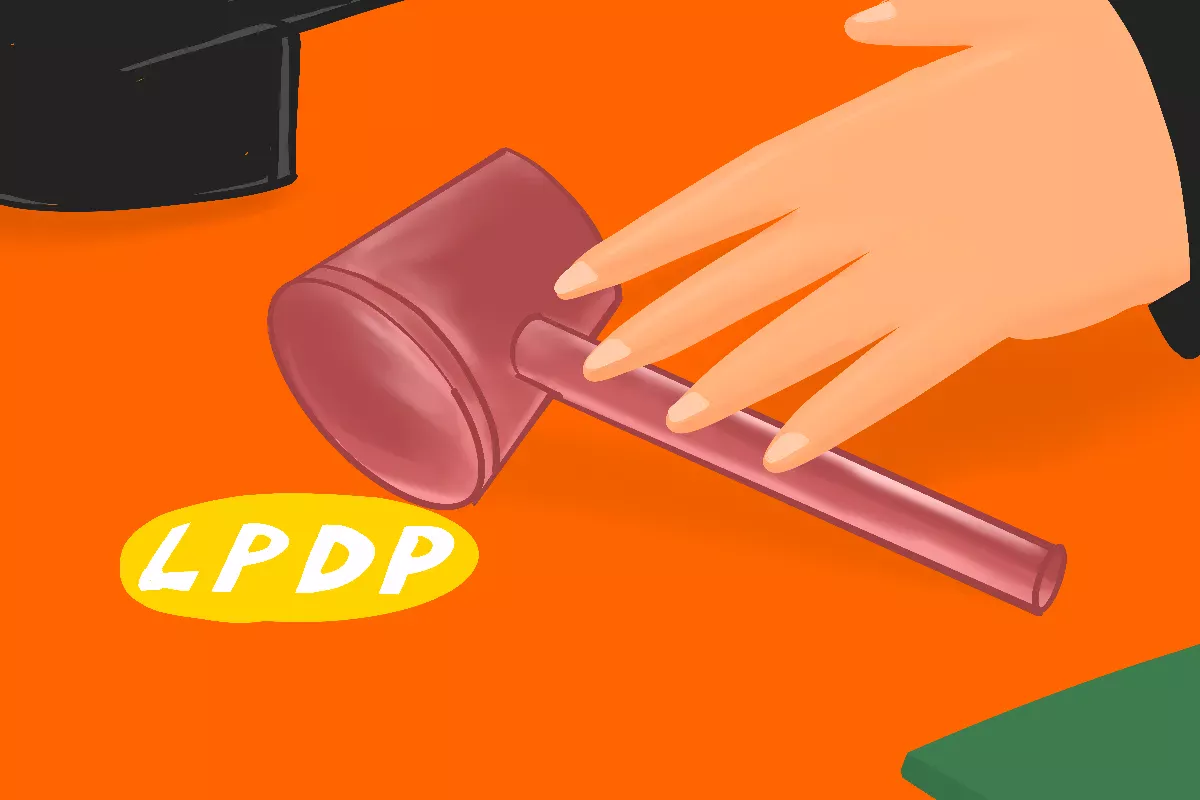“Dan terjadi lagi, kisah lama yang terulang kembali”
Potongan lirik lagu dari band Noah itu tampaknya sangat cocok untuk menggambarkan nasib Paris Saint-Germain sekarang. Lagi dan lagi, klub asal Paris itu harus terpongkeng di UEFA Champions League. Pada laga yang berlangsung dini hari tadi, Leo Messi dkk. mesti rela dipecundangi Bayern Munich dengan skor 2-0, atau 3-0 secara agregat. Kekalahan itu otomatis membuat impian mereka untuk merengkuh Si Kuping Besar harus kembali kandas.
Setelah pertandingan usai, satu hal yang seketika terpikir adalah PSG sepertinya memang tidak ditakdirkan untuk juara UCL.
Ya, tak peduli seberapa banyak uang yang mereka kucurkan untuk merekrut pemain bintang; tak peduli seberapa sering mereka bergonta-ganti pelatih, hasil akhirnya selalu sama: PSG selalu tumbang di UCL. Musim ini oleh Bayern Munich. Sebelumnya oleh Real Madrid. Lalu sebelumnya lagi oleh Manchester City. Dan masih banyak momen-momen eliminasi menyakitkan lainnya di musim-musim sebelumnya.
Di Champions League, nasib tim yang bermarkas di Stade de France itu tak berbeda jauh dengan Barcelona. Di kompetisi domestik, mereka boleh tampil begitu superior. Namun, ketika mereka mesti berhadapan dengan klub-klub tangguh dari negara lain, segala kehebatan itu seketika sirna.
Dalam kasus PSG, saya dapat mengidentifikasi beberapa faktor yang membuat mereka terus bernasib nahas di UCL. Beberapa faktor ini, jika tak kunjung dibenahi, akan selalu menjadi batu sandungan mereka dalam meraih kejayaan di kompetisi tersebut. Jadi, apa sajakah faktor-faktor yang saya maksud?
Skuad mahal tak selalu berdampak baik
Dalam sekitar satu dekade terakhir, PSG selalu menjadi salah satu tim dengan skuad terbaik di dunia. Hal itu tentu tak lepas dari faktor “uang Arab” yang mereka dapatkan dari sang pemilik klub. Dengan kucuran dana yang seperti tak ada batasnya itu, mereka dapat memboyong deretan pemain bintang yang diharapkan dapat memberikan banyak prestasi bagi klub. Namun, apakah iya seperti itu?
Seperti yang tadi saya katakan, di liga domestik, PSG memang mampu tampil digdaya. Akan tetapi, ketika tiba saatnya berkompetisi di UCL, uang dan kumpulan superstar saja tidak cukup untuk membuat mereka menjadi kampiun. Tak peduli mau lini depan mereka dihuni oleh Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar Jr., cita-cita untuk mengangkat trofi UCL masih saja belum dapat direalisasikan.
Lagi pula, skuad mahal memang justru dapat menjadi bumerang tersendiri. Para pemain bintang selalu ingin menjadi bintang; mereka ingin selalu menjadi pusat perhatian dibandingkan penggawa-penggawa lainnya. Maka dari itu, tak usah heran jika melihat performa PSG dalam beberapa musim terakhir seperti tidak begitu kompak; seperti klub yang diisi oleh sebelas pemain bergaji selangit, tetapi terlihat ogah-ogahan untuk bekerja sama sebagai tim.
UCL yang amat kejam
Jika hanya mengandalkan keahlian individu saja, hal itu takkan cukup untuk membuat sebuah tim keluar sebagai juara dari kompetisi sekaliber UCL. Dan itulah yang selalu terjadi pada PSG, bukan?
Selain itu, saya juga selalu memandang Champions League sebagai sebuah ajang yang kejam. Di sana, tim terbaik belum otomatis akan keluar sebagai pemenang. Begitu pun tim dengan skuad paling mewah. Tanpa adanya keberuntungan, langkah mereka akan selalu terhenti sebelum sampai di puncak. Terkadang, tim yang memenangi UCL adalah tim yang paling beruntung, bukan tim yang paling superior dan mempertontonkan sepak bola ciamik.
Atau, sehebat apa pun permainanmu, sejago apa pemainmu, ujung-ujungnya Real Madrid yang jadi juara.
Sekali lagi, UCL adalah kompetisi penuh kekejaman, penuh hasil yang tak adil. Dan menurut saya, Paris Saint-Germain merupakan salah satu tim yang paling sering merasakan kekejaman dan ketidakadilan itu.
Pelatih yang tidak tahu cara mempersatukan bintang
Di musim ini, jabatan juru taktik PSG dipegang oleh Christophe Galtier, pelatih yang sebelumnya sukses membuat Lille menjadi juara Ligue I musim 2020/2021. Prestasi itu lantas membuat manajemen PSG kepincut dengan sang pelatih, lantas memutuskan untuk merekrutnya guna menukangi tim yang identik dengan warna biru itu.
Ketika di Lille, Galtier terbiasa memberikan instruksi kepada pemain-pemain yang statusnya bukanlah superstar. Oleh sebab itu, para penggawa tersebut otomatis cenderung akan mudah untuk diatur dan lebih “nurut” dengan kehendak sang pelatih. Namun, di PSG, yang terjadi adalah suatu hal yang sangat berbeda. Pria 56 tahun itu mesti memberikan arahan kepada Neymar, Mbappe, Messi, Marco Verratti, Sergio Ramos, dan nama-nama besar lainnya. Ketahuilah, bukan tugas yang mudah untuk dapat mempersatukan mereka semua agar mau “nurut”.
Bagi saya, hal ini menjadi salah satu faktor tersendiri mengapa Galtier belum bisa membuat PSG-nya tampil seimpresif Lille di era kepelatihannya. Di satu sisi, ia memang dibekali dengan skuad menawan dan para pemain yang “sudah jago dari sononya”. Namun, di sisi lain, para pemain tersebut barang tentu menyadari bahwa mereka sudah jago, sehingga mungkin akan lebih bandel untuk mau menuruti segala macam perintah ribet yang diberikan.
Andai saja Galtier mampu mempersatukan mereka, saya yakin hasilnya akan seperti yang diraih oleh Zinedine Zidane dan Carlo Ancelotti di Real Madrid. Dengan bimbingan yang tepat, sebuah skuad yang dihuni oleh banyak superstar pasti akan menjelma tim tangguh yang sulit dikalahkan. Tengok saja El Real yang mampu meraih banyak prestasi bergengsi selama dilatih oleh dua manajer tersebut. Apa rahasia di balik kejayaan tersebut? Ya, apa lagi kalau bukan kepiawaian sang pelatih dalam mempersatukan bintang-bintangnya. Saya rasa, kemampuan itu masih belum dimiliki oleh Christophe Galtier saat ini.
PSG memang tidak sehebat itu
Faktor terakhir yang saya pikir menjadi alasan mengapa Paris Saint-Germain selalu bernasib apes di UCL adalah kenyataan bahwa PSG memang tidak sehebat itu. Kasus ini kurang lebih sama seperti ungkapan “Di atas langit masih ada langit”. Dengan kata lain, PSG memang tim hebat, tetapi masih banyak tim yang lebih hebat lagi di atas mereka. Entah itu Real Madrid, Manchester City, ataupun Bayern Munich yang baru saja membuktikannya beberapa jam lalu.
Jika inilah yang sesungguhnya terjadi, kekalahan PSG di UCL haruslah diterima dengan lapang dada. Akui saja fakta bahwa masih ada klub lain yang performanya lebih baik, taktiknya lebih ciamik, dan permainannya lebih efektif. Maka dari itu, yang perlu PSG lakukan adalah berbenah; meningkatkan kualitas tim agar bisa menjadi lebih baik lagi agar kelak bisa menjadi kampiun di UCL.
Namun, itu masih kelak, loh, ya. Untuk sekarang, saya masih percaya pada perkataan saya di awal: “PSG sepertinya memang tidak ditakdirkan untuk juara UCL”.
Jadi, untuk setiap fans PSG, yang sabar, ya. Jangan lupa makan, nanti sakit, loh. Hehehe.
Penulis: Bintang Ramadhana Andyanto
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Leonardo, Pelawak Arogan dari Paris