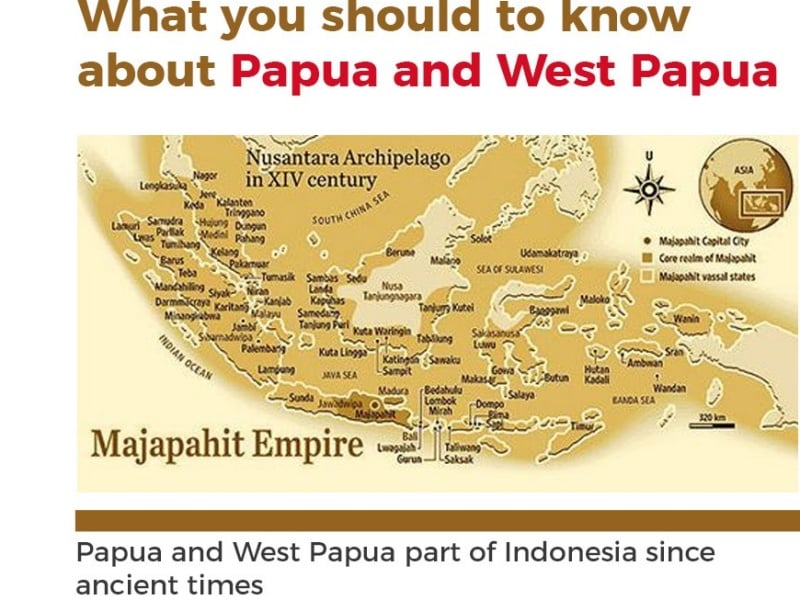Bicara soal Papua hari ini sungguh harus hati-hati. Jika perlu berbisik selemah mungkin, agar hati kita saja yang mendengar.
Tragedi kemanusian terlanjur terjadi. Darah anak negeri tumpah sudah. Serangkaian kerusuhan yang mematikan seharusnya sudah lebih dari cukup menyadarkan kita untuk segera duduk bersama, gunakakan bahasa santun, tanggalkan emosi, dan hancurkan egoisme!
Sedikit mengenang masa lalu…
Saya pernah diberi kesempatan beberapa kali pergi ke Papua. Di satu kesempatan saya ngobrol panjang lebar dengan Erik Sarkol, kurator museum Asmat di Agats. Dari mulai hilangnya Michael Rockefeller saat ekspedisi di Papua hingga soal spirit dalam ukiran Asmat.
Sekali saya bertanya hal yang mengendap lama di pikiran soal perangai orang Papua.
“Pak Erik, saya sebenarnya takjub dengan kesantunan orang Papua. Maaf, hal yang sebelumnya justru saya ragukan dapat saya temui”
Beliau mengulum senyum dan sempat terhenti lama.
“Para misionaris yang membuat kami bisa demikian. Mereka yang mengajari kami dari mulai bahasa hingga soal yang remeh, menyapa jika berpapasan”
Memang betul demikian adanya. Di keremangan malam dan di antar derit papan kayu yang menghubungkan jalan-jalan di atas rawa tersebut saya kerap kaget.
“Selamat malam, Bapak”
Kalau anak kecil atau remaja, biasa mereka hanya mengucapkan selamat malam saja.
Saya pendatang baru. Kami tidak saling mengenal, tetapi mereka lebih dahulu menyapa, tanpa menyelidik siapa saya ini dan apa maksudnya “berkeliaran” di Asmat.
Sikap ‘seandap asor’, berusaha menyapa lebih dulu tersebut terus terang tidak banyak saya temui di wilayah lain di Endonesa. Ini bukan glorifikasi hanya menggambarkan bagaimana mereka sebenarnya terbuka dengan pendatang.
Beberapa bulan ini situasinya sudah lain. Di Papua, salah satu pulau terbesar di dunia, beberapa daeeah seperti menjadi ladang pembantaian. Darah sudah tumpah antara aparat dengan penduduk, penduduk dengan penduduk.
Narasinya akan menjadi lain kalo kita hanya mengabarkan penduduk yang tewas tapi tidak menyebut aparat yang tewas. Penduduk pun mulai coba dibedakan mana yang asli, mana yang pendatang.
Apakah yang akan kita narasikan sekarang setelah menyebut pendatang vs penduduk, konflik sektarian atau antar ras? Tidak bisakah kita menyebut mereka ini semua sebagai korban?
Tragedi ini menjadi semakin sulit diatasi kalau kita marah karena ada sekeluarga Minang yang terbunuh, rumit kalau kita menyebut ada seorang dokter yang rela meninggalkan keluarga di Jogja demi tugas kemanusian. Dalam situasi seperti ini, semua bisa terbunuh.
Belum orang yang marah berdasarkan kesamaan profesi. Marah karena Pak Soeko yang dari Jogja tersebut seorang dokter, marah karena ada aparat yang menjalankan tugas negara terbunuh.
Kalau ada yang melaporkan kejadian rusuh bagaimana? Tergantung dari sisi apa kita memandang. Seringkali orang menganggap bahwa penyampai informasi kerusuhan identik dengan provokator.
Tambah rumit lagi kemudian ada kontra narasinya, “ternyata yang meninggal aparat, bukan mahasiswa”. Aparat atau penduduk kalau urusan nyawa sama berharganya!Ya, termasuk kalau dia membawa bendera OPM sekali pun. Nyawa tetap sama berharganya!
Saya terus terang kecewa kalau ada institusi yang menyebut, “dari 26 korban tewas, 22 di antaranya merupakan pendatang”. Itu belajar komunikasinya di mana?
Katanya NKRI harga mati? Kita ada di manapun di wilayah negeri ini tetap orang endonesa, bukan asli dan pendatang. Mari kita belajar sejarah peradaban manusia, kita semua ini pendatang. Intinya, kita semua ini adalah korban. Kita semua ini sudah rugi menjalani kesia-siaan ini. (*)
BACA JUGA Kerusuhan di Papua: Mau Nyalahin Siapa? atau tulisan Haryo Setyo Wibowo lainnya. Follow Facebook Haryo Setyo Wibowo.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.