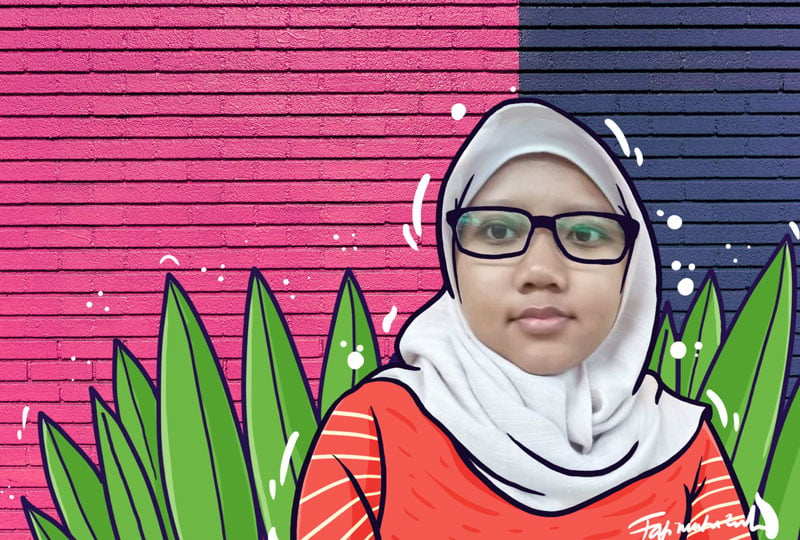Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini kemarin, tapi kok ya takut di bilang Jawasentris—penganut orba—dan tidak mau mengakui sosok pahlawan lain yang lebih berdarah-darah (secara fisik) memperjuangkan tanah dan air seperti Keumalahayati yang non-Jawa. Namun saat ingin mengakui laksamana perempuan (Islam pula) Aceh satu ini, saya kok takut dikira pro dengan GAM—dengan para penanam ganja—juga dengan daerah yang dipenuhi praktek Syariat Islam sebagai hukum bersosial.
Namun reputasi beliau tidak bisa dilupakan, apalagi saat menang duel di geladak kapal dengan Cornelis de Houtman, seorang pimpinan Belanda dibunuh dengan rencong di tangannya—juga di saat yang sama telah mengakomodir para perempuan. Keumalahayati atau biasa disebut Laksamana Malahayati, pemimpin para janda yang tangguh. Ia perempuan yang pernah mengenyam pendidikan militer jurusan Angkatan Laut di Baitul Maqdis. Lalu peristiwa Teluk Haru yang berdarah-darah merebut suaminya yang tumbang dalam pertahanan, ia dengan segala ketersiksaan sebagai janda bersama ibu-ibu lainnya menyusun barisan dan melawan.
Juga beberapa tahun lalu, seorang ibu-ibu paruh baya bernama Ibu Patmi meninggal saat membela tanah Kendeng. Bu Patmi melawan seperti ledakan emosi Malahayati dengan cara yang begitu lain, perlawanan yang semenjana, sangat dramatik sebagai sebuah performance art saat menyemen kakinya berhari-hari, dan sekarang telah menjadi mendiang.
Kutarik kesimpulan sementara, perempuan-perempuan itu selalu punya cara untuk melawan. Dan sudah seharusnya perempuan tidak punya persentase lebih tinggi di dapur, kamar, sumur daripada laki-laki.
Namun, bagaimana hari ini mengukur emansipasi, dan seperti apa kesataraan ruang publik bagi perempuan yang dibutuhkan? Karena beberapa tahun lalu saya bertanya kepada teman-teman perempuan saya sebelum debat antar fakultas di salah satu kampus jogja: bagaimana pendapat kalian bila seorang pemimpin itu perempuan? Jawab mereka ringan, seperti ingin mengulang penjelasan yang sudah ada bahwa bumi harus diurus kholifah, artinya jika selama ada laki-laki kenapa mesti perempuan yang memimpin.
Maksud saya bagaimana mengukur kesetaraan atau kebebasan perempuan jika dalam diri mereka sendiri bermasalah? Semua begitu adanya karena laki-laki bung! Makanya perempuan begitu. Laki-laki patut disalahkan, karena mereka semua bagian dari ketertindasan perempuan—ungkap salah satu kawan yang mendaku dirinya seorang Feminis.
Lalu saya tidak mau komentar-komentar lagi, biarlah perempuan menemukan cara melawan sendiri jika sudah begitu. Tapi saya melihat isapan jempol nama Kartini dalam setiap perhelatan negara. Artinya bukan masyarakat yang membutuhkan Kartini, melainkan negara ingin menjejali pengetahuan dan ingin berkata ini lo tokoh perempuan jawa yang melawan dengan keinginan kuat agar perempuan berdaya dan mampu ikut serta memikirkan tanah dan air yang di injak-injak para penjajah.
Hari ini, di kota-kota besar semakin menunjukkan ruang bebas bagi perempuan. Bahkan “gegar budaya” yang dirasakan oleh Ben Anderson saat pertama kali di Jakarta sudah lain. Ia dulu berkata “mengapa perempuan harus rumit mengurus izin keluar saat malam hari, dibanding seorang anak laki-laki?” dan saya terus membaca Hidup di Luar Tempurung karya si Om Ben, dan diwaktu yang sama ibu saya melarang anak—anak perempuannya kuliah jauh-jauh. Kalaupun jauh, harus jelas yang akan menjaganya! Kalo anak laki-laki terserah. Ibu minta khusus anak perempuan biar ibu yang menentukan. Aku dan saudara-saudara yang lain diam dan tak mampu mengatakan dunia sudah berubah dari zaman yang ibu rasakan.
Namun bila kembali menelusuri jejak si Laksamana perempuan pertama, apakah sikap patriotisme Malahayati tumbuh seperti Gayatri yang juga harus meneruskan kerajaan yang baru berdiri saat Raden Wijaya mendiang? Kami sebagai generasi millenial mendapati kesulitan untuk mendapati beberapa buku tentang kedua tokoh ini. Singkatnya, tidak mudah mendapatkan data biografi mereka.
Tapi di kesempatan lain, saat saya selo, ada berita yang dilansir oleh kumparan bahwa akan ada film Malahayati, di produseri oleh Marcella Zalianty dan itu juga diinisiasi oleh Jendral Gatot. Jangan-jangan ini akan menggunakan narasi dari data tentara juga, pikirku. Tapi bukan itu yang perlu disorot terlebih dahulu, melainkan niat mulia para sineas untuk mengetengahkan cerita seorang perempuan yang memimpin para janda. Bukan kumpul-kumpul arisan macam istri para tentara, dokter, pengacara, yang secara nilai juang jauh panggang dari api. Juga tokoh fiktif Nyai Ontosoroh yang memiliki jiwa perlawanan, tertera kegitiran perlawanannya dalam dialog ending novel Bumi Manusia yang sekarang juga sedang masuk dapur film. Semoga tidak seperti film Kartini yang diperankan mbak Dian Sastro garapan Pakde Hanung, hehehehe.
Kemudian saya coba cari-cari informasi lanjutan di YuoTube, namun yang ada masih Marcella membaca puisi berjudul “Malahayati atau Perempuan Penjaga Purnama” meskipun sementara ini tidak santer di pembahasan media daring. Yang tersisa hanyalah pengangkatan kepahlawanan untuk Laksamana Malahayati oleh Jokowi beberapa tahun silam. Dan Sinema seperti yang diulas oleh Ariel Haryanto dalam buku Kenikmatan dan Identitas memiliki pengaruh untuk kalangan masyarakat menengah.
Lalu bagaimana kita menyentuh lapisan terbawah masyarakat? Haruskah semurah Dilan 1990 seri pertama yang begitu membekas di anak-anak muda? Atau kita mengambil sekaligus meyakini semangat atau spirit yang dikatakan Nadine Labaki dalam wawancaranya di The Guardian.
“Saya sangat percaya, sinema dapat memberikan efek sosia.” begitu tegas yang dikatakan perempuan kelahiran Lebanon pasca film Capernaum (2018) menjadi pembahasan tingkat internasional di berbagai festival film dan dapat memberikan dampak positif di Lebanon.
Selain itu mari terus menjaring data, apapun bentuknya, tentang perempuan-perempuan yang tak pantas dilupakan secara gerakan dan semangat perlawannya untuk berpartisipasi dalam segala hal kehidupan. Seperti Malahayati yang mengobarkan semangat para janda di kapal “Inong Bale” dari segala ketertindasan menjadi nyala perlawanan. Dan jika kita para lelaki hanya berpikir perempuan harus pandai meracik bumbu, menjemur baju, dan trengginas di ranjang, maka kapan lagi kita persilahkan mereka untuk memimpin armada bak Malahayati atau bagai Ibu Patmi yang menyemen kakinya berhari-hari.