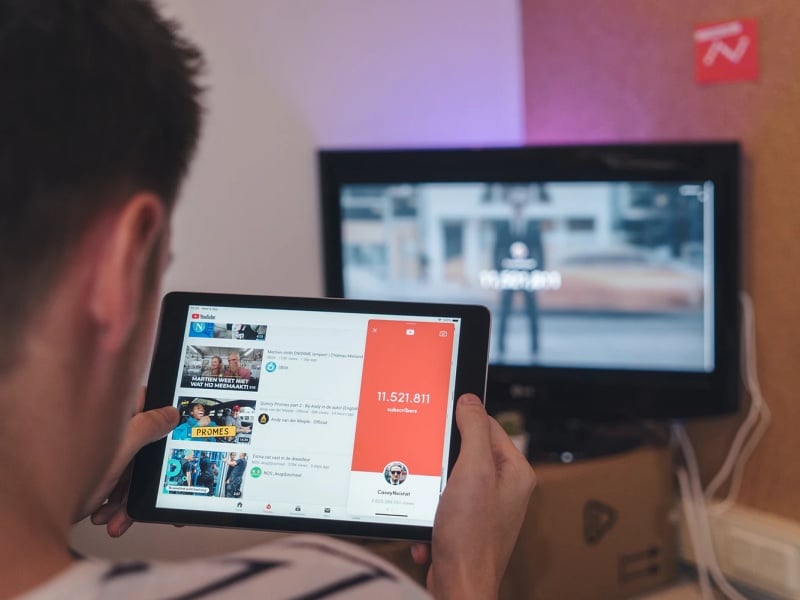Kematian. Ketika seseorang mati lalu meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, orang-orang terdekatnya akan didera kesedihan. Namun, di balik kematian, ada sebuah tradisi panjang khususnya di Jawa Barat yang mengharuskan keluarga jenazah memberikan “amplop” atau uang yang sudah dipatok harganya kepada orang-orang yang mengurus tetek-bengek prosesi jenazah itu.
Dari mulai orang yang memandikan, mengafani, menyalatkan, hingga menguburkan: semua ada rentang harganya (yang disepakati secara tidak tertulis). Bagi keluarga jenazah yang berada, ini bukanlah suatu masalah. Namun, bagaimana jika keluarga jenazah tersebut tak mampu untuk membayarnya? Inilah yang coba dikisahkan sebuah film pendek berjudul Ngiring Belasungkawa (The Envelope of Grief).
Film besutan Pradipta Blifa yang saya tonton di pemutaran daring Jogja-NETPAC Asian Film Fest 2021 di KlikFilm ini sukses membikin saya mempertanyakan kembali tradisi tersebut. Tentu saja karena di kampung tempat saya tinggal, tradisi seperti ini kadang masih berlaku.
Bagi orang Sunda, dari judulnya saja sudah ketahuan bahwa film pendek ini berlatar di Jawa Barat. Bagi orang Sunda juga (kayak saya), film ini akan terasa akrab karena merepresentasikan suatu tradisi turun temurun yang sampai sekarang masih eksis, apalagi percakapan di dalamnya memang menggunakan bahasa Sunda.
Film dibuka dengan adegan Euis, sang anak perempuan yang sedang menangis dipelukan uaknya karena sang ayah baru saja meninggal. Alih-alih mendoakan ayahnya dengan khusyuk, Euis justru kebingungan karena ternyata ia harus memberikan sejumlah uang serta fidyah yang sudah dipatok di kampungnya. Nominalnya mencapai jutaan. Bagi keluarga yang tak berkecukupan seperti Euis, jelas hal ini sangat memberatkan.
Saya jadi teringat momen-momen ketika menyalatkan jenazah di kampung. Ketika saya salat jenazah di kampung, saya memang kerap mendapat amplop. Saya pikir, hal ini merupakan sesuatu yang lumrah. Berkali-kali saya mendapat amplop atas “ibadah” yang saya lakukan. Lama-kelamaan, saya merasa ada yang mengganjal dari praktik seperti ini: semuanya menjadi serba materialistik. Dalam tradisi ini, relasi antara orang yang melakukan prosesi jenazah dengan keluarga jenazah tak ubahnya relasi antara penyedia jasa dan konsumen. Padahal dalam Islam, hukum mengurusi jenazah adalah fardhu kifayah alias wajib.
Terkadang, saya melihat bahwa ada beberapa orang di kampung saya yang ikut menyalatkan jenazah bukan karena ikhlas, melainkan karena tahu bahwa nanti bakal diberi uang, terutama anak-anak. Pertanyaan lainnya, bagaimana jika keluarga-keluarga jenazah di kampung saya kemampuan ekonominya kurang? Mereka yang untuk makan sehari-hari saja sudah kesusahan?
Dalam film Ngiring Belasungkawa, Euis terpaksa harus meminjam uang kepada tetangga almarhum ayahnya untuk honorarium mereka yang membantu proses prosesi jenazah. Euis pada awalnya sempat menolak dan memberi tahu uaknya agar memberikan uang semampu mereka saja. Namun, uaknya menolak dengan alasan tak ingin “dibicarakan” orang sekampung karena tidak menjalankan tradisi tersebut.
Saya bertanya-tanya, apakah orang di kampung saya juga setega demikian? Keluarga jenazah yang harusnya di-support, diringankan bebannya, dibiarkan agar khusyuk mendoakan jenazah, justru malah disandera oleh tradisi mengakar yang sangat tak masuk akal ini? Memang sih tak ada yang salah dengan memberikan sejumlah uang pada orang-orang yang sudah membantu. Namun, ya semampunya aja.
Film pendek Ngiring Belasungkawa ini mengajak masyarakat di Jawa Barat untuk mulai berpikir kritis. Untuk apa tradisi ini dijalankan? Mengapa tradisi ini mesti dilestarikan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu hanya lontaran retoris semata. Akan tetapi, saya harap, dengan kemunculan film pendek ini, masyarakat Jabar bisa lebih aware betapa “tradisi” bisa membuat orang menderita dua kali lipat. Sudah mah keluarganya meninggal, eh malah ditambah lagi dengan keharusan menjalankan tradisi yang di luar kemampuan mereka.
Sumber Gambar: Viddsee