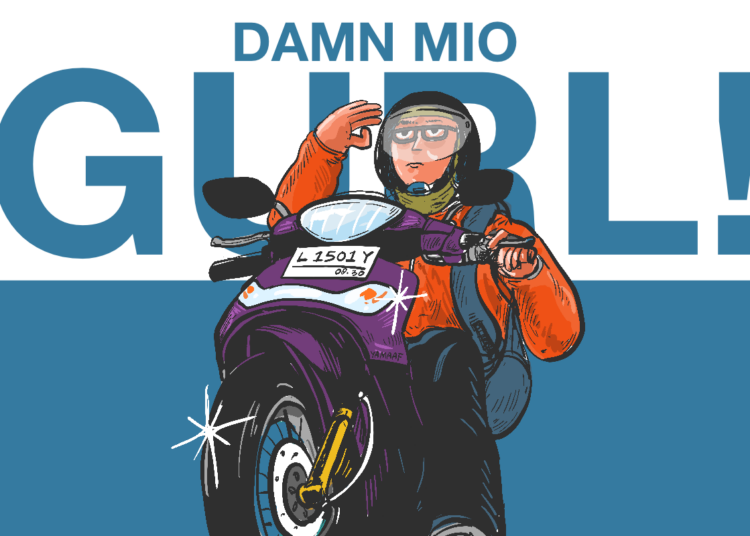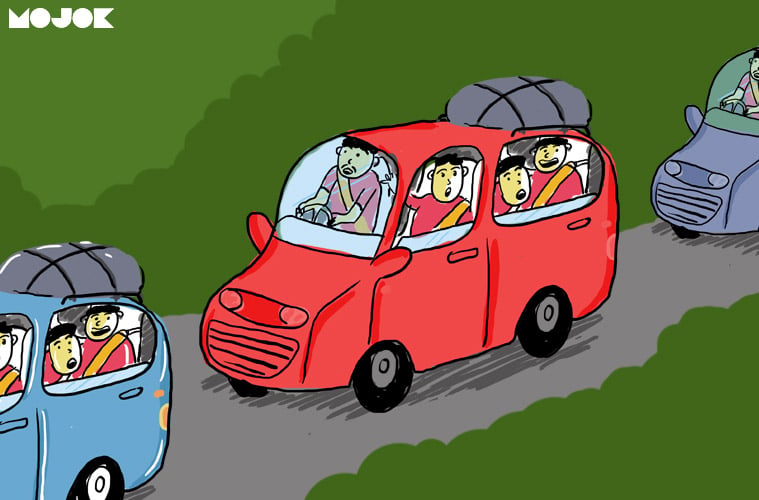Saya mengamati banyak orang memposisikan dirinya seolah ia adalah orang terpenting sedunia. Seolah-olah jika tanpa kehadirannya, maka dunia ini akan kacau balau. Lantaran itu, ia pun tak pernah mau absen untuk berpendapat perihal apa saja.
Ketika ada permasalahan agama, ia angkat bicara; lagi ngomongin politik, ia turut berpendapat; ada kisruh sepakbola, ia juga tak tinggal diam; ada gosip artis, ia ngoceh. Pokoknya apa saja topik yang sedang ngehits, ia akan ambil bagian.
Masalahnya, orang tersebut adalah manusia biasa. Ia bukan sejenis manusia super yang dianugerahi kemampuan sanggup memahami apa pun. Ia juga bukan seorang nabi yang menerima wahyu. Seperti kita, ia hanya manusia biasa dengan segala keterbatasannya.
Seharusnya setiap orang menyadari keterbatasannya masing-masing. Ada banyak hal yang tak bisa kita terabas, sehebat apa pun kita. Kita mungkin seorang doktor dalam bidang agama, tapi bukan berarti ketika ada polemik seputar pertambangan, mesti ikut berpendapat seolah-olah ahlinya. Padahal tidak tahu apa-apa soal itu.
Saya menemui banyak sekali orang-orang semacam itu. Orang-orang yang hanya karena kepandaiannya dalam suatu hal, merasa boleh berpendapat dan ikut campur dalam segala persoalan.
Ada seorang ustaz lulusan Timur Tengah berbicara tentang sastra. Mengatakan bahwa membaca novel itu tidak ada manfaatnya. Lebih baik waktu digunakan untuk membaca al-quran dan mengkaji materi agama.
Pada satu titik, apa yang diucapkannya benar adanya. Namun—tanpa mengurangi penghormatan saya kepada sang ustaz—perkataannya itu terlalu naïf. Seringkali orang yang mengatakan “baca novel itu tidak ada gunanya” dan semacamnya adalah orang yang tidak pernah membaca novel atau pernah tapi yang dibacanya adalah novel berkualitas teruk.
Bagaimana mungkin membaca novel dikatakan tidak ada gunanya sedangkan dalam novel terkandung banyak sekali kisah yang dapat menambah kepekaan perasaan dan merangsang pikiran. Bagaimana mungkin membaca Max Havelaar dikatakan tidak bermanfaat, sedangkan novel itu menjadi salah satu buku yang menggerakkan para pejuang untuk berani melawan kezaliman penjajah.
Kesalahkaprahan sejenis juga menimpa orang-orang yang konon ahli sastra. Orang-orang yang sudah membaca dan menulis banyak buku sastra. Lalu, lantaran latar belakang tersebut, ia pun jadi berani berbicara mengenai apa saja. Sampai masalah tafsir alquran dan fikih pun dicampurinya juga. Padahal ia tak punya kapasitas untuk itu.
Ia mengujarkan pendapatnya dengan balutan kata-kata indah dan memesona. Padahal, kalau dilihat dari segi keilmuan tafsir dan fikih, kata-katanya tak lebih dari bualan orang pandir semata. Ia mungkin hebat dalam masalah sastra, tapi bukan berarti menjadi berhak bicara hal yang tak dipahaminya.
Kecuali ia seorang Buya Hamka. Orang yang ahli agama juga pandai masalah sastra (kendati mengenai poin kedua kita bisa berdebat panjang).
Daftar jenis orang yang suka membicarakan sesuatu yang bukan bidangnya bisa sangat panjang. Daftar tersebut akan terus bertambah panjang kalau orang-orang itu tidak juga sadar akan posisinya. Bahwa ia manusia yang punya batas dan bahwa “kebebasan berpendapat” adalah frasa yang harus dibincangkan lebih jauh.
Ada pepatah Arab yang cocok mengenai ini: “Kalau kau lihat ada seseorang yang bicara bukan pada bidangnya, niscaya kau akan melihat berbagai keajaiban keluar dari mulutnya.”
Memang ajaib betul orang-orang yang doyan ngomong sesuatu yang tak ia kuasai. Tepatnya, ngawur betul. Ia mungkin pakar dalam sebuah disiplin ilmu, tapi begitu dengan percaya dirinya ia ikut-ikutan ngomong dalam disiplin ilmu yang tak dikuasainya—hanya karena topik tersebut lagi viral, misalnya—maka yang bakal muncul dari mulutnya bukanlah ilmu, tapi kengawuran belaka.
Saya heran mengapa banyak sekali orang merasa harus berpendapat terhadap segala hal. Okelah kalau ia paham atau paling tidak tahu soal apa yang dibicarakannya tersebut. Masalahnya, dengan dalih kebebasan berpendapat, banyak sekali orang yang ngomong asal-asalan saja alias cuma memperbanyak populasi sampah di dunia ini.
Maka tak heran, ada anak muda yang sehari-hari hanya ngegame, berani bicara soal fatwa halal-haram. Atau pekerja yang sehari-harinya jauh dari buku, berani bicara soal masalah orang banyak. Atau seorang artis kemarin sore, dengan polosnya menyamakan sebuah karya sastra monumental dengan roman picisan murahan.
Semuanya tak lain karena mereka merasa harus berpendapat. Padahal, apa susahnya sih diam. Mengunci mulut agar tak mengucapkan selain sesuatu yang kita pahami. Lagi pula, apa pentingnya sih ucapan kita? Memangnya kita siapa, nabi? Nabi saja ketika ditanya soal sesuatu yang tidak beliau pahami bilang “antum a’lamu bi-umuuri dunyaakum” (kalian lebih tahu perihal urusan dunia kalian), kok. (*)