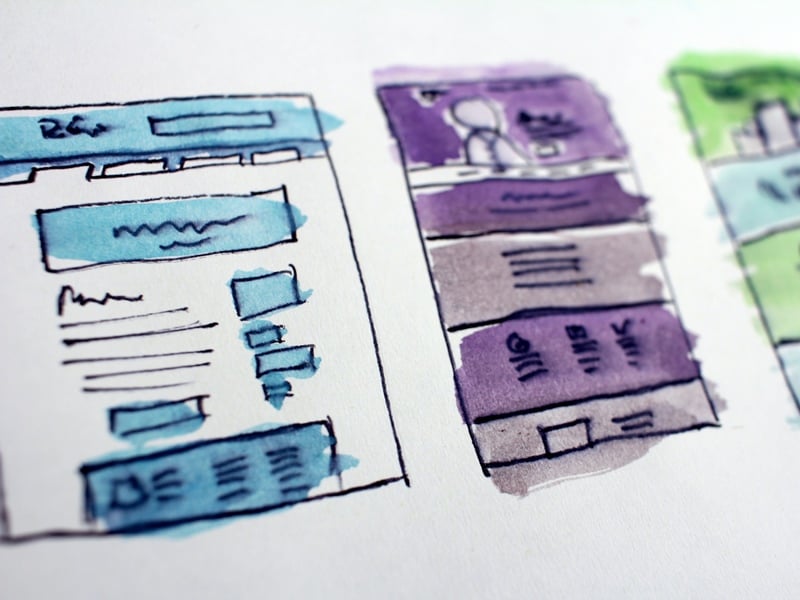Minggu ini adalah minggu terakhir pengisian nilai di Siakad, aplikasi layanan akademis mahasiswa di kampus saya mengabdi. Namun, baru akan mengisi nilai, saya mendapatkan kendala. Menu jurusan saya belum juga muncul di sana. Akhirnya, saya mencoba menghubungi sekretaris jurusan untuk segera menambah menu jurusan di akun Siakad saya. Sialnya, fitur centang biru miliknya dimatikan, pesan WhatsApp saya hanya centang dua pucat, dan tidak dibalas dalam tiga hari. Dan sampai sekarang, pesan itu masih misteri: apakah sudah dibaca atau belum sama sekali?
Jengkel, itulah yang saya rasakan kala itu. Pemaknaan macam-macam yang mengarah ke hal negatif tidak bisa saya halangi untuk muncul di benak saya. Ditambah dengan waktu yang sudah deadline menambah kegelisahan saya.
Saya tidak jengkel karena pesan saya hanya centang dua pucat. Saya hanya jengkel mengapa belum ada tanggapan hingga sekarang. Untunglah ada kontak lain yang bisa saya hubungi dan masalah saya selesai.
Di dunia yang lain, fitur centang biru dianggap meresahkan. Baru-baru ini, Mbak Ajeng Rizka dalam tulisannya yang berjudul “Mendebat Secara Profesional Kaum yang Mematikan Centang Biru WhatsApp” mengkritik keras orang-orang yang mematikan fitur centang biru ini. Blio menjelaskan, ini berbahaya untuk kepentingan bisnis dan beberapa kepentingan yang lain.
Jujur saja, saya termasuk orang-orang yang tidak mematikan fitur centang biru ini. Pasalnya menurut saya, centang biru hanyalah semata-mata fitur tambahan di era empat titik nol. Tidak kurang dan tidak lebih.
Begini, Mbak Ajeng Rizka, meskipun saya juga korban dari orang yang mematikan fitur centang biru itu karena banyak mahasiswa yang “tidak membaca” pesan WhatsApps saya. Namun, saya tetap membela mereka. Kali ini secara historis. Bukan profesional seperti yang Mbak Ajeng.
Kalau dirunut secara historis, kita baru bisa menikmati fitur centang biru di aplikasi BBM (BlackBerry Messenger) yang baru marak di era saya masih kuliah sekitar 2009. Sebelumnya, kita masih sangat menikmati fitur SMS yang masih berbayar tiap karakter satu rupiah hingga tiap pesan 350 rupiah.
Dalam fitur SMS yang kita nikmati bersama waktu itu, yang dengan itu saya menemukan jodoh, kita tidak mendapatkan fitur centang biru. Maksimal, kita hanya akan mendapatkan pesan pop up yang memberitahukan bahwa pesan yang kita layangkan sudah diterima oleh yang bersangkutan. Entah dibaca atau belum, kita tidak bisa tahu. Yang jelas, kita sudah merasa lega kala muncul kata “message sent” hingga “message delivered”.
Saya masih ingat betul manakala saya menyatakan cinta kepada pujaan hati. Sungguh, betapa berdebarnya hati saya ketika pesan saya itu sudah berstatus “delivered”. Ya, saya sama sekali tidak pernah memikirkan apakah pesan itu sudah dibaca atau belum. Yang jelas pesan itu sudah benar-benar masuk di gawainya.
Dari situlah, alasan orang-orang yang mematikan fitur centang biru saya temukan. Mereka adalah umat manusia secara historis merupakan “anak ideologis” dari kenyamanan ber-SMS. Di mana mereka tidak pernah merasakan betapa melegakannya fitur centang biru itu.
Hasil tempaan dan cobaan fitur SMS dalam rentang waktu yang cukup lama semestinya akan menjadikan generasi 80-an menyadari hingga mampu mengatakan “Alhamdulillah” ketika pesan yang dikirim hanya memperoleh dua centang. Dan rasa syukur inilah yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi, agar generasi sekarang tidak ahistoris memahami fitur debatable ini. Dan, bukankah ini juga sebuah momen untuk menempa rasa pasrah kita kepada Yang Maha Esa sekaligus sabar dan rasa syukur?
Jadi, untuk apa kita terlalu menuntut seseorang mengaktifkan centang birunya? Toh, nyatanya kita masih bisa hidup dengan baik ketika pesan tersebut sudah berstatus “terkirim”, bukan?
BACA JUGA 5 Alasan Orang Hide Story WhatsApp dan tulisan Ahmad Natsir lainnya.