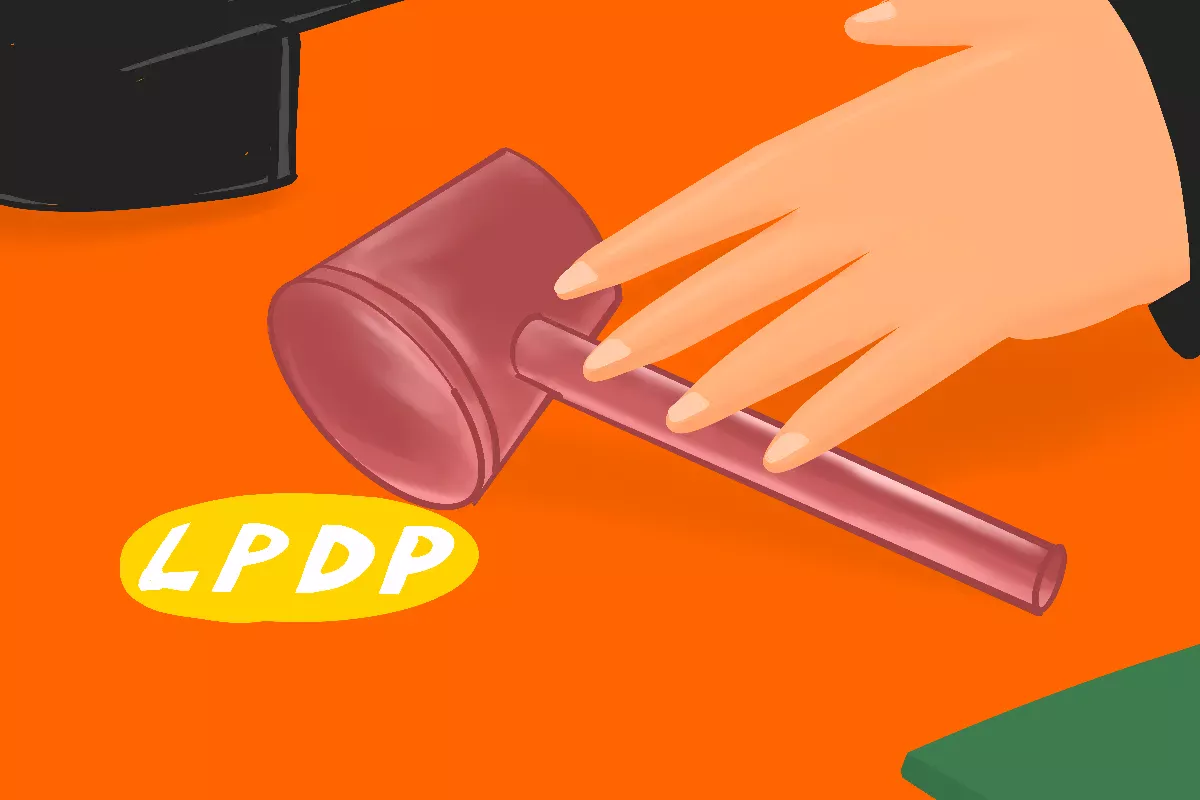Sektor pariwisata Jogja memang sedang terpukul karena pandemi. Tapi bukan berarti urusan pariwisata ini diam di tempat. Toh, selama pembatasan mobilitas saat Jogja kacau balau karena peningkatan kasus positif Covid-19, promosi pariwisata tetap berjalan penuh romantisasi.
Saya pribadi sudah kebal dengan model romantisasi Jogja. Biasanya seputar angkringan dan sopan santun masyarakatnya. Paling banter membahas makanan murah dan spot foto yang ngangenin. Namun, kali ini ada model promosi yang cukup nggatheli. Mungkin karena putus asa dengan situasi selama pandemi, atau kreativitas yang terlewat kebablasan.
Akhir-akhir ini, promosi pariwisata Jogja tengah gencar memainkan narasi cocoklogi. Yang dicocok-cocokkan adalah spot wisata daerah lain. Baik dari Jogja rasa Ubud, Jogja rasa Bali, Jogja rasa Santorini, sampai Jogja rasa Korea. Pokoknya, yang ada di Jogja dibuat rasa-rasa daerah lain yang dipandang lebih menarik.
Mungkin bisa kita maklumi bersama. Lantaran kalau Jogja rasa monarki, Jogja rasa UMR rendah, atau Jogja rasa klitih sudah biasa. Tanpa dipromosikan saja semua orang juga tahu hal tersebut. Apalagi Jogja kan memang terbuat dari UMR rendah, hotel penghisap air tanah, dan klitih, toh?
Namun, saya hanya mampu memaklumi sampai di situ saja. Soalnya, mau serasa-rasa apa pun, promosi model demikian itu memuakkan. Memasarkan spot wisata yang dimirip-miripkan daerah lain itu sudah menyedihkan. Apalagi dilakukan oleh daerah yang terkenal menyimpan potensi budaya dan wisata yang adiluhung.
Begini lho, Dab. Apakah Anda para pelaku usaha pariwisata mulai miskin ide? Atau memang tidak bisa kreatif di luar perkara mengepul uang wisatawan dan memperluas jurang ketimpangan? Memaksakan spot wisata dimirip-miripkan daerah lain itu seperti menunjukkan bahwa tidak ada potensi wisata di sana. Karena tanpa potensi, spot wisata tadi dipaksakan seperti spot wisata yang lebih populer. Ia jadi versi lite dari tempat yang lebih viral dan menarik.
Dari situ saja sudah kelihatan, industri pariwisata hanya peduli dengan uang pengunjung. Apa itu kearifan lokal dan budaya adiluhung. Kalau tidak laku dijual, ya akhirnya merombak potensi yang sudah ada demi minat pasar. Lalu akan dibawa ke mana potensi yang sudah turun temurun bertahan di daerah tadi? Ya, disingkirkan bersama masyarakat yang mengais-ngais remah-remah bisnis pariwisata demi menyambung hidup.
Dan yang kita bicarakan adalah Jogja. Jogja, kan, digadang-gadang sebagai daerah budaya dan penuh potensi keindahan alam. Jarang-jarang ada daerah yang bisa menyajikan wisata gunung dan pantai sekaligus. Belum lagi dengan eksotisme budaya Jawa yang sebenarnya makin tergusur. Jogja itu saingan berat Bali dan tidak pernah sepi dari wisatawan lokal maupun mancanegara.
Ya, kalau sekarang sepi, jelas karena penanganan pandemi yang amburadul. Tapi biar saja, kan kata Pak Gubernur, “Aku ra kuat ngragati.”
Sudah jelas, Jogja sudah laku sebagai tempat wisata. Lalu untuk apa dipaksakan menjadi mirip daerah lain? Kenapa Jogja harus punya rasa Ubud? Kenapa harus terasa seperti Korea? Apa Jogja memang minim potensi? Atau Jogja sudah kering karena eksploitasi wisata yang sama parahnya dengan penambangan pasir liar?
Ketika lini pariwisata sibuk mengeksploitasi Jogja, kearifan lokal akan menjadi seperti kembang tebu sing kabur kanginan. Terlepas dari akarnya dan terganti oleh panen raya para pemodal. Berlebihan? Mari silakan nikmati Jogja hari ini. Harga barang makin meroket, masyarakat tergusur dari lokasi wisata, dan budaya Jogja tinggal jadi pengisi buku siswa IPS.
Saya pikir sudah waktunya masyarakat Jogja melek situasi. Lantaran situasi hari ini tidak lebih dari penindasan terselubung terhadap kearifan dan kehidupan masyarakat lokal. Bumi yang dulu penuh unggah-ungguh dirudapaksa oleh spot selfie yang 3 bulan lagi menjadi sampah di Piyungan. Masyarakat yang dulu bisa mengusahakan tanah dan air dengan penuh senyum, kini terdesak oleh pemaksaan budaya luar karena rasa-rasa tadi.
Untung saja Jogja punya pegangan narimo ing pandum. Kalau tidak, nyinyiran masyarakat seperti saya sudah menjadi batu besar yang menghalangi konglomerasi pariwisata. Tapi apa lacur, terlalu banyak masyarakat yang memuja Jogja rasa-rasa ini. Bahkan mereka ikut dalam antrean wisatawan yang mementingkan feed Instagram daripada nasib manusia dan budaya yang tergusur itu sendiri.