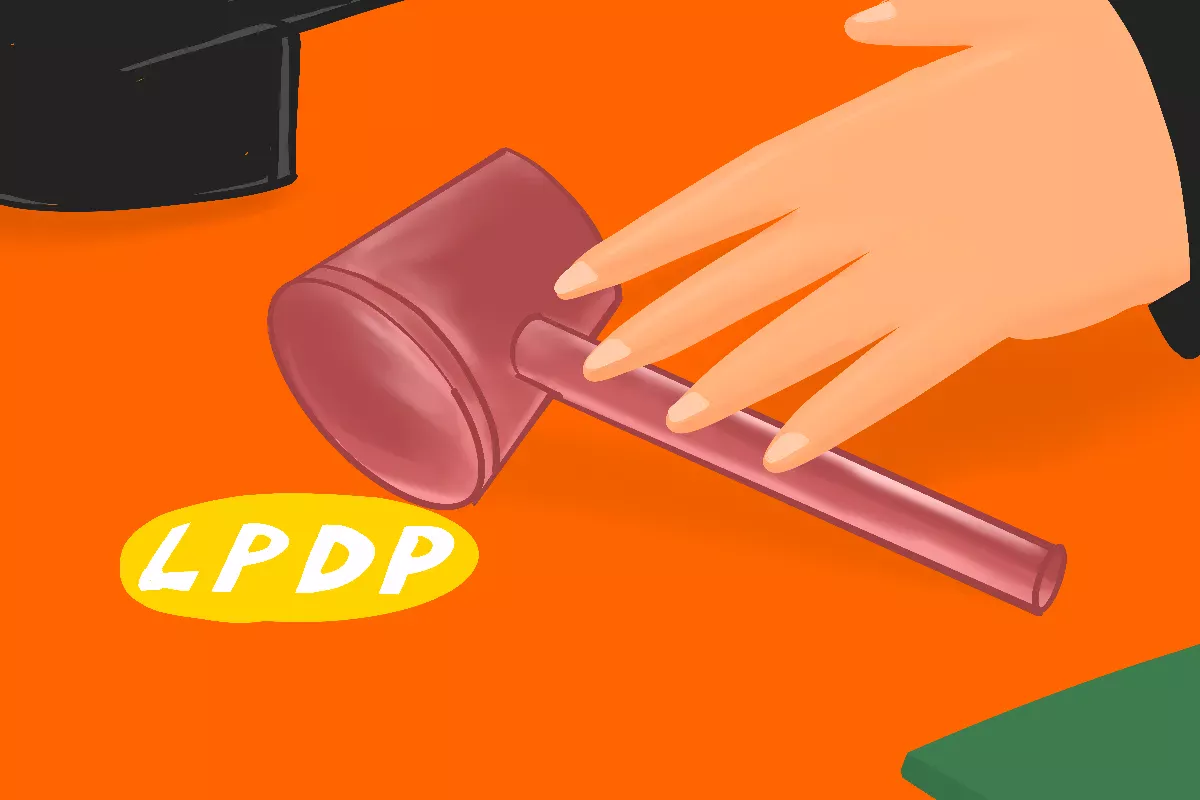Di kepala sebagian orang, pustakawan merupakan pekerjaan paling damai sedunia dengan gaji yang setara UMR kota. Duduk manis, ruangan ber-AC, dikelilingi buku, sesekali menegur pengunjung yang berisik. Tidak ada lembur, tidak ada tekanan. Beres jam operasional, langsung cus pulang. Padahal kenyataannya tidak begitu. Dari sudut pandang orang-orang yang belum pernah sehari saja bekerja di perpustakaan asumsi nyaman dan menyenangkan bakal tergambar.
Faktanya, menjadi pustakawan itu tidak sesederhana menata buku saja. Profesi ini menuntut pekerjanya punya stok kesabaran yang melimpah, kecerdasan emosional saat menemui peminjam yang riweh, hingga kemampuan bertahan hidup di tengah minimnya anggaran dari lembaga yang menaungi. Jika menghitung semua tuntutan itu, rasanya wajar kalau pustakawan minta dibayar mahal.
Namun kenyataannya bagai jauh panggang dari api. Tuntutan segunung tidak diimbangi dengan pendapatan yang bisa membuat untung.
Sering disalahkan, apa saja kaitannya dengan perpustakaan
Dalam praktiknya, pustakawan itu customer service versi paling kompleks dengan beban moral dan struktural yang lebih berat. Semua komplain mampir ke meja pustakawan. Dari pengunjung, dari dosen, dari siswa, bahkan dari atasan sendiri.
Koleksi kurang lengkap? Pustakawan yang disalahkan. Buku tidak update? Kami yang salah lagi. Ruang baca membosankan? Tetap pustakawan. Fasilitas tidak nyaman? Ya salah kami lagi.
Padahal kan pustakawan bukan pemilik anggaran. Tapi setiap kali kritik naik ke meja atasan, ujung-ujungnya pertanyaannya selalu sama.
“Lho, kenapa koleksinya bisa nggak lengkap?”
Jawabannya sebenarnya sederhana, semua bisa maksimal asal ada anggaran. Tapi kalimat itu jarang diterima dengan lapang dada.
Di titik ini, pustakawan dituntut tetap tabah, tetap ramah, dan tetap tersenyum korporat. Menjelaskan kondisi yang ada dengan bahasa sehalus mungkin agar pengunjung tidak kapok datang, dan atasan tidak merasa diserang. Ini bukan sekadar kerja teknis semata, melainkan kerja-kerja yang menguras emosi jiwa.
Pustakawan palugada, kerja keras bagai kuda sampai lupa segalanya
Di dunia ideal, pustakawan itu punya spesialisasi. Ada yang fokus teknis, ada yang IT, ada yang promosi, ada yang layanan, dll. Di dunia nyata? Oh jelas tidak seperti itu. Semuanya dilebur jadi satu orang. Lowongan kerja untuk pustakawan hari ini biasanya berbunyi seperti ini:
“Menguasai sistem perpustakaan, inovatif, bisa desain (Canva nilai plus), paham IT, komunikatif, bisa kerja tim dan kalau bisa sekalian jago coding,”
Intinya, satu orang diharapkan mengisi lima peran. Pustakawan dituntut jadi perencana sekaligus eksekutor. Jadi konseptor sekaligus pelaksana. Kalau semua bisa dikerjakan satu orang, kenapa harus banyak? Logika efisiensi macam ini yang bikin pustakawan sering jadi profesi palugada, kerja keras bagai kuda sampai lupa segalanya, nahas gaji tetap segitu-gitu saja.
Pustakawan dituntut selalu solutif meski tak diberi pilihan alternatif
Menjadi pustakawan berarti harus punya satu soft skill utama, memberi solusi tanpa biaya dengan alternatif pilihan terbatas. Ini biasa terjadi ketika koleksi dianggap kurang. Saya sebagai pustakawan tentu saja menawarkan solusi untuk pembaruan buku. Tetapi pertanyaan lanjutan hampir selalu sama dari atasan, “Kenapa harus diperbarui? Bukunya kan masih banyak.”
Di sinilah pustakawan diuji. Bukan hanya soal pengetahuan, tapi soal kecerdikan meramu argumentasi. Bagaimana menjelaskan bahwa buku bisa banyak tapi tidak relevan. Bahwa informasi yang usang itu berbahaya. Bukan sekadar ketinggalan jaman tapi bisa menyesatkan. Serta bagaimana menjelaskan dengan baik bahwa perpustakaan bukan gudang buku mati.
Ironisnya, solusi yang sudah dipikirkan matang pun sering ditolak karena dianggap tidak prioritas. Di negeri ini, perpustakaan sering diagungkan saat bicara literasi, tapi dilupakan saat menyangkut anggaran dari birokrasi.
Jago tawar-menawar, bukan cuma pintar teori
Saat pengadaan buku, pustakawan harus berhadapan dengan realitas ekonomi. Harga buku mahal, anggaran terbatas, kebutuhan banyak. Harus tahu diskon, paham vendor, dan cerdas menyesuaikan prioritas.
Kalau salah hitung, anggaran bisa boncos. Kalau terlalu hemat, koleksi jadi tidak relevan. Ini seni tawar-menawar yang membutuhkan kecerdasan ekonomi dan persuasi, bukan sekadar catatan administrasi. Pun jika hasil akhirnya tetap dianggap kurang, pustakawan lagi yang diminta evaluasi.
Belum lagi, pustakawan juga dituntut pintar promosi, tapi tanpa biaya anggaran yang disediakan. Kebanyakan perpustakaan saat ini harus terlihat aktif, kreatif, dan menarik agar pengunjung banyak yang datang supaya tidak dianggap bangunan usang dengan tumpukan buku yang membosankan. Tapi sering lupa satu hal, kalau promosi juga butuh biaya.
Kalau tidak ada anggaran, lagi-lagi pustakawan yang menjadi korban. Maka jangan heran jika pustakawan juga merangkap admin media sosial, desainer dadakan, bahkan event organizer setengah jadi ketika ada hajatan seminar kepustakaan.
Jadi, apa masih menganggap pustakawan cuma jaga buku doang? Semoga tidak, ya. Sebab, pustakawan saat ini seperti bekerja di persimpangan antara idealisme literasi dan realitas anggaran yang menghantui. Dituntut serba bisa, serba paham, serba sabar, dan serba solutif, tapi sering kali tanpa dukungan yang sepadan. Seolah pekerjaannya hanya duduk dan bersantai lalu pulang.
Kalau semua itu masih dianggap pekerjaan ringan, mungkin yang perlu dibaca ulang bukan koleksi perpustakaannya, tapi cara kita memandang profesi pustakawan itu sendiri. Apalagi dengan beban kerja seperti saat ini, rasanya wajar kalau pustakawan minta dibayar mahal. Benar apa betul?
Penulis: Ferika Sandra
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Jurusan Ilmu Perpustakaan: Kuliahnya Gampang, Nyari Kerja Juga Gampang, Gampang Ditolak Maksudnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.