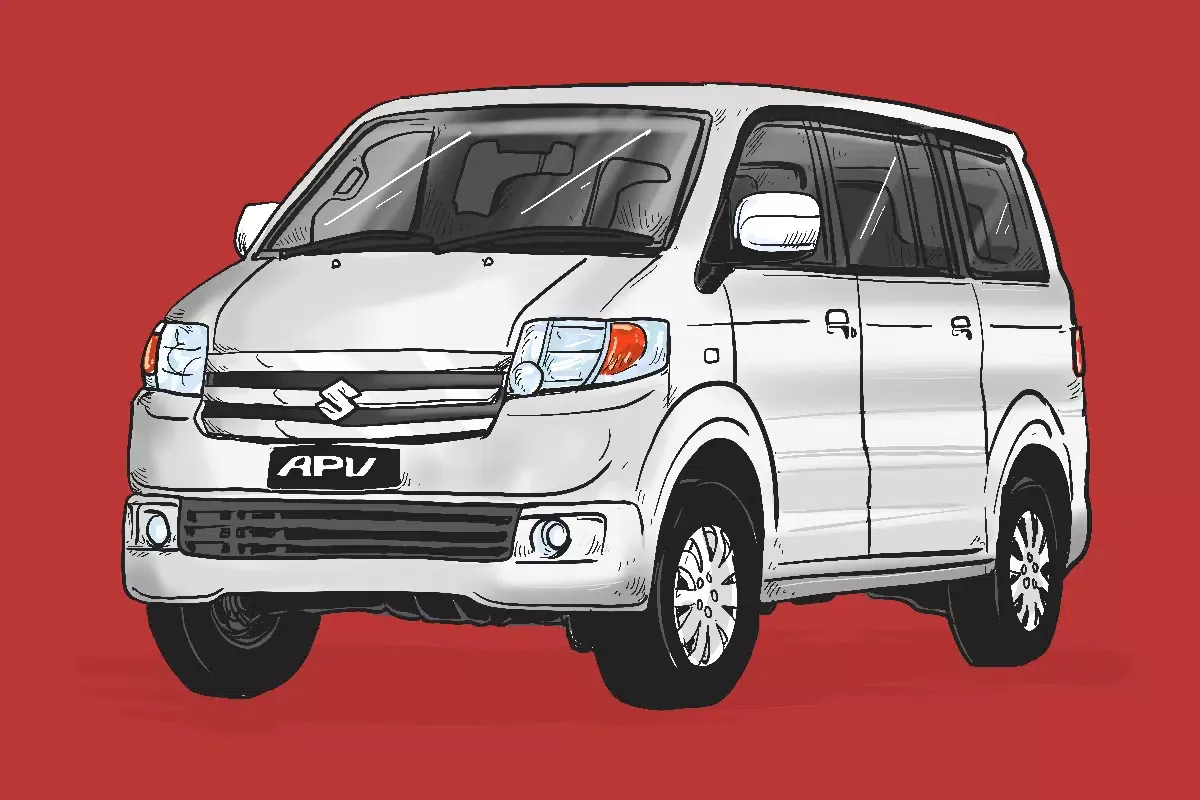Akhir Juli kemarin saya dan pacar mudik ke kampung. Bermodal rapid test dengan hasil non-reaktif, kami berniat mengurus pernikahan yang dilangsungkan akhir Agustus kemarin.
Persiapan cuma sebulan? Tetek bengek lain sudah diurus jauh hari. Agendanya juga cuma ijab qabul yang dihadiri sekitar 20 orang (menurut aturan, maksimal 30 orang).
Pikiran saya sederhana. Jakarta jadi episentrum corona, sementara daerah asal saat itu masuk zona kuning. Seharusnya hati lebih tenang. Seharusnya. Tapi, tak lama setelah mudik ke desa kelahiran, sebut saja K, situasinya justru lebih horor ketimbang di Ibu Kota.
Kenapa? Jika di Jakarta orang-orang lumayan disiplin protokol, setidaknya keluar pakai masker, orang-orang kampung saya beraktivitas seakan-akan virus asal Wuhan itu hoaks belaka.
Saya mengarantina diri selama dua minggu di rumah. Sembari WFH, tentu saja. Tidak pernah tidak pakai masker, selalu jaga jarak dengan orang rumah, rajin cuci tangan, menolak salaman atau kontak fisik lain.
Saya kira itu common sense. Saya pun melakukannya selama di Jakarta. Bukan apa-apa. Selain khawatir sama diri sendiri, saya juga tidak mau jadi OTG (orang tanpa gejala) yang diam-diam menularkan virus ke orang terdekat. Apalagi orang tua dan mbah saya masuk kategori rentan secara usia.
Lewat dua minggu, saya mulai memberanikan diri keluar rumah. Utamanya untuk mengurus administrasi KUA dan perpanjangan SIM motor.
Nah, di titik ini saya mulai menyaksikan bagaimana mayoritas warga kampung K menyepelekan protokol kesehatan.
Masker, barang paling standar tapi efektif untuk mencegah penularan virus, jarang ada yang pakai. Atau dipakai sembarangan dengan hidung masih mengatung keluar. Atau dipakai selama naik motor, tapi anehnya dilepas saat sudah sampe tujuan, di tempat ngumpul.
Entah kenapa saya merasa banyak yang pakai masker karena formalitas saja. Mungkin mirip peraturan lain yang dilakukan atas nama: ya karena jadi aturan. Kurang paham esensinya. Semata karena yang lain juga pakai. Atau biar nggak kena razia.
Jaga jarak? Apa itu jaga jarak. Di pertigaan, para gondes masih nongkrong ria. Udad-udud, ketawa-ketiwi. Di pasar dan tempat kerumunan lain pengunjung tetap berdesak-desakan.
Satu tetangga bisa menggelar resepsi pernikahan tanpa didisiplinkan kepolisian setempat, hal yang sama kemudian dilakukan warga lain. Ingat, dan bayangkan, itu semua berlangsung dengan tanpa atau sedikit yang pakai masker.
Tahu kan rasanya melakukan satu hal yang masyarakat lain tidak lakukan? Saya merasa seperti orang konyol. Orang paranoid, yang ketika keluar pakai masker justru mendapat tatapan heran, atau kadang malah senyum ejekan.
Saya mungkin dipandang sedang merusak keayem-temtreman kampung, mencederai kenormalannya, keguyubannya. Mengutip seorang tetangga pas papasan di jalan, “Di kampung ini udah nggak ada corona.”
Satu malam saya pulang jalan kaki dari rumah Mbah. Di satu pengkolan ada beberapa pemuda desa yang duduk mengelilingi api unggun. Tidak ada yang maskeran. Salah satunya adalah teman masa kecil saya. Saya cuma menyapa sebentar, lalu lanjut jalan.
Baru beberapa langkah, saya mendengar si teman itu komentar, “Kok dia masih maskeran?” Tahu apa jawaban pemuda di sebelahnya? “Iya tuh, si Awal emang masih ketakutan”.
Itu belum apa-apa dengan pengalaman salat berjamaah. Hampir mustahil untuk tidak dibecandai jemaah lain saat saya mencoba menerapkan jaga jarak. Meski sudah gelar sajadah sekitar 50 cm, selalu ada yang nyelonong dari belakang untuk merapatkan barisan.
Barangkali tidak terima jika saf kosong. Toh kiai setempat sejak awal pandemi tidak pernah mengatur jarak. Pokoknya rapat-pat!
Puncaknya saat salat Idul Adha. Sudah hampir separuh jamaah tidak memakai masker, berdesak-desakan di dalam masjid, tiap beberapa detik ada yang batuk-batuk pula, gimana saya nggak gelisah?
Sebelum salat dimulai, saya memutuskan keluar masjid, menuju emperan samping yang masih kosong. Saya kira di emperan itu nanti cuma akan dihuni dua orang per baris, ada ruang kosong di tengah.
Eh, ketika salat mau mulai, satu orang mendesak ke ruang kosong itu. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Pak RT. Tanpa masker, dia mengatur jamaah lain pakai dark joke,
“Ayo, ayo… dirapetin, nanti coronanya kesenengan (karena bikin saf bolong).”
Jemaah di belakang ada yang menyahut, “Eh, jangan bolong safnya… ntar coronanya liwat… hihihi….”
Saya menyerah.
Saya sampai hampir membatalkan acara nikah karena saking khawatirnya. Tapi segalanya sudah fiks, tinggal jalan. Ya, apa boleh buat. Yang penting sembari menjalankan protocol dan rombongan kecil keluarga saya dipastikan dalam kondisi sehat walafiat.
Dua minggu selepas acara, saya bersama istri sudah kembali ke Jakarta. Beberapa hari setelahnya saya tanya kabar ke orang rumah. Dijawab, “Alhamdulilah, sehat kabeh,” sehat semua. Begitu juga warga kampung. Sepengetahuan saya, tidak ada satu pun yang sakit atau meninggal dalam kondisi positif Covid-19.
Apa berarti saya memang paranoid? Dan warga kampung sedang menertawakan saya?
Mengingat positif-negatifnya warga hanya bisa diketahui melalui tes dan di kampung tidak diselenggarakan swab atau rapid test massal, sementara tingkat tes yang digelar pemerintah Indonesia juga masih rendah, saya cuma bisa bilang: entahlah. Mbuh.
Sejujurnya saya juga berharap saya ini memang salah. Bahwa semuanya cuma hasil dari pemikiran yang berlebihan.
Diketawain dong? Nggak apa-apa. Asal semuanya sehat sampai pandemi berlalu dan kita bisa menjalankan aktivitas secara normal.
Semoga.
BACA JUGA Hindari Corona, Tetaplah Hidup Walau Tidak Berguna dan tulisan Awal Hasan lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.