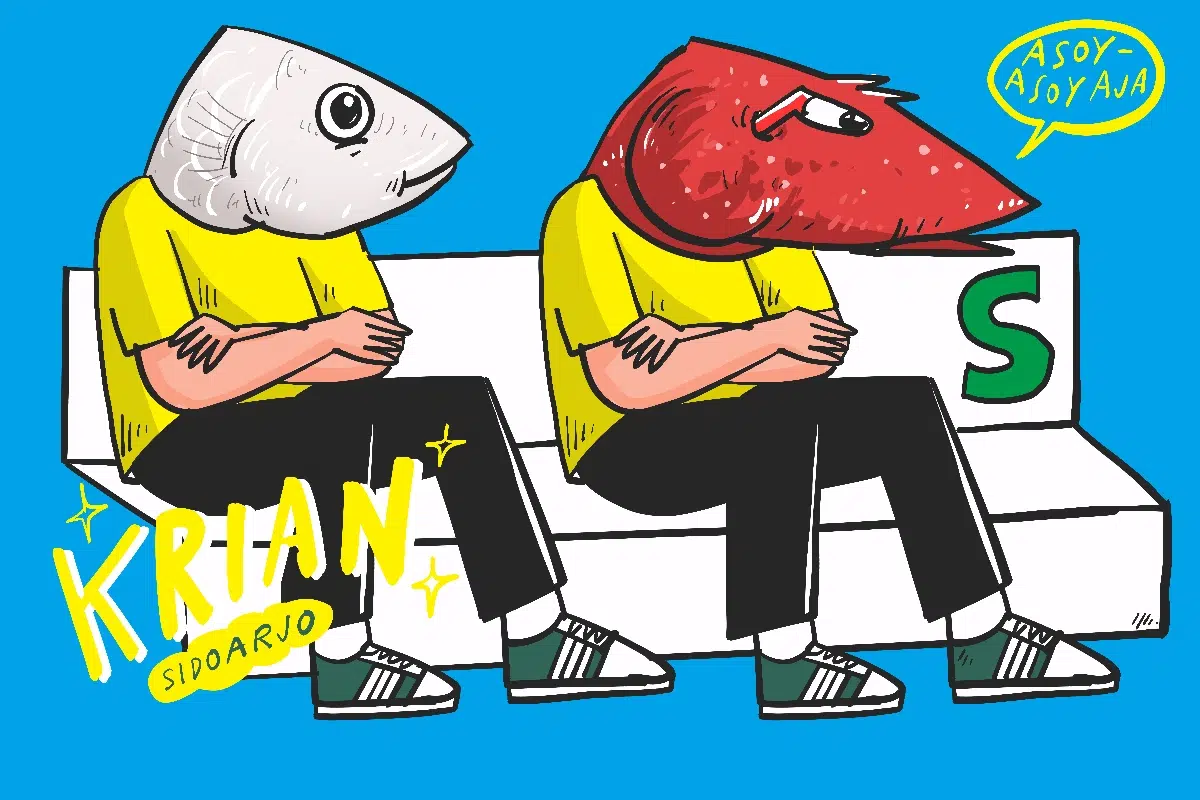Orang sering mengenali Indramayu, kampung halaman saya bukan dari peta, tapi dari kenangan jalanan. “Indramayu? Wah, waktu kecil saya sering lewat sana pas mudik,” begitu kata teman-teman saya dari kota lain. Bagi mereka, Indramayu bagian pantura hanyalah episode perjalanan. Bagi saya, pantura adalah rumah tempat saya tumbuh, sebuah bentang aspal yang membesarkan saya tanpa saya sadari.
Coba kita putar waktu sejenak ke era sebelum tahun 2015. Sebelum Tol Cipali hadir sebagai dewa penyelamat kaum urban, Pantura adalah panggung utama ritual mudik nasional. Jutaan manusia tumpah ruah di sini, mengubah jalanan menjadi lautan lampu rem yang tak berujung. Macetnya bisa berhari-hari. Warung dadakan, penjual asongan, sampai jasa pijat di pinggir jalan menjamur seperti di festival tahunan. Wilayah di Indramayu seperti Lohbener, Jatibarang, dan Eretan mendadak jadi pit stop vital dalam perjalanan kolosal ini.
Di sanalah masa kecil saya dihabiskan. Pantura adalah guru geografi dan otomotif saya yang pertama. Saya belajar plat nomor kendaraan bukan dari buku, tapi dari parade kendaraan tak pernah habis: B untuk Jakarta, G untuk Tegal-Brebes, H untuk Semarang, AB untuk Yogyakarta, L untuk Surabaya, dan seterusnya.
Saya hafal nama-nama perusahaan bus era 90-an mungkin seperti anak-anak dari kota lain menghafal tokoh superhero Jepang: Luragung, Sahabat, Garuda Mas, hingga Lorena. Mereka bukan sekadar angkutan, melainkan karakter dalam epik mudik tahunan. Bahkan, saya dan kakak memiliki ritual kami sendiri: tebak-tebakan merek dan model mobil dari kejauhan, hanya dari bentuk lampu depan atau siluet bodinya yang samar.
Denyut ekonomi yang menuju mati
Namun, parade kendaraan ini bukan sekadar tontonan gratis. Setiap bus yang merapat, setiap mobil yang menepi karena mesin overheating, dan setiap keluarga yang turun membeli es kelapa, adalah denyut nadi ekonomi yang nyata. Seorang ibu yang punya warung es kelapa, bisa menghidupi keluarga dan menyekolahkan anaknya hingga sarjana hanya dari rezeki para musafir yang haus itu. Ekosistemnya sempurna. Ada bengkel-bengkel yang selalu kedatangan kendaraan, ada penjual telur asin, dan warung nasi rames yang ramai hingga larut malam.
Saat itu, Pantura bukan sekadar jalan, ia adalah sebuah ruang hidup yang berdenyut. Suasana ini persis seperti adegan kilas balik di film Cars, di mana Radiator Springs masih ramai oleh mobil-mobil yang antusias melintasi Route 66, mengisi setiap pom bensin dan motel.
Lalu, Datanglah Sang “Penyelamat” Bernama Ruas Tol Cikopo-Palimanan, Cipali.
Indramayu menjadi Radiator Springs
Awalnya, kami menyambutnya dengan penuh harap seperti Doc Hudson menyambut kedatangan Lightning McQueen. Akhirnya, solusi untuk macet yang sudah menjadi legenda! Tidak ada lagi truk yang mogok di depan rumah, tidak ada lagi suara klakson yang membangunkan kami di tengah malam. Kami membayangkan kehidupan yang lebih tenang.
Tapi, kami, warga Indramayu, tidak menyadari bahwa kemudahan dan kecepatan adalah komoditas yang mahal harganya. Cipali, dengan mulus dan efisien, mengalihkan bukan hanya kendaraan, tapi juga aliran kehidupan, uang, dan cerita. Ia adalah Interstate 40 yang baru. Dingin, teratur, dan punya satu tujuan: sampai, cepat-cepat! Di tol, tidak ada ruang untuk spontanitas membeli camilan atau sekadar bertanya arah sambil ngopi. Semuanya serba transaksional: bayar tol, isi bensin di rest area, lanjut jalan.
Dampaknya? Sepi yang menghantui.
Kini, melintas di Pantura Indramayu terasa seperti memasuki film dokumenter pasca-industri. Banyak rumah makan dan warung tenda sudah gulung tikar. Bengkel-bengkel sepi. Pemiliknya lebih banyak duduk-duduk sore sambil ngopi, mengenang masa ketika tangannya kotor oleh oli dan dompetnya tebal oleh rupiah. Ia bagai Mater si tow truck yang hanya bisa bernostalgia, “Ka-chow!,” sementara dunia telah melupakan mereka.
Pom bensin yang dulu antrenya bisa sampai ke jalan, kini sepi. Pantura ini telah berubah menjadi Radiator Springs di era modern: sunyi, dengan bangunan-bangunannya yang masih berdiri bagai monumen untuk kenangan. Kita seperti Luigi dengan toko bannya, memandangi produk-produk yang masih bagus, menunggu pelanggan yang telah memilih jalan bebas hambatan. Karakter-karakter yang dulu hidup, kini menjadi hiasan di museum sendiri.
Lalu, apakah Cipali sejatinya adalah tokoh antagonis?
Jujur, tidak sepenuhnya. Sebagai orang yang juga kerap mudik, Cipali adalah anugerah. Ia menghemat waktu dan tenaga. Persoalannya bukan pada hadirnya tol, tapi pada luka yang ditinggalkannya pada ekonomi kerakyatan yang dulu hidup dari “ketidaknyamanan” itu.
Pemerintah kerap berkoar tentang membangun ekonomi dari bawah, tapi ketika sebuah jalan tol membawa pembangunan yang terpusat dan steril, usaha-usaha kecil di jalur lama justru mati pelan-pelan. Ironis, bukan?
Dan kini, seperti pukulan terakhir, muncul rencana pembangunan Tol Kerta Ayu, atau yang dulu dikenal sebagai Tol Indrajati. Ruas yang akan menghubungkan Indramayu dan Kertajati. Proyek ini dibahas kembali di masa kepemimpinan Bupati Lucky Hakim, sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan Rebana yang digagas pemerintah provinsi dan pusat.
Mendengar kabar ini, saya membayangkan wajah-wajah pedagang dan pemilik bengkel di sepanjang Pantura. Ekspresi mereka bukan lagi harap-harap cemas, melainkan pasrah yang getir. Ini seperti adegan di Cars ketika para penghuni Radiator Springs mendengar rencana pembangunan jalan bypass baru. Sebuah kepastian bahwa mereka akan dilupakan selamanya.
Jika Cipali sudah membuat denyut nadi Pantura melemah, Tol Kerta Ayu berpotensi menjadi paku terakhir di peti mati. Para “Mater” dan “Luigi” lokal ini seolah dipaksa menyaksikan kematian pelan-pelan kota mereka, sambil bertanya: masih adakah ruang bagi mereka di peta pembangunan ini?
Pantura Indramayu pernah muda, kini menua
Apa yang tersisa dari Pantura sekarang? Mungkin justru keasliannya. Dia menjadi jalur alternatif yang lebih “jujur”. Di sini, kita masih bisa melihat petani menjemur padi di bahu jalan, melihat anak-anak berenang di kali, dan merasakan denyut nadi Indramayu yang sebenarnya, tanpa polesan lampu neon rest area.
Mungkin nasib Pantura Indramayu memang seperti siklus hidup. Ia pernah muda dan ramai, kini mulai menua dan sepi. Tapi, seperti Radiator Springs yang akhirnya ditemukan kembali pesonanya bukan sebagai jalan utama, tapi sebagai destinasi, saya masih punya harapan.
Mungkin Pantura perlu menemukan jati dirinya yang baru. Bukan lagi sebagai arteri utama, tapi sebagai urat nadi kecil yang menghidupi hal-hal yang tak bisa diberikan tol: keaslian, ketenangan, dan secangkir kopi di warung tua yang masih bertahan.
Saya, sebagai anak yang dibesarkan di tepinya, akan terus mengenangnya. Sambil lalu, berharap suatu saat nanti ada “Lightning McQueen” berikutnya, seorang traveler, sengaja keluar dari Cipali yang steril, singgah, dan menemukan bahwa di balik sepinya, masih tersimpan hangatnya nasi rames dan senyum warga yang pantang menyerah.
Ka-chow!
Penulis: Janzuar Ramadhany
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.