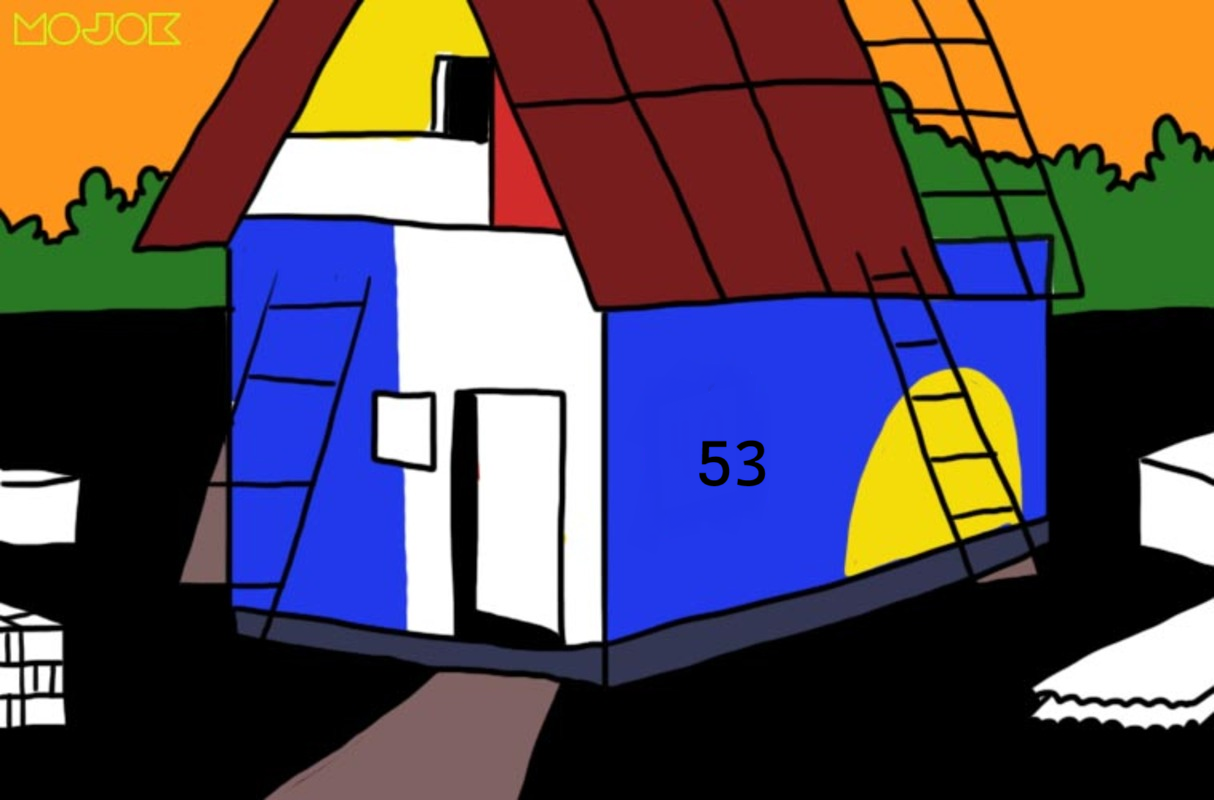Waktu pertama kali diterima di UIN, aku sempat mikir, “Wah, akhirnya aku bakal kuliah di lingkungan yang religius banget!” Dalam bayanganku, semua mahasiswanya rajin ke masjid, kajian di mana-mana, dosennya adem kayak ustaz di televisi, dan suasana kampusnya penuh keberkahan. Pokoknya, versi akademik dari surga kecil di bumi.
Tapi realitas, seperti biasa, nggak pernah seindah ekspektasi.
Baru semester satu aja, aku udah sering mikir: ini kampus Islam atau kampus bebas bersyarat? Kadang kalau lihat pemandangan di pelataran kampus, malaikat pencatat amal mungkin juga butuh cuti sejenak buat mikir: ini mau dicatat di kolom pahala atau dosa?
UIN: Islamnya nama, bukan suasana
Jujur, UIN (Universitas Islam Negeri) itu keren secara konsep. Ada kata Islam-nya, tapi tetap terbuka buat semua kalangan. Tapi yang menarik—dan kadang miris—adalah bagaimana sebagian mahasiswa justru menganggap kata “Islam” itu cuma hiasan di papan nama kampus.
Ada yang kuliah di jurusan Syariah tapi masih bingung membedakan aurat dengan gaya. Ada juga yang belajar tafsir, tapi story-nya kadang lebih sering berisi kegiatan nongkrong ketimbang ayat yang dipelajari. Belum lagi yang suka menulis kutipan Islami di bio, tapi isi unggahannya tetap tentang keseharian yang jauh dari nuansa dakwah.
Nggak salah, sih, mahasiswa UIN juga manusia biasa. Hanya saja, ironinya, semua itu terasa begitu biasa seolah kampus Islam memang sudah terbiasa hidup di antara dua dunia: idealisme dan realitas.
Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, terutama di Fakultas Tarbiyah—tempat calon guru dibentuk—adalah gaya berpakaian yang kadang bikin lupa konsep “teladan.” Celana yang ketat, atasan yang menonjolkan bentuk tubuh, ditambah kerudung yang dibiarkan tanpa peniti sampai leher dan sebagian rambut terlihat ke mana-mana. Rasanya agak janggal, mengingat mereka sedang belajar jadi pendidik yang mestinya bisa memberi contoh.
Tapi ya, di sisi lain, mungkin begitulah potret generasi kita: masih mencari jati diri di tengah benturan antara nilai dan tren.
Sholat yang kalah oleh rapat
Ada juga fenomena lain yang bikin miris sekaligus lucu: sholat yang sering kalah sama rapat organisasi. Entah kenapa, setiap kali adzan berkumandang, kalimat “nanti aja, habis rapat” terdengar jauh lebih populer daripada “ayo ke musala dulu”. Kadang malah ada yang bilang, “bentar lagi kok, lima menit lagi,” padahal lima menit itu berubah jadi setengah jam. Begitu rapat kelar, waktu sholatnya sudah lewat.
Ironisnya, agenda yang dibahas pun seringnya soal kegiatan dakwah atau acara keislaman. Tapi justru di situ kita sering lupa pada inti keislaman itu sendiri. Aku kadang bertanya dalam hati, “Kita ini sedang berjuang untuk Islam, atau justru terlalu sibuk sampai lupa pada Allah-nya?”
UIN dan label Islam nggak selalu sama dengan nilai Islam
Masalahnya mungkin ada di mindset. Banyak yang berpikir, “Ah, kan kuliah di kampus Islam, berarti udah aman.” Padahal kampus Islam itu bukan jaminan otomatis jadi Islami. Kayak beli baju gamis, tapi perilakunya belum tentu mencerminkan nilai-nilai keislaman.
Pendidikan Islam mestinya membentuk karakter, bukan sekadar hafalan atau seragam. Tapi yang terjadi, kadang justru sebaliknya: banyak yang hafal teori akhlak tapi lupa praktiknya. Ada juga yang hafal hadis tentang menuntut ilmu, tapi absen kuliah terus.
Bahkan di kampus Islam, ada budaya “standar ganda” yang lucu: kalau orang lain melakukan hal yang dianggap nggak syar’i, langsung dikritik habis-habisan. Tapi kalau temen sendiri yang melakukannya? “Ya udah, namanya juga manusia.” Malaikat mungkin senyum getir di atas sana.
Antara tuntutan iman dan tuntutan eksistensi
Nggak bisa dimungkiri, pengaruh media sosial juga besar banget. Di satu sisi, mahasiswa dituntut beriman, tapi di sisi lain mereka juga ingin diakui eksistensinya. Kadang, status “anak UIN” jadi semacam beban sosial: harus tampak modern, tapi juga tetap Islami. Akhirnya, jadilah perpaduan unik—antara hijrah dan highlight story.
Kita bisa lihat sendiri, banyak yang lebih sibuk bikin konten dakwah bergaya estetik daripada ikut kegiatan masjid. Yang penting caption-nya bagus, walau realitas
nya masih jauh dari isi ceramahnya. Entah ini dakwah atau sekadar branding spiritual.
Mungkin kita semua sedang lupa esensi
Tapi jujur, aku nggak sedang menyalahkan siapa pun. Aku juga bagian dari sistem yang sama. Mungkin kita semua sedang lupa: kampus Islam bukan hanya tempat menuntut ilmu agama, tapi tempat untuk belajar mempraktikkannya dalam kehidupan nyata.
Label “Islam” seharusnya bukan sekadar identitas, tapi tanggung jawab. Kalau kampus lain saja bisa menanamkan budaya disiplin dan etika, masa kampus Islam kalah dalam menanamkan nilai-nilai agamanya sendiri? Mungkin sudah saatnya kita berhenti bangga hanya karena kuliah di UIN, dan mulai bertanya: sudah seberapa “Islami” perilaku kita di dalamnya?
UIN tetap kampus yang hebat. Banyak dosen inspiratif, banyak mahasiswa cerdas, banyak kegiatan keislaman yang luar biasa. Tapi di balik semua itu, ada realitas yang nggak bisa diabaikan: Islam belum sepenuhnya hidup di keseharian mahasiswanya.
Jadi, kalau suatu saat malaikat pencatat amal terlihat menghela napas panjang di langit Purwokerto, Yogyakarta, atau Ciputat, mungkin mereka lagi bingung: mau nulis “mahasiswa kampus Islam”, atau cukup “mahasiswa yang sedang belajar menuju Islam”?
Penulis: Assyifa Furqon Gaibinsani
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Keunikan UIN Jogja, Mahasiswanya seperti Nggak Kuliah di Kampus Islam
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.