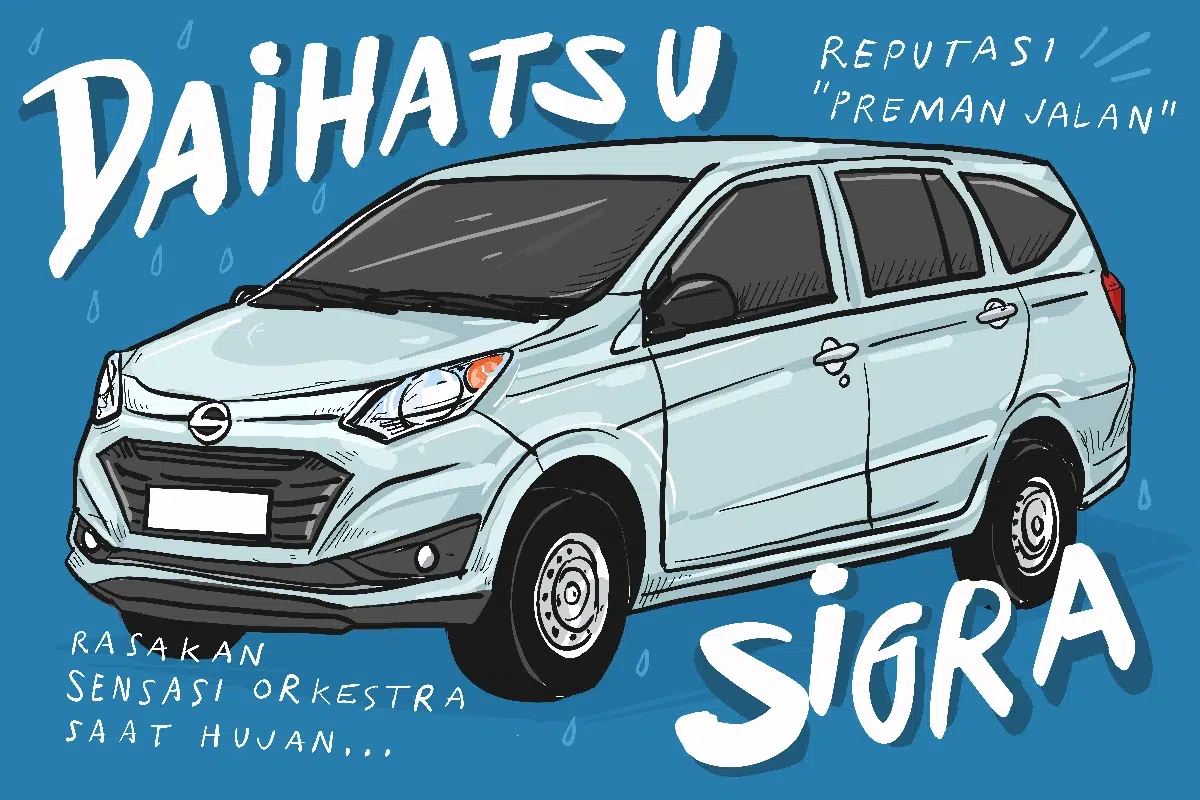Saat pertama kali masuk ke universitas swasta Jogja ini, saya seperti nyasar ke dunia yang bukan milik saya. Perasaan itu muncul karena kesadaran latar belakang saya jauh berbeda dengan kebanyakan mahasiswa di kampus. Asal tahu saja, universitas yang saya masuki, yang identik dengan warna biru itu, dikenal sebagai salah satu universitas swasta “elit” di Jogja. Biayanya nggak main-main, tapi itu memang sebanding dengan kualitasnya.
Kebaikan kampus atas beasiswanya yang mengantarkan saya bisa masuk ke sini. Sebuah tiket emas untuk anak dari keluarga pas-pasan seperti saya, yang kalau ikut bayar penuh, mungkin hanya bertahan satu semester saja. Sedikit gambaran, UKT satu semester bisa untuk membeli Nmax dan itu berlaku untuk semua mahasiswa. Untuk kaum mendang-mending seperti saya, kalau punya duit segitu mending buat beli franchise Olive Chicken yang laku banget di Jogja. Pasti bisa balik modal cepat.
Rasa canggung yang tidak bisa terhindarkan
Persoalan yang muncul kemudian adalah, beasiswa itu hanya membayar biaya kuliah dan tempat tinggal. Tidak membayar rasa canggung yang muncul saat teman-teman bolak balik ke kafe, sementara saya hanya bisa membolak-balik alasan tidak ikut. Beasiswa itu juga tidak menutup rasa minder saat semua orang pakai iPhone dan laptop mahal, sedangkan saya masih mengandalkan laptop bekas mini yang harus dicas terus.
Mungkin kalimat di atas terdengar tidak bersyukur. Tapi, percayalah, bukan itu maksud saya. Kalimat itu semacam hasil perenungan saya selama awal-awal kuliah di universitas swasta elit itu. Kalau tidak bersyukur, mana mungkin bisa bertahan kuliah.
Saya tidak malu kok sehari-hari mengenakan sepatu tidak bermerek, ransel butut, baju yang itu-itu saja, motor matic bebek, dan helm warna ijo sisa narik ojek online.
Saya hanya sedikit terpukul karena sering tidak bisa ikut kegiatan organisasi yang butuh biaya. Bayar seragaman, raker di kafe, hingga patungan buat acara semua perlu biaya. Saya tidak takut terlihat berbeda atau dinilai “nggak pantas”, tapi budaya organisasi yang menurut saya mahal biaya itu sering membuat menghela nafas. Memperluas jaringan tidak bisa untuk semua kalangan kah?
Tekanan tidak kasat mata di kampus swasta elit Jogja
Ada semacam tekanan tak kasat mata yang membuat saya harus berusaha lebih keras. Sebagai mahasiswa beasiswa di sebuah universitas swasta jogja, saya harus pintar, aktif, dan baik supaya bisa diterima. Saya tidak boleh malas, tidak boleh gagal karena merasa keberadaan saya di kampus ini selalu dalam status “ujian kelayakan”. Kalau saya jatuh, takut orang-orang berpikir, “Tuh kan, udah gratisan gatau diri.” Lah anjir, tau diri kan kewajiban semua orang. Wong situ juga kuliah gratisan orang tua.
Saya tahu, mungkin mereka tidak pernah berpikir begitu. Namun, kepala saya kadung dipenuhi oleh prasangka-prasangka buruk tentang bagaimana dunia memandang orang miskin yang “nyasar” ke ruang-ruang eksklusif.
Beasiswa memang membantu secara finansial, tapi tidak secara emosional. Kami tetap harus berjuang mengelola rasa minder, rasa ingin diterima, rasa tidak nyaman saat sadar bahwa kami berbeda. Dan, di lingkungan seperti ini, berbeda bisa sangat melelahkan.
Saya masih ingat momen saat teman-teman saya cerita habis liburan ke anu ke sana ke itu, ada yang ikut volunteer ini-itu. Saya hanya diam. Saat giliran ditanya, saya jawab, “Liburan kerja, part time.” “Di mana?” “Di laundry.” “Oh.” Dikuping saya, oh yang mereka ungkapkan terdengar canggung. Saya menyelipkan tawa setelahnya supaya hidup saya tidak terkesan menyedihkan.
Obrolan soal brand fashion, motor, mobil, dan tempat brunch hits Jogja pun sering membuat saya terdiam. Bukan karena saya tidak tertarik, tapi karena saya tidak bisa relate. Ada jurang yang tak kelihatan di antara kami. Jurang yang dibangun oleh uang, lalu diperlebar oleh pengalaman dan orientasi hidup yang jauh berbeda.
Fase penerimaan yang perlu waktu panjang
Kendati tekanan tidak kasat mata itu terjadi berkali-kali, lambat laun saya mulai menemukan napas saya sendiri. Saya mulai menyadari bahwa tidak harus menyesuaikan segalanya. Saya mulai fokus pada hal-hal yang saya bisa, bukan yang saya punya. Menulis sana sini, coba berbagai bisnis, jualan, menjadi sedikit lebih tahu dari orang lain dan menjadi tempat bertanya. Sedikit demi sedikit, orang mengenal saya bukan dari apa yang saya kenakan, tapi dari apa yang saya kerjakan.
Saya mulai belajar berdamai dengan kenyataan bahwa saya tidak bisa punya semuanya, tapi masih bisa berkarya. Saya berhenti memaksakan diri untuk terlihat seperti mereka, dan mulai nyaman menjadi diri sendiri. Dan, yang paling penting, kesadaran bahwa saya tidak sendiri.
Banyak mahasiswa lain yang juga datang dari latar belakang sederhana, tapi diam-diam terus berjuang dengan cara masing-masing. Menjadi mahasiswa dari keluarga tidak mampu di universitas swasta elit Jogja memang bukan perkara mudah. Tapi. bukan juga perkara mustahil. Privilese itu nyata, tapi bukan berarti kita yang tidak punya harus mundur. Justru karena tidak punya, kita belajar lebih cepat untuk bertahan.
Kita mungkin tidak bisa ikut semua gaya. Tapi, kita bisa ikut membuat perubahan. Kita mungkin tidak punya banyak uang, tapi kita punya banyak alasan untuk terus maju. Dan, di balik semua perjuangan diam-diam itu, kita tetap melangkah. Dengan kepala tegak. Dengan harga diri yang utuh.
Penulis: Diha Maulana Yusuf
Editor: Kenia Intan
BACA JUGA Kuliah di Mana pun Itu Sama Saja Adalah Omong Kosong yang Terus Dipertahankan
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya