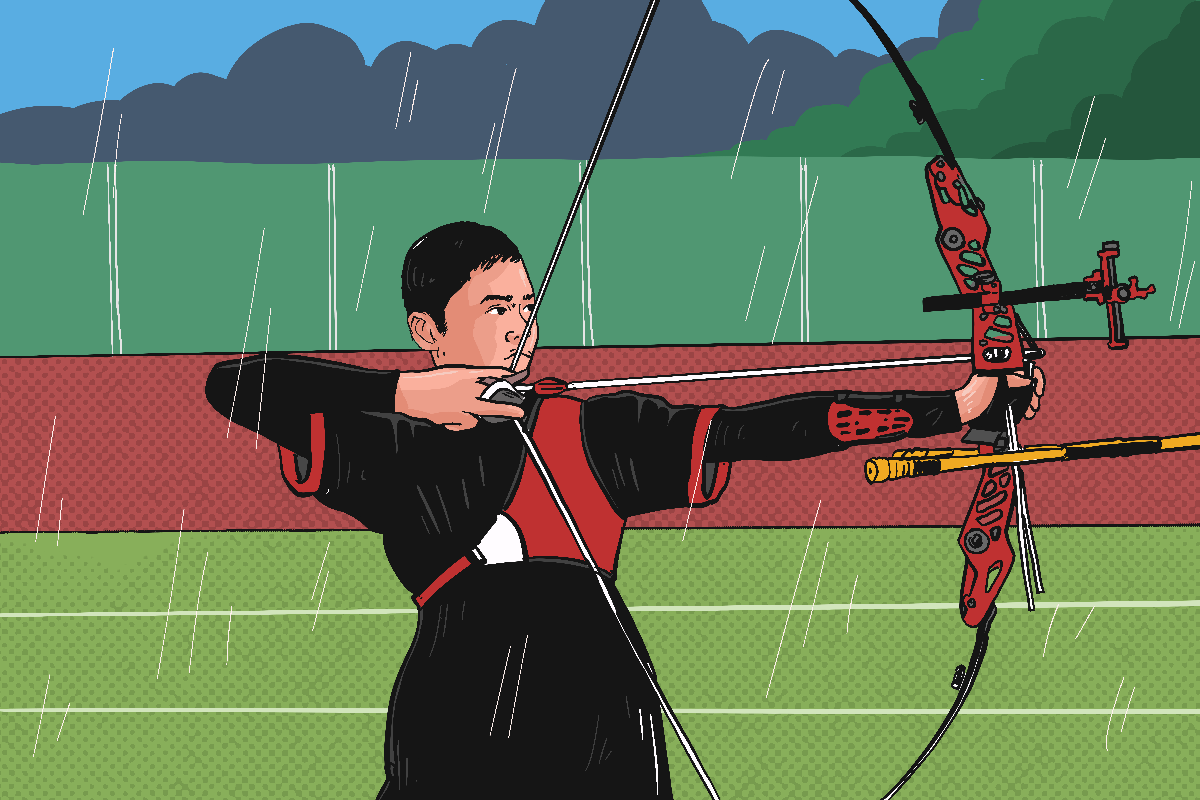Malioboro memang menjadi paran jujugan wisatawan ketika singgah di Jogja. Bahkan nama “Malioboro” mulai diadopsi daerah lain. Perpaduan pusat perbelanjaan, andong, dan pedagang kaki lima (PKL) menjadi roh yang ngangeni. Tapi salah satu roh ini harus hengkang dari hiruk pikuk Malioboro: para PKL.
PKL ini sering disebut perko, singkatan dari emperan toko. Maklum, posisi mereka memang berdagang di emperan toko Malioboro. Emperan sepanjang hampir 2 km ini menjadi layaknya bazaar. Terutama di sisi barat, PKL ini berebut pembeli dengan riuh yang khas. Tidak hanya antar PKL, tapi juga dengan toko yang terasnya menaungi mereka.
Teras toko di Malioboro ini bagaikan goa yang menaungin pejalan kaki serta lapak para PKL. Berbagai macam pernak-pernik dijajakan: kaos bertema Jogja, sandal anyaman, topi bootleg, sampai gantungan kunci dan miniatur. Ada juga pernak-pernik ala punk seperti gesper dan skull ring. Kenapa saya tahu? Ya, karena saya termasuk pelanggan PKL perko ini.
Namun, 2022 akan menjadi akhir dari kehadiran PKL ini. Sebanyak 1700 PKL ini akan direlokasi di dua tempat: eks bioskop Indra yang penuh sengketa dan bekas gedung Dinas Pariwisata DIY. Alasannya bisa ditebak: menata ulang Malioboro yang terlanjur penuh sesak.
Tentu proses relokasi ini menimbulkan polemik. Ada yang setuju, ada yang menolak. Sebagian sepakat relokasi ini memperindah area Malioboro. Tapi yang menolak merasa relokasi PKL membunuh ciri khas Malioboro. Sebagian lagi merasa relokasi ke dua lokasi ini membunuh pendapatan PKL.
Saya sendiri merasa wagu ketika Malioboro tanpa deretan PKL. Tapi sebelum makin jauh, saya harus mempertegas ini: opini saya tidak memiliki kepentingan tertentu. Maklum, relokasi PKL Malioboro sarat dengan kepentingan ekonomi. Dan opini saya ini semata-mata atas apa yang saya lihat dan rasakan sebagai warga Jogja.
Apakah Malioboro tetap istimewa ketika para PKL ini direlokasi dan dipusatkan? Sedangkan banyak PKL yang telah berdagang di emperan toko ini lebih dari 25 tahun. Selama lebih dari 25 tahun ini, para PKL ini menjadi daya tarik Malioboro. Jika bicara pusat perbelanjaan saja, mungkin setiap destinasi wisata punya “Malioboro”nya sendiri. Tapi Malioboro Jogja menjadi istimewa karena kehadiran PKL.
Seperti yang saya sebutkan di atas, PKL di sini membangkitkan nuansa bazaar dan pusat perbelanjaan sekaligus. Wisatawan seperti diberi dua tawaran: beli oleh-oleh di toko atau di PKL. Tentu dengan ciri khas dan mahar masing-masing. Mau beli yang berkelas, ada di toko. Mau beli yang hemat, ada di PKL.
Daya tarik PKL tidak hanya bicara harga, tapi juga suasana. Pengalaman menawar harga lebih mungkin terjadi ketika belanja produk PKL daripada pusat perbelanjaan. Bahkan ada tantangan tersendiri untuk kuat-kuatan menawar harga di PKL Malioboro ini. Seni tawar menawar inilah yang sulit Anda temui di supermarket atau mal.
Masalah pendapatan para PKL juga menjadi perhatian. Relokasi menawarkan lokasi baru yang lebih nyaman dan aman. Tapi ketika para PKL dipusatkan, apa bedanya mereka dengan pusat perbelanjaan lain? Selama ini mereka hidup dari seliweran wisatawan yang kepincut dagangan mereka. Karena para wisatawan ini sedang menikmati suasana Malioboro, mata mereka tertarik pada dagangan para PKL.
Ketika para PKL dipusatkan, apa yang menjadi alasan khusus wisatawan untuk mengunjungi mereka? Situasi yang tidak berbeda dengan pasar mereduksi keistimewaan PKL Malioboro ini. Dan sudah pasti, kurangnya daya tarik ini mengikis pendapatan mereka.
Kalau bicara kerapian, saya pikir tanpa relokasi para PKL ini bisa dirapikan. Toh selama puluhan tahun, kehadiran PKL ini tidak menjadi momok bagi wisatawan. Bahkan riuh di sepanjang emperan toko tersebut sering diabadikan oleh wisatawan. Ketika para PKL direlokasi, akan ada yang hilang di rekam gambar para wisatawan.
Memang kehadiran PKL ini tidak selamanya positif. Dari oknum yang mematok harga terlampau mahal sampai ancaman copet menjadi masalah tersendiri. Belum lagi isu perebutan ruang pedestrian oleh para PKL. Dan kalau bicara isu ekonomi, toh sejak 2008 pihak pertokoan juga mengeluhkan kehadiran PKL yang merebut konsumen mereka. Relokasi PKL menjadi jawaban manis ketika melihat permasalahan ini.
Tapi apakah budaya puluhan tahun yang tidak benar-benar bermasalah ini harus kukut? Apakah PKL yang jadi ciri khas Malioboro ini perlu hengkang? Apakah demi tata ruang yang (katanya) demi mengejar Kota Warisan Budaya Dunia, keistimewaan Malioboro harus direlokasi?
Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Audian Laili