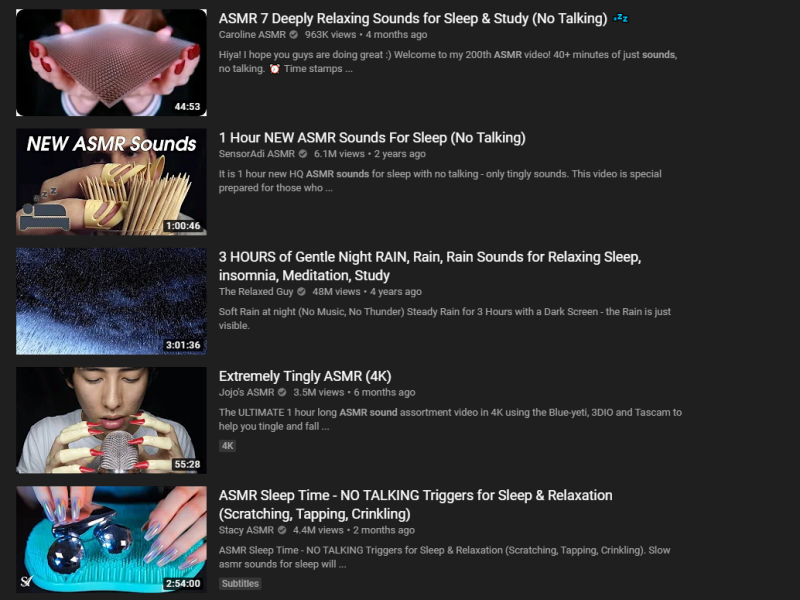Banyak film dokumenter Indonesia yang sangat layak untuk ditonton karena dikerjakan dengan serius. Beberapa di antaranya berdurasi panjang sampai dua jam lebih, tapi ada pula yang hanya berdurasi beberapa menit. Di antara banyaknya film dokumenter Indonesia yang ada, saya mencoba membuat daftar pendek film dokumenter yang bisa dengan mudah ditonton di kanal YouTube, pun dengan durasi yang tidak melebihi tiga puluh menit. Saya mencoba memasukkan beberapa film dengan pembahasan yang berbeda, mulai dari kebudayaan, agama, lingkungan, politik, dan fenomena urban yang sedang terjadi. Berikut adalah daftarnya.
#1 Cimplung
Film dokumenter ini hanya berdurasi 14.41 menit, menceritakan warga di Tulungagung yang terdampak pandemi covid19. Warga yang dulu hidup dari penggilingan tebu, mendadak kehilangan mata pencaharian mereka karena sepinya permintaan. Demi mencari alternatif mata pencaharian lain, akhirnya beberapa dari mereka memilih untuk berjualan cimplung, makanan khas warga Tulungagung yang terbuat ketela rebus dicelupkan ke dalam gula cair sehingga memiliki rasa manis.
Gula cair yang digunakan adalah langsung dari cairan tebu yang direbus, sehingga rasa manisnya masih sangat alami tanpa campuran tambahan. Kealamian itulah yang menjadi daya jual tersendiri. Ini bikin warga mulai percaya diri untuk mengemas cimplung dan menjualnya.
Masalah kemudian muncul: kepada siapa mereka akan menjualnya? Mayoritas warga di sana menyukai cimplung, tetapi mereka juga dapat membuatnya sendiri. Pada akhirnya salah satu warga mencoba menjualnya secara online dan ternyata banyak yang membeli. Setelah itu, banyak dari warga yang memutuskan untuk menjual online cimplung mereka. Ada yang menjualnya sendiri, ada juga yang menitipkan cimplung mereka untuk dijualkan.
Film dokumenter yang disutradarai oleh Ardie C. Firsttiant ini menampilkan bagaimana warga Tulungagung beradaptasi dengan dunia digital. Cimplung, yang awalnya hanyalah makanan untuk dikonsumsi pribadi maupun menyambut tamu, kini bertransformasi menjadi ke ranah industri. Banyak harapan dari transofmasi ini, seperti kelak cimplung akan seperti makanan khas populer Tulungagung layaknya Bapkia di Jogja. Akan tetapi, masih perlu diperhatikan: apakah perubahan itu hanyalah alternatif sesaat karena pandemi atau bisa bertahan lama bahkan selepas pandemi nanti?
Selain narasi sosial budaya dan transformasi digital yang diusung, film Cimplung juga menyajikan sinematografi yang indah. Lanskap desa dan aktivitas para warga ditampilkan dengan sangat mengagumkan, dipadukan dengan editing yang sangat baik, sehingga proses menonton film ini menjadi sangat menyenangkan.
Hanya saja kalau boleh mengkritik, film yang meraih penghargaan dalam Festival Film Dokumenter Jawa Timur ini rasanya tidak memerlukan intro yang dibuat puitis, karena saya rasa narasi di intro tidak terlalu sejalan dengan keseluruhan film. Narasi puitis itu menjelaskan tentang pandemi, lantas kesabaran, lantas betapa hebat orang sabar, dan ditutup dengan pertanyaan kapan pandemi akan berakhir? Kalau memang harus menggunakan narasi di intro, sepertinya membahas bagaimana transformasi dan kemauan untuk adaptasi akan lebih sesuai.
Kritik lainnya, entah kenapa semua tokoh yang ditampilkan di film ini tidak dilakukan perkenalan sama sekali, bahkan tidak disebutkan nama, pun tidak disebutkan latar belakang mereka. Setiap tokoh hanya akan muncul dan membicarakan kehidupan mereka.
#2 Liyan
Apa yang tersaji pada film dokumenter berjudul Liyan sungguh sangat dalam. Film berdurasi 32.06 menit ini merekam betapa tingginya toleransi beragama di Wonosobo. Para penganut agama minoritas hidup rukun satu sama lain dan tidak pernah mempermasalahkan perihal kepercayaan. Agama maupun kepercayaan adalah urusan pribadi masing-masing dan tidak untuk digembar-gemborkan di muka umum.
Film ini dibuka dengan situasi di desa Binangun, Watumalam, Wonosobo, menyoroti kehidupan para penganut Penghayat Kepercayaan. Jumlah Penghayat Kepercayaan di Wonosobo sekitar 13 ribu jiwa dan tersebar di berbagai wilayah. Desa Binangun adalah salah satu daerah dengan penganut Penghayat Kepercayaan paling banyak.
Bagian pertama film ini menyoroti Sarno Kusnandar, salah satu penganut Penghayat Kepercayaan di desa Binangun. Ia dalam kesehariannya hidup rukun dan bekerja bersama di ladang dengan penganut agama lain. Pak Sarno dan para penganut Penghayat Kepercayaan beribadah setiap pukul 19.00, dan mereka tetap bisa khusyuk sekalipun pada waktu-waktu tersebut azan isya juga dikumandangkan.
Bagian kedua dari film ini menyoroti wilayah perkotaan, tempat para penganut Syiah yang berjumlah 200 jiwa berada. Pada bagian ini, para penganut Syiah mengatakan bahwa Wonosobo adalah daerah yang paling bisa menoleransi perbedaan. Ketika Syiah di tempat lain dianggap seperti komunis, di Wonosobo Syiah bisa hidup damai dan menjalani aktivitas bersama masyarakat yang beragama lain.
Jumlah penganut yang hanya 200 jiwa menjadikan Syiah menjadi sangat minoritas. Pun ketika ditanya kenapa tidak mencoba menjadi lebih besar, halangan terberat tentu saja adalah bahwa stigma Syiah telah dianggap sesat oleh sebagian besar penduduk Indonesia, padahal semua itu hanyalah miskonsepsi.
Lantas, bagian ketiga dari film ini menyoroti Jemaah Ahmadiyah Qaidan yang terpusat di Desa Lengkong, Kecamatan Garung, dengan pengikut sekitar 6 ribu jiwa. Ahmadiyah sudah ada di Wonosobo sejak 1952. Ini membuat masyarakat di sana sudah mengenal Ahmadiyah jauh sebelum daerah-daerah lain di Indonesia. Lantaran mereka sudah lama mengenal, toleransi itu tercipta.
Film ini sangat luar biasa menggambarkan betapa keberagaman tidak menjadi masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa konflik itu timbul jika tidak mengenal satu sama lain. Karena masing-masing penganut agama dekat dengan satu sama lain, konflik itu sangat minim terjadi.
#3 Mutualisme
Film ini diproduksi oleh IDN Times. Digarap dengan serius dan sungguh sukses menampilkan lanskap hutan Petungkriyono di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pengambilan gambar, editing, backsound, semuanya sungguh luar biasa. Film berdurasi 17.15 menit ini menceritakan bagaimana penduduk yang mulai sadar bahwa hutan tidak boleh terlalu dieksploitasi. Bahwa keberlangsungan hidup warga juga sangat tergantung dengan keberlangsungan hutan tersebut.
Perburuan satwa sering terjadi pada 2006 hingga 2008. Selain berburu, pepohonan juga ditebangi begitu saja untuk dijual. Selain itu, banyak juga yang memanen madu lebah dengan menghancurkan sarang mereka, padahal hal itu bisa mengganggu keberlangsungan hidup lebah, yang pada dasarnya adalah spesies kunci di ekosistem karena memegang peran penyerbukan.
Saking seringnya dieksploitasi, hutan sempat rusak dan berakibat banjir bandang. Lantas, kesadaran mulai muncul. Jika aktivitas mengeksploitasi hutan tetap dilakukan, bisa jadi hutan hujan yang kaya akan flora dan fauna itu akan hilang. Hilangnya hutan, akan berpengaruh pada berkurangnya populasi owa yang notabennya hidup di sana.
Agar tidak mengeksploitasi lebih jauh, banyak warga yang beralih mata pencaharian. Dari yang awalnya berburu binatang, lantas beralih menjadi petani kopi. Pun dari yang awalnya memanen madu dengan merusak sarang lebah, kini memiliki alat tersendiri untuk menyedot madu tanpa merusak sarangnya.
Proses transisi itu terus dilakukan sehingga hutan tidak semakin tereksploitasi, dan warga juga bisa hidup dengan alternatif yang kini mulai tersedia. Mereka mencoba hidup berdampingan dan saling member manfaat bagi satu sama lain.
#4 Di Balik Kilang
Film ini menyoroti fenomena sumur-sumur tua peninggalan Belanda yang pada akhirnya digunakan masyarakat Wonocolo untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ada sekitar 148 sumur yang dibangun Belanda di Wonocolo, tapi yang berhasil ditemukan hanya setengahnya.
Ini adalah film 2015 dan menjadi film dokumenter terbaik Festival Film KPK. Dengan durasi 26 menit, film ini sempurna menggambarkan aktivitas warga di Wonocolo mengelola sumur-sumur penghasil minyak.
Masalah yang terjadi di kawasan itu adalah karena sifat manusia yang tidak mudah puas. Karena hasil minyak dirasa masih bisa ditingkatkan lagi, maka banyak orang yang melakukan pengeboran ilegal di daerah-daerah yang sebenarnya tidak dianjurkan.
Masalah lain juga terjadi karena regulasi yang berbelit-belit untuk melakukan pengeboran titik baru, mulai dari izin ke KUD, ke gubernur, dan masih banyak lagi. Ditambah, sejumlah permainan uang yang juga ternyata terjadi di sana-sini sehingga semuanya tampak semakin rumit.
#5 Badut Jalanan
Kalau membahas film dokumenter produksi Paradoks, sebenarnya ada banyak film yang bisa dimasukkan ke dalam list ini. Bahkan bisa saja saya mengambil semua film produksi mereka untuk list di dalam artikel ini, tetapi agar lebih beragam, saya hanya akan memasukkan satu film saja dari produksi mereka.
Badut Jalanan saya pilih karena kedekatan dengan keseharian saya. Saya ingin mengetahui seperti apa kehidupan para badut yang senantiasa menghibur di lampu merah Yogyakarta. Film berdurasi 21.47 menit ini menyoroti dua badut yang berasal dari latar belakang berbeda. Ada yang perantauan dan tidak memberitahu keluarga. Ada pula pelajar yang terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.
Masih dengan pakaian badut yang dikenakan, mereka berdua menceritakan jerih payah mereka. Mulai dari pertikaian dengan sesama badut karena berebut lokasi, maupun perselisihan dengan pengais rezeki di lampu merah lainnya. Penghasilan mereka tak seberapa, hanya berkisar Rp70-150 ribu, pun masih harus membayar sewa kostum badut mereka. Ditambah, mereka juga kerap menerima ejekan dari orang-orang, atau sesekali terserempet kendaraan yang kadang menerobos lampu merah.
Film ini membantah stigma masyarakat yang beranggapan bahwa mereka yang meminta-minta di jalanan selalu berpenghasilan besar. Ya, beberapa memang bisa mendapat penghasilan besar, seperti musisi jalanan dengan sound system lengkap yang pernah saya ajak ngobrol. Mereka bisa mendapat lima ratus ribu hanya dalam waktu empat jam. Pun di sisi lain, ada pula yang seperti para badut jalanan, yang hanya mendapat sedikit uang dan masih harus membayar sewa baju.
Sumber gambar: Unsplash.com