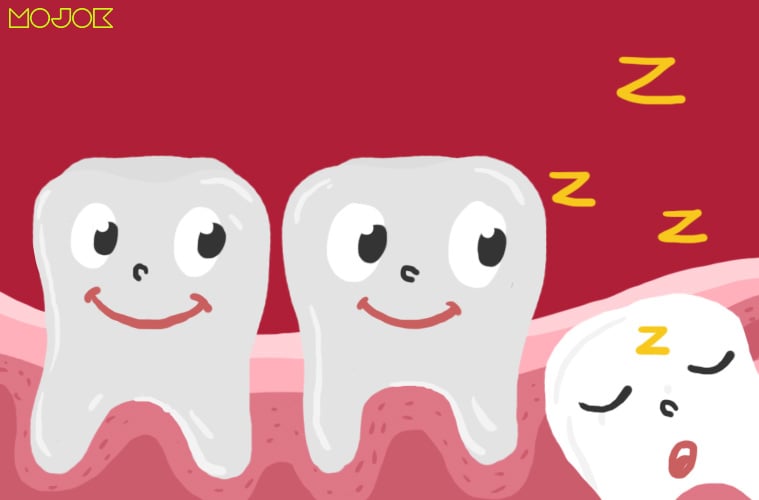Tiap kali hujan deras, bagian ruangan antara ruang tengah dan ruang tamu di rumah kontrakan saya selalu bocor. Air hujan merembes melalui ternit dan kemudian menetes ke lantai.
Rumah yang baru saya tinggali beberapa bulan setelah menikah itu pun kemudian menjadi semacam ladang perjuangan tersendiri. Tiap kali hujan, saya harus berjibaku mengambil panci atau ember untuk saya taruh tepat di beberapa titik di bawah tetesan air yang rembes akibat kebocoran tersebut.
Bagi banyak orang, rumah yang bocor adalah salah satu simbol kemiskinan. Dalam berbagai cerita tentang kemiskinan, keluarga yang melarat sering digambarkan menempati rumah yang berlantaikan tanah dan atapnya bocor, sehingga air selalu rembes tiap kali hujan.
Dengan narasi tersebut, keluarga kecil saya yang terdiri dari saya dan istri saya rasanya sudah layak untuk dicap sebagai keluarga melarat. Yah, walau lantai rumah kami tidak berlantaikan tanah, tapi kan setidaknya ada atap yang bocor.
Atap yang bocor itu membuat sensasi kemiskinan di dalam rumah kami cukup tervalidasi. Sehingga kalau kawan-kawan kami sedang berlomba unjuk kemiskinan, kami punya cukup amunisi untuk nimbrung dalam perlombaan tersebut.
Saya sengaja belum mau memperbaiki atap yang bocor itu karena beberapa alasan. Pertama, saya tak punya tangga. Kedua, saya sudah lama tidak memanjat, dan takut jatuh kalau nanti saya nekat naik ke atap. Dan ketiga, saya merasa terlalu aneh untuk membayar tukang hanya untuk memperbaiki atap yang bocor. Saya merasa, saat saya membayar tukang, maka harus ada gangguan serius yang ia kerjakan, dan atap yang bocor saya anggap tidak masuk dalam kategori gangguan serius.
Setidaknya hampir dua bulan lamanya saya dan istri saya harus gelisah tiap kali hujan. Kami harus selalu siap dan waspada. Kondisi yang setelah sekian lamanya ternyata cukup tidak mengenakkan.
Pertahanan saya akhirnya runtuh. Saya akhirnya memutuskan untuk membeli tangga dan kemudian memberanikan diri untuk memperbaiki atap rumah yang bocor.
Pada akhirnya, memperbaiki atap ternyata tak serumit yang saya kira. Hanya butuh waktu lima menit untuk menggeser salah satu genteng yang ternyata melorot sehingga kalau hujan datang airnya langsung tumpah ke ternit untuk kemudian merembes dan jatuh ke lantai.
Sesaat setelah memperbaiki atap tersebut, saya merenung, betapa bodoh dan ruginya saya sebab selama ini mengorbankan kenyamanan selama dua bulan untuk terus waspada kalau hujan datang. Padahal hanya dengan lima menit dan sedikit usaha, saya tak perlu senantiasa waspada selama dua bulan tinggal di rumah.
“Keparat, kenapa saya nggak memperbaiki genteng dari dulu, ya?” Batin saya.
Segala upaya saya dalam mengambil panci, menaruhnya, ditambah sesekali mengepelnya, selama berhari-hari tiap kali hujan datang adalah upaya yang terlalu mahal untuk ditukar dengan lima menit naik ke atap menggunakan tangga untuk kemudian menggeser satu genteng saja.
Saya jadi ingat dengan hal yang sama persis yang terjadi pada gigi saya.
Saya tak ingat sejak kapan persisnya, namun yang pasti, sejak kecil, ada satu gigi kecil yang tumbuh nyelip di antara gigi seri dan gigi taring saya. Gigi yang tumbuh tak sempurna. Dan karena tumbuh pada tempat yang salah, maka ia pun menimbulkan kesusahan tersendiri.
Gigi itu sering menimbulkan rasa ngilu. Utamanya saat gigi tersebut saya pegang dan saya goyang-goyangkan. Hal yang, entah kenapa, walau saya sadar kalau saya lakukan akan menimbulkan ngilu, tapi tetap saja sering saya lakukan.
Ngilu juga sering datang saat saya harus membrakot buah secara langsung, misal jambu atau apel. Kalau apel mungkin bisa saya hindari. Tapi jambu? Alamak, ini buah gratis yang hampir selalu menjadi sasaran penjarahan oleh saya dan kawan-kawan saya di kampung.
Saya sering kali memaksa untuk mencabut paksa gigi tersebut dengan mendorongnya dengan tangan saya keras-keras. Namun setiap kali usaha itu saya lakukan, selalu saja saya tak sanggup untuk meneruskanya karena ngilunya begitu luar biasa.
Kelak, saat buku saya terbit dan saya mendapatkan royalti yang lumayan besar, saya nekat untuk memeriksakan gigi saya. Itulah pertama kalinya saya ke dokter gigi.
Saya membersihkan karang gigi saya yang tentu saja sudah sangat kotor karena terakhir kali dibersihkan adalah dulu saat SD, itupun melalui dokter gigi puskesmas yang rutin memeriksa murid-murid SD.
Di ruangan dokter gigi itu, gigi saya dibersihkan. Ia kemudian bertanya pada saya tentang gigi kecil yang nyelip itu. Ia menawari saya untuk mencabutnya. Saya iyakan. Dan ia pun kemudian mencabut gigi tersebut dengan sangat cepat, dengan sakit yang sangat minimalis. Tak sampai sepuluh detik. Biayanya pun ternyata tak mahal. Hanya beberapa dua ratus lima puluh ribu, tak sampai berjuta-juta seperti yang saya bayangkan sebelumnya.
Lagi-lagi, setelah saya selesai memeriksakan gigi saya, termasuk mencabut gigi yang nyelip itu, saya merenung. Betapa ngilu yang saya rasakan selama bertahun-tahun karena gigi nyelip keparat itu ternyata adalah rasa sakit yang terlalu bodoh untuk saya tanggung sebab hanya dengan tindakan sepuluh detik saja dan uang yang hanya sekian ratus ribu saja, rasa ngilu selama bertahun-tahun itu tak perlu saya rasakan.
“Keparat, kenapa saya nggak ke dokter gigi sejak dulu, ya?” Batin saya.
Tampaknya memang benar apa kata orang-orang. Penyesalan memang akan selalu datang belakangan. Dan kedatangannya selalu ditumpangi oleh penderitaan dan kemalangan yang sebenarnya tak perlu kita rasakan.