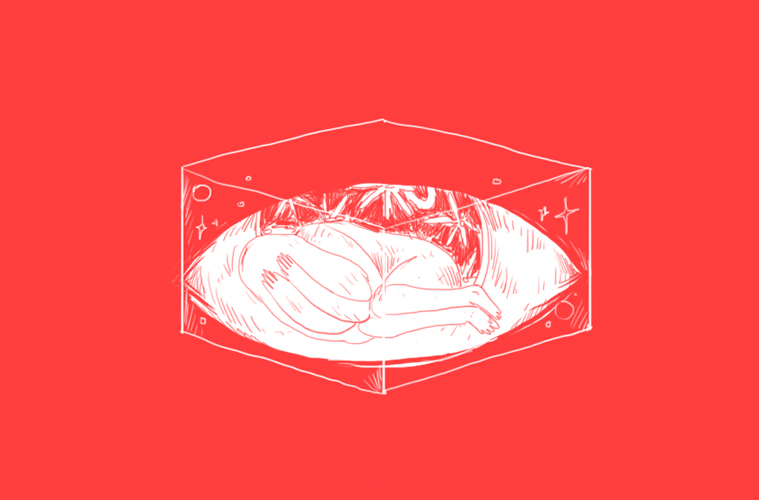MOJOK.CO – “Korban seharusnya segera lapor polisi! Kasus ini harus viral, bukti-bukti chat pelaku dan korban harus segera disebar agar pelaku jera dan tidak memakan korban lain! Korban KBG harus berani speak up ke media agar pelaku segera ditangkap!”
Itu hanya beberapa contoh kalimat–ditambah hujatan tentunya–yang biasanya terlontar ketika sebuah kasus kekerasan terungkap. Namun yang terjadi, bukannya pelaku mendapat sanksi, justru identitas korban semakin jauh dari privasi.
Siapa, sih yang tidak marah pada pelaku kekerasan, apalagi kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG), terutama kekerasan seksual, yang menimpa perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya? Dorongan rasa marah pada pelaku begitu kuat, rasanya ingin sekali pelaku segera mendapat hukuman setimpal lewat upaya diviralkan, spill the case, call out, dan cara lain yang bisa membuatnya jera.
Semuanya selalu tentang pelaku. Kita fokus pada nasib pelaku, sibuk berusaha memviralkan kasus demi sanksi sosial pada pelaku, hingga tanpa sadar kita juga spill bukti, chat, dan sebagainya yang berpotensi membuka jati diri korban. Media dan masyarakat seakan lupa bahwa ada korban yang juga perlu kita perhatikan kondisi mental, trauma, proses pemulihan, dan sekian hal yang bisa membuat posisinya sebagai korban semakin terancam.
Fokus pada pelaku, tapi lupa pada luka korban
Awal 2020, seorang perempuan korban kekerasan seksual (KS) menghubungi saya melalui akun pribadi. Dia mengalami KS yang dilakukan oleh sesama aktivis kampus, bahkan mengalami Infeksi Menular Seksual (IMS). Sayangnya, dia harus menghadapi kalimat-kalimat yang menghakimi dan menyalahkan dari seorang dokter di sebuah rumah sakit. Dia juga belum mengakses pengada layanan manapun untuk menghadapi kasusnya, sementara pelaku tetap beraktivitas dengan tenang.
Ada juga organisasi gerakan yang dengan bangganya mempublikasikan kronologi kasus lengkap lewat bukti tangkapan layar pesan antara pelaku dan korban. Semua bukti terpampang jelas, identitas korban terang-benderang hingga mau tidak mau korban harus menghadapi media tanpa pendampingan. Sementara ketika mengakses pengada layanan, korban diminta segera melaporkan kasusnya pada kepolisian. Padahal, yang dibutuhkan korban adalah pemulihan, khususnya mental, hingga berdaya.
Ketika kasus sudah viral dan identitas korban terungkap, lalu apa? Organisasi maupun individu yang awalnya semangat memviralkan atas dasar “peduli”, malah lepas tangan ketika kondisi mental korban KBG semakin terpuruk ke dasar jurang. Bahkan, kasus pun akhirnya hanya menguap di media dan tidak pernah sampai ke pengadilan. Pelaku tetap melenggang menikmati hidup, sementara para korban harus menanggung trauma seumur hidup.
Tak ada yang salah dengan rasa marah pada pelaku, itu wajar dan pada konteks tertentu memang perlu dilakukan. Namun, apakah benar korban menginginkan kasusnya viral? Apakah penyebaran informasi sudah mendapatkan persetujuan (consent) dari korban? Apakah yang menurut kita baik, baik juga menurut korban? Siapkah korban menghadapi dampaknya?
Jangan sampai, hal yang terbaik menurut kita ternyata malah membahayakan korban. Apalagi jika kita adalah orang yang dipercaya korban sebagai support system, baik sebagai teman curhat, pendamping korban, konselor, maupun psikolog.
Ironisnya, tindakan-tindakan yang kadang membahayakan korban bukan hanya dilakukan oleh individu yang mengaku peduli pada korban, tetapi juga oleh lembaga pengada layanan atau organisasi-organisasi yang selama ini melakukan advokasi pada korban KS dan KBG lainnya.
Awalnya, saya menolak percaya bahwa pengada layanan melakukan pemaksaan terhadap korban. Awalnya, saya tidak percaya bahwa ada seorang psikolog maupun psikiater yang victim blaming korban.
Mendapat kabar seorang advokat dan juga aparat penegak hukum yang secara langsung meragukan keterangan korban, hingga melakukan penghakiman atas apa yang dialami korban pun rasanya tidak masuk di akal.Sayangnya itu semua nyata. Bukannya memvalidasi pengalaman dan menguatkan korban, yang terjadi korban justru disalahkan.
Itu pun akhirnya saya alami ketika berkolaborasi atau tiba-tiba diminta mendampingi beberapa korban setelah kasusnya diviralkan salah satu organisasi gerakan perempuan. Padahal, saya sebelumnya meyakini bahwa organisasi yang selama ini melakukan pendampingan dan advokasi korban kasus KBG pasti perspektifnya sudah jelas berpihak pada korban dan berbasis empati. Namun, saya harus kecewa, bahkan beradu argumen untuk meyakinkan bahwa suara pertama yang perlu kita dengar adalah suara korban.
Persetujuan korban adalah segalanya, jangan malah memaksakan kehendak seakan korban tak memiliki keputusan atas hidupnya. Karena aktor utama adalah korban, bukan pendamping korban, maka segala keputusan harus berbasis consent dari korban yang paham pada sekian dampak yang akan dia alami di masa depan. Semuanya harus berdasar pada keputusan sadar korban, bukan pendamping atau siapa pun.
Jangan sampai korban mengalami kekerasan berulang
Dengan berpihak pada korban KBG, kita bukan hanya menguatkan mentalnya.Lebih dari itu, kita mampu mencegah korban mengalami kekerasan berulang. Apalagi ketika kita sudah memiliki pemahaman tentang keadilan gender, analisis relasi kuasa, mampu bersifat empati, hangat, dan akomodatif, punya kemampuan mendengar aktif serta memvalidasi perasaan korban, dan yang paling penting adalah tidak menghakimi korban.
Tidak jarang, budaya menyalahkan korban yang berani speak up atau victim blaming juga dilakukan oleh pihak-pihak yang diharapkan dapat membantu korban. Di berbagai lini, korban kembali dipersalahkan karena dianggap tidak melawan atau memberikan kesempatan pada kekerasan seksual untuk terjadi pada dirinya.
Seringkali, cerita korban dipertanyakan hingga korban berada dalam tekanan dan mengubah pernyataannya. Risiko-risiko itulah yang membuat banyak korban memilih untuk bungkam.
Pahami juga bahwa korban adalah manusia utuh yang memiliki keputusan sadarnya. Meskipun korban dalam kondisi tertekan dan masih sangat sulit untuk memproses situasinya, hal tersebut bukanlah alasan untuk menganggap pengalaman korban tidaklah valid. Keberpihakan dan kepercayaan yang diberikan pada korban serta pengalaman-pengalamannya merupakan dukungan terbesar yang bisa kita berikan.
Ruang aman berbasis empati dan keberpihakan terhadap korban
Tidak semua korban merasa nyaman mengakses dukungan, apalagi jika sistem pendukung di lingkaran pertama seperti keluarga ternyata menormalisasi kekerasan. Seorang perempuan penyintas kekerasan seksual memilih menghubungi ruang aman berbasis komunitas daripada keluarga, lingkaran terdekat dari dirinya. Dia memilih memikirkan dan mengatasi masalahnya sendiri tanpa kehadiran kedua orang tuanya.
Kadang kita sering mempertanyakan, mengapa begitu banyak anak yang memilih menyembunyikan masalah dari orang tuanya? Mereka berjuang sendiri, bertanggung jawab, dan mengambil risiko, bahkan ada yang mengorbankan tubuh dan jiwanya, hanya karena merasa tak ada lagi pilihan selain mengorbankan dirinya.
Namun, dalam kondisi tertentu, seseorang memang bisa saja merasa tidak ada pilihan selain mengandalkan dirinya sendiri atau bergantung pada sosok yang justru menjadi pelaku atas kekerasan yang dialaminya. Maka menjadi privilese tersendiri ketika para penyintas ini dapat mengakses ruang aman berbasis komunitas atau pengada layanan terdekat yang memiliki keberpihakan terhadap korban.
Meskipun tidak sempurna, namun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memiliki perspektif keberpihakan terhadap korban. UU TPKS memastikan hak korban untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Dalam hal ini salah satunya menekankan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat terkait kewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan seksual ke kepolisian, serta menyediakan pendampingan bagi korban (Pasal 40).
Aspek penting lainnya adalah didorongnya peran keluarga, masyarakat, hingga pemerintah pusat maupun daerah dalam pencegahan kekerasan seksual (Pasal 79-86). Salah satu bentuknya adalah dengan mewajibkan pendidikan dan pelatihan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi aparat penegak hukum. Meski demikian, UU TPKS perlu diikuti dengan perbaikan di pengaturan lain, seperti turunan peraturan institusional yang mengarah pada penguatan peran dan wewenang aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban.
Masing-masing institusi pelaksana hingga kelompok masyarakat sipil perlu mengawal implementasi UU TPKS ini, serta memastikan adanya kerangka pengawasan dan evaluasi kebijakan yang komprehensif. Kini saatnya kita memastikan bahwa UU TPKS diterapkan dan dapat bermanfaat bagi korban sebagaimana tujuan diciptakan.
Penulis: Alimah Fauzan
Editor: Agung Purwandono