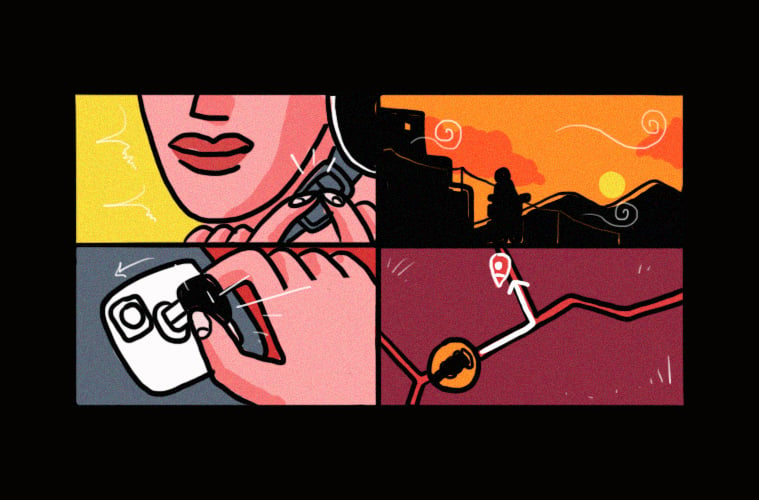MOJOK.CO – Sudah menjadi pemandangan sehari-hari di lanskap perkotaan, para driver ojol hilir-mudik mengantar penumpang, barang, atau makanan. Mereka adalah bagian dari gig economy, situasi di mana begitu banyak pekerja lepas atau freelancer bertebaran di muka bumi ini. Menjadi pekerja gig ibarat kata siap terjebak dalam kerentanan. Lantas, seperti apa kerentanan yang dialami pekerja gig perempuan?
Teknologi telah memengaruhi berbagai lini kehidupan kita. Dalam konteks ketenagakerjaan, banyak jenis pekerjaan baru yang muncul karena teknologi. Meski di sisi yang berbeda, teknologi juga menghilangkan banyak jenis pekerjaan yang lain.
Beberapa tahun belakangan, salah satu industri yang muncul dan besar karena teknologi adalah platform gig economy berbasis lokasi. Platform-platform ini menangkap kebutuhan konsumen untuk mendapatkan jasa dan barang dengan lebih mudah. Caranya, menghubungkan konsumen dengan pekerja/penjual/mitra melalui aplikasi berbasis internet. Gojek, Grab, Shopee Food, dan Maxim adalah contoh dari beragamnya aplikasi ini.
Sebagian besar dari kita kemungkinan rutin menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Melihat para pekerja berjaket hijau, orange, dan kuning di jalanan juga sudah jadi hal yang lumrah. Namun, pernahkah kita bertanya-tanya mengapa hanya sedikit perempuan yang bekerja sebagai ojek/kurir online? Apakah aplikasi online dapat memberikan keamanan dan perlindungan bagi pekerja perempuannya?
Saya melakukan penelitian tentang kondisi kerja pekerja gig perempuan, dan mewawancarai perempuan-perempuan yang bekerja di aplikasi-aplikasi gig. Cerita mereka jarang terdengar karena kebanyakan penelitian tentang gig economy bias gender, mengingat sebagian besar dari pekerja gig adalah laki-laki.
Penghasilan lebih kecil dibanding pekerja laki-laki
Jika dibandingkan dengan penghasilan laki-laki yang bekerja sebagai ojek online, penghasilan pekerja gig perempuan cenderung lebih rendah. Jika dirata-rata, penghasilan harian pekerja gig perempuan ada di angka 50-60 ribu per hari. Sedangkan, penghasilan pekerja laki-laki masih bisa mencapai angka 100-150 ribu per hari.
Salah satu faktor penyebabnya, penghasilan yang timpang ini bisa jadi karena pekerja perempuan cenderung bekerja dengan waktu lebih pendek dari pekerja laki-laki. Sebagian besar dari mereka baru mulai bekerja setelah menyelesaikan pekerjaan domestik rumah tangga di rumah, seperti: memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, dan mengantarkan anak sekolah.
Artinya, mereka baru bisa mulai “nge-bid” di jam 9 atau 10 pagi, dan harus break kembali ketika waktunya jam anak pulang sekolah. Para pekerja gig perempuan ini biasanya punya tanggung jawab untuk menjemput anak, masak makan siang, dan lain sebagainya. Bahkan, banyak juga dari mereka yang mengaku membawa anaknya sambil bekerja, hal yang sebenarnya sangat berbahaya jika dilihat dari kacamata Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Cerita yang saya dapatkan dari pekerja gig perempuan di atas, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh European Institute for Gender Equality (EIGE), yang menunjukkan bahwa beberapa daya tarik utama gig work, seperti fleksibilitas, seringkali cenderung merugikan perempuan.
Penelitian ini melaporkan bahwa perempuan rata-rata memilih menjadi pekerja gig karena mereka dapat menggabungkannya dengan pekerjaan rumah tangga dan komitmen keluarga. Namun hasilnya, banyak perempuan yang bekerja dalam jam-jam yang kurang menguntungkan, dan akhirnya mendapatkan penghasilan di bawah pekerja laki-laki.
Lebih sering kena cancel konsumen
Alasan lain kenapa pekerja perempuan cenderung mendapatkan penghasilan lebih minim adalah karena mereka lebih sering mengalami pembatalan order dibandingkan pekerja laki-laki, terutama dalam orderan ride. Menurut cerita pekerja-pekerja gig perempuan, masih banyak konsumen laki-laki yang merasa tidak nyaman jika dibonceng driver perempuan, dan karenanya memilih untuk meng-cancel jika mendapatkan driver perempuan.
Masalahnya, pembatalan-pembatalan seperti ini menyebabkan performa pekerja perempuan di aplikasi menurun. Menurunnya performa ini akan berimbas pada berkurangnya kesempatan mereka untuk mendapatkan order selanjutnya.
Pengalokasian order berdasar algoritma seperti yang dilakukan oleh aplikasi-aplikasi gig memang seringkali dikritik bias gender. Secara umum, sistem algoritma dan artificial intelligence yang di-training dengan dataset yang bias, sangat mungkin menghasilkan sistem yang menebalkan bias gender. Pekerja-pekerja gig perempuan yang di-cancel oleh penumpangnya karena alasan gender tadi, misalnya, oleh sistem hanya akan dibaca sebagai pekerja yang “tidak bisa menyelesaikan order dengan baik”, tanpa kemudian sistem bisa membaca alasan sebenarnya mereka di-cancel oleh konsumen.
Rentan mengalami pelecehan seksual
Hal menyedihkan lain yang saya temukan dari mendengarkan cerita para pekerja gig perempuan adalah pengalaman mereka mengalami sexual harassment atau pelecehan seksual. Mayoritas pekerja gig perempuan pernah mengalami pelecehan seksual selama mereka bekerja.
Bentuknya beragam, mulai dari komentar seksis di kolom rating aplikasi, berondongan pertanyaan: “Sudah nikah belum?” ; “Ngapain perempuan kok ngojol?”; hingga “Yuk, habis ini ke tempat saya sekalian”. Sampai dengan pelecehan secara fisik, seperti penumpang yang menempelkan tubuhnya selama dibonceng, memeluk dari belakang, dan lain sebagainya.
Sebagian dari mereka langsung sigap menolak dan menurunkan konsumen yang melakukan pelecehan-pelecehan seperti itu. Namun ada juga yang bilang tidak berani mengonfrontasi, dengan alasan khawatir diberi rating jelek di aplikasi. Mereka bilang, lapor ke aplikasi pun malas, karena belum tentu ditanggapi dengan cepat.
Tidak terlindungi aturan ketenagakerjaan
Status mitra yang disandang oleh pekerja-pekerja gig economy di Indonesia secara umum menyebabkan mereka tidak terlindungi oleh aturan-aturan ketenagakerjaan. Ketentuan mengenai upah minimum, waktu kerja, dan jaminan sosial, misalnya, tidak berlaku kepada mereka. Sehingga, kebanyakan berada dalam kondisi yang lebih rentan jika dibandingkan dengan pekerja dalam hubungan kerja.
Dalam konteks pekerja perempuan, ketiadaan perlindungan ini berefek lebih berat. Karena artinya, mereka tidak bisa mengakses hk-hak dasar maternitas seperti cuti melahirkan. Akibatnya, beberapa pekerja gig perempuan yang saya temui tetap bekerja hingga hamil besar, dan segera kembali bekerja setelah mereka melahirkan. Hal yang lagi-lagi sangat berbahaya jika dilihat dari perpektif Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
Peluang di tengah keterbatasan
Membaca pengalaman-pengalaman di atas, pembaca mungkin bertanya: Lalu, kenapa perempuan-perempuan ini tetap bertahan bekerja sebagai ojek/kurir online?
Sebagian dari mereka menjawab: Karena tak ada pilihan lain. Lebih lagi, pekerjaan ini memberikan mereka fleksibilitas yang tidak bisa ditawarkan oleh pekerjaan lain.
Bagi banyak dari pekerja perempuan ini, ekonomi gig tetap dipandang sebagai peluang karena mereka rata-rata merasa tidak akan bisa lagi mendapatkan pekerjaan lain di usia yang sekarang. Seperti kita ketahui, diskriminasi usia dalam lowongan pekerjan di Indonesia adalah hal yang dianggap wajar. Sehingga, bagi perempuan-perempuan yang sempat berhenti bekerja karena hamil, melahirkan, dan mengurus anak; kesempatan untuk mencari pekerjaan baru ketika mereka sudah masuk usia 30an bukanlah perkara mudah.
Di sinilah kesempatan untuk bekerja sebagai ojol, kurir online, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ditawarkan oleh platform gig, dilihat oleh para pekerja perempuan sebagai pilihan satu-satunya bagi mereka. Belum lagi, bekerja sebagai mitra Gojek, Grab, Shopee Food, Maxim, dan berbagai aplikasi lain, memberikan mereka ruang untuk tetap mengerjakan tanggung jawab rumah tangga dan mengurus anak.
Bagi banyak perempuan yang saya wawancarai, gig economy kemudian dipandang sebagai juru selamat. “Setidaknya saya setiap hari dapat uang untuk masak besok, Mbak,” kata salah satu dari mereka.
Di sinilah pentingnya negara berperan untuk mengintervensi. Jika memang gig economy adalah masa depan karena pekerjaan-pekerjaan turunan dari teknologi memang tidak bisa dibendung, sudah jadi kewajiban negara untuk membuat kebijakan yang dapat memastikan bahwa pekerja-pekerja yang berada di jalanan, menggerakkan ekosistem gig ini, dapat terlindungi dengan baik.
Penulis: Nabiyla Risfa Izzati
Editor: Amanatia Junda
BACA JUGA Isu Pekerja Perempuan yang Penting Dibahas Saat Musim Kampanye dan Pemilu