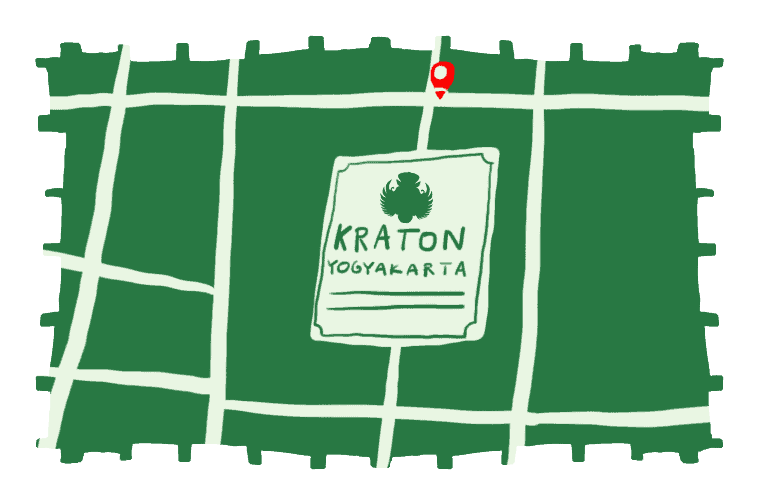

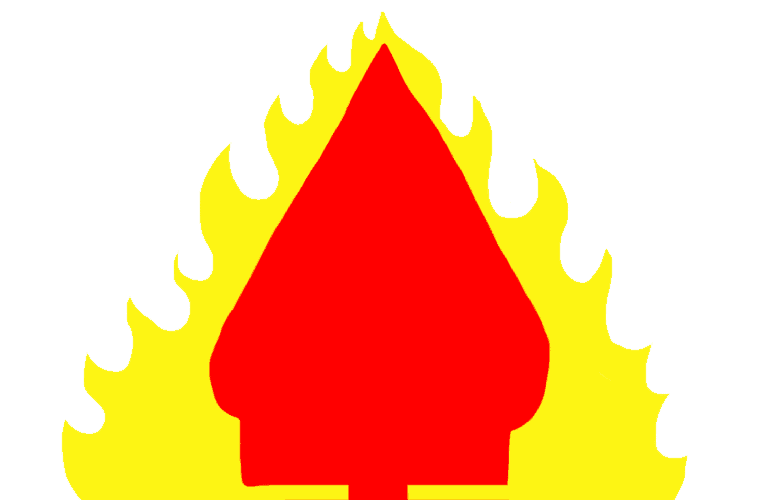
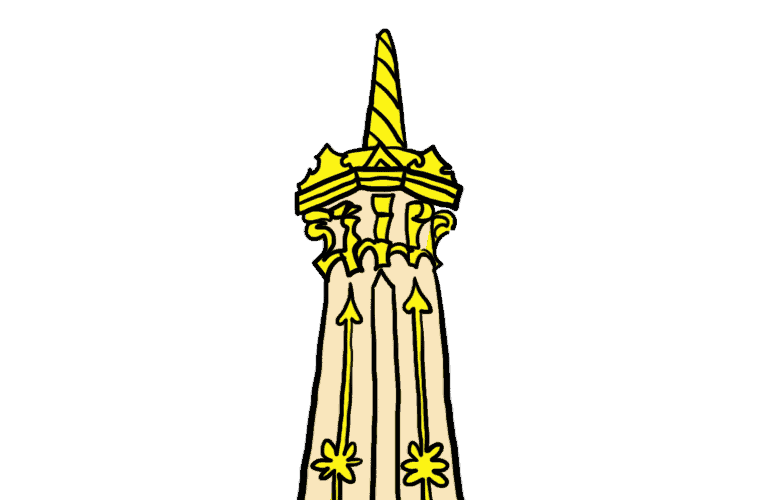
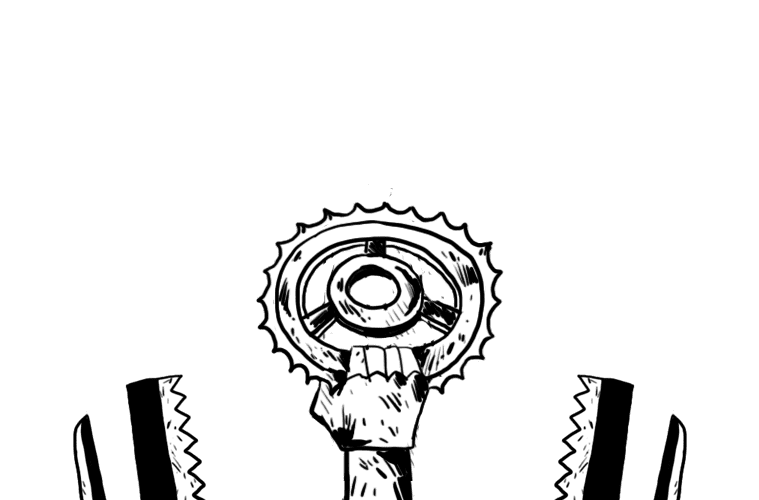


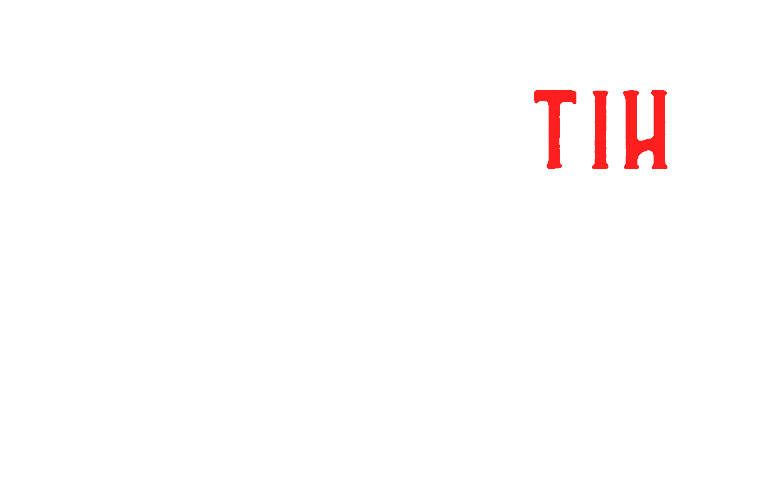

Menelusuri Akar Klitih di Jogja
Klitih atau kejahatan jalanan jadi momok menakutkan di Jogja satu dekade belakangan. Pelaku terkadang menyasar korban secara acak. Pelajar, pekerja, dan warga sipil yang tak tahu menahu jadi sasaran. Klitih membuat darah tumpah di jalanan Jogja.
Sebelum istilah klitih muncul, Jogja memang punya sejarah panjang tentang kekerasan di jalan. Beberapa dekade silam, beberapa geng legendaris pernah mewarnai jalanan. Rivalitas tumbuh antar satu geng dengan yang lain. Saling serang jadi kebiasaan. Namun, menurut pelaku sejarah, apa yang terjadi dulu punya perbedaan dengan klitih yang marak beberapa tahun belakangan.
Mojok mencoba menggali cerita kekerasan jalanan di Jogja dari era geng legendaris sampai era klitih atau kejahatan jalanan di Jogja. Menelusuri motif mengapa pelaku klitih hari ini, begitu acak memilih korban. Hingga darah tumpah bahkan nyawa jadi taruhan.
Kenangan Ervian Parmunadi (55) melayang jauh ke masa mudanya. Pada 1985, saat usianya tujuh belas tahun dan masih duduk di bangku SMA, bersama beberapa rekan ia mendirikan salah satu geng legendaris di Jogja bernama Joxzin.
Keberadaan geng setelah Petrus mereda

Momen itu terjadi tak lama setelah geger penembakan misterius (Petrus) 1983 di Jogja. Petrus adalah operasi rahasia Orde Baru untuk menanggulangi kejahatan yang tinggi saat itu. Sasaran utamanya saat itu adalah gali atau preman. Jogja menjadi kota pertama dimulainya operasi ini. Operasi ini berakhir di tahun 1984.
Nama Joxzin berasal dari tempat tongkrongan mereka di daerah Kauman, di dekat lokasi bernama Pojok Bensin. Generasi pertama Joxzin, menurut Ervi, diisi oleh remaja usia 15-17 tahun.
“Pokoknya saat itu, kami rata-rata kelahiran 1968-1970,” ujarnya sambil menyesap rokok kretek. Ervi saya temui di sebuah warmindo yang terletak di Jalan Tamansiswa pada Kamis (23/2). Ia meluangkan waktu sebelum menghadiri sebuah rapat bersama beberapa koleganya.
Era Joxzin bersamaan dengan beberapa geng besar lain di Jogja seperti Qzruh dan TRB. Ketiganya punya corak berbeda. Joxzin misalnya, anggotanya mayoritas berasal dari kampung Kauman, Kotagede, dan Karangkajen. Daerah tersebut dikenal sebagai basis salah satu ormas Islam besar sehingga kebanyakan remaja tersebut punya pandangan yang sama.
Sedangkan Qzruh dan TRB berasal dari daerah lain yang tentu punya kecenderungan corak ideologis yang berbeda. Hal ini menurut Ervi membuat tiga geng besar di Jogja saat itu dengan mudah bisa terasosiasi ke partai politik tertentu.
“Ada tiga geng besar dan saat itu ada tiga partai besar di Indonesia. Merah, kuning, hijau. Jadi jelas sudah,” terangnya.
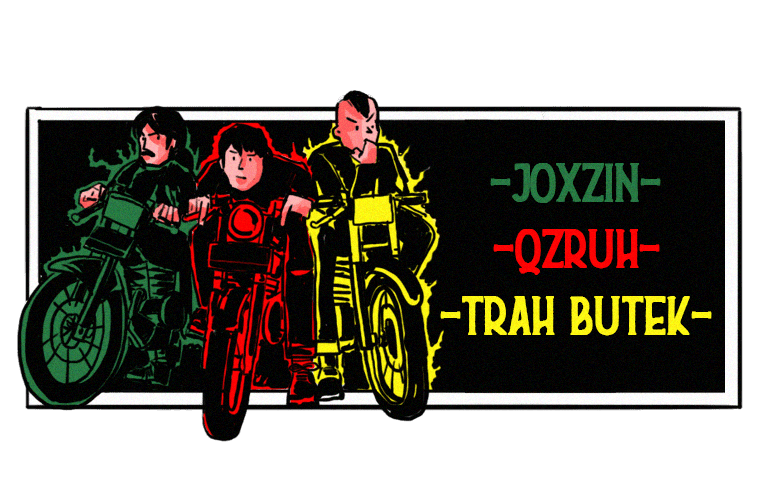
Jaya di era 1990-an
Akhir 1980-an sampai awal 1990-an menjadi masa kejayaan buat Joxzin. Mereka punya banyak anggota. Sekali kumpul, hampir seratus motor bisa berderet memenuhi pinggiran jalan. Bahkan lebih dari seratus kalau sedang ada acara besar tertentu.
Motor sebanyak itu, juga terkadang terlibat pada pertempuran antargeng di jalanan. Ervi mengingat bahwa hampir setiap bulan ada saja pertikaian di jalan. Biasanya salah satu geng mubeng di malam hari. Di jalan, sengaja atau tidak, mereka kerap berpapasan dengan rombongan rival. Seketika pertempuran tak terelakkan.
Saat itu dengan alat komunikasi yang belum secanggih sekarang, mereka tak bisa leluasa saling berkabar. Tak mudah untuk mengetahui lokasi pasti lawan di jalan. Berbeda dengan sekarang, setiap pergerakan massa besar bisa terlacak di lini masa media sosial.
“Kalau (ribut) yang besar-besar itu sering juga. Pernah di jalan sekitar Kotagede, Kauman, sampai Kaliurang”
“Kalau (ribut) yang besar-besar itu sering juga. Pernah di jalan sekitar Kotagede, Kauman, sampai Kaliurang,” kenang mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 ini.
Berkeliling menggunakan motor secara rombongan memang kerap dilakukan secara sengaja. Pertikaian menjadi hal yang mereka cari.
“Memang sengaja golek-golek musuh kadang-kadang,” ujar lelaki dengan rambut sudah beruban ini. Senyum merekah saat mengingat masa mudanya yang sarat akan kekerasan.
Pertikaian skala besar biasanya terjadi di malam hari. Sedangkan untuk perkelahian senggel atau satu lawan satu antar-anggota kerap mereka lakukan di siang hari. Pelaku yang hendak melakukan senggel ini umumnya sudah membuat janji. Jalan ini mereka tempuh jika merasa punya masalah personal dengan salah satu anggota geng.
Apa yang geng-geng ini lakukan menurut Ervin adalah upaya pencarian jati diri. Ada kebanggaan tersendiri. Mereka tidak saling berebut daerah kekuasaan atau daerah palakan. Hanya unjuk gigi adu kekuatan di jalan.
Ervin sedikit menunduk lalu menoleh ke kanan dan kiri, seolah memperlihatkan badannya. Ia mengaku tak pernah mengalami luka serius akibat kekerasan jalan yang ia lakoni bersama rekannya. Namun, ia pernah melihat adiknya menjadi korban pembacokan.
“Adik saya selisih empat tahun di bawah saya. Dia juga gabung Joxzin,” terangnya.
Saat itu adiknya sedang berkeliling dengan enam orang rombongan berboncengan dengan tiga motor. Saat tiba-tiba ada sekelompok lain datang mendekat. Seketika menebas senjata tajam ke kepala. Tanpa menggunakan helm, adik Ervi pun harus mendapat luka. Tujuh jahitan di kepala pun ia terima.
Mengaku tak pernah asal bacok

Tapi, ketika itu, rekan-rekan Joxzin langsung mengetahui siapa pelaku dan motif di balik penyerangan itu. Ervin yakin bahwa otak di balik hal ini adalah konflik antargeng yang sedang mereka jalani.
“Dulu sasaran kita jelas. Ya hanya menyasar anggota geng lain yang sedang punya masalah. Mereka juga sama-sama bersenjata, kok,” terangnya.
Setiap hendak melakukan serangan, ia mengaku mengamati secara detail. Ketika bisa memastikan bahwa itu dari kelompok musuh, syukur-syukur sama-sama membawa senjata tajam, maka mereka segera menghantam.
“Pokoknya kalau zaman dulu itu dimatke tenanan. Barangkali keliru, kita khawatir juga. Setelah itu, kami serang dan kelahi di jalan,” paparnya.
Meski begitu, Ervi mengakui kalau dulu tidak ada mekanisme khusus untuk mencegah salah sasaran selain berupaya memperhatikan betul calon lawan. Namun, biasanya mereka sudah familiar dengan ciri-ciri kelompok yang akan mereka serang.
Hal itu dimudahkan dengan sebaran anggota geng yang berasal dari beragam sekolah dan kampung. Ada banyak anggota geng yang bersekolah atau bertetangga kampung dengan anggota geng rival sehingga mudah untuk mengenalinya.
“Tapi ya kadang ada miss. Kalau salah sasaran ya, berarti podo siale,” ujarnya.

Menyayangkan klitih yang asal sikat
Hal itu berbeda jauh dengan fenomena klitih yang marak di Jogja belakangan. Ervi mengaku tindakan yang dulu ia lakukan bersama kelompoknya membuat resah masyarakat. Namun, ia menegaskan kalau dulu tidak pernah asal bacok dengan warga sipil tak bersalah.
“Nggak ada ceritanya kami waton bacok orang di jalan. Orang mau ke pasar kena pedang, mahasiswa diganggu. Itu hal-hal yang tidak terjadi di zaman kami,” katanya.
Ia mengaku bingung dengan pola yang terjadi sekarang. Dulu, aparat kepolisian dengan mudah bisa menandai para pelaku dan orang yang berpotensi melakukan hal serupa. Hal itu lantaran anggota geng dan afiliasinya mudah dikenali.
“Kadang saya jadi bingung, ini kok ada anak SMA Muhammadiyah nyerang sesama SMA Muhammadiyah”
“Kalau sekarang, mereka berkelompok berdasarkan apa juga kurang jelas. Kadang saya jadi bingung, ini kok ada anak SMA Muhammadiyah nyerang sesama SMA Muhammadiyah,” paparnya.
Menurut Ervi, Joxzin lawas generasi 85 setelah 1992 sudah mulai jarang berkegiatan lagi. Hal itu sejalan dengan beberapa arsip pemberitaan pada 1993. Salah satunya Harian Kompas yang merilis berita mengenai aksi tawuran remaja yang masif di Jogja pada awal 1990-an.
Hal itu membuat Kepolisian Wilayah DIY saat itu, mulai melakukan pemetaan keberadaan geng di Jogja. Di antaranya Joxzin dan Qzruh. Pemetaan ini membuat polisi dengan mudah bisa mengawasi pergerakan geng saat melakukan perkumpulan.

Menolak disebut akar klitih
Setelah masa itu, generasi penerus dengan membawa bendera yang sama masih ada. Namun, gerakannya tidak semasif dahulu. Mereka juga sudah tidak menyemai konflik yang telah tertimbun lama. Joxzin misalnya, masih punya anggota, namun lebih kerap berasosiasi dengan sayap partai politik dan eksistensinya lebih terlihat saat masa kampanye politik.
Pada 2017, Joxzin lawas generasi Ervi kemudian berkumpul kembali. Mereka mulai membangun jejaring dengan visi yang berbeda dengan sebelumnya. Mereka ingin berbagi manfaat melalui dua koridor utama yakni sosial dan keagamaan.
“Ini juga sebagai salah satu upaya penebusan dosa,” terangnya.
Maka ketika beberapa waktu lalu, muncul tudingan melalui pemberitaan Tempo.co bahwa sejumlah geng lawas Jogja seperti Joxzin dan Qzruh sebagai akar klitih, sejumlah tokoh angkat suara. Brigade Joxzin, yang mendaku sudah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan mengaku keberatan dengan tudingan tadi.
Ervi juga mengatakan bahwa, menganggap apa yang mereka lakukan dahulu sebagai akar klitih merupakan hal yang tidak tepat. “Jauh panggang dari api,” tegasnya.
“Nakal kok diturunkan? Jadi ketika ada yang mengaitkan dengan kami, kami anggap lucu saja,” terangnya seraya tertawa.
Selain Ervi, Mojok sempat menghubungi mantan anggota Joxzin dan sejumlah geng lawas lain di Jogja. Beberapa di antaranya enggan berbagi cerita. Selain itu, hingga tulisan ini tayang, ada pula yang belum merespons permohonan wawancara.

Melacak sejarah klitih
Kemunculan fenomena klitih beserta berkembangnya istilah tersebut untuk menggambarkan kejahatan jalanan memang muncul jauh setelah era Joxzin lawas. Ada beberapa versi tentang yang menyebutkan awal kemunculan istilah ini.
Klitih, secara bahasa dapat diartikan sebagai aktivitas arti jalan-jalan mencari angin atau keluyuran. Namun istilah ini mengalami pergeseran makna di Jogja.
Tahun 2002, di Jogja siswa SMAN 1 Jogja bernama Andhika Adityaputra meninggal dunia terkena paser atau paku yang dibuat pipih yang mengenai jantungnya. Saat itu ia sedang nongkrong di dekat SMAN 9 Yogyakarta bersama dua orang temannya. Ada serangan dari pelajar sekolah lain yang saat itu bermusuhan dengan SMAN 9. Andhika bisa disebut korban salah sasaran. Saat itu, seperti dikutip dari Liputan6.com edisi 15 Oktober 2002, istilah klitih sebagai bentuk tindak kriminal belum muncul.
Sosiolog kriminal UGM, Soeprapto berpendapat bahwa pergeseran makna itu mulai terasa sejak 2004. Fenomena ini mulai terasa saat Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat kebijakan sanksi bagi pelajar yang terlibat tawuran. Jika terlibat tawuran pelajar akan dikeluarkan dari sekolah.
Tren tawuran yang terjadi sejak lama, pascapendisiplinan itu, membuat remaja ini merasa terbatasi dan tak punya ruang untuk menonjolkan eksistensi dirinya. Sehingga mulai timbul kejadian-kejadian penyerangan di jalan secara masif.
“Akhirnya sekarang mengisi waktu luang tapi ditumpangi mencari musuh sehingga setiap kali bilang klitih maknanya menjadi mencari musuh,” ujar Soeprapto kepada Liputan6.com.
Salah satu peristiwa di Jogja yang cukup menghebohkan lainnya adalah meninggalnya siswa SMAN 6 Yogyakarta karena pelajar dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta di tahun 2009. Serangan itu dinilai salah sasaran karena di zaman geng sekolah, musuh bebuyutan SMAN 6 adalah SMAN 4 Jogja.
Era itu sebutan klitih masih identik dengan serangan dari sekolah lain kepada sekolah musuhnya.
“Tahun itu, misalnya nih SMAN 6 musuh tawuran SMAN 4. Kalau pulang sekolah atau malam Minggu biasanya pada motor-motoran, sebutannya udah klitih. Ntar kalau ketemu anak SMA 4 ya dipukul gitu, tapi kalo bukan ketemu sekolah musuh, ya keliling motoran biasa,” kata alumni SMAN 6 Jogja yang nggak mau disebutkan namanya.
Peristiwa meninggalnya siswa SMAN 6 Jogja, mengubah sekolah tersebut. Sebelumnya, sekolah di Terban ini dikenal memang jago tawuran. Namun, sejak peristiwa tersebut sekolah ini dikenal sebagai sekolah riset bahkan ditetapkan sebagai “The Research School of Jogja” yaitu sekolah tingkat SMA yang berbasis riset atau penelitian yang pertama di Jogja dan Indonesia.
“Zaman itu klitih itu paling bawa batu, paling mentok bom molotov,” katanya. Masa-masa itu ia mengingat, hampir semua pelajar di Jogja memakai jaket. Itu untuk menutupi badge sekolah. Kalau pun tidak, para pelajar akan menggunakan badge yang bisa dilepas.
Cerita tentang klitih yang identik dengan serangan dari geng di sekolah kepada sekolah lain, bisa dibaca di liputan Mojok sebelumnya, “Sisi Lain dari Klitih Anak Sekolah di Yogyakarta”.
Perlahan istilah klitih semakin berkembang, bukan lagi serangan dari sekolah lawan. Media mulai menggunakannya sebagai istilah untuk mendeskripsikan kejahatan jalanan di Jogja pada pemberitaan. Melalui sejumlah penelusuran, pada 2014 sejumlah media mulai masif menggunakan istilah ini untuk menyebut penyerangan yang dilakukan secara acak.
Satu dekade belakangan, kasus klitih telah banyak memakan korban. Baik korban dengan luka hingga korban yang meregang nyawa. Hal ini menunjukkan klitih yang semakin marak di jalan.
Kengerian klitih
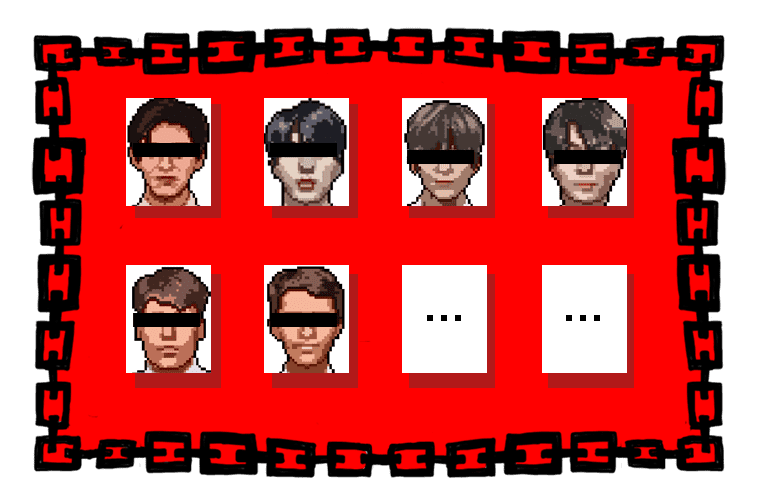
Selama kurun waktu 2016-2022, ada sejumlah kasus kejahatan jalanan yang menimbulkan korban jiwa. Hal ini menjadi gambaran kengerian klitih yang menjadi momok bagi warga Jogja. Jogja Police Watch (JPW) mencatat sejumlah aksi brutal klitih yang membuat korban meregang nyawa sebagai berikut :
Aksi klitih sempat sedikit mereda saat pandemi. Pembatasan mobilitas berdampak pada turunnya angka kriminalitas jalanan. Sepanjang 2021 tercatat ada 58 laporan polisi terkait kejahatan jalanan. Pada pertengahan 2022 lalu, kepada Mojok, Humas Polda DIY menerangkan bahwa pelonggaran pembatasan mobilitas setelah pandemi mereda, melonjaknya angka kasus tersebut. Kasus pada enam bulan pertama 2022 telah melampaui sepanjang 2021.
Sleman memang menjadi daerah dengan angka klitih tertinggi di DIY. Kota Yogyakarta menyusul di peringkat kedua, kemudian Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Merdeka.com pernah menghimpun data mengenai lokasi klitih klitih berdasarkan kecamatan sejak 2016-2022. Kecamatan Depok, Sleman menduduki peringkat pertama dengan 13 kasus pada periode tersebut.
Untuk tindak kejahatan yang dilakukan di tahun 2022 menurut laporan Polda DIY berupa pengeroyokan, perusakan, penganiayaan, dan hingga sekadar membawa senjata tajam.
Sebenarnya, pihak Polda DIY dan jajaran mengaku telah memprediksi adanya lonjakan ini. Yuliyanto menegaskan pihak kepolisian selalu melakukan kegiatan berdasarkan prediksi, perkiraan, dan hasil evaluasi yang dilakukan secara rutin.
“Kegiatan Polda DIY dan jajaran berupa kegiatan yang bersifat preemtif, preventif, dan represif untuk menciptakan situasi kamtibmas yg kondusif di wilayah DIY,” tegasnya saat itu.

Pola klitih
Pada data kajian kenakalan anak di jalanan di DIY milik Pemda DIY, tampak ada pola dari kasus-kasus klitih yang terjadi. Kajian itu mencatat sampel kasus kejahatan jalanan pada rentang 2018-2021. Mayoritas kasus terjadi pada bulan Desember-Januari.
Selain itu, ada temuan menarik mengenai motif pelaku kejahatan jalanan pada rentang waktu tersebut. Data ini membagi tiga jenis motif yakni balas dendam atau rasa tidak suka, ekonomi, iseng, dan tanpa motif. Balas dendam dan rasa tidak suka mendominasi motif kasus yang terjadi di seluruh kabupaten/kota di DIY.
Mengurai masalah klitih
Sementara itu, sosiolog UGM, Andreas Budi Widyanta berpendapat bahwa persoalan kejahatan jalanan di Jogja perlu ditinjau secara lebih mendalam. Sejak awal ia mengingatkan bahwa kejahatan jalanan yang pelakunya di bawah 18 tahun baiknya disebut sebagai kenakalan anak di jalanan.

“Bahwa dia melakukan kriminalitas betul. Tapi merujuk ke SPPA, jika masih di bawah umur kita sebutnya kenakalan anak di jalanan,” terangnya.
Andreas lalu menyoroti tiga hal yang menurutnya telah tergerus sehingga tumbuh potensi liar di diri remaja. Ketiganya yakni pendidikan (sekolah), keluarga, dan masyarakat. Ketiga hal ini menurutnya merupakan konsep tri pusat pendidikan.
“Saat ini semua orang dibentuk menjadi bersifat individual. Sekolah mendorong mereka untuk kompetitif, keluarga dan masyarakat juga melakukan hal serupa,” terangnya.
“Kita melihat sekarang banyak anak mengalami defisit dari sisi afeksi di keluarga. Orang tua fokus dan sibuk bekerja. Afeksi pada anak jadi berkurang. Mereka tidak mendapat perhatian di rumah,” paparnya.
Kurangnya afeksi di ranah keluarga membuat anak kemudian mencari perhatian di luar. Di sisi lain, sekolah juga penuh tekanan. Ia melihat ruang kebahagiaan anak di sekolah seperti kegiatan olahraga hingga agenda class meeting juga merupakan agenda yang minor.
“Anak menjadi stress dan tidak punya ruang kebahagiaan”
Anak kemudian mencoba untuk mencari ruang di masyarakat. Namun di ranah ini, anak yang terlanjur dianggap bengal dan nakal kerap mendapat menjadi korban stigma. Anak dengan karakteristik kerap melawan aturan mendapat anggapan tidak normal dan kurang mendapat penerimaan.
“Tudingan seperti itu membuat anak tidak punya ruang di masyarakat juga. Lalu ke mana anak-anak ini larinya? Ya ke jalanan pada akhirnya,” tegasnya.
Ketiadaan ruang kebahagiaan di tiga aspek tadi membuat sebagian anak tumpah ruah ke jalan. Di jalanan, potensi masuk ke lingkaran yang cenderung negatif muncul. Hal itu mendorong mereka menyalurkan energi berlebih dengan cara-cara yang merugikan orang lain.
“Hasil riset saya 2022 lalu untuk Pemda DIY menunjukkan, usia rawan itu ada di kelas 9, 10, dan 11,” terangnya.
Pada usia itu, proses sentuhan dengan geng kerap muncul. Proses transfer nilai tidak hanya terjadi di sekolah, namun juga di luar. Bahkan Andreas berpendapat banyak reproduksi kekerasan secara senyap yang terjadi di luar sekolah. Misalnya antara alumni dengan anggota baru di geng sekolah. Hal yang mungkin tidak disadari pemangku kebijakan di sekolah.
“Pada dasarnya sekolah tidak bisa mengontrol mereka berelasi di mana,” ujarnya.
Selanjutnya, Andreas melihat ketika anak sudah masuk ke lingkaran negatif dengan kekerasan, sekolah punya kecenderungan untuk mempersuasi mereka agar keluar. Anak dianggap merepotkan dan mencemarkan sekolah lewat perilakunya. Andreas melihat bahwa ini membuat anak semakin tak memiliki ruang yang menerimanya.
“Maka yang terjadi, kanal yang terdekat, ruang jalanan dipilih sehingga mereka menyalurkan adrenalin secara tidak sehat di sana,” terangnya.
Tidak ada jalan pintas
Melihat persoalan yang terjadi, Andreas yakin bahwa pengentasan kenakalan anak di jalanan membutuhkan proses panjang. Pada beberapa kesempatan, pihak kepolisian di DIY juga mengatakan pentingnya peran orang tua hingga masyarakat pada proses pencegahan kasus.
“Kita nggak bisa menyalahkan satu entitas saja dalam persoalan ini. Persoalan pada tri pusat pendidikan yang menjadi permasalahannya,” terangnya.
Ia juga beranggapan, minimnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di Jogja turut menyumbang peran pada persoalan kekerasan di jalanan. Anak muda perlu mengakses ruang yang bisa mereka gunakan untuk mengekspresikan diri.
Sejatinya kenakalan anak di jalan tidak hanya terjadi di Jogja. Andreas menganggap sorotan terjadi ke Jogja karena daerah ini merupakan parameter untuk beragam hal. Terkhusus urusan pendidikan. Sehingga saat ada persoalan semacam ini menimbulkan perhatian yang besar.
Ia mengingatkan perlunya masyarakat Jogja untuk tidak sekadar menyalahkan subjek individu pada persoalan ini. “Inilah watak neoliberalisme. Ketika ada ketidakberesan maka subjek individu yang dipersalahkan. Tidak menjadikan sistem sebagai persoalan,” pungkasnya.
***
Menelusuri akar klitih tak semudah mencari siapa pelaku kejahatan jalanan itu sendiri. Menurut peneliti arsip, Muhidin M Dahlan, klitih bukan sesuatu yang muncul begitu saja; kenakalan remaja belaka. Ada jejak panjang kekerasan yang terjadi di Yogyakarta, bahkan sejak masa Mataram Islam. Tulisan Muhidin M Dahlan di Mojok yang berjudul “Jogja (Menuju) Kota Bandit” memberikan perspektif tentang persoalan sesungguhnya.




