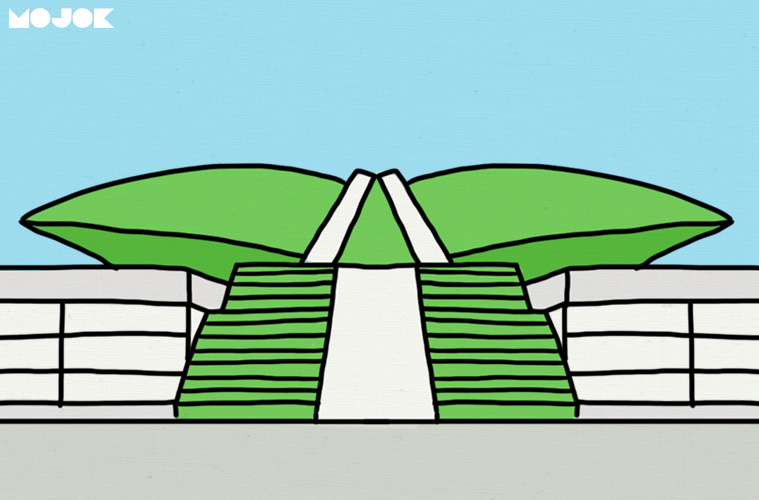MOJOK.CO – “Tahu kosakata ngeyel? Nah, DPR itu ahlinya ngeyel. Revisi UU MD3 contoh termutakhirnya.”
Politisi Senayan selalu tahu cara menjadi sorotan media. Belum reda dengan masalah dugaan lobi politik antara Komisi III dan Hakim MK Arief Hidayat mengenai pemilihan kembali dirinya sebagai ketua MK, yang kemudian memunculkan gelombang publik meminta Arief mundur dari MK, DPR kembali merebut perhatian dengan mengesahkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD (UU MD3).
Wajar sekali pengesahan UU MD3 kemarin bikin resah, bikin orang menduga-duga, permainan apa sih yang sedang dimainkan DPR? UU ini rentan di-uji ke Mahkamah Konstitusi ini, dan kalau publik ingat, dalam setahun terakhir, ini kali kedua DPR melangkahi putusan MK.
Tahu kata ngeyel? Ini contoh terbaik untuk menjelaskan arti kata itu.
Yang pertama soal hak angket KPK. Awal 2017, bersamaan dengan mulai panasnya pengusutan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Papa Setnov, tiba-tiba DPR melancarkan Hak Angket terhadap KPK.
Padahal, jika kita runut putusan MK 2006 silam, yaitu putusan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, KPK bukanlah bagian dari pemerintah (lembaga eksekutif). Artinya? KPK bukan objek hak angket DPR. Setelah keributan Hak Angket itu, awal tahun 2018 ini MK di bawah Yang Mulia Arief Hidayat memutuskan bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif.
Saat itu, sempat muncul pendapat mengenai perluasan objek Hak Angket dengan memperluas makna “pelaksana undang-undang”. Karena KPK adalah “pelaksana undang-undang”, maka ia bisa menjadi objek hak angket DPR. Perluasan tersebut potensial menjadi sangat bias: siapa pun dia, asal “pelaksana undang-undang”, bisa di-Hak-Angket-kan oleh DPR.
Misalnya, buzzer politik macam Mas Iqbal Aji Daryono. Apabila blio taat membayar pajak, blio adalah pelaksana undang-undang. Ibu-ibu di jalan yang menyalakan sign ke kiri dan benar-benar belok kiri juga merupakan pelaksana undang-undang. Nah, bisa-bisa, hanya soal Hak Angket, DPR akan sibuk mengabsen satu per satu orang yang ngemplang pajak atau salah nge-sign. Sangat tidak berfaedah dan membuat duo FF tak punya waktu lagi untuk mengkritik presiden.
Persoalan yang kedua menyangkut revisi UU MD3 tadi. Revisi yang disahkan kemarin itu intinya menyatakan bahwa jika penegak hukum ingin melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada anggota dewan yang terlibat kasus pidana, proses itu harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Mong-ngomong, aturan ini adalah aturan main lama yang sudah pernah dibatalkan lewat Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014. Alasan pembatalannya: unsur pengaturan itu dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan bermasalah secara rasionalitas hukum.
“Bahwa anggota DPR sebagai subjek hukum, terlepas dari jabatannya sebagai anggota dewan, harus diberlakukan sama di hadapan hukum. Aturan tersebut telah memberikan keistimewaan terhadap anggota DPR yang sedang menjalani proses hukum tanpa rasionalitas hukum yang jelas,” begitu kutipan pertimbangan dalam putusan MK tersebut.
Bisa dibayangkan keistimewaan anggota dewan di UU MD3 yang sudah disahkan ini. Jika ada anggota dewan yang terlibat dalam sebuah kasus pidana, kasusnya tidak bisa langsung dipolisikan. Kasus tersebut harus dilaporkan dulu ke MKD untuk dimintakan pertimbangan. Padahal kita tahu siapa yang ada di lembaga ini. Yak, betul, sesama anggota dewan sendiri, kawan seperjuangan.
Pada akhirnya, asas peradilan yang bebas dari intervensi, cepat, dan sederhana hanya diberlakukan untuk rakyat biasa. Untuk anggota dewan, asas peradilan yang berlaku adalah “bisa di-pool dulu di MKD”. Kayak bis.
Selain itu, revisi ini juga memasukkan aturan yang mengindikasikan bahwa DPR sedang ingin menjadi lembaga terakreditasi “A” alias “Antikritik”. Di kala ujung tombak DPR, duo FF, sedang nyaring-nyaringnya mengkritik pemerintah yang berusaha memasukkan rumusan pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, justru DPR sendiri yang malah mengesahkan aturan sejenis dalam undang-undangnya.
Bunyi aturan dalam UU MD3 yang telah disahkan pada intinya memberikan kewenangan kepada MKD untuk dapat mengambil langkah hukum terhadap orang, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR.
FYI aja, pada dasarnya dalam konsep negara Indonesia, setiap lembaga negara termasuk DPR memiliki hak untuk dijaga kehormatannya oleh rakyat. Namun, memberikan bumbu ancaman di dalam ruang-ruang kritis terhadap sebuah lembaga negara bukanlah cara yang tepat untuk menjaga kehormatan.
Persoalan di ataslah yang kemudian dikait-kaitkan dengan hak imunitas. Hak imunitas adalah hak kekebalan anggota DPR untuk tidak dapat dituntut di pengadilan. Di satu sisi, hukum memang memberikan keistimewaan imunitas tersebut kepada setiap anggota dewan. Namun, hak imunitas yang melekat tujuannya untuk memfasilitasi anggota DPR memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk berlindung di balik kejahatan yang pernah atau akan dilakukan. Bukan juga untuk meniadakan kritik-kritik dari rakyat dan konstituennya sendiri. Itulah kenapa hak imunitas diberikan bukan tanpa batas. Jika anggota dewan memperjuangan kepentingannya menggunakan cara yang menabrak aturan, nir-etika, dan melanggar moral, hak itu sudah pasti harus gugur dan tidak lagi bisa dijadikan sebagai alasan untuk kebal hukum.
Seseorang pernah mewariskan cerita kepada saya mengenai cara mendapatkan ilmu kebal. Salah satunya dengan meditasi. Meditasi paling tepat untuk menahan diri dari godaan yang berbau duniawi. Yang kedua dengan puasa. Dengan cara berpuasa, manusia dilatih untuk menahan diri dari sifat konsumtif sehingga lambat laun akan kebal dari rasa lapar.
Saya sebetulnya tidak ingin berprasangka apa-apa, tetapi tampaknya para anggota DPR ini telah menemukan cara lain untuk mendapatkan ilmu kekebalan, yaitu dengan merevisi undang-undangnya sendiri.