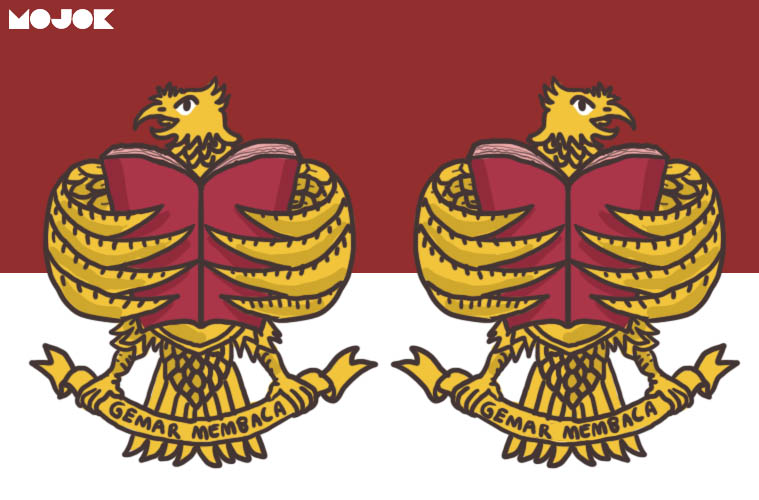MOJOK.CO – Belakangan ini bertebaran infografis di medsos soal minat baca Indonesia yang rendah. Disebutkan Indonesia berada di peringkat kedua—dari bawah. Ah, masa sih?
Dua-tiga hari ini, di temlen Facebook saya berseliweran sejenis meme—atau apalah namanya—yang isinya sajian infografis tentang nasib ngenes Indonesia sebagai negara dengan minat baca terendah kedua sedunia.
Infografis itu dibubuhi judul mencolok: “Negara-negara Pemakan Buku Terbanyak”. Di bawahnya ditaruh gambar-gambar buku dengan motif bendera lima negara paling yoi. Dari Finlandia, Norwegia, Islandia, Swedia, sampai Denmark.
Lalu di bawahnya, buku-bermotif-bendera Indonesia tampak tersungkur sambil mewek, begitu pula buku-bermotif-bendera Botswana. Kita tahu, kedua negara yang digambarkan sedang mewek itu berada di posisi dua peringkat terbawah.
Di baris terakhir, dituliskan “Sumber: PISA dan CCSU”.
Seperti biasa, banyak orang membagi gambar itu dengan gegap gempita. Membagikan ke dinding akun medsos mereka sebagai bentuk kepedulian? Membagikan untuk menumbuhkan minat baca?
Hajelas bukan, lah!
Infografis tersebut dibagikan untuk mencibir—itu lebih tepat.
Persisnya lagi, para pembagi gambar itu rata-rata menyampaikan pesan: “Nih, mangap kalian, wahai kaum yang nggak pernah makan buku! Kalian tu doyannya berita hoax dan fitnah! Ngakunya beragama tapi malas baca!”
Warbiyasa gagah sekali. Bermartabat sekali.
Sembari bilang begitu, mereka yang merasa berliterasi tinggi itu manut saja dengan infografis yang mengaku-ngaku bersumber dari PISA (Programme for International Student Assessment) dan CCSU (Central Connecticut State University, Amerika) itu.
Literasi? Idih, cah literasi kok manutan.
Gini ya, Gaesss. Saya mohon izin untuk bilang: sama infografis yang jatuhnya malah kayak meme ginian jangan gampang dipercaya.
Pertama, itu infografis jelas bukan dari PISA dan CCSU, melainkan dari CCSU saja. Kalau memang mengacu ke PISA, harap tahu, Indonesia di tahun 2015 bukan lagi nomor dua dari bawah, tapi sudah “lumayan” naik ke peringkat 62 dari 72 negara. Rangking tersebut dikaitkan juga mengenai kualitas pendidikan, karena PISA urusannya dengan itu.
Kalau pakai PISA juga, tiga besarnya bukan negara-negara Skandinavia itu, melainkan Singapura, Hongkong, Kanada, baru kemudian Finlandia.
Lalu kenapa PISA dibawa-bawa?
Ya jelas jawabnya: karena membawa-bawa nama lembaga ilmiah terkenal akan mendongkrak derajatmu secara gampang dan instan. Sehingga jamaah mana pun dengan takzim bakalan manggut-manggut di hadapanmu, seolah kamu sudah menjadi pemegang otoritas ilmiah itu sendiri.
“Menurut penelitian baru-baru ini di Amerika…”; “Seorang pakar dari Harvard University mengatakan…”; “Berdasarkan riset yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari lembaga-lembaga ilmiah ternama di 9 negara maju…”
Cukup dengan memakai pembukaan seperti itu saja audiens akan langsung terpukau dan percaya. Apalagi kalau sudah menyebut nama spesifik seperti PISA! Toh, para pendengar yang manutan itu nggak bakalan memeriksa akurasi datanya, to? Mau cari apa itu PISA juga paling-paling ogah.
Kedua, dalam rangking versi CCSU, dengan tajuk Most Literate Nation in The World (MLNW), kriteria yang dipakai untuk menetapkan tingkat literasi masyarakat negara-negara sedunia itu ada empat, yakni: libraries, newspapers, education inputs, education outputs, dan computer availability. Silakan cek di web-nya kalau nggak percaya.
Nah, pertanyaan saya, apakah kriteria-kriteria itu mempertimbangkan juga perbedaan bentuk dari kultur membaca di setiap negara?
Begini maksud saya. Ada banyak sekali kawan saya yang gila membaca. Mereka tekun-tekun, tergila-gila dengan buku. Tapi sangat sedikit—atau bahkan nyaris tidak ada—kawan saya yang getol berkunjung ke perpustakaan (padahal itu salah satu kriteria terpenting dalam ranking versi CCSU).
Mereka membaca dari buku milik mereka sendiri, bikin perpustakaan pribadi sendiri yang tidak terpantau data resmi. Buku-buku mereka itu didapatkan dari beli di toko, beli di lapak-lapak online, pinjam teman nggak dibalikin, atau donlot PDF haram bajakan.
Nggak usah mereka, saya sendiri pun begitu. Meski saya nggak gila-gila amat dengan buku (saya cuma gila sama uang dan kenikmatan dunia), toh tetap saja saya pembaca buku. Tapi, catat ini baik-baik: saya bukan pengunjung perpustakaan.
Saya ingat-ingat, terakhir kali saya mengunjungi perpustakaan di Indonesia tuh belasan tahun silam sewaktu masih kuliah. TKP-nya di Perpustakaan Santo Ignatius Kotabaru, perpus paling keren se-Jogja.
Waktu masih di Australia, saya memang mengunjungi perpustakaan juga, yakni di Cambridge Library, Floreat, Perth (cek saja di Google Map, itu perpustakaan kecamatan yang lumayan besar). Tapi di situ sebagai kurir saya cuma mengantarkan barang kiriman. Isinya tinta printer, saya serahkan ke mbak resepsionis berwajah mestizo, dan saya lebih suka mengobrol sama dia daripada menjelajahi rak-rak buku.
Dengan angka kunjungan perpustakaan yang nyaris nol, hamosok terus serta merta saya dibilang “nggak pernah makan buku”? Enak aja, saya nggak setipis itu.
Ringkasnya, situasi antara satu negara dengan negara lain tidak bisa dipukul rata, variabel-variabel penilaian atas minat baca tidak bisa ditetapkan dengan ukuran sepihak yang semena-mena.
Saya kasih secuil perbandingan yang agak saya pahami. Ini antara Indonesia dan Australia, dua tempat yang pernah saya diami.
Di Australia, toko-toko buku memang lumayan sepi. Tapi perpustakaan-perpustakaan negeri stabil ramainya, lengkap fasilitasnya, di tiap kelurahan ada, dari anak-anak hingga manula selalu punya acara di sana. Bahkan, karena sudah mendaftar sebagai anggota, istri saya pun sampai sekarang masih bisa meminjam e-book dari perpustakaan kampung di sebelah rumah kontrakan kami dulu.
Di Indonesia, mungkin perpustakaan sepi. Tapi lihat, toko-toko buku masih ramai. Itu baru toko buku, belum pameran-pameran. Kolega saya bos event organizer, namanya Hinu OS, setiap tahunnya rutin menggelar pameran buku di 60 kota se-Indonesia, dan semakin hari Hinu tampak semakin berisi, makmur, dan—jelas—kaya raya. Jauh lebih kelihatan makmur ketimbang buzzer politik malah.
Itu baru offline. Yang lebih seram lagi yang online. Toko-toko buku online semakin bersimaharajalela. Di Facebook, Marketplace, Instagram, Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Coba, berapa akun toko buku online yang sampeyan pernah lihat? Tak terhitung, kan?
Agus Mulyadi saja, Pemimpin Redaksi sebuah media sebesar Mojok sampai bikin toko buku online sendiri. Konon omzet dari jualan bukunya dua sampai tiga kali lipat dari gajinya sebagai Pemred yang udah selangit itu. Kawan saya yang lain, seorang dosen Hukum Tata Negara, punya toko buku di Instagram dengan omset puluhan juta per bulannya. Dan masih banyak lagi, nggak usah diabsen semua, nanti jadi mirip ucapan terima kasih skripsi.
Semua fenomena toko buku online itu harus saya sebut, karena kecenderungan pola konsumsi buku di Indonesia sekarang ini ya harus dilihat dari situ. Bukan dari perpustakaan, wahai Mas CCSU! Semakin laris toko-toko buku online, seiring model promosi (dan provokasi) buku via media sosial, artinya minat publik untuk membaca buku terus merayap naik.
“Lho, beli buku kan belum tentu dibaca! Palingan dipajang di rak, jejeran koleksinya dipakai buat bekgron selpi, aplot!”
Iya, iya, itu terjadi di mana-mana, kelakuan wajar homo sapiens pada umumnya. Namun sebagaimana buku yang dibeli belum tentu dibaca, buku yang dipinjam orang dari perpus juga belum tentu dibaca. Dibaca ding, tapi cuma dikutip satu paragraf buat nambah-nambahi daftar pustaka tugas kuliah doang.
Poin saya, beberapa gambaran di atas rasanya cukup untuk menunjukkan bahwa alat ukur CCSU soal minat baca itu sangat terbuka untuk dikritik, karena mengabaikan kekhasan kultur sosial masing-masing wilayah penelitiannya. Saran saya sih, infografis macam gitu ya abaikan saja, sembari tetap dan terus membaca, jangan langsung gampang percaya.
Soalnya percaya itu cuma sama Tuhan lalu sama Nabi, bukan sama CCSU. Lha wong di kitab bocoran soal-soal pertanyaan di alam kubur saja nggak bakal ada pertanyaan: “Berapa minat baca di negaramu, Kisanak?”