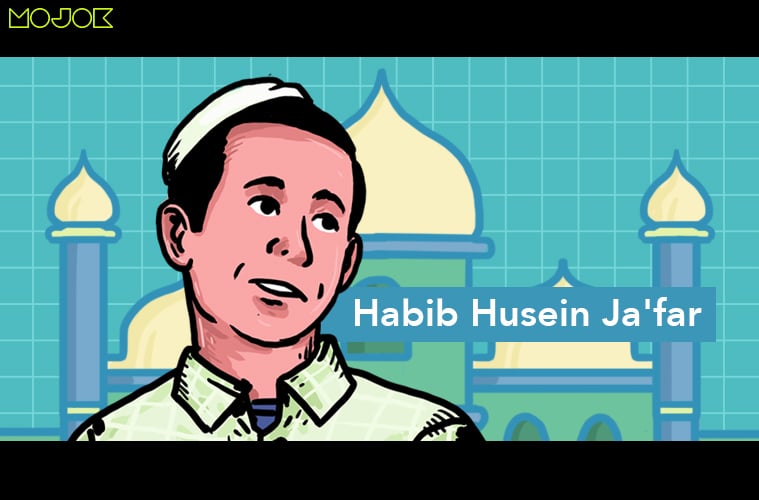Kalau kamu coba tonton TV di suasana Ramadan seperti sekarang, kamu akan menemukan kalau tak sedikit artis yang mengubah tampilannya menjadi lebih “islami”. Entah dengan balutan kain dari kepala hingga tubuhnya, misalnya.
Terutama kalau nanti sudah menjelang Lebaran, mau dibilang masih pandemi, pasar-pasar bakalan tetap sesak oleh umat Islam yang berbelanja untuk keperluan busana Lebaran.
Thomson Reuters melaporkan bahwa pada 2015 Indonesia berada di lima teratas negara konsumen busana Muslim di dunia. Dan, pada 2020 Indonesia melaju ke urutan tiga teratas. Adapun kalau Ramadan dan Lebaran, pertumbuhannya bisa mencapai tujuh kali lipat.
(((tujuh kali lipat)))
Saat ini, betapa pun di kota besar seperti Jakarta, wanita berjilbab hampir jadi kelompok yang dominan di sebuah kafe, acara, tongkrongan, atau kerumunan-kerumunan lainnya. Lelaki berjenggot dan bercelana cingkrang juga bukan pemandangan langka—tidak kayak dulu.
Bahkan, sebagian orang “berjihad” sangat keras untuk menumbuhkan jenggotnya betapapun secara genetik sulit. Begitu juga tak jarang sebagian orang hingga menggulung atau menggunting celananya agar cingkrang.
Tentu, kita patut bangga melihat semua fenomena itu. Betapapun itu menunjukkan semangat keberislaman dalam satu sisi yang begitu menggelora.
Namun, itu saja tak cukup. Itu baru “kulit” Islam, belum “daging”-nya. Berislam itu harus kaffah, yakni utuh sampai ke “daging-daging”-nya. Karena Islam bukan hanya identitas, tapi juga (bahkan utamanya) makna.
Misalnya, apa makna dari identitas bercelana cingkrang?
Nabi Muhammad dalam berbagai hadis memang memerintahkan kita untuk bercelana cingkrang dan mengutuk yang bercelana melebihi mata kaki atau isbal.
Tak tanggung-tanggung, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi katakan orang yang bercelana isbal itu tempatnya di neraka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa kata Nabi, Allah kelak takkan melihat kepada orang-orang yang di dunia bercelana isbal.
Tentu, ini ancaman yang serius. Dan dari sana sebenarnya kita sudah mendapat kode bahwa ada makna mendalam di balik larangan celana isbal. Tak mungkin hanya perkara celana, orang masuk neraka dan berkumpul dengan pembunuh, pezina, dan lain-lain. Rasanya kurang fair gitu.
Maka, usut punya usut, dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dari ibnu Umar, didapatkan maknanya yakni yang di neraka karena celana isbal adalah lantaran sombong. Jadi, celana isbal itu dipermasalahkan karena jadi penyebab kesombongan.
Tak sampai di sana, juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang lain dikisahkan Sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq pernah datang ke Nabi dan menyampaikan bahwa celananya isbal, dan apakah ia masuk neraka?
Lalu Nabi bertanya, apakah itu dilakukannya karena sombong? Tentu tidak, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau begitu, kata Nabi, berarti kau bukan termasuk orang-orang yang disindir sebagai penghuni neraka karena isbal tersebut.
Dari sini kita tahu bahwa maknanya pada kesombongan. Adapun celana isbal adalah identitas belaka.
Dulu, di zaman Nabi, celana isbal adalah identitas kesombongan. Mungkin, kalau zaman ini, seperti celana yang bermerek dan harganya fantastis. Jadi, Nabi melarang kalau itu dipakai karena kesombongan. Kalau tak sombong, tak apa tak cingkrang dan juga tak apa memakai celana bermerek yang mahal.
Justru jadi masalah yang agak pelik kalau kesombongan muncul dari kita yang bercelana cingkrang. Misalnya, karena sudah cingkrang, kita lalu sombong karena merasa paling nyunah dan memandang rendah orang lain yang isbal padahal kita tak tahu isi hatinya apakah ia sombong atau justru hanya karena bertipikal seperti Sayyidina Abu Bakar.
Maka, dari sini kita belajar tentang pentingnya menggali makna dari seluruh identitas keislaman kita yang diajarkan Al-Quran maupun Sunnah. Jangan sampai tersesat hanya di identitas, karena bukan itu utamanya.
Dengan tools itu, kita bisa mulai mengecek identitas-identitas lain dalam Islam. Seperti mengapa kita disuruh salat berjamaah? Agar kita belajar dan terbiasa berjamaah atau bersolidaritas.
Maka, bentuk berjamaah di tengah pandemi seperti sekarang adalah justru tak berjamaah karena itu implementasi dari solidaritas yang sesungguhnya, yakni saling menjaga satu sama lain dari penularan corona.
Contoh seperti itu tadi sebenarnya juga sudah diwanti-wanti melalui Al-Quran.
Salat misalnya, dalam Al-Quran diorientasikan sebagai sesuatu yang akan menjauhkan pelakunya dari kekejian dan kemungkaran (QS. Al-‘Ankabut: 45), sebaliknya bahwa neraka jadi tempat bagi mereka yang salat untuk riya’ dan tak mau memberi pertolongan (QS. Al-Ma’un: 4-7), zakat menjadi sia-sia jika diikuti kata-kata yang melukai (QS. Al-Baqarah: 264), dan lain-lain.
Sekali lagi, hal seperti ini perlu direnungkan dan direformasi secara serius agar terjauh dari diktum Muhammad Abduh, tokoh pembaharu Islam:
“Saya melihat Muslim di Mesir, tapi saya tak melihat Islam di sini. Adapun di Eropa saya tak melihat Muslim, namun saya melihat Islam di sana.”
Sebab, dalam kurun waktu penelitian Scheherazade. S Rehman dan Hossein Askari dari The George Washington University bertema “How Islamic are Islamic Countries” menyuguhkan hasil bahwa dari 208 negara di dunia yang diteliti, dalam 2010 dan 2014 memperlihatkan justru negara-negara non-Muslim menempati posisi teratas dan negara-negara Muslim (termasuk negara Islam) menempati posisi bawah.
Arab Saudi berada di urutan ke-131. Tak terkecuali Indonesia yang berada di urutan ke-140, meskipun kita ini ada fenomena atau gerakan salat subuh berjamaah di masjid atau one day-one juz, dan lain-lain.
Begitu pula Indeks Kota Islami (IKI) yang pernah diselenggarakan Maarif Institute pada 2016 menunjukkan bahwa dominasi pemeluk Islam tak menjamin tingginya nilai IKI.
Terbukti, Denpasar yang merupakan kota berpenduduk mayoritas Hindu justru berada di urutan atas, yakni urutan ke-3. Adapun kota-kota yang menerapkan syariat Islam, seperti Aceh berada di urutan bawah atau maksimal di tengah, yakni peringkat ke-14.
Mengapa? Karena yang beragama Islam dan menjalankan ritual Islam ternyata tak berbanding lurus dengan menjalankan nilai-nilai Islam secara substantif dalam kehidupannya bermasyarakat.
Lagipula, secara konsep seharusnya kesalehan secara ritual itu bisa mendidik atau membiasakan kita jadi saleh secara sosial, bukan hanya stop di tahap personal atau di batas celana isbal.
Sepanjang Ramadan, MOJOK menerbitkan KOLOM RAMADAN yang diisi bergiliran oleh Fahruddin Faiz, Muh. Zaid Su’di, dan Husein Ja’far Al-Hadar. Tayang setiap hari.