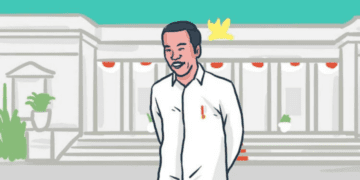MOJOK.CO – Kalau Indonesia saja kamu anggap ada di bawah rezim otoriter sejak dipimpin Presiden Jokowi, negara-negara tetangga yang warganya sampai melarikan diri itu kamu anggap apa?
“Situasi di negeri saya sedang kacau. Ada 500 orang lebih telah menjadi korban kediktatoran rezim yang sedang berkuasa saat ini,” kata Dru, sahabat baik saya dari Nikaragua, menceritakan kondisi terkini negaranya. Kabarnya, 510 orang telah tewas terbunuh dan sekitar 1.300 hilang–setidaknya menurut laporan Asosiasi Hak Asasi Manusia Nikaragua.
Jumlah 510 tentu saja bukan angka belaka. Mereka adalah jiwa yang harus menjadi korban keserakahan dan kebiadaban pemerintahnya sendiri. Presiden Nikaragua, Daniel Ortega, mengontrol dan mengendalikan semua arus informasi dan menggunakan aparat untuk bertindak represif terhadap warganya sendiri. Ia terkenal korup dan mempraktikkan nepotisme; membagi-bagikan jabatan kepadanya keluarganya sendiri.
Kondisi yang sama ditemui di Honduras dan Kuba. Di Honduras, sang presiden yang secara konstitusi tidak boleh lagi maju, memaksakan revisi undang-undang. Di hari pemilihan, suaranya jauh tertinggal dari lawannya. Singkat cerita, ia beraksi dengan mengacaukan dan melacak sistem. Pun, ketika sistem sudah baik, tiba-tiba ia balik memimpin. Orang-orang protes dan menyebabkan kekacauan, tapi ia menggunakan kediktatorannya untuk melawan warganya sendiri. Saat ini, ribuan orang Honduras melarikan diri dari negaranya.
Lihatlah pula Venezuela yang warganya kelaparan dan harus makan daging busuk untuk bertahan hidup. Beberapa hari lalu, Jail Bolsonaro yang disebut-sebut sebagai Trump versi Brazil, terpilih menjadi presiden di sana. Ia dianggap sebagai seorang militer diktator dan suka mengeluarkan ujaran kebencian. Dan kita semua tahu, kebebasan berpendapat adalah ilusi belaka jika hidup di bawah rezim diktator.
Setidaknya itu pula yang dialami Li, teman saya dari Cina. Negara aseng kafir laknatullah ini memang negara maju, tapi tak ada jaminan kebebasan berpendapat. Pemerintah mengontrol arus informasi dan melacak setiap warga yang mencurigakan. Jika kedapatan mengkritik Presiden Koh Xi Jinping, siapkan mental dan fisik menuju penjara—itu pun kalau masih diperkenankan hidup.
Di Rusia, keadaannya sama saja. Anastasia, teman karib saya yang senyumnya manis itu, tiba-tiba berubah ketika saya tanya tentang kebebasan berbicara politik di negaranya.
“Kamu harus memastikan seseorang benar-benar teman dekatmu jika ingin berbicara politik dengannya, atau kamu diciduk.”
Hiii. Ngeri banget yha rezim otoriter macam itu?
Oh, atau kamu mau dipimpin pemimpin Islami? Baiklah, mari kita bandingkan. Tapi rujukannya siapa, ya? Mr. Presiden Erdogan? Boleh sih, tapi jangan lupakan saat-saat ia menangkapi para demonstran yang pernah mengkritik pemerintahnya, ya.
Lalu, bagaimana dengan Arab Saudi? Boleh juga, tapi ingat pula, ya: Sang Pangeran pernah memerintahkan ‘orangnya’ memutilasi warganya sendiri, Jamal Khashoggi. FYI aja nih, Jamal adalah seorang jurnalis yang vokal mengkritik pemerintahan. Plus, jangan lupa pula saat Sang Pangeran—yang penampilannya Arab kaffah itu—menangkapi ulama-ulama yang dianggap radikal.
Gini deh, ya, akhi-dan-ukhti–yang-terus-terusan-bilang–rezim–sekarang-selalu-mengkriminalisasi–ulama, coba sebutkan ulama yang ditangkap secara sewenang-wenang? Lalu, coba pikirkan baik-baik: kalaupun ada, mungkin itu ulamamu saja—ulama yang selalu bikin resah di sana-sini. Ulama yang bukannya meneduhkan malah bikin emosi. Benar, tidak?
Oh, jangan lupa: tengok pulalah Suriah dan Yaman. Sekarang, Suriah luluh lantak karena perang saudara. Beribu-ribu warganya kehilangan harapan dan harus meninggalkan tanah kelahirannya. Sementara itu, warga Yaman kini menderita kelaparan di tengah-tengah pemerintahan yang korup. Dua teman baik saya memilih tak pulang ke negaranya karena situasi di sana. Sedih rasanya ketika mereka curhat sedang merindukan keluarganya yang telah terpisah bertahun-tahun lamanya.
Seorang teman lain dari Afganistan tak ingin kembali selepas studi sebab menghindari deru gencatan senjata yang harus ia dengar setiap kali pulang kerja. Sewaktu-waktu, nyawanya bisa melayang. Semua orang tentu akan mati, tapi kita tentu tak ingin mati konyol, bukan? Dengan keadaan ini, rasanya nyawa hanyalah mainan saja di bawah pemerintah diktator dan rezim otoriter!
Indonesia tentu bukan negara-negara seperti mereka—setidaknya belum. Jaraknya masih ribuan kilometer, tapi hal yang sama bisa saja terjadi. Maksud saya, siapa yang pernah menduga Suriah yang indah dan menjadi salah satu destinasi favorit mancanegara itu kini tinggal puing-puing? Atau, siapa pula yang meramalkan orang-orang di Nikaragua bakal tak lagi berani bersuara, bahkan lewat Facebook, gara-gara pemerintahnya yang diktator akan melacak dan hidupnya bisa selesai dalam semalam?
Ingat, mylov: apa yang terjadi di negara-negara tersebut bisa saja kelak terjadi di Indonesia jika kita tidak dewasa. Ha gimana nggak: saat negara kita menjamin kebebasan berpendapat dan mengkritik, kebebasan tersebut justru digunakan untuk menyebarkan hoaks dan fitnah. Kurang payah apalagi coba? Nanti, giliran dimintai pertanggungjawaban, mereka dengan enteng bakal bilang bahwa pemerintah adalah rezim diktator, rezim otoriter, bahkan rezim biadab. Hadeeeeh, please, deh!
Saya tidak mengerti ketika dedek-dedek mahasiswa yang tukang demo itu dengan enteng menyebut pemerintah biadab dan otoriter. Padahal, di waktu bersamaan, dengan seenaknya mereka merusak fasilitas umum dan menghina presidennya sendiri, Presiden Jokowi. Bayangkan!
Yang tak kalah lucu tentu saja organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka yang menyerukan antidemokrasi, tapi mereka pula yang menikmati buah demokrasi. Setiap kali berdemo—kini dengan menumpang aksi bela ini dan itu—selalu menyebut pemerintah thogut dan represif. Lalu, ketika dibubarkan, ujung-ujungnya mereka selalu menyebut pemerintah sekarang adalah rezim biadab. Ckck.
Kita tahu pula pentolan-pentolan mereka: Felix Siauw salah satunya. Di akun media sosial, ia dengan enteng menyerang pemerintah dengan nyinyir. Ia selalu ngeyel mau ganti ideologi negara, tapi berlindung di balik kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Heran saya—apa ia kira bebas ngomong seperti itu di negara antidemokrasi seperti yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya???
Saya penasaran juga pada satu hal: mereka yang teriak-teriak dan menuduh pemerintah rezim diktator dan rezim otoriter serta tidak sabaran ganti presiden—itupun kalau calonnya terpilih—sebenarnya menginginkan pemerintah seperti apa, sih??? Apa mereka mau pemimpin yang seperti Presiden Nikaragua, Honduras, Kuba, Brazil, Cina atau Rusia???? Atau, presiden yang sedia setiap waktu untuk menciduk ketika warganya kedapatan protes, atau bahkan memberi putusan mutilasi syar’i ala sang pangeran Arab???
Sungguh, semakin hari kok rasanya kita semakin menjadi orang tidak tahu bersyukur di negeri sendiri. Negeri ini memang punya kekurangan, tapi juga memiliki kelebihan. Kalau selalu kekurangannya yang dibesar-besarkan, ya jelas kita tidak akan pernah bersyukur. Memang Mas-mas dan Mbak-mbak ini mau seperti negara apa, sih??? Bahkan nih ya, Amerika Serikat yang superpower itu pun tak lepas dari banyak masalah. Biaya pendidikan dan kesehatan di sana saja astagfirullah tingginya!
Jadi, Mas, Mbak, Akhi, dan Ukhti, kalau tidak bisa belajar dari negara-negara yang kini menderita konflik berkepanjangan, setidaknya kita bisalah belajar dari rezim otoriter Presiden Soeharto selama 32 tahun. Saat itu, ketika kamu berani mengkritik, besoknya bisa saja kamu lenyap tak berjejak. Mau begitu lagi?
Yah, kalau masih tetap penasaran bagaimana rasanya, bolehlah kamu mencobanya di negara-negara yang saya sebutkan di atas itu. Pesan saya, pastikan saja kamu sudah membuat kata-kata perpisahan kepada keluargamu. Demi meninggalkan negara rezim diktator, rezim otoriter, dan rezim biadab, kan?
Gimana? Ditunggu, ya, bosqu~