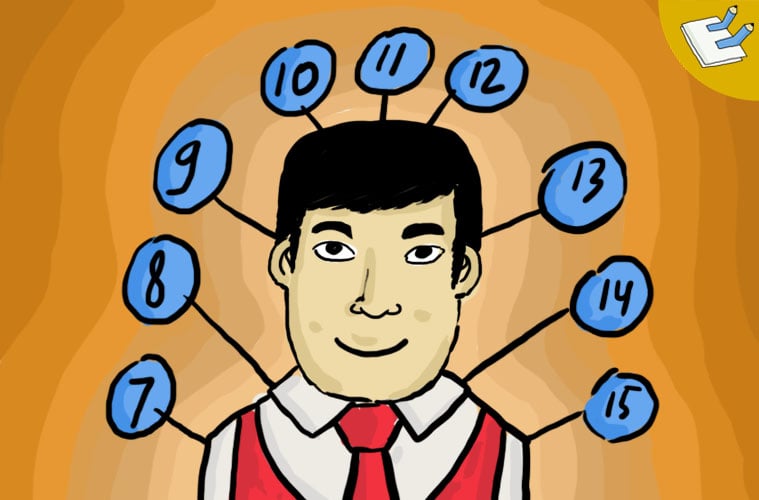Ketika sekolah di Finlandia hanya 3-4 jam per hari, dan penelitian tentang jam biologis anak atau “Circadian Rhythm” mulai dipakai di Inggris dan Amerika, Indonesia justru mulai menerapkan sekolah 8 jam.
Gagasan sekolah sehari penuh (full-day school) yang kontroversial secara resmi memang tak jadi diterapkan. Tapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menerapkan konsep sekolah lima hari (Senin-Jumat), yang akan diberlakukan mulai tahun ajaran baru, Juli 2017.
Karena Sabtu libur, sebagai gantinya, jam sekolah diperpanjang jadi 8 jam, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Biasanya sekolah berlangsung 5-6 jam per hari.
Konsep ini memang tidak (belum) berlaku nasional. Diserahkan kepada kesiapan masing-masing sekolah. Menurut Menteri Muhadjir, kebijakan ini terkait dengan apa yang disebut “Penguatan Pendidikan Karakter”. Idenya, anak-anak tidak harus belajar di kelas. Jam tambahan itu bisa diisi kegiatan ekstrakurikuler seperti seni, olahraga, eksperimen ilmiah, atau jalan-jalan dengan tujuan khusus seperti ke sanggar atau tempat-tempat ibadah (Kompas, 14 Juni 2017).
Mereka yang biasa menempuh pendidikan khusus usai jam sekolah seperti mengaji atau kegiatan gereja, dapat mengonversi aktivitas tersebut sebagai mata pelajaran agama. Teknisnya belum jelas. Apakah sang guru ngaji akan membuat rapor yang diadopsi oleh sekolah atau cara lan. Tapi yang jelas, tidak benar jika pelajaran agama akan dihapus begitu saja.
Sekolah 5 hari (hanya sampai Jumat) sejatinya lebih baik, mengingat banyak yang menyebut anak-anak Indonesia mengalami “over schooling“. Siswa kelelahan dengan aneka menu pelajaran atau les tambahan. Itu belum termasuk aneka kursus minat bakat seperti musik hingga pelajaran agama di luar sekolah seperti mengaji.
Tapi mengompensasi libur Sabtu menjadi sekolah delapan jam per hari, jelas memperburuk keadaan.
Sekolah rata-rata dimulai jam 7 pagi karena para orangtua harus berangkat bekerja. Jam itu sendiri memang jam biologis orang dewasa memulai aktivitas. Itu pun masih bias pekerja atau buruh urban.
Nelayan cumi di Lombok Timur melaut jam enam petang, tapi nelayan tongkolnya berangkat jam tiga dini hari. Dengan demikian siklus tidurnya pun berbeda. Hanya pemburu paus dan pari di Lamalera yang jam kerjanya mirip orang kantoran: berangkat jam 7 pagi, pulang jam 3 sore.
Sebuah penelitian yang melibatkan para pakar di Oxford University terhadap 100 sekolah di Inggris menunjukkan, jam biologis anak usia SD dimulai jam 9 pagi. Sedangkan usia SMP dimulai jam 10 pagi. Sebab, kebutuhan tidur mereka masih 10 jam per hari. Lebih lama dari rata-rata orang dewasa yang 8 jam.
Penelitian serupa yang terpisah dilakukan Bradley Hasbro Children’s Research Center di Rhode Island, Amerika, dengan hasil yang sama. Jika sekolah lebih siang 25 menit, jumlah anak yang tidur lebih dari 8 jam meningkat signifikan dari 18 persen menjadi 44 persen.
Sekolah lebih siang tidak membuat anak-anak makin larut tidur (karena memang di usia SMP-SMA atau puber, jam tidur mereka tetap jam 11 malam), tapi justru makin mudah bangun.
Bandingkan dengan DKI Jakarta yang sejak 2012 menerapkan jam masuk sekolah lebih pagi dengan alasan “mengurangi kemacetan”. Bel sekolah anak-anak Jakarta berbunyi jam 6.30 WIB.
Hasil penelitian ini juga menjelaskan mengapa selama ratusan tahun orangtua selalu berperang dengan anaknya yang susah bangun pagi. BBC melukiskannya sebagai “pertempuran abadi” antara orangtua dan anak.
Dengan memahami “Circadian Rhythm”, siswa akan benar-benar optimal menerima pelajaran.
Bias Orang Dewasa
Sistem pendidikan kita makin jauh menyeret anak-anak dalam bias kepentingan orang dewasa (pekerja industri) lewat kebijakan sekolah 8 jam ala Menteri Muhadjir Effendy.
Aturan ini berbarengan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 19/2017 tentang Guru yang menyebut bahwa setiap guru harus mengajar (tatap muka) minimal 24 jam dan maksimal 40 jam seminggu—seperti jam kerja PNS pada umumnya, termasuk libur hari Sabtu. Dengan sekolah yang hanya sampai jam 1 siang, dan konsep tatap muka dibatasi hanya jam pelajaran di kelas, target itu sulit dicapai seorang guru, dan memengaruhi tunjangannya.
Maka kita melihat lagi-lagi konsep pendidikan anak-anak harus beradaptasi dengan sistem administrasi dan birokrasi orang dewasa, alih-alih sebaliknya. Dari mana datangnya angka 24 jam pelajaran sepekan untuk setiap guru? Mengapa tidak 12, 37, atau 23,5 jam?
Tentu jawabannya kembali pada beragam menu mata pelajaran dan target yang ditetapkan kurikulum pemerintah sendiri. Maka di sinilah sumber masalahnya.
Jika dalam sistem baru ini ekstrakurikuler atau studi lapangan (field trip) dihitung sebagai bagian dari jam pelajaran seperti tatap muka di kelas, mengapa itu tidak dilakukan dalam kerangka 5-6 jam pelajaran sehari? Mengapa harus menambah jadi 8 jam?
Sudah jelas pemerintah tak ingin mengurangi target kurikulum yang tetap ingin dijejalkan kepada anak-anak, mulai dari butir-butir Pancasila, rumus Phytagoras, hafalan doa, nama latin tumbuhan, sampai pelajaran bahasa asing. Menu seperti ini berlaku nasional dari Sabang sampai Merauke, tak peduli sekolah itu ada di pedalaman Papua atau di pesisir Mentawai.
Karena obsesinya memang menstandarkan nilai lewat Ujian Nasional. Sebab hanya itulah satu-satunya ukuran yang bisa diterima pasar kerja industri lewat ijazah dan IPK.
Tak peduli apakah buku-buku pelajaran biologi di Papua menyebut nama latin sagu. Toh, tak ada soal ujian nasional yang bertanya “Sebutkan kelebihan sagu dibanding beras bagi kesehatan manusia”. Atau jika dianggap terlalu sulit, “Sebutkan lima jenis makanan yang berbahan dasar sagu”.
Sebab kurikulum pendidikan kita memang tidak didesain untuk mendekatkan anak dengan potensi maksimalnya beradaptasi dengan konteks sosial dan lingkungan, melainkan menyiapkannya menjadi pelayan industri dan birokrasi.
Sistem sekolah kita membuat anak-anak di Pulau Galang tak ingin menjadi nelayan seperti orangtuanya, dan seorang guru di Rembang sibuk mendukung pendirian pabrik semen karena, “Saya tidak ingin murid-murid saya hanya menjadi petani”.
Maka ketika Menteri Muhadjir menyebut kebijakan sekolah 8 jam adalah bagian dari “Penguatan Pendidikan Karakter” dari Presiden Jokowi, kita patut menggeledah, karakter apa yang dimaksud oleh presiden dan menterinya ini.
Karakter anak-anak di pedalaman Madobag dan Kahaungu Eti atau anak-anak di Menteng dan Pondok Indah?
Apalagi konsep sekolah 8 jam ini juga diklaim ingin mengembalikan hakikat guru sebagai pendidik (Kompas, 14 Juni 2017). Dengan sekolah 8 jam, guru dituntut terlibat dalam pendidikan ekstrakurikuler, bahkan di luar sekolah, dan tidak hanya lewat tatap muka di kelas. Sampai di sini idenya sudah benar.
Namun, apakah negara sudah menyiapkan tenaga guru dengan kecakapan seperti itu?
Apakah sekolah negeri di Karangasem memiliki guru yang mengerti tenun geringsing agar anak-anak Tenganan dapat mempertahankan pengetahuan ini seratus tahun lagi?
Atau benarkah negara sudah memprogram agar guru-guru memahami teknik memancing “huhate” yang ramah lingkungan, sehingga “hakikat guru sebagai pendidik” dapat optimal dengan sekolah 8 jam bagi anak-anak nelayan di Tomalao?
Jika jawabannya tidak, ungkapan seperti “penguatan pendidikan karakter” atau “mengembalikan hakikat guru” adalah narasi-narasi besar yang tak ada kaitannya dengan apakah sekolah cukup 5 atau jadi 8 jam. Karena bahkan negara dan pejabatnya tak cukup cakap mendefinisikan “karakter” dan “hakikat”.
Di Klojen, kami menyebutnya “Kakean cangkem”. Di Miliran, kami menyebutnya “Asal mangap”. Tak ada yang butuh terjemahan atau keterangan lokasinya, karena ini semua tak akan ada di soal Ujian Nasional.