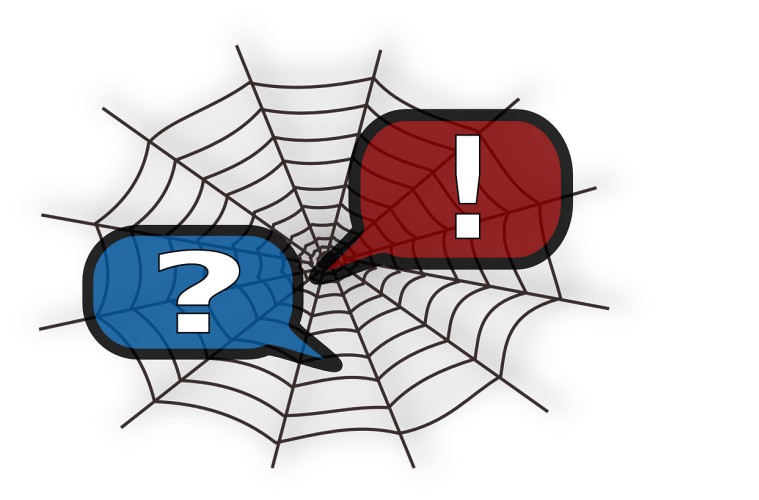Saya suka menjadi penggerutu, dalam arti mengkritisi tiap hal yang ada di sekitar saya. Kritis membuat saya mencari tahu, mencari tahu membuat saya paham, setelah paham saya bisa berhati-hati menghakimi. Tapi belakangan saya percaya bahwa menahan diri untuk tidak mengomentari segala hal adalah kemewahan tersendiri.
Di abad media sosial yang kepalang brengsek ini, semua orang berlomba-lomba untuk berkomentar dan menjadi pakar, tapi hanya sedikit saja yang mau memahami masalah. Lalu apa sebenarnya yang kita cari dari berkomentar? Apakah sekadar menunjukkan bahwa kita tahu akan sesuatu, peduli sesuatu, atau sekadar untuk eksistensi diri?
Seingat saya, sebelum adanya pemilu tahun lalu, sebelum gegap-gempita pertikaian pendukung Jokowi dan Prabowo, media sosial adalah tempat yang baik-baik saja. Tentu ada twitwar, tentu ada perbedaan pendapat, tapi seingat saya belum ada perkelahian karena membela capres atau penyebaran kebencian atas nama isu sektarian. Lantas ada apa sebenarnya dengan kita?
Menjelaskan itu tentu akan sangat membosankan lagi menyebalkan. Ia bisa jatuh menjadi khotbah, dan saya benci khotbah. Setiap Jumatan saya kerap datang paling akhir karena malas mendengar khotbah. Bagaimana bisa menikmati khotbah kalau isinya hanya mengkafirkan ini, menyesatkan itu, dan menghalalkan darah si anu. Saya sudah malas menghadapi negativitas. Berat badan, cicilan, utang, dan beban pekerjaan sudah cukup membuat saya lelah, lhah kok ndadak mesti denger kotbah yang isinya kebencian?
Yang paling hangat dan paling dekat, bagaimana para pengguna media sosial merespons tragedi Paris. Beberapa yang waras akan berempati, beberapa yang religius akan berdoa, sisanya makhluk-makhluk tanpa otak dan hati yang berebut mengomentari apa saja seperti pemakan bangkai. Pemakan bangkai ini salah satunya adalah Eddward S Kennedy—menghakimi yang peduli dan yang nyinyir, seolah dialah hakim yang paling adil.
Tentu saja ada banyak makhluk yang lebih menjijikkan. Misalnya, satu akun pegiat Indonesia Tanpa Jaringan Islam Liberal (ITJIL) yang memuat komik untuk menyindir solidaritas Paris dan kebungkaman pada Palestina. Ia boleh jadi benar, tapi apa yang ia lakukan membuat saya bertanya. Apakah si pegiat ITJIL (hati hati bilang ITIL, itu jorok) paham bahwa Perancis adalah salah satu negara yang mengakui kedaulatan Palestina? Lebih dari itu, Perancis merupakan salah satu negara yang menyumbang dana paling besar untuk para pengungsi Palestina.
Jadi goblok dan tolol itu adalah hak. Saya gak bilang para pegiat ITJIL yang suka nyinyir pada solidaritas Paris itu tolol, ya, tapi sejauh mana mereka paham tentang konsep solidaritas? Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), disebutkan bahwa Perancis menyumbangkan setidaknya $ 16.800.000 untuk para pengungsi Palestina. Kira-kira pegiat ITJIL itu butuh waktu berapa lama agar bisa mencapai angka itu?
Dari daftar yang dirilis UNRWA itu kita bisa belajar untuk adil. Misalnya, jika aktivis pluralis sering koar-koar minimnya peran Saudi di Palestina, mereka bisa kaget dan terdiam melihat jumlah sumbangan Saudi untuk pemulihan Palestina. Pada 2014 saja, Arab Saudi menyumbang $ 103.519.499 untuk pemulihan dan kebutuhan para pengungsi Palestina. Nah sementara pegiat ITJIL, FPI, MMI, HTI dan sejenisnya juga bakal ambeien jika tahu total sumbangan Amerika untuk Palestina $ 408.751.396. Situ mau ngehina negara yang udah banyak nyumbang buat Palestina?
Sampai di sini, egonya udah bisa diturunin dikit? Nah, Anda boleh tidak percaya pada angka ini, atau bahkan menggugat, dan menuduh angka sumbangan itu bohong. Kabar baiknya, badan PBB selalu memberi laporan penggunaan dana beserta akuntabilitasnya. Anda sekalian, aktivis pluralisme dan antipluralisme, bisa saling menguji apakah benar angka sebanyak itu digunakan untuk pemulihan dan pengungsi Palestina. Jangan-jangan untuk mendanai ISIS? Jangan-jangan digunakan untuk dana kebencian di Indonesia?
Kemampuan terbaik dari pemalas yang enggan membaca adalah mengomentari apa saja tanpa adanya pemahaman. Misalnya, ngomong gini: giliran Perancis diserang kalian rame, ke mana dunia saat Iraq diinvasi? Jika ada orang kelewat dungu yang komentar kayak gitu, jawab aja gini: Dominique Reynié, seorang akademisi dari Perancis (eng-ing-eeeng!), menyebutkan bahwa antara Januari hingga April 2003 terdapat 3.000 protes invasi Iraq yang dilakukan di seluruh dunia. Total ada 36 juta orang yang ambil bagian dalam protes ini dan mengutuk invasi sebagai kejahatan kemanusiaan. Gak pernah tahu? Mungkin karena Anda kebanyakan baca PKS Piyungan.
Lalu jika ada yang bilang 140 orang mati di Paris dunia berduka, setiap hari orang mati di Afganistan tak ada yang bersuara. Nah, jika ada ustadz, atau yang ngaku ustadz, atau ustadz-ustadzan karena baru masuk Eslam, atau alumnus Insistut Tarbiyah Bapuk, yang ngomong gitu, bilang aja sejak 2001 sampai 2014 dunia Barat telah mengutuk dan memprotes perang di Afganistan. Di Amerika sendiri, sepanjang maret 2009 ada beberapa aksi dengan total lebih dari puluhan ribu orang yang memprotes perang di Afganistan.
Lho, kok gak tahu? Kok bisa gak tahu? Lha ini yang gak peduli sebenarnya siapa? Yang dituduh ikut-ikutan solidaritas tragedi Paris, atua kalian yang sebenarnya cuma baca media gak jelas? Kalian boleh tidak percaya saya, kalian hanya perlu mencari lebih banyak. Dan sekali lagi, berita-berita kayak gini emang gak akan ada di media macam PKS Piyungan, Ar Rahmah, VOAIslam atau sejenisnya.
Tapi ya apa itu penting? Poin penting komentar kan waton muni, asal bisa bersuara. Masalah paham isu atau tidak, itu urusan belakangan.
Ketika warga Pati menang gugatan di Semarang, orang bijak tentu akan mencari tahu sejarah dan konteks perjuangan para petani tadi. Nah, yang pikirannya medioker akan berkomentar sesuai kapasitas kepalanya. Misalnya dengan berkata, “Keadilan mah kalo menang sidang, kalo kalah dibilangnya gak adil.” Sudah, jangan marah, orang model begituan cuma mengeluarkan isi kepalanya kok. Mereka gak punya kewajiban untuk jadi pinter.