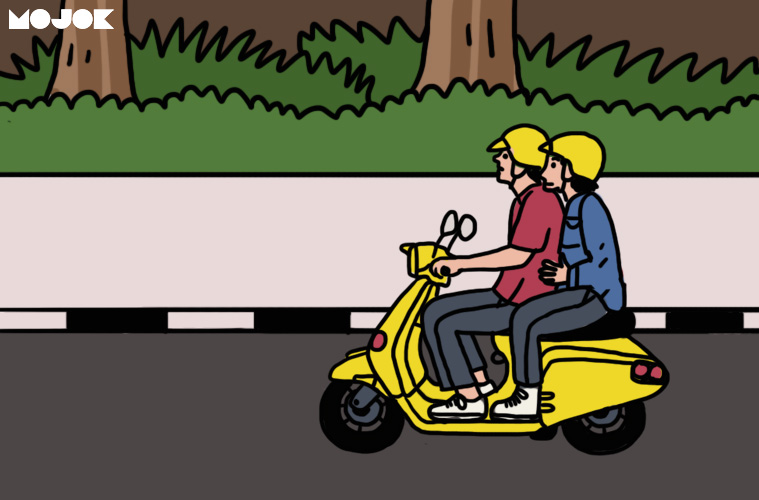Baca cerita sebelumnya di sini.
“Kita ini mau ke mana, Lid?”
“Nantilah, kau akan tahu.”
Jelas itu bukan jawaban. Stang gas motor yang ditariknya hanya menegaskan bahwa ia sedang tidak ingin ditanya tujuannya.
Sejak huru-hara yang terjadi di pekarangan rumah Kaji Badrun itu, Ulid dianggap oleh sanak keluarga dan teman-temannya terguncang batinnya. Ia macam tokoh cerita yang ditarik keluar dari ceritanya dan dipaksa berada di cerita orang lain. Ia linglung. Ia terlihat sering bengong, bicara sendiri, tingkah lakunya sulit dimengerti. Bila ada orang lain yang mencoba mengajak ngobrol, ia hanya termangu menatap titik di kejauhan. Namun, saat tak sedang ada yang mengajaknya bicara, ia akan nyerocos ke mana-mana, tentang apa saja. Ia seperti punya dunia yang berbeda, yang tak bisa orang lain raba dan kira, dan Ulid seperti tak peduli dengan itu.
Mereka yang tahu riwayat cintanya, akan punya pemakluman lebih. Ia patah hati ketika cinta dan cita-cita itu justru sedang kuat-kuatnya. Dan itu meruntuhkan nyaris seluruh dunianya. Teman-teman yang mengerti kisah-kisah kegagalannya bisa mengerti apa yang mesti dilewati lelaki rapuh itu. Dan kini, setelah ditemukan nyungsep dengan kepala tertimbun berkeranjang-keranjang pentol bakso, semua orang bersepakat bahwa mungkin saja ada sebutir pentol bakso yang menghantam titik terlembut dan paling sensitif di kepalanya. Dan, begitulah ia. Bahwa tokoh kita ini masih bisa mengenali wajah-wajah orang dan masih memelihara kemampuan mengendalikan tetes ilernya, itu jelas hal patut disyukuri.
“Ayolah, ini sudah terlalu jauh.”
“Bukankah kita memang sudah terlalu jauh?”
“Maksudnya?”
“Masa kamu nggak ngerti?”
“Tidak. Sungguh.”
“Kalau begitu tak usah banyak tanya. Ikut saja.”
“Bagaimana kalau nanti budemu tanya?”
“Ada urusan apa dengan budeku? Aku tadi sudah ngomong sama Emak kok.”
“Lho, makmu bukannya di Malaysia?”
Ulid tertawa. Dan tertawa lebih keras. “Siapa bilang? Kamu kan tahu sendiri ia di rumah.”
“Aku tahunya beliau di Malaysia.”
“Tadi kan ngobrol sama kamu, Min?”
“Min siapa?”
“Kamu Yamin, kan?”
“Aku bukan Yamin.”
“Mana mungkin aku berboncengan denganmu, Jib?”
“Najib, maksudmu? Tidak, aku bukan Najib. Coba lihat baik-baik di kaca spion.”
“Lho, kamu siapa?”
“Masa nggak tahu?”
“Kamu siapa, sih?
“Aku Mahfud.”
“Heh?”
“Mahfud!”
“Mahfud yang mana? Mahfud temanku seingatku nggak mirip kamu.”
“Mahfud yang itu lho… yang—bagaimana ngomongnya ya? Yang… pernah menulis cerita tentangmu itu, lho!”
“O….” ada jeda yang agak panjang, lalu ketawa yang lebih panjang, diikuti oleh gerakan memukul-mukul stang sepeda motor. “O…. Mahfud yang itu toh….” Dan ketawa lagi. “Yang membikin-bikin cerita yang tidak pernah terjadi seolah-olah benar-benar terjadi. Apa namanya? Oh ya, ‘Berdasar kisah nyata’. Ha ha ha….”
“Lho, itu memang kisah nyata, kan? Kisah yang benar-benar terjadi kepadamu, bukan begitu?”
“Itu kisah yang kau pikir benar-benar terjadi kepadaku, mari kita bedakan itu, Bos!”
“Berarti kisah yang kau ceritakan kepadaku itu tidak benar-benar terjadi?”
Tertawa lagi. “Ya nggaklah!”
Senyap seketika.
“Jadi…,” yang bertanya jadi sedikit gagu. “Jadi, emakmu benar tidak di Malaysia?”
“Tidak. Dan tidak pernah. Dia di rumah. Stres ngurus Bapak sama aku.”
“Oh, bapakmu juga di rumah? Pasti setelah capek jadi TKI, ya, ‘kan?”
“Bapak di rumah saja. Tak pernah ke mana-mana. Dan mungkin karena itu agak stres.”
“Kenapa tidak mengajar lagi saja?”
“Mengajar apa? Dia dulu MC untuk acara-acara Golkar, selain bantu-bantu membuat dan memasang alat-alat peraga kampanye, dan bantu-bantu hal lainnya juga. Kalau tidak ada yang membaca gema wahyu ilahi, dia juga yang lakukan. Tapi seringnya ia merangkap sebagai penyanyi. Suaranya cocok untuk lagu-lagu Mansyur S., meskipun lagu yang paling sering dinyanyikan tentu saja lagu “Dua, dua…” dari Muchsin Alatas. Tapi, sejak Reformasi, semuanya berhenti. Stop. Habis semua. Ia tak terpakai. Dan pihak lain juga tak mau memakainya. Dan ia tak melakukan apa pun sejak itu, sebab ia tak bisa melakukan hal lainnya.”
“Lho, kok beda sama yang dulu kau ceritakan?”
“Aku kan menceritakan yang ingin kau dengar, to?”
Suara mesin motor menderu. Percakapan sejenak berhenti.
“Jangan-jangan…. namamu juga bukan Ulid?”
“Bukan. Tapi panggil saja begitu. Tak apa.” Senyum menyeringai terlihat di kaca spion kanan. “Kita sudah sampai.”
Motor melambat.
“Tempat apa ini?”
“Warung kopi. Tempat kesukaanmu, ‘kan?”
“Kok tahu?”
“Aku tahu dirimu jauh lebih banyak dibanding dirimu tahu aku.”
“Jadi, kau baca buku-bukuku?”
Tertawa lagi. “Masa kesimpulannya begitu?”
Motor kemudian membelok ke jembatan kecil di atas selokan besar yang menghubungkan badan jalan dan pekarangan warung mungil yang tampak tua dan sepi. Bangunan warung itu dari papan kayu bercat hijau muda yang sudah memudar dengan kisi-kisi jendela kiosnya kuning terang, yang sepertinya tidak pernah diperbarui sejak dicat pertama kalinya mungkin setengah abad lalu. Kita bisa melihat rumah dan bangunan lain dari depan warung itu: rumah di seberang jalan, penggilingan dan tempat pengeringan gabah, kandang sapi, dan gudang palawija. Tapi, rasa-rasanya, tempat itu terpisah dari dunia sekitar.
“Ini warung kopi apa?”
“Yang jelas, tak ada anak-anak main hape di sini.”
“Kenapa kita mesti ke sini? Sejauh ini?”
“Kau akan tahu nanti.”
Mereka masuk warung. Hanya ada dua dipan bambu yang memutari sisi depan dan samping meja yang berisi gorengan bertimbun cabe dan aneka jajanan dan stoples-stoples berisi permen-permen langka yang seperti dicuri dari koleksi sebuah museum kuliner. Dari balik meja mengalun suara Oma Irama dalam tarikan nada dan vokal yang terdengar lebih berat dari biasanya. Itu tampaknya tape recorder lama yang memutar kaset dengan pita yang terlalu sering diputar. Lagu “Tabir Kepalsuan” dari film Kemilau Cinta di Langit Jingga baru dimulai.
Ternyata hatimu…
buta…
buta karena…
tabir kepalsuan….
“Kopi! Dua!” teriaknya, ke arah dapur.
“Orangnya lagi keluar. Ditunggu sebentar.” Seseorang dari dipan di sisi samping menyahut. Ia bersama dua orang lainnya. Mereka mengelilingi sebuah asbak dan dua gelas kopi yang hampir habis.
“Oh, kamu toh, Lid!” satu orangnya lagi menoleh. “Bagaimana kabar Bapak?”
“Baik, Pakde. Tapi, ya… begitulah. Seperti biasa. Lebih banyak diam. Kalau pun melakukan sesuatu, ya ia melakukan sesuatu yang seperti biasanya: mengutak-atik radio Cawang tuanya.”
“Ya ini, ya bapaknya si Ulid ini, yang kemarin bikin orang kalang kabut dengan hujan pentol di orkesannya Kaji Badrun,” kata yang satu lagi.
“Benar, Lid?”
“Ngakunya sih begitu,” jawab Ulid. “Cuma, aku tidak tahu benar tidaknya. Wong orangnya juga tidak ke mana-mana, di rumah saja.”
“Ya, kalau bukan bapakmu, siapa yang bisa bikin begitu,” sela yang pertama bicara. “Hanya Rokeman yang bisa begitu. Ya ‘kan, Rut? Kau ingat dia bisa membuat ribuan orang di kampanye Golkar menangis tersedu-sedu setiap juru kampanye menyebut nama Pak Harto. Itu tahun ‘92, ingat toh?”
“Ya, hanya Rokeman yang di zaman begini masih bisa melakukan macam itu.” Orang yang dipanggil Rut ikut bicara. Ia mencopot topi AC Milan di kepalanya, dan segera terlihat bekas parutan di separoh mukanya. “Tapi kupikir kejadian macam ini sudah tak mungkin lagi terjadi. Kau pernah dengar kalau bapakmu bisa membuat lima remaja yang mengisruh kampanye joget selama sehari semalam, Lid?”
“Pernah. Tapi apa memang begitu?”
“O… kamu tak percaya apa yang bisa dilakukan bapakmu ya?”
“Tapi itu lumrah, To. Hanya kita-kia yang mengenalnya yang percaya bahwa bapaknya Ulid yang melakukannya. Orang lain pasti tak akan percaya. Dan itu bagus, ‘kan?”
“Jadi benar itu, De?”
“Kau pikir siapa yang bisa membuat orang-orang percaya si Mugiyono jadi Megi J. Ade? Bapakmu!”
“Oh ya,” Ulid menyela. “Di kampung pada ribut. Ada saksi mata yang cerita, Om.”
“Lha, kan memang kita bikin begitu. ‘Biar ramai’, itu intinya.” Megi J Ade yang ternyata Mugiyono menyerobot dengan cengiran mirip Meggy Z.-nya. “Sekarang bagaimana perasaanmu setelah Kaji Badrun mati?”
“Baguslah, Om. Brengsek orang tua itu.”
Suara Oma Irama seperti menyela.
Kutahu kau terjerat dan terbenam dalam kepalsuan
Buta tak dapat lagi membedakan siapa dan yang mana…
“Cuma begitu?”
“Ya, itu setidaknya akan mengurangi tanggapan-tanggapan atas musik macam itu berkurang. Ya, ‘kan?”
Meggy Z. palsu mengangguk-angguk. “Ya, pikirku juga begitu.”
“Terus kenapa si kupluk Bob Marley itu disikat juga, Pakde Tato?”
“Ya, kalau menurut firasatku, orang ini akan membawa dampak buruk bagi dangdut di kelak kemudian hari. Dan lebih baik kulenyapkan daripada terlambat.
Semua yang hadir mengangguk-angguk tanda memahami. Oma Irama sudah berada di ujung laginya. Musik “Tabir Kepalsuan” sudah kembali ke intronya. Dan semua orang, termasuk Ulid ikut terangguk-angguk. Lalu, mereka kompak ikut berdendang.
(Teng… tong teng…. tong teng…)
Telah kupaparkan segalanya padamu siapa diriku…
Kini kuserahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu
Lalu, semua orang menaikkan volume suaranya.
Kan kuterima itu walaupun hati pedih dan merana…
Karena kutahu tak seorang pun bisa memaksakan cinta…
O… o… o… o…
Dan, seperti Oma yang baru saja menjelaskan segala hal yang salama ini disalahpahami oleh kekasihnya Aida, di akhir film Kemilau Cinta di Langit Jingga, mereka semua begitu lega.
“Oh ya, kenalkan temanku, Pakde, Om. Dia ini penulis. Ya, dulu pernah menulis tentang aku, sih. Sepertinya dia ini suka dangdut. Itu yang kutahu sih. Kalian bisa uji sendirilah. Kalau tipu-tipu sikat saja.”
“Memang kau sama siapa?”
“Lho, ke mana dia? Tadi di sini kok.”
Baca cerita berikutnya di sini.