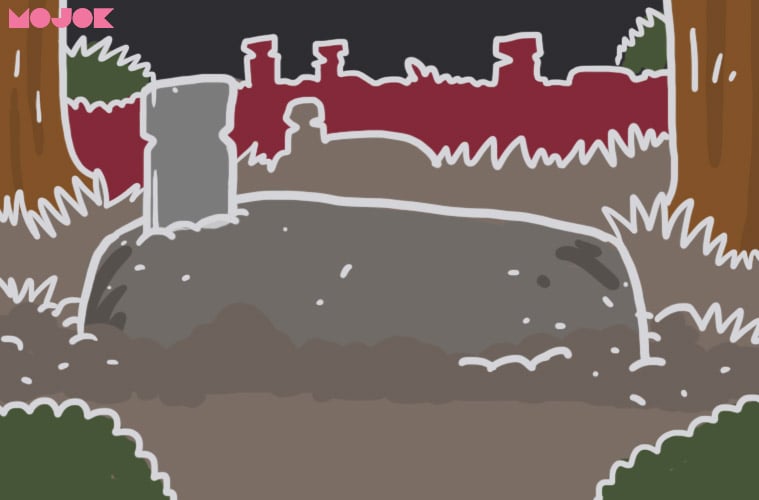Baca cerita sebelumnya di sini.
Dendam hanya akan melahirkan luka demi luka yang baru apabila tak diobati. Aku mencoba menyembuhkan hal itu. Setidaknya aku tak menginginkan ada dendam di antara orang-orang yang kutinggalkan.
Aran dan Adimas, terutama bagi mereka berdua. Aku tak menginginkan dendam dirawat dengan subur selepas peninggalanku. Maka, haruslah aku yang berbicara mengenai persoalan yang ada. Dari semua sebab dalam hidupku, ternyata akulah muara dari semuanya. Kecemasan, cemburu, sakit hati, amarah, luka yang menggores di beberapa hati pun ternyata lantaran diriku. Sebisa dapat aku harus memperbaiki semuanya.
Nama Rilla muncul begitu saja selayaknya sebuah ilham setelah aku termenung-menung memikirkan bagaimana caranya meluruskan semuanya selepas kematianku. Maka kupilih Rilla, kawan baik yang sudah kuanggap sebagai adik sendiri. Kuminta ia menerangkan segala sesuatu yang selama ini tampak gelap. Kuberikan warna-warna kepada Rilla untuk meluruskan semuanya yang abu-abu. Aku tak ingin meninggalkan hal-hal yang masih tampak kacau selama ini.
Rilla melakukan segalanya dengan sangat baik. Dia seperti yang kuduga sebelumnya. Rilla tak pernah mengecewakanku sejak dulu. Adimas telah menemukan dirinya yang dulu. Dirinya yang sempat hilang lantaran ditelan amarah dan dendam. Kutemukan sorot yang begitu kukenal dari mata sahabat baikku itu. Selepas Rilla menemuinya, kudapati Adimas sudah jauh lebih nyenyak tidur. Setidaknya, itu yang kulihat malam selepas Rilla menemuinya.
Jauh malam-malam setelah kematianku, Adimas kerap urung tertidur. Pola hidup sehat yang selama ini dia amalkan menjadi sangat kacau. Pada banyak waktu, Adimas hanya merenung. Amarah dan benci kerap bermain di kedua bola matanya. Aku sangat sedih melihatnya. Kehilangan jati diri sahabatku ternyata jauh lebih menyedihkan ketimbang kehilangan nyawaku sendiri. Adimas telah menerangkan mengenai hal itu meski dia tak pernah mengucapkannya lewat kata-kata. Aku bisa membaca dari dirinya setelah aku dimakamkan hari itu.
Tetapi, dari sekian hal yang dilakukan Rilla untuk membantuku, ada satu yang membuatku benar-benar menangis: saat Rilla bersilang pandang dengan Aran di ruang besuk tahanan, saat mata Aran melihat sekantong plastik tempe kemul kesukaannya.
Sungguh, aku tak bisa lagi menggambarkan betapa baiknya Rilla atas itu. Akhirnya, lidah lelaki yang kupilih menjadi suami itu merasakan lagi gurihnya tempe kemul kesukaannya. Lidahnya mungkin nyaris mati rasa dengan masakan tahanan yang selama ini kelewat “apa adanya” itu. Melihat binar di matanya, aku tahu bahwa dia sangat berterima kasih dengan oleh-oleh yang dibawa Rilla.
Setelah Rilla pulang dan dia kembali ke selnya, Aran terlihat lebih banyak diam. Dia duduk di pojok ruangan seperti beberapa waktu belakangan. Matanya menatapku sekilas, lalu menunduk seolah mengingat-ingat sesuatu.
Seorang sipir mengetuk pintu selnya. Aran menoleh, lalu dia mengangkat tangan sembari tersenyum mengabarkan bahwa dia baik-baik saja. Melihat sipir itu pergi, aku mendekatinya. Perlahan aku duduk di depannya. Tapi, seolah tak melihatku, Aran kembali menundukkan kepala menatap ubin.
“Kau marah aku meminta Rilla menemuimu?” aku menatap Aran dengan saksama.
Perlahan dia mengangkat kepalanya dan tampak pias. Keringat dingin membasahi wajahnya yang kini kurus itu.
“Tidak. Aku malah berterima kasih dengan Rilla atas kedatangannya hari ini. Aku kini percaya bahwa dia benar-benar baik seperti yang kau bilang dulu.”
Mendengar jawaban Aran, aku menyentuh pipinya. Sayangnya, aku tak lagi bisa merasakan suhu tubuhnya. Tanganku terlalu dingin. Tapi aku melihat bahwa Aran sedang tak baik-baik saja. Seperti itulah dirinya ketika tidak enak badan. Pucat, keringat dingin, dan nada suaranya terdengar lemah. Andai aku bisa menggosoknya dengan minyak angin seperti dulu atau membuatkannya minuman jahe dengan gula aren panas, mungkin Aran akan terlihat jauh lebih baik.
“Aku mengira kau akan marah,” sahutku lagi.
“Aku dilahirkan tak hanya untuk marah-marah saja, Sayang,” desah Aran perlahan.
Aku tersenyum. Aran benar. Dari sekian banyak kebersamaan kami, kemarahannya mungkin hanya 40%. Sisanya, dia menghabiskan waktu untuk berbagi hidupnya denganku dengan caranya. Seperti di awal, kebersamaan kami dirajut dengan segala macam problema kehidupan yang kerap mengundang keheranan dari diriku sendiri atau orang-orang sekitarku.
“Kau tahu, Sonya? Aku sedang memikirkan kehidupanku ke depan setelah kau menghilang nanti. Jika Tuhan benar-benar telah memanggilmu kembali, bagaimana dengan diriku? Aku tak memiliki siapa-siapa lagi, Sonya. Ayahku telah meninggalkanku sejak aku masih kecil, ibuku yang mungkin masih hidup kini entah berada di mana. Orang-orang yang mengenalku telah terang-terangan tak ingin mengenalku lagi. Aku pikir, bagaimana nanti hidupku setelah lepas dari sel ini lima belas tahun lagi? Aku tak akan memiliki siapa-siapa, dirimu pun tak bisa kumiliki lagi meski sebatas bayangan,”
Aran menggigit bibirnya. Kedua matanya menatap nanar tembok pucat di hadapannya. Lima belas tahun nanti dia akan lepas dari jeruji besi ini. Mungkin bisa lebih cepat dari angka itu, setelah pengacaranya yang katanya andal itu bisa melobi hakim yang bijaksana.
Aku mengharapkan Aran lepas dari kungkungan jeruji besi ini lebih cepat dari dakwaan yang dituntut jaksa penuntut umum. Memang gila, mungkin korban yang menginginkan sang terdakwa segera bebas dan menghirup udara bebas hanya aku seorang.
“Mengapa kau mengatakan itu? Kau akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Setelah keluar dari sini, kehidupan lain akan menunggumu. Bahkan kau bisa mendapatkan pengganti diriku kelak. Kau akan menikah lagi dan memiliki anak-anak yang baik dan lucu. Seperti keinginanmu dulu,” aku mengucapkan hal itu dengan kegetiran yang luar biasa di ulu hati. Dulu, Aran kerap kali mengungkapkan impiannya itu kepadaku. Mimpinya itu kelak menjadi mimpi kami berdua.
Aku sendiri dulu membayangkan bahwa kami akan baik-baik saja. Kami akan menjalani sisa umur pernikahan kami dengan kebahagiaan seperti pasangan lainnya. Anak-anak yang baik akan menjadi pelengkap hidup kami. Di masa tua ketika kami lelah bekerja, kami akan banyak menghabiskan waktu berdua untuk bersantai di rumah sembari menonton televisi dan menikmati kudapan-kudapan kegemaran kami. Cucu yang lucu dan manis akan menambah semarak hidup kami berdua.
“Tidak. Dulu aku berpikir begitu karena ada kau di sampingku. Kini semua itu tak penting lagi,” sahut Aran cepat. Wajahnya bertambah pucat.
“Kau sakit,” desahku sembari menggenggam tangannya. Kini aku merasakan tangannya bergetar hebat, meski tetap saja aku tak bisa mengetahui suhu tubuhnya.
“Aku tidak sakit. Aku sudah lupa bagaimana rasanya sakit,” Aran merebahkan tubuhnya.
Aku hanya menatapnya dengan nanar. Awal pernikahan kami berdua, aku sempat kebingungan saat melihat Aran meringkuk di sofa. Tubuhnya menggigil, suhu tubuhnya tinggi saat itu. Terlebih, tak lama setelahnya, dia terdengar mulai meracau. Aku kebingungan. Dengan cepat aku mengambil balok-balok kecil es batu di lemari pendingin dan kukompres Aran segera. Saat melihatnya agak membaik, aku membawanya ke praktek dokter yang tak jauh dari rumah.
“Jika sedang sakit, mengapa kau tak bilang? Bikin gugup orang saja,” desahku antara kesal dan khawatir.
Aran terdiam. Dia tergolek di ranjang dengan lemas, wajahnya pucat. Matanya sedikit memerah lantaran panas tubuh yang tadi sempat tinggi.
“Aku sudah terbiasa menahan sakit seorang diri sejak ditinggal ayah. Kini aku lupa bahwa aku sudah punya istri.”
Seketika aku tercenung. Aran memang telah lama menghabiskan hidupnya seorang diri sepeninggal ayahnya. Dia tak terbiasa berbagi hidup dengan orang lain. Hal itu kudapati setelah kami menikah. Di awal pernikahan, Aran kerap lupa bahwa di rumah kini dia tak sendiri lagi. Ada aku menjadi teman hidupnya.
Tak hanya masalah jika sakit. Dulu saat lajang, aku jarang sekali memasak. Namun setelah menikah, aku selalu berusaha menghadirkan makanan di meja makan. Belum terbiasa memasak membuatku kerap melupakan beberapa bumbu yang seharusnya kububuhkan untuk memperkuat masakan. Seringnya aku melupakan garam. Sayur asam, sup, bahkan tumis terkadang rasanya hambar saja. Aku kerap dibuat mengerutkan kening ketika merasakan masakanku sendiri.
Tapi Aran terlihat biasa saja, dia makan dengan lahap. Sayur sup yang hambar itu dimakannya seolah masakan buatanku demikian sedapnya.
“Apa kau tak merasakan kalau sayur sup ini hambar?” tanyaku hati-hati sembari menatap Aran dengan rasa bersalah. Besok jika memasak, stoples garam itu harus kuletakkan tepat di depan mataku.
“Biasa saja. Terkadang jika memasak, aku juga lupa menambahkan garam. Apalagi jika garam di rumah habis dan aku malas untuk membelinya. Masakanmu masih aman,” jawab Aran sembari menyeruput sisa kuah sup di mangkuk.
Aku tak tahu harus menangis atau tertawa melihat dan mendengar jawaban suamiku. Di satu sisi, aku terharu dengan bagaimana dia menjawab pertanyaanku. Begitu polosnya dan jujur, tak ada sesal di suaranya meski aku menyajikan sup hambar tanpa garam. Di sisi lain, aku ingin menangis lantaran bingung dengan sikap pendamping hidup yang baru kunikahi beberapa waktu yang lalu ini.
Kini aku dan Aran berada di tempat yang sama dalam situasi berbeda seperti dulu. Kami berada di dalam jeruji besi. Tubuh dan jiwaku mungkin bebas, tapi tidak dengan Aran. Tubuh dan jiwa Aran terkungkung di tempat ini untuk belasan tahun yang akan datang. Diriku kelak akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Aran tak akan bisa melihatku seperti saat ini. Mungkin aku akan muncul sebatas lewat mimpinya.
Aran melenguh. Tangan kanannya terlihat bergetar memegang perutnya. Dia masih meringkuk di pojokan ruang tahanan.
“Kau sakit. Panggillah sipir untuk datang ke sini membantumu,” aku memegang pipi Aran dengan cemas.
“Tidak. Aku sudah terbiasa sakit seperti ini,” suara Aran terdengar lemah.
“Tapi kau kelihatan sangat sakit. Percayalah padaku, Aran. Panggil sipir untuk kemari membantumu!”
Aran tak menjawab. Dia hanya menggeleng. Napasnya sedikit berat. Kali ini kedua tangannya memeluk perutnya sendiri dengan erat. Wajahnya pucat pasi, dia terlihat menyeringai menahan sakit.
Dengan cemas aku berlari ke arah pintu sel. Dengan sekuat tenaga aku memanggil-manggil sipir penjara. Tapi seolah tertelan udara, suaraku tak didengar oleh sipir atau penghuni penjara lainnya. Aran masih meringkuk. Kedua lututnya ditekuk sampai ke perut. Dia mengerang perlahan.
Kalimat-kalimat yang diucapkannya tadi terngiang kembali di telingaku. Masa-masa kebersamaan kami kembali berputar seperti film di layar bioskop. Ketakutan Aran untuk hidup sendiri aku lihat dengan jelas ketika melihatnya meringkuk menahan sakit seperti malam ini. Perlahan aku berjalan mendekatinya. Air mataku meleleh. Tuhan, bagaimana aku bisa begitu mencintai manusia ini?
Air mataku terus meleleh meski aku tak menginginkan menangis malam ini. Kelenjar air mataku seakan hidup kembali setelah tubuhku mati berminggu-minggu yang lalu. Aku duduk di depan Aran, kubelai pipinya sembari berucap,
“Kau tadi takut hidup sendiri, kan? Kini aku pun tak rela kau hidup sendiri. Bagaimana jika kau ikut aku saja, Sayang? Di samping makamku masih ada tanah kosong, tepat di bawah pokok mahoni. Mungkin kau akan menyukainya. Bagaimana?”
Baca cerita berikutnya di sini.