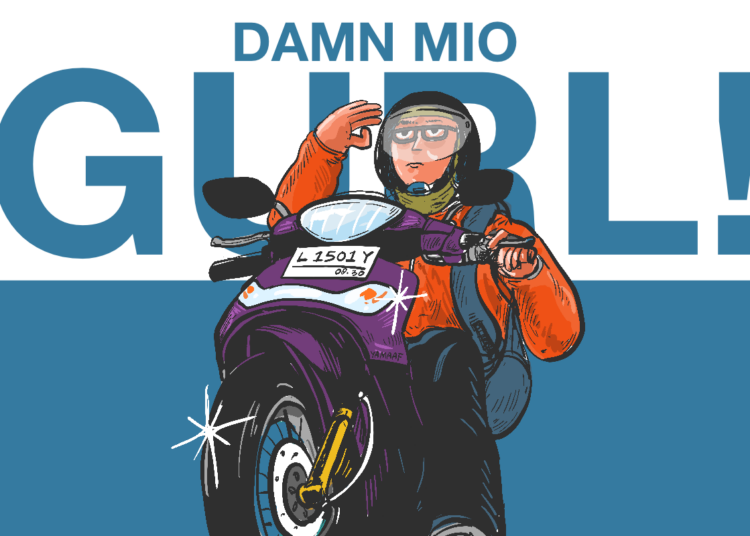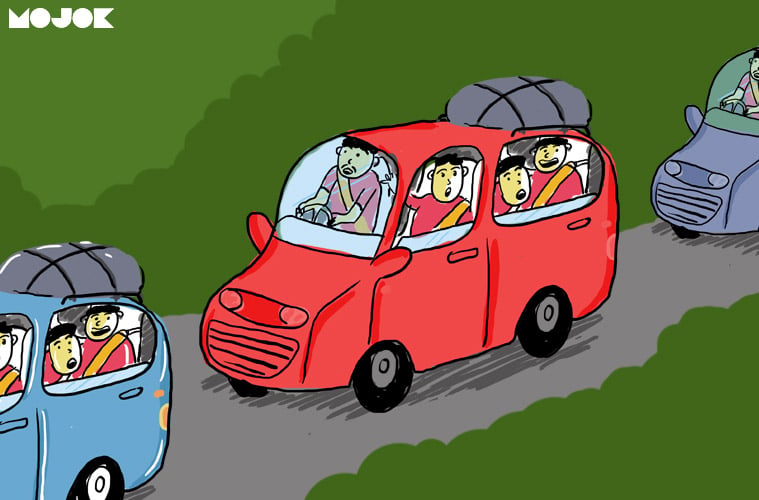Kalau Anda orang Sukoharjo asli, pasti pernah mengalami momen yang satu ini: sedang nongkrong di luar kota, kenalan baru tanya, “Asli mana?” Anda jawab, “Sukoharjo.” Mereka akan tersenyum, matanya berbinar, lalu berkata mantap, “Ohhh… Bekonang toh.”
Padahal mungkin saja Anda lahir di Grogol, mainnya ke mall Solo Baru, dan nggak pernah sekalipun menenggak minuman hasil fermentasi tetangga. Atau justru Anda orang Tawangsari atau Weru, yang begitu jauh dari Bekonang.
Tapi tetap saja, stempel Bekonang itu nempel di jidat semua warga Sukoharjo, sama seperti orang Malang yang otomatis diasosiasikan dengan Arema, atau orang Madura yang selalu diasosiasikan dengan sate meskipun ada yang vegetarian.
Identitas resmi Sukoharjo sebenarnya rapi dan terhormat. Pemerintah mencetak di spanduk dan gapura selamat datang bahwa, “Sukoharjo Makmur” atau “Kota Jamu”. Bahkan ada monumen jamu gendong, simbol bahwa kita ini gudangnya herbal penyehat badan.
Masalahnya, branding resmi itu kalah telak oleh branding rakyat. Kalau Anda tanya ke mahasiswa perantauan, sopir truk lintas Jawa, atau pedagang kaki lima di luar kota, mereka akan lebih cepat menyebut ciu Bekonang ketimbang jamu gendong. Bagi mereka, Sukoharjo itu kota ciu. Titik.
Sekilas tentang ciu bekonang
Ciu Bekonang ini bukan minuman biasa. Ia punya status cultural landmark, sejarahnya panjang. Orang ke Jogja nyari bakpia pathok, orang ke Palembang nyari pempek, orang ke Sukoharjo/Bekonang? Nyari ciu. Dan mereka akan bercerita ke teman-temannya seolah baru pulang dari wisata kuliner legendaris. Bedanya, kalau bakpia bisa diposting di Instagram dengan caption manis, ciu Bekonang biasanya diposting di status WhatsApp jam tiga pagi dengan caption “hidup cuma sekali”. Itu pun memprivasi beberapa orang.
Kalau wine di Prancis disajikan di gelas kristal dengan lampu temaram, ciu Bekonang disajikan di botol Aqua bekas yang tutupnya kadang sudah miring. Kalau Sake Jepang diminum sambil berkumpul dengan keluarga, ciu Bekonang diminum sambil main gaple dan curhat tentang pahitnya cinta. Keduanya sama-sama hasil fermentasi, tapi bedanya yang satu masuk majalah gaya hidup, yang satu masuk laporan razia Satpol PP.
Lucunya, jamu dan ciu ini sebenarnya saudara jauh. Sama-sama dari bahan alami. Sama-sama melewati proses fermentasi. Bedanya, jamu diundang ke seminar kesehatan, ciu diundang ke acara 17-an RT. Jamu bikin badan segar, ciu bikin mulut lancar, terutama saat mengkritik kepala desa.
Masyarakat luar Sukoharjo mungkin melihat ini sebagai paradoks. Kok bisa, kota yang terkenal jamu sehat juga terkenal ciu mabuk? Tapi buat orang lokal, mungkin ini bukan kontradiksi, ini keseharian. Pagi minum beras kencur, malamnya sedikit ciu. Sehatnya dapat, hangatnya juga dapat.
Malu-malu iya
Masalahnya, pemerintah agak canggung mengakui identitas ini. Mereka terus menggembar-gemborkan Sukoharjo sebagai kota jamu di setiap pertemuan daerah, tapi di lapangan, jejak ciu Bekonang jauh lebih mudah ditemukan ketimbang monumen jamu. Kalau ada lomba branding daerah paling realistis, Bekonang sudah juara provinsi tanpa perlu anggaran promosi.
Saya pernah membayangkan bagaimana jadinya kalau Pemkab Sukoharjo berhenti pura-pura dan mulai jujur soal ini. Bayangkan tagline resmi: “Sukoharjo, Kota Jamu dan Ciu: Tradisi Fermentasi Nusantara.” Atau festival tahunan “Jamu Herbal & Ciu Bekonang Fair” di mana pagi hari para warha meracik jamu beras kencur, malamnya lomba karaoke dangdut sambil ciu rasa kelapa. Sponsor acara? Yang jelas pasti bukan Kementerian Kesehatan.
Bukan berarti saya yang hanya menumpang tinggal di Sukoharjo mempromosikan mabuk-mabukan. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa ciu Bekonang ini lebih kuat melekat di ingatan publik ketimbang semua prestasi industri Sukoharjo yang lain. Bahkan Sritex, pabrik tekstil raksasa yang seragamnya dipakai tentara NATO sekalipun kayaknya kalah pamor di obrolan warung kopi dibanding botol ciu.
Yang lebih menarik, reputasi ini bertahan tanpa strategi pemasaran, tanpa influencer, tanpa anggaran pariwisata. Semua tumbuh alami lewat cerita dari mulut ke mulut dan botol ke botol. Mungkin inilah yang disebut organic marketing versi pedesaan.
Sukoharjo, mengaku saja
Tentu ada sisi gelapnya: mabuk di jalan, kecelakaan, masalah kesehatan. Tapi kalau kita jujur, di setiap daerah ada warisan yang statusnya semi-resmi seperti ini. Malang punya Topi Miring, Bali punya arak arakannya, Sukoharjo punya ciu Bekonang. Bedanya, Bekonang berhasil menjadikan namanya sinonim dengan produknya, kayak Aqua buat air mineral, Indomie buat mi instan.
Buat orang luar, ini lucu. Buat orang dalam, ini campur aduk. Ada yang malu, ada yang bangga, ada yang pura-pura nggak tahu. Tapi ujung-ujungnya, kalau ke luar kota dan ketemu orang tanya, “Bekonang?” kita cuma bisa nyengir. Menyangkal juga percuma.
Sukoharjo ini, kalau dianalogikan, mirip teman SMA yang dulu juara olimpiade biologi, tapi sekarang lebih terkenal karena sering nongkrong di angkringan sampai pagi. Kita bangga sama masa lalunya, tapi gosip terbarunya jauh lebih seru.
Jadi, wahai Pemkab Sukoharjo, silakan terus promosikan Kota Jamu di baliho dan kunjungan kerja. Rakyat tidak akan melarang. Tapi rakyat juga punya promosi sendiri yang jauh lebih hemat anggaran dan lebih efektif: cerita yang dibawa perantau ke luar daerah, lengkap dengan sedikit aroma fermentasi.
Karena di dunia nyata, reputasi itu bukan soal apa yang kita tulis di papan nama, tapi apa yang orang lain ceritakan di warung kopi. Dan di warung kopi itu, Sukoharjo sudah lama berhenti jadi Kota Jamu. Ia kini jadi Kota Ciu. Mau masyarakatnya marah, malu, atau bangga, dia tetaplah rumah mereka.
Penulis: Alfin Nur Ridwan
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Sukoharjo, Kabupaten Indah yang Terasa Nanggung
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.