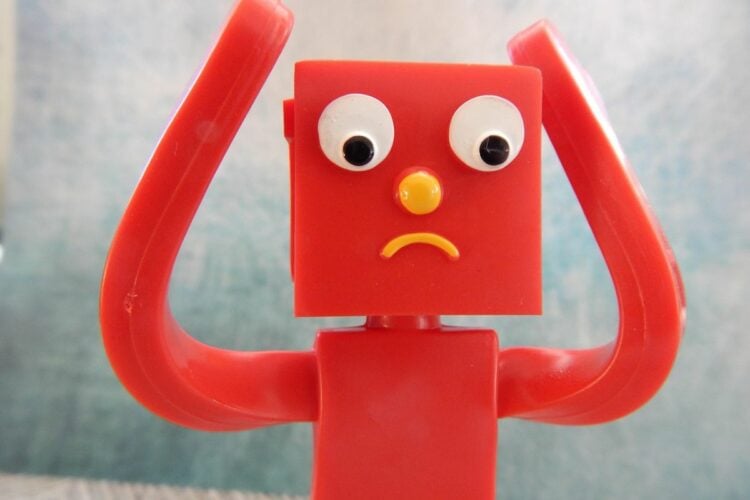Kalau ada satu hal yang saya sesali setelah empat semester menginjakkan kaki di Universitas Islam Negeri, itu bukan soal UKT atau dosen hobi ghosting. Bukan. Keresahan terbesar saya bersifat sosial, kultural, dan spiritual. Keresahan yang membuat saya ingin mencopot label “UIN” dari kehidupan, kalau saja itu mungkin.
Menjadi mahasiswa UIN adalah sebuah seni menanggung malu yang paripurna. Kami adalah wujud nyata dari pepatah “maju kena mundur kena”. Kami adalah middle-child dalam sistem pendidikan Indonesia. Terjepit, serba salah, dan tidak pernah dipahami sepenuhnya.
Membedah keresahan lapis pertama: fenomena sakral bernama “Pulang Kampung”
Bagi kawan saya yang kuliah di kampus umum mentereng, sebut saja UI, UGM, atau ITB, libur semester adalah healing. Mereka pulang, pamer foto di kafe aesthetic, ditanya soal prospek karier di startup unicorn, atau paling banter disuruh jadi panitia 17-an. Hidup mereka normal.
Sedangkan, bagi saya yang anak UIN, libur semester adalah fit and proper test keulamaan. Mereka tidak peduli Anda di kampus banting tulang di jurusan apa. Mau Anda jungkir balik di Komunikasi Penyiaran Islam belajar framing media, atau pusing tujuh keliling di Ekonomi Syariah menghafal akad mudharabah. Di mata Bude, Pakde, dan Pak RT, semua itu tidak relevan.
Yang relevan adalah tiga huruf sakti: U, I, dan N.
Di benak masyarakat, UIN adalah Pesantren Plus yang kebetulan ada gedung rektoratnya. Lulusannya otomatis bersertifikat SNI (Standar Nasional Imam-tahlil).
Maka, jangan kaget. Malam pertama Anda di rumah, baru saja melepas rindu dengan kasur yang bau apek, tiba-tiba Pak RT sudah mengetuk pintu. “Mas, ngapunten. Nanti malam ada tahlilan tujuh hari di rumah Pak Bejo. Sampeyan yang mimpin, nggih? Sekalian kultum sedikit. Kan mahasiswa UIN.” Dunia Anda serasa berhenti berputar. Keringat dingin mulai menetes.
Anda mau bilang apa? Mau jujur kalau di kampus kerjaan Anda cuma nongkrong di basecamp UKM sambil ngopi dan gitaran? Bahwa satu-satunya bacaan Arab yang Anda kuasai di luar kepala adalah menu di warung nasi kebuli. Apa ya mau jujur kalau di mata kuliah Filsafat Islam, Anda baru saja diajari dosen cara meragukan eksistensi Tuhan?
Tidak bisa. Itu semua adalah aib.
Maka, dengan pasrah, Anda mengambil peci bapak yang kebesaran. Berbekal Google yang dibuka diam-diam di bawah sarung, Anda memimpin tahlil dengan suara gemetaran. Anda adalah Ustaz Karbitan yang dipaksa keadaan dan korban ekspektasi.
Anda adalah kiai di mata tetangga. Sebuah gelar kehormatan yang terasa seperti tamparan.
Mahasiswa UIN bisa menjadi ancaman bagi umat
Itu baru masalah pertama. Masalah kedua jauh lebih pelik. Ini terjadi ketika saya bertemu dengan kiai beneran.
Jika di kampung saya dicap sebagai “Harapan Umat”, maka di hadapan kiai sepuh jebolan Lirboyo, Ploso, atau Sarang, saya adalah “Ancaman Umat”.
Saya adalah biang kerok liberalisme. Saya adalah agen JIL. Mahasiswa UIN adalah generasi yang rusak karena terlalu banyak membaca buku. Kenapa? Sebab, di UIN inilah, saya disodori racun paling mematikan bagi pikiran lurus seorang santri: Teori Kritis.
Di UIN, saya tidak hanya diajari cara membaca kitab kuning. Saya diajari cara membongkar kitab kuning. Dosen saya, yang biasanya bergelar Doktor lulusan Australia atau Belanda, dengan santainya masuk kelas dan berkata, “Oke, hari ini kita akan dekonstruksi konsep nusus (teks) menggunakan pemikiran Hassan Hanafi.” Mampus.
Di UIN saya berkenalan dengan nama-nama yang kalau didengar kiai kampung, beliau bisa langsung istighfar seharian. Nama-nama seperti Fazlur Rahman, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud, dan tentu saja, biang keladi segala keresahan intelektual: Hermeneutika.
Saya diajari bahwa tafsir itu tidak tunggal, fiqh adalah produk sejarah yang bisa dinegosiasi, dan perempuan boleh jadi imam salat Jumat (setidaknya secara teoretis di dalam kelas).
Kepala saya yang dulu lurus-lurus saja, kini jadi penuh tanda tanya. Saya merasa tercerahkan dan tentu merasa progresif. Lalu, dengan semangat pencerahan yang meluap-luap, saya mencoba sowan ke kiai pesantren di dekat rumah. Saya mencoba berdiskusi.
“Mohon izin, Kiai,” saya memulai dengan sopan, “Terkait hukum waris, bukankah itu kontekstual zaman Nabi? Kalau kita pakai analisis gender-nya Fatima Mernissi…”
Belum selesai saya bicara, Pak Kiai sudah meletakkan cangkir kopinya. Wajahnya memerah.
“Le, Le,” katanya sambil menggelengkan kepala. “Ngaji-mu itu ketinggian. Adab-mu mana? Kamu itu baru belajar secuil ilmunya orang Barat sudah berani membantah Qur’an. Itu pemikiran liberal! Sesat itu! Ndak ada sanad-nya! Cepat kamu istighfar!”
Selesai.
Mendapat cap sesat
Saya di-skakmat. Dicap sesat. Dianggap anak hilang yang terlalu sombong karena lebih hafal nama filsuf Prancis daripada nama rawi hadis.
Maka, inilah saya. Inilah takdir mahasiswa UIN. Kami adalah spesies amfibi yang paling gagal. Kami tidak bisa hidup di dua alam. Di hadapan masyarakat awam, kami dipaksa menjadi representasi Islam paling ortodoks. Di hadapan ulama ortodoks, kami dianggap sebagai representasi Islam paling liberal.
Kami terlalu Islami untuk bergaul dengan kawan-kawan kami di kampus sekuler yang bebas. Mahasiswa UIN terlalu liberal untuk diterima di lingkaran kawan-kawan kami yang salafi murni.
Kami adalah produk nanggung. Mau jadi kiai, hafalan kami pas-pasan. Mau jadi pemikir bebas, kami masih takut kualat.
Jadi, kalau lain kali Anda bertemu mahasiswa UIN, tolong jangan suruh kami memimpin doa. Ajak saja kami ngopi. Karena di situlah satu-satunya tempat kami bisa menjadi diri kami sendiri, tanpa harus menjadi kiai atau menjadi sesat.
Penulis: Rendi
Editor: Yamadipati Seno
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.