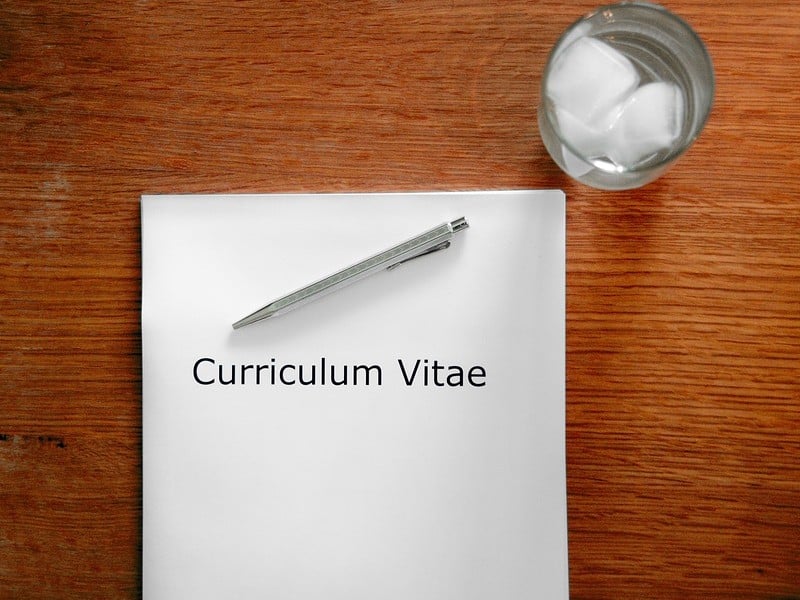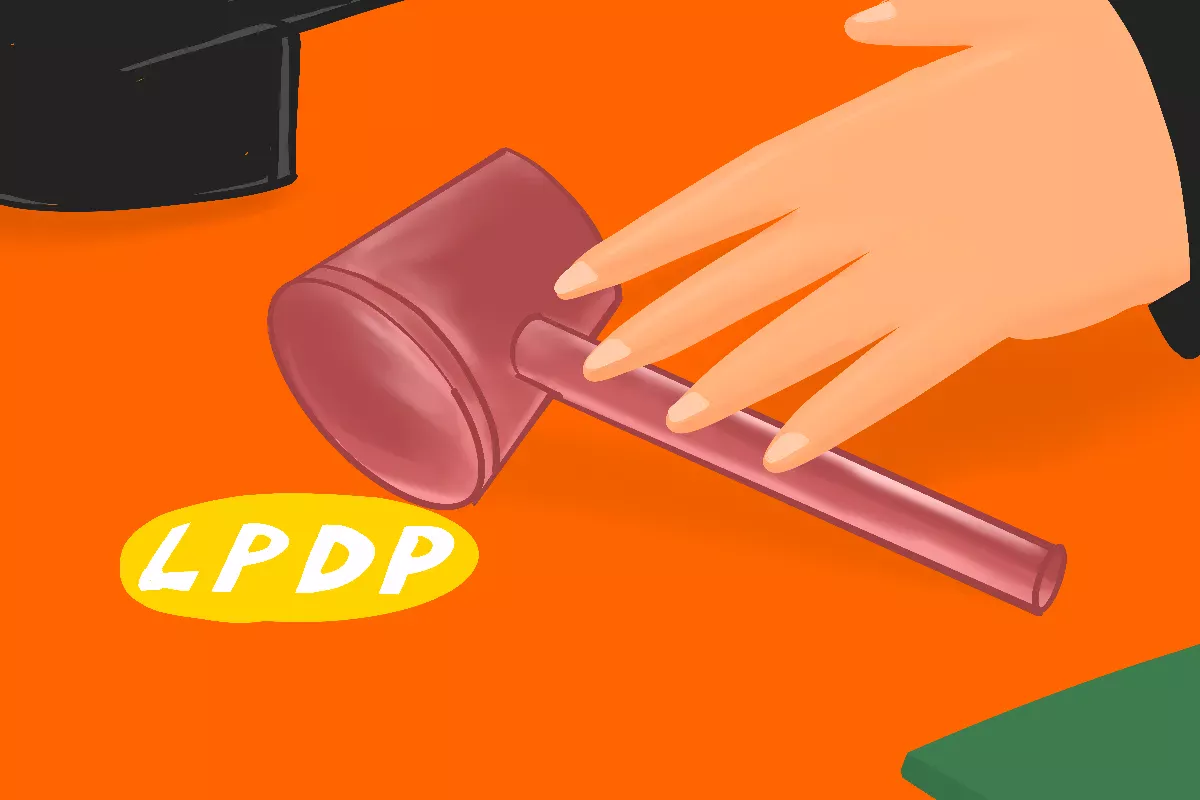Selamat datang di dunia perkuliahan, di mana angka-angka di transkrip menjadi mata uang utama. Sementara itu, kesehatan mental hanyalah catatan kaki yang sering diabaikan. Keberhasilan mahasiswa dinilai dari seberapa tinggi IPK mereka, bukan dari seberapa sehat dan stabil kondisi mentalnya.
Kampus menuntut mahasiswa untuk selalu berprestasi, mengerahkan seluruh tenaga demi nilai sempurna. Namun, banyak kampus tidak memberi ruang bagi mahasiswa untuk bernapas.
Tidur cukup? Sebatas mimpi. Hidup seimbang? Hanya dongeng yang terdengar indah. Kampus dengan bangga mencetak lulusan-lulusan cumlaude dengan IPK tinggi. Sayangnya, mereka lupa bertanya. Apakah mahasiswa benar-benar siap menghadapi dunia atau hanya menjadi korban dari sistem akademik yang kejam?
Ada kampus yang hanya menjadi “pabrik”
Bayangkan sebuah pabrik yang berjalan tanpa henti. Mahasiswa adalah produk yang harus selalu berfungsi, sementara IPK adalah label kualitas yang menentukan nilai mereka di mata dunia.
Tidak ada ruang untuk lelah, tidak ada waktu untuk istirahat. Tidur hanya 3 jam? Normal. Menghabiskan malam dengan mata sembab karena menangis sambil mengerjakan tugas? Itu bukan tanda kelelahan, melainkan “bagian dari proses belajar.”
Tidak ada yang peduli apakah mahasiswa masih menikmati hidup, masih punya semangat, atau bahkan masih waras. Yang penting, mereka bisa menyerahkan tugas tepat waktu, hadir di kelas tanpa absen, menyetor skripsi sesuai deadline, dan mencetak IPK tinggi.
IPK tinggi, semua dianggap baik-baik saja
Sistem ini terus berjalan, menganggap mahasiswa sebagai mesin tanpa perasaan. Kampus dengan bangga memamerkan lulusan unggulan, tetapi tidak melihat banyak di antara mereka telah kehilangan jati diri, semangat, dan kesehatan mentalnya.
Selama IPK masih tinggi, semua baik-baik saja. Tapi pertanyaannya, apa gunanya gelar cumlaude jika yang tersisa hanyalah tubuh lelah dan mental yang terkuras?
Kampus sering berkoar soal kesehatan mental. Namun, solusi mereka tidak lebih dari seminar “Manajemen Stres”. Ironisnya, seminar itu ada saat mahasiswa sudah di ambang kehancuran. Mahasiswa mendengarkan materi tentang menjaga keseimbangan hidup, sementara tugas dan deadline terus mencekik. Hasilnya? Formalitas tanpa dampak nyata.
Butuh konseling? Silakan daftar dan bersabar menunggu antrean hingga 3 bulan ke depan dengan catatan. Itu kalau mentalmu belum keburu ambruk hanya demi IPK tinggi.
Curhat ke dosen? Harapan tinggal harapan. Ada saja dosen yang merespons, “Coba lebih disiplin. Jangan manja.” Alih-alih mendapatkan empati, mahasiswa justru dianggap terlalu banyak mengeluh.
Pada akhirnya, solusi sesungguhnya tidak datang dari kampus, melainkan dari mahasiswa itu sendiri. Caranya? Kopi sebagai bahan bakar utama, overthinking sebagai strategi bertahan hidup, dan bercanda soal kelelahan mental di media sosial sebagai mekanisme bertahan hidup.
Sekadar reality show, IPK tertinggi pasti menang
Menjadi mahasiswa di era ini terasa seperti mengikuti reality show bertahan hidup. Asal IPK tinggi, pasti menang.
Bedanya, di acara survival, ada hadiah untuk pemenang. Sementara itu, di kampus, hadiahnya adalah burnout, overthinking, dan kebingungan eksistensial.
Setiap semester, mahasiswa menghadapi ujian mendadak, revisi skripsi tanpa henti, serta tekanan sosial untuk tetap terlihat “baik-baik saja” meskipun sudah di ambang kehancuran. Ada yang menyerah dan drop out, ada yang lulus dengan IPK 4.0 tetapi kehilangan semangat hidup, dan ada yang sukses… di rumah sakit, karena kelelahan fisik dan mental.
Ironisnya, sistem seolah tidak peduli cara mahasiswa bisa bertahan. Yang penting kampus bisa pamer angka kelulusan tinggi dan jumlah lulusan cumlaude. Sementara itu, cerita mahasiswa yang tumbang akibat tekanan akademik hanya menjadi bisik-bisik di sudut kampus.
Dunia yang sadis
Setelah bertahun-tahun mengejar IPK sempurna, akhirnya gelar sarjana berhasil diraih. Tapi apakah perjuangan selesai? Sayangnya, dunia kerja jauh lebih sadis dibanding ruang kelas dan lembar ujian.
Jika dulu di kampus, mahasiswa berjuang mendapatkan nilai A, kini mereka harus berjuang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan yang bahkan tidak peduli dengan IPK mereka. Alih-alih bertanya soal teori, perusahaan lebih ingin tahu seberapa baik seseorang bisa berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan bekerja dalam tekanan.
Sayangnya, kampus lebih fokus mengajarkan cara mengejar angka, ketimbang cara menghadapi dunia nyata. IPK hanya target fana.
Mahasiswa yang dulunya terbiasa dengan silabus dan ujian kini terjun ke dunia yang penuh ketidakpastian. Banyak lulusan baru yang gamang dan mengalami krisis eksistensial.
“Setelah ini, aku harus bagaimana?” Ironisnya, kampus yang dulu mengagungkan mereka saat lulus kini sudah tidak peduli. Seminar “Karier Sukses Setelah Lulus” hanya formalitas, sementara mahasiswa dibiarkan mencari jalannya sendiri.
Saatnya kampus berhenti memandang mahasiswa sebagai IPK berjalan. Pendidikan seharusnya tidak hanya mencetak lulusan dengan transkrip sempurna, tetapi juga manusia yang siap menghadapi hidup. Karena di dunia nyata, tidak ada yang peduli berapa IPK-mu. Yang penting, apakah kamu bisa bertahan atau tidak?
Penulis: Reza Oktavia Rachman
Editor: Yamadipati Seno
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.