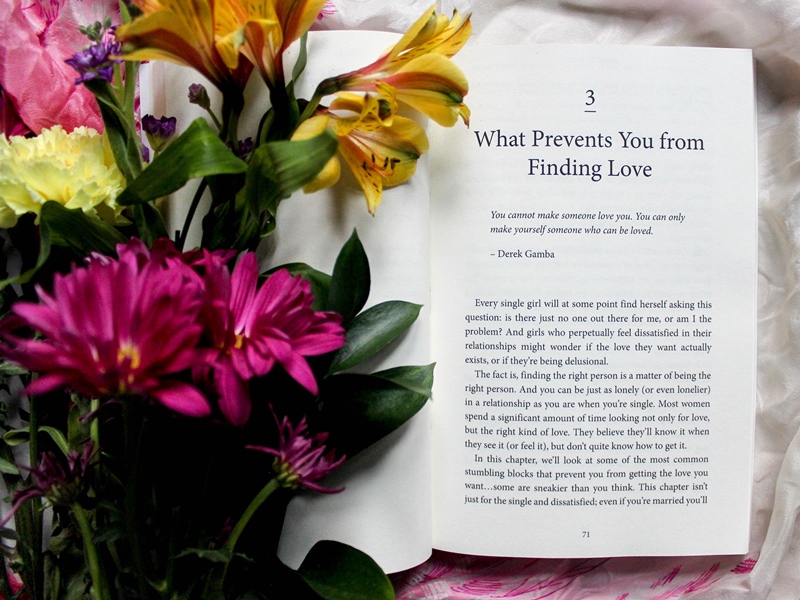Sore itu salah seorang penggiat literasi yang saya kenal membagikan melalui akun media sosialnya, sebuah artikel bertajuk “Wattpad Menunjukkan Betapa Menyedihkannya Selera Kebanyakan Pembacanya” yang tayang di kanal Terminal Mojok. Saya tertegun sejenak. Awalnya ingin kesal, tapi akhirnya ikut tertawa.
Saya tertawa karena sebetulnya tulisan itu sangat tepat, hanya banyak orang tidak ingin mengakuinya. Ketika saya membaca artikel tersebut, tawa saya hilang dan digantikan oleh kerut-kerut di dahi yang tidak kunjung menghilang. Saya berpikir panjang mengenai banyak hal, sebagian besar mengenai ketidakpahaman saya melihat bagaimana fenomena ini dijelaskan dengan begitu sederhana. Padahal, jelas, ini bukan masalah sederhana.
Inti dari tulisan yang dibuat oleh Hilman Azis tersebut adalah sesuatu yang sudah diketahui banyak orang-orang yang menyukai kegiatan membaca dan menulis, apalagi di ranah digital.
Jika boleh mengutip, Hilman Azis menyebut fenomena tersebut sebagai “cerita (di Wattpad-red) yang mendapatkan jumlah pembaca yang banyak hampir semua begitu-begitu aja, genre romansa remaja dengan tema dan pola yang serupa.” Lalu fenomena yang begitu besar dan menarik ini dikecilkan menjadi urusan (yang sekali lagi saya kutip secara langsung) “selera pembaca Wattpad di Indonesia yang mayoritas adalah para remaja dan dewasa awal, mudah ditebak, selalu tentang cinta dengan pola yang sama dan berulang-ulang.”
Sontak hal tersebut membuat saya mengerutkan dahi. Jika kita semua terjebak dengan kata selera yang begitu subjektif dan adalah hak masing-masing pribadi, bagaimana kita akan bisa sampai pada tujuan utama untuk meningkatkan literasi di skena penerbitan buku di Indonesia?
Pasalnya, permasalahan utama yang sebetulnya disampaikan juga dalam tulisan oleh Hilman Azis adalah kurangnya variasi (terutama urusan topik dan isu) pada karya fiksi di Indonesia (atau dalam ranah yang lebih kecil, Wattpad). Lalu, jika saya boleh menambahkan sesuai pengamatan saya pribadi, masalah lainnya adalah masih kurangnya kualitas tulisan dari segi diksi yang digunakan dan hal itu.
Tentu saja, ini berhubungan erat dengan “panggung” atau “wadah” yang tersedia bagi karya-karya dengan tema lain di luar romansa dan urusan bucin-bucinan yang juga bertaburkan diksi yang kaya. Mari bersepakat bahwa ini memang sebuah kekacauan. Ingat, untuk dapat berubah menjadi lebih baik, kita harus menerima dan mengakui hal-hal buruk yang terjadi.
Jadi, kini kita lanjutkan tulisan ini dengan sebuah hipotesis asal-asalan dari saya yang mungkin akan terdengar terlalu berani dan mengada-ada. Dalam hipotesis saya ini, saya menghubungkan Wattpad dengan industri penerbitan secara keseluruhan. Lantaran faktanya, saat ini banyak bermunculan buku dan novel yang diambil dari karya-karya yang sebelumnya tayang di aplikasi Wattpad.
Maka, alih-alih menggunakan selera sebagai kambing hitam dari kekacauan ini, saya merasa sistem kapitalisme yang terlalu mengakar dalam industri ini secara keseluruhan adalah subjek yang seharusnya menerima paling banyak kecaman. Berdasarkan Oxford Dictionaries, pada dasarnya kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar.
Dalam kasus literasi dan Wattpad di Indonesia, pemilik modal yang menguasai industri ini, bergerak semata-mata ke arah pasar yang memiliki keuntungan terbesar. Siapakah pasar dengan keuntungan terbesar itu? Tentu saja masyarakat yang sudah bertahun-tahun terbuai dengan kisah romansa bak dongeng putri dan pangeran yang menghantar anak-anak kecil tertidur ke dalam mimpi indah.
Dalam sistem yang lebih besar dari sekadar industri penerbitan maupun industri literasi di mana Wattpad sebetulnya bergerak, sistem kapitalisme bekerja dengan begitu keras sehingga orang-orang merasa sesak dibuatnya. Kesesakan itu perlu ditutupi agar tidak terjadi kerusuhan besar manakala orang-orang tak lagi merasa ini adalah sesuatu yang mungkin tidak seharusnya terjadi. Romansa adalah alat paling mutakhir untuk membuai kesadaran publik. Pendapat saya ini tidak terbatas pada fenomena Wattpad dan selera baca yang ada di Indonesia saat ini, tapi juga fenomena literasi romansa dan kapitalisme secara keseluruhan di belahan dunia manapun.
Hubungan dekat antara romansa dan kapitalisme juga pernah disampaikan oleh Laurie Essig yang adalah seorang Profesor Sosiologi di bidang heteroseksualitas di Middlebury College (Amerika Serikat). Essig menyampaikan gagasannya ini pada gelaran TEDxVienna yang tayang di kanal YouTube TEDx Talks pada 10 Desember 2014.
Dalam pidato dan penjelasannya, Essig menyampaikan gagasan singkat bahwa kapitalisme memodifikasi perasaan kita menjadi sesuatu yang kita beli, salah satunya novel-novel romansa. Di samping itu, dari sistem kecil tersebut dengan romansa yang telah dimodifikasi, sistem kapitalis menyandera kepekaan kita akan isu-isu lain di luar janji manis cerita romansa.
Kita tidak lagi butuh mempertanyakan hal-hal lain yang barangkali kurang tepat dalam hidup kita karena kisah romansa sudah menjadi pelipur lara yang tepat. Bahkan, dari pelipur lara yang memanipulasi kesadaran kita, sistem ini bergerak kembali mendapatkan keuntungannya sendiri.
Maka, sadar atau tidak, industri penerbitan kita telah lama terkungkung dalam sebuah sistem yang tidak membiarkannya lari dari pusat keuntungan yaitu produk-produk yang memodifikasi perasaan manusia, apa pun itu bentuknya. Sekali lagi, hal ini terbukti ketika pada Februari 2019, Dhania Sarahtika dari Jakarta Globe mengeluarkan artikel yang mempertanyakan mengenai variasi topik dan isu dalam skena literasi novel young adult (YA) untuk sasaran pembaca dewasa-muda di Indonesia.
Dalam tulisan berjudul “Where Are the Serious Young Adult Novels in Indonesia?”, Dhania Sarahtika mencoba menyandingkan jajaran judul novel YA di Indonesia dengan judul-judul yang terbit di negara lain. Terlihat fenomena dan fakta bahwa novel YA di Indonesia jarang sekali menyentuh isu-isu serius sementara negara lain sudah memiliki novel-novel YA yang mengangkat tema “berat” seperti isu imigran, deportasi, homoseksual, penyintas kanker, bunuh diri remaja, dan lain-lain.
Ketika mencoba mendapatkan penjelasan mengenai hal ini dengan menanyakannya pada editor YA dari salah satu penerbit besar di Indonesia, jawaban yang didapatkan dan saya kutip langsung adalah demikian, “Most of our readers are girls who love romance. They feel life is hard enough, so they read for entertainment. Heavy topics stress them out. They don’t even like sad ending.” (Kebanyakan pembaca kami adalah perempuan yang menyukai romansa. Mereka merasa hidup sudah cukup berat sehingga mereka menjadikan bacaan sebagai hiburan. Topik-topik yang berat membuat mereka stres. Mereka bahkan tidak menyukai akhir yang menyedihkan.)
Apakah hal ini masih kurang cukup jelas menunjukkan bahwa kapitalisme dan literatur di Indonesia sudah begitu lama saling menjalin hubungan erat?
Sekarang, apa yang kira-kira dapat kita lakukan alih-alih menyalahkan sistem yang sudah ada? Ketika membaca ini membuat Anda bisa menerima bahwa permasalahan ini sudah jauh di luar selera, saya rasa saat itulah kita baru bisa melanjutkan diskusi ke arah berikutnya, yaitu perubahan.
Sebelum itu, Anda dan saya harus sama-sama mengakui hal ini terlebih dahulu. Kita harus sama-sama yakin bahwa berhentinya perkembangan literasi di Indonesia bukan urusan Wattpad maupun selera. Selera memang berbeda-beda, tapi sifatnya yang subjektif tidak menjadikannya landasan yang tepat untuk bergerak.
Selera dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Selera hanyalah kambing hitam dan kita perlu untuk sekali lagi melihat lebih jauh ke dalam sistem yang saat ini berjalan di industri literasi dan penerbitan Indonesia. Kita perlu sama-sama yakin bahwa ini adalah masalah yang perlu diselesaikan. Pasalnya jika tidak, rencana besar revolusi pendidikan Indonesia untuk meningkatkan literasi di Indonesia akan menjadi mentah dan tidak berdaya.
Ingat, literasi bukan hanya tentang membaca atau menulis. Jauh lebih dari itu, literasi adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan literasi, menurut UNESCO berhubungan erat dengan kompetensi bidang akademik, konteks nasional, institusi, nila-nilai budaya serta pengalaman.
Permasalahan ini besar karena ini berarti kemampuan literasi masyarakat Indonesia secara komunal, menjelaskan begitu banyak hal termasuk akademik, institusi, nilai budaya, dan pengalaman yang nyata di negara ini. Apakah selamanya kita ingin menjadi masyarakat yang terbuai dalam isu-isu romansa untuk melupakan isu-isu dan 99 masalah lainnya yang sebetulnya juga ada dalam kehidupan kita, tapi tidak pernah dituangkan dalam kegelisahan berbentuk tulisan dan bacaan?
Sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara, untuk memutuskan.