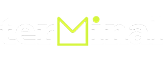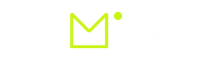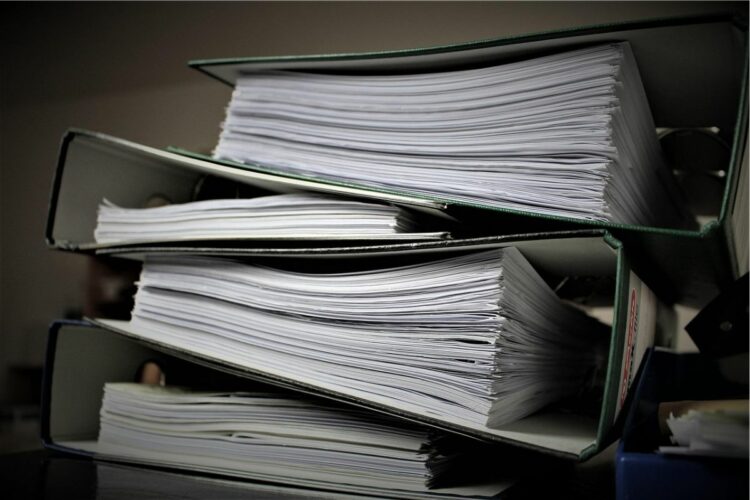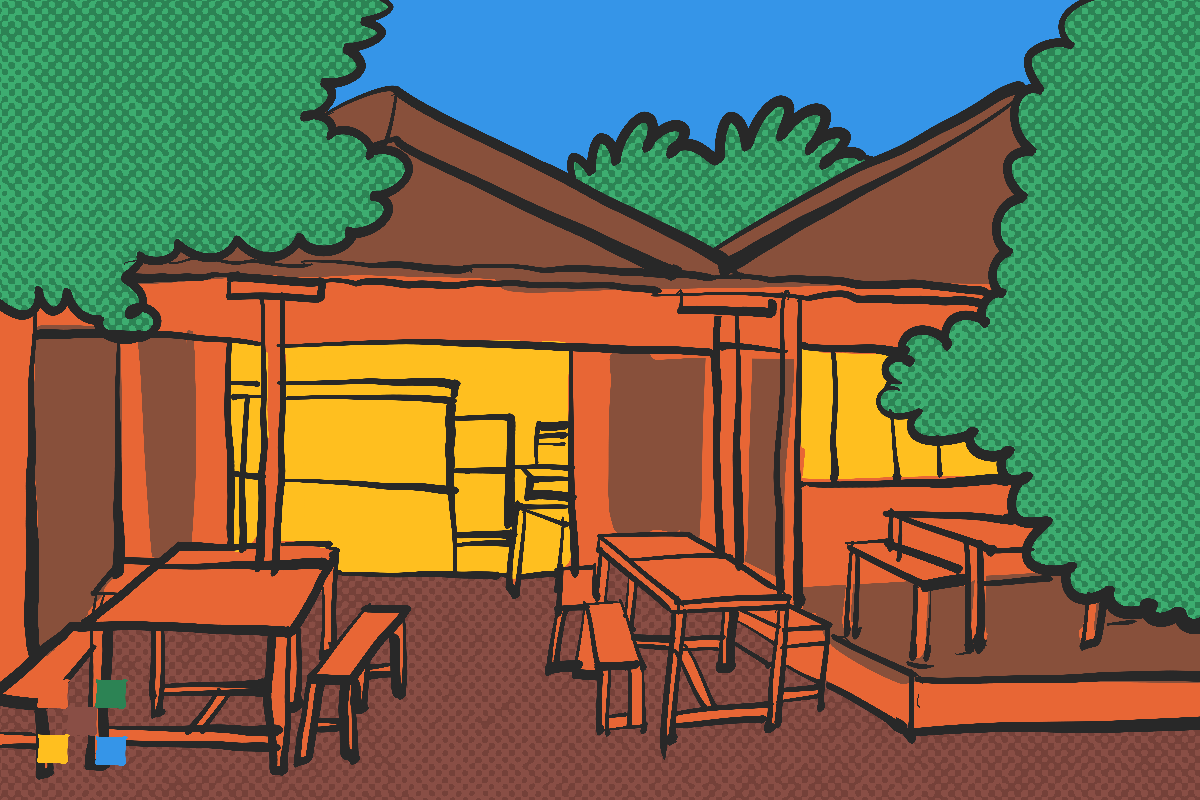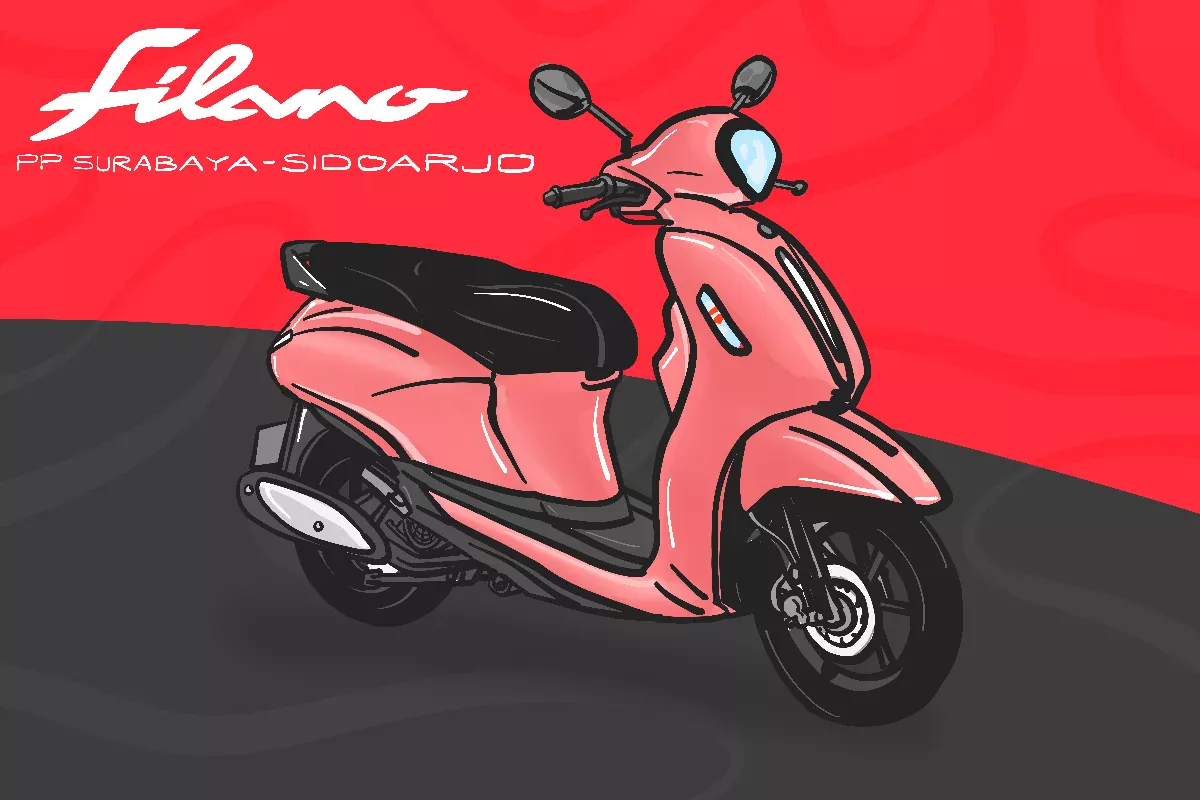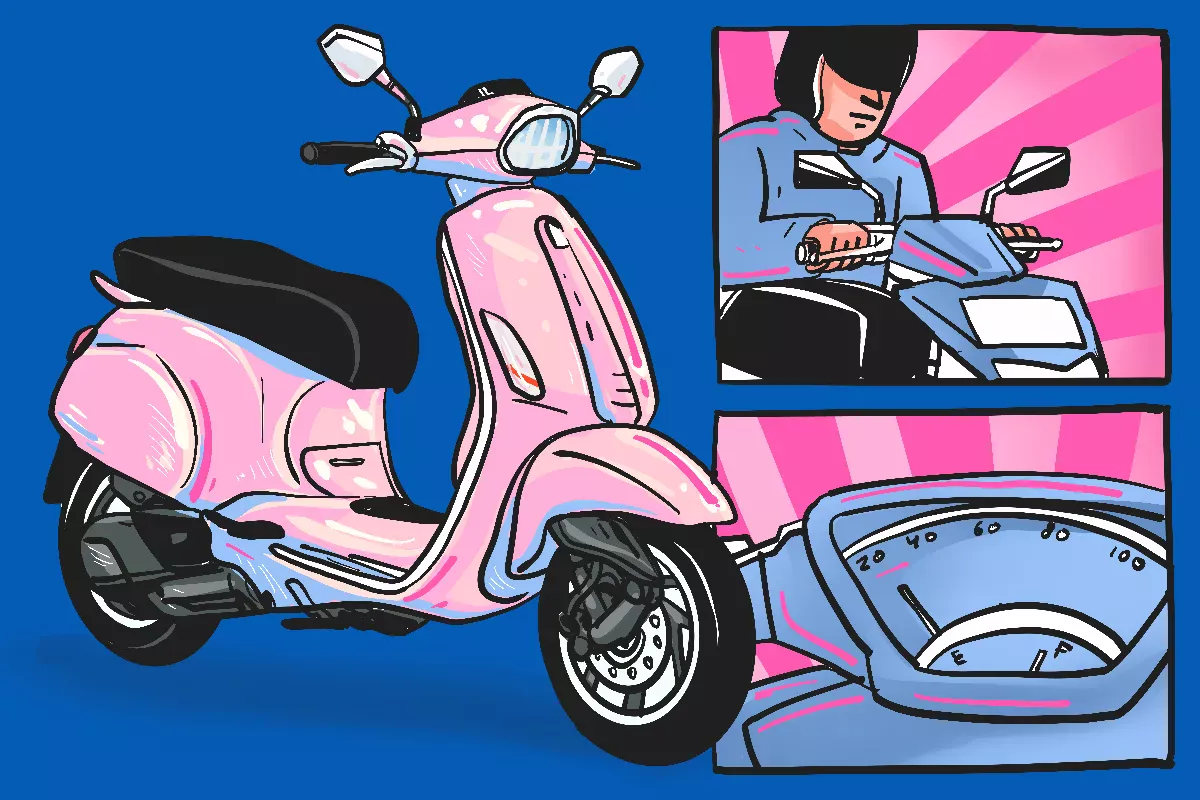Ada banyak hal yang membuat mahasiswa terlatih jadi manusia tangguh: dosen killer, tugas dadakan, skripsi mandek, dan satu lagi yang tidak boleh dilupakan, birokrasi kampus. Ia tak pernah hadir di modul perkuliahan, tapi selalu muncul sebagai ujian hidup yang sebenarnya. Tidak ada SKS untuk mengulangnya, tapi cukup satu kesalahan format surat saja, kita bisa disuruh bolak-balik tanpa ampun.
Birokrasi kampus sering kali tidak rumit karena substansinya, tapi karena alur yang seperti labirin dan logika yang… ya sudah, jangan dicari. Mengurus satu dokumen bisa melibatkan lima ruangan berbeda, tiga tanda tangan, dua cap basah, dan satu petugas yang entah ke mana. Ironisnya, semua ini terjadi di institusi yang dengan bangga menyuarakan “digitalisasi pelayanan.” Tapi kenyataannya, buka laman layanan online saja butuh refresh tiga kali, doa lima kali.
Yang bikin tambah getir, sistem ini sudah berlangsung lama, tapi dibiarkan begitu saja. Karena semua orang sudah terbiasa ribet, maka keribetan itu dianggap wajar. Lama-lama mahasiswa tidak lagi bertanya kenapa prosesnya harus serumit itu, tapi lebih fokus ke strategi: “Mending berangkat jam 7 pagi biar duluan antre tanda tangan.” Dalam ekosistem birokrasi kampus, adaptasi jadi semacam survival skill. Dan kami, para mahasiswa, adalah peserta ospek seumur studi.
Birokrasi kampus: semua serba “standar prosedur”, tapi prosedurnya seperti teka-teki silang
Kampus selalu bilang semua sudah ada “standar prosedur.” Tapi anehnya, standar ini sering kali tidak ditulis jelas, tidak ditempel di papan pengumuman, dan kalau pun ada di website, biasanya tersembunyi di sudut terdalam laman yang butuh sepuluh klik untuk sampai. Lebih mirip quest game RPG ketimbang informasi pelayanan.
Kalau tanya ke petugas, jawabannya kadang beda-beda tergantung siapa yang ditanya dan jam berapa nanyanya. Pagi bilang satu hal, siang sudah berubah haluan. Bahkan ada momen ketika saya disarankan balik keesokan harinya karena “yang pegang kunci ruangannya lagi tidak ada.” Entah saya sedang urus dokumen akademik atau sedang main petak umpet.
Yang menyebalkan bukan cuma prosesnya yang panjang, tapi ketidakjelasan itu bikin mahasiswa selalu dalam posisi bingung. Mau tanya takut dianggap nggak inisiatif, tapi kalau nekat bergerak sendiri, bisa-bisa salah jalur dan disuruh ngulang dari awal. Di titik ini, birokrasi kampus bukan cuma menguji kesabaran—tapi juga keberanian, kejelian, dan kadang, iman.
Chat masuk, centang dua, tapi jawabannya menguap
Entah sejak kapan WhatsApp jadi kanal resmi komunikasi kampus. Tapi nyatanya, hampir semua urusan kini diarahkan ke sana. “Silakan hubungi admin via WA, ya,” kata petunjuk di website. Awalnya saya senang, karena tampaknya ini solusi cepat dan praktis. Ternyata, saya keliru. Yang cepat cuma waktu kita kirim pesan. Setelah itu… hening. Pesan centang dua, tapi tanpa balasan. Seolah dikirim ke gua hampa sinyal.
Ada teman saya yang sampai bikin template reminder dengan nada sopan maksimal, kirim tiap dua hari sekali, berharap dibaca. Tapi tidak pernah ada yang muncul selain “last seen yesterday.” Bahkan ada yang nekat kirim stiker lucu dulu biar ‘ice breaking’—hasilnya tetap nihil. Mungkin perlu mantra khusus supaya pesan mahasiswa bisa masuk ke hati para pengelola birokrasi kampus.
Yang ironis, saat mahasiswa lambat membalas email atau WA dosen, langsung kena cap kurang sopan. Tapi saat kami menunggu jawaban dari kampus berhari-hari, itu dianggap bagian dari proses. Padahal, kadang kami cuma butuh jawaban simpel: “Iya, bisa” atau “Maaf, belum.” Tapi yang kami terima malah jadi bahan renungan: apakah hidup ini layak diperjuangkan kalau chat ke TU saja tak kunjung dibalas?
Birokrasi kampus: kalau mahasiswa salah, dibilang kurang teliti. Kalau sistem salah, dibilang wajar
Ada pola aneh dalam ekosistem birokrasi kampus: ketika mahasiswa keliru isi formulir, lupa tanda tangan, atau salah upload berkas, reaksi langsung cepat dan tegas—“nggak bisa diproses,” “ulang dari awal,” atau yang paling klasik, “sudah kami jelaskan di awal, Dek.” Tapi ketika sistem kampus yang ngadat, informasi yang simpang siur, atau admin yang hilang entah ke mana, semua bisa dimaklumi. “Namanya juga masih transisi,” kata mereka, seolah-olah mahasiswa harus maklum sampai kiamat.
Di titik ini, birokrasi kampus bukan lagi sekadar sistem yang berbelit, tapi jadi bentuk kekuasaan kecil-kecilan. Mahasiswa diharapkan patuh, tidak banyak bertanya, dan kalau bisa, paham sendiri tanpa harus dijelaskan. Bukan cuma soal dokumen, tapi juga soal relasi kuasa yang diam-diam menguji siapa yang tahan paling lama. Birokrasi kampus telah menjelma jadi ritual pengabdian: kamu harus tahu caranya menyenangkan dewa loket dan dewi tanda tangan kalau ingin lulus dengan damai.
Banyak mahasiswa belajar bahwa yang penting bukan tahu alur, tapi tahu siapa yang harus ditemui duluan. Bukan soal prosedur, tapi soal siapa yang bisa bantu “cepet kelar.” Di sinilah reformasi birokrasi jadi terlihat lucu—karena yang berubah hanya format, sementara pola lama tetap lestari: mahasiswa harus bisa membaca situasi, bukan membaca panduan.
Reformasi birokrasi (seolah) hanya ilusi dan topeng
Kata “reformasi birokrasi” sudah sering dilontarkan dalam seminar kampus, siaran pers, hingga pidato pimpinan universitas. Kalimatnya manis, penuh janji perbaikan, dan kadang disertai jargon seperti “transparansi,” “akuntabilitas,” atau “layanan humanis berbasis teknologi.” Tapi di balik kata-kata keren itu, mahasiswa masih menghadapi prosedur yang itu-itu juga: tidak efisien, tidak ramah, dan sering kali membuat frustrasi.
Reformasi birokrasi kampus, dalam praktiknya, lebih sering menjadi kosmetik daripada solusi. Alur pengurusan dokumen tetap panjang, admin tetap sulit dihubungi, dan informasi penting tetap tersebar di pelbagai grup chat, bukan di pusat informasi resmi. Bahkan kadang reformasi justru menambah satu lapis birokrasi baru—yang katanya untuk mempermudah, tapi nyatanya cuma menambah antrean.
Buat mahasiswa, reformasi birokrasi sering kali tidak terasa sebagai perubahan sistem, tapi sebagai perubahan istilah. Dulu namanya “surat manual,” sekarang jadi “unggah dokumen PDF.” Dulu ngantre di ruang TU, sekarang ngantre di sistem digitalisasi ala-ala. Hasilnya sama: lambat dan membingungkan. Dan kami pun akhirnya kembali ke mode bertahan: cari jalur paling aman, tanya kakak tingkat, dan berharap tidak salah format lagi. Karena di kampus ini, yang paling stabil justru ketidakpastian prosedurnya.
Kalau memang tidak niat dan nirkompetensi, untuk apa dipertahankan?
Sistem birokrasi kampus yang lambat, ruwet, dan membingungkan kadang bikin saya bertanya serius: apakah memang tidak ada niat sungguh-sungguh untuk memperbaikinya, atau memang tidak tahu bagaimana caranya? Dua-duanya sama menyedihkan. Sebab kalau niat saja tidak ada, itu artinya kampus sengaja membiarkan mahasiswanya terjebak dalam sistem yang menyita waktu, energi, dan kadang kesehatan mental. Tapi kalau tidak tahu caranya, maka siapa sebenarnya yang harus belajar lagi?
Tidak semua orang bisa mendesain sistem layanan publik. Tapi, setidaknya, siapa pun yang diberi amanah mengelola birokrasi kampus mestinya punya dua hal: empati dan akal sehat. Empati untuk melihat bahwa mahasiswa datang bukan untuk ngemis tanda tangan, tapi untuk menuntut hak layanan akademik yang layak. Dan akal sehat untuk tidak membuat prosedur tambahan yang tak ada fungsinya selain memperpanjang antrean.
Birokrasi kampus yang tidak kompeten, tapi tetap dipertahankan, lama-lama menjadi bentuk pengabaian sistemik. Ini bukan sekadar soal “maklum namanya juga banyak mahasiswa,” tapi soal tanggung jawab institusi yang harusnya mendidik dengan cara melayani, bukan menyiksa diam-diam lewat meja loket dan website ala-ala. Kalau memang tidak ada kapasitas dan kemauan untuk memperbaiki, mungkin yang perlu direformasi bukan hanya sistemnya, tapi juga cara berpikir orang-orang yang menjalankannya.
Penulis: Raihan Muhammad
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Kampus Mempersulit Legalisir Ijazah, Menyengsarakan Lulusan yang Mau Segera Kerja Setelah Wisuda