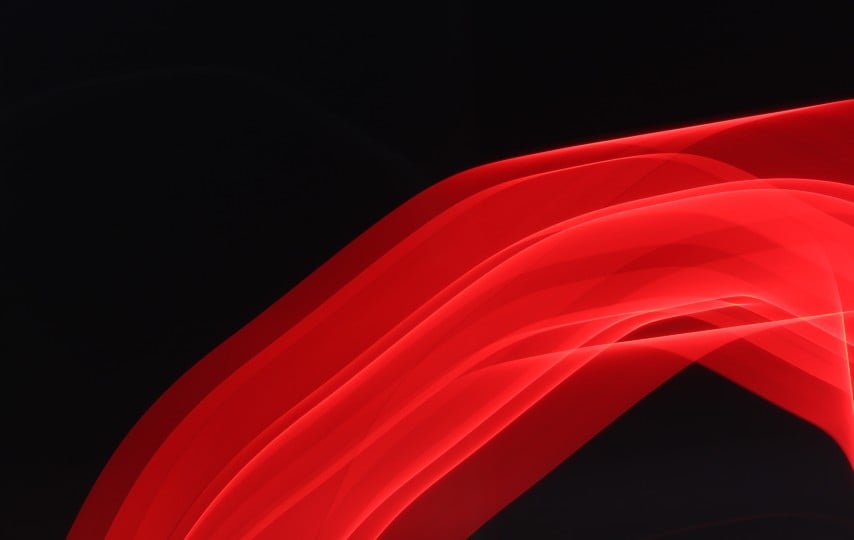“Layar tancap harus disiapkan. Ada dana tambahan buat kacang dan jagung rebus,” begitu kata Kobis, sebut saja begitu. Ia salah satu ketua karang taruna di sebuah desa. Kerjanya membabi-buta hanya karena dua perkara saja dalam satu tahun, yakni ketika mau ada 17-an dan (belakangan) ketika menyambut akhir September.
“Nanti layar akan terkembang di lapangan voli. Orang tua duduk di depan, anak muda seperti kita duduk di belakang,” begitu tambahnya. Ia tutup dengan kalimat yang begitu pulen seperti nasi Olive dan eco seperti Gudeg Yu Djum, “Kita ini harus menghormati orang tua, lebih-lebih kita juga harus merawat sejarah bangsa. Kata Bung Besar, jas merah.”
“Mau ada apa tho, Bis?” begitu tanya saya ketika suatu malam melewati cakruk, sepulang dari Kaliurang, dan bersua dengan mereka yang wajahnya penuh coreng bedak—entah karena kalah karambol atau catur. Kata sang ketua, mereka mau memutar film Pengkhianatan PKI. Film yang genre-nya menurut saya pribadi nggak jelas-jelas amat. Embuh historia, biografi, aksi, gore, hardcore, atau BDSM.
“Kamu kan mahasiswa Fakultas Filsafat, harusnya membantu kami giduh sana-sini ngurusin acara bersejarah yang saban tahun mulai karang taruna agendakan ini,” begitu kata Kobis. Saya di motor hanya cekikikan sendiri karena melihat wajah Kobis yang sudah mlotrok.
“Lha, kok, kamu malah ketawa, Gus?” tanya Kobis. Saya menjawab dengan hanya menggelengkan kepala. Selain mukanya Kobis yang lucu, semangat berapi-api Kobis juga patut dirayakan. Lantaran dalam setahun, hanya dua kali wajah Kobis amat bergairah seperti ini. Yakni seperti malam ini, sebuah malam menuju akhir September, dan ketika menunggu daging kambing ba’da Idul Qurban dibagikan.
Kobis mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang harus tahu kebengisan sebuah era di mana manusia dengan mudahnya dibunuh dan—bahkan kok ya bisa—para jendral kuat dimasukkan ke dalam satu lubang. “Kamu tahu, Gus, satu hal yang buat aku kesal?” saya hanya menggelengkan kepala. Kobis melanjutkan, “Anak-anak zaman sekarang, seusia kita, malah menganggap film itu hanyalah propaganda.”
Kobis jelas nggak salah. Film Pengkhianatan PKI pun nggak salah. Saya apalagi, pastinya nggak salah juga lha wong sampai paragraf ini saya belum beropini apa-apa. Yang salah hanya wajah Kobis. Ia tak pantas berseru dengan tegas, menengok wajahnya itu amat lucu. Di paragraf ini, saya bercanda. Sama, lah, seperti cara Orde Baru “bercanda” lewat film buatan mereka.
Tapi kesampingkan sajalah wajah mlotrok Kobis dan betapa lucunya ketika ia kalah judi. Ada satu hal yang penting dan harus diketahui bahwa isu kebangkitan PKI, dari desa ke desa di pedalaman Banguntapan hingga Imogiri, itu masih sering kali terjadi. Ya, di sebuah zaman di mana gawai ada di tangan kenan ketika berak, tangan kiri untuk cebok, isu kebangkitan PKI masih ada dan bisa saja berlangsung di sekitar kalian.
Nggak ada yang lucu memang dengan isu kebangkitan PKI. Ketakutan manusia, itu nggak bisa disalahkan secara total karena berkaitan dengan tingkat pendidikan, literasi, juga akses mereka mendapatkan informasi.
Belantara media sosial, menjerat Kobis ke dalam sebuah lubang bahwa PKI akan bangkit tiap bulan September. “Dari pesan WhatsApp A-1 desa sebelah,” katanya. Membuat hoaks perihal PKI, jika boleh jujur walau menyakitkan, itu mudah sekali. Yah, katakan lah semudah Freddy Mercury nembang “Somebody to Love” pada bagian ayat-ayat terakhir. Atau semudah Ernest Hemingway menarik pelatuk shotgun 12 gauge laras ganda pada akhir hidupnya.
Saya pun bisa membuat ramuan broadcast hoax. Mudah, amat mudah. Begini misalnya;
“Seorang musisi papan atas Amerika, Billie Joe Armstrong, berhasil memprediksi kapan PKI bangkit lagi. Blio membuat sebuah pesan rahasia dalam penggalan lirik lagunya yang penuh ketakutan dan meminta lebih baik ia tidur dan dibangunkan ketika September sudah berakhir. Wake me up when September ends… Jangan sampai pesan ini berakhir di Anda.”
Kobis, ketika ia sibuk mengulum bibirnya dan juga menggoyang lidahnya seraya banyak bercakap perihal betapa bahayanya PKI, membuat saya sadar satu hal, film yang kembali diputar beberapa tahun ini, menarik histeria massa dan melankolia generasi baru bagi anak-anak muda. “Gara-gara PKI negara ini hampir hancur,” kata Kobis.
Melankolia adalah kesedihan bersama dan pemutaran kembali film Pengkhianatan PKI berhasil menciptakan bibit baru melankolia tersebut. Tere Liye, penulis wahid yang digandrungi nom-noman masa kini bahkan pernah bersuara bahwa PKI layaknya rezim Pol Pot di Kamboja. Ngeri, bahkan penulis sekaliber blio pun turut urun rembug bersuara.
Terlepas film ini hanya sekadar alat onani Suharto dan kolega atau memang sebuah kebenaran, nyatanya PKI itu hanya hantu, kok. Iya, PKI itu partai mati. Sama lah seperti Partai RepublikaN—sebuah partai yang serius mau ngusung Sultan jadi Presiden. Eh, tapi ada bedanya, selain ideologi, partai RepublikaN dan sembilan partai nonparlemen yang kalah di Pemilu 2014 bergabung jadi Partai Hanura.
PKI itu sudah mati lho ini. Kok ya bisa hantunya ditakuti. Marx mungkin berkata bahwa hantu-hantu komunisme bergentayangan di Eropa, sedang saya ingin sekali menulis bahwa hantu-hantu PKI bergentayangan di desa saya. Dan itu menyebalkan menengok warga desa saya ini amat religius dan nggak percaya hantu. Di sini saya merasa kasihan sama pocong lha wong hantu PKI saja masih ada harganya untuk ditakuti.
“Gimana, Gus? Jadi panitia, ya?” begitu ajak Kobis ketika saya mau pulang ke rumah. Saya menolak. Kata saya, kalau filmnya Endgame atau Suicide Squad, saya pikir-pikir lagi untuk menerima ajakannya. Mereka kompak misuh, nggak ada yang tertawa. Ternyata, kalah judi bikin pusing juga, ya.
Lalu saya bilang, Indonesia harusnya bikin lagi film-film model begitu. Tapi bukan tentang partai politik, melainkan tentang sebuah komisi yang tindak tanduknya sudah aneh di luar batas nalar manusia pada umumnya. “Isi filmnya begini…” kata saya. Kobis dan kawan-kawan menyimak. “Kalau film Pengkhianatan PKI penuh simbah darah, film ini penuh dengan simbah sensor.”
Misalnya, menyensor bikini Shizuka ketika diajak Doraemon dan Nobita ke pantai dengan pintu ke mana saja. Atau menyensor Shandy si Tupai dengan BH ungu melulu yang nggak pernah ganti-ganti itu.
Kenapa bikini tupai saja sampai disensor di film itu? Memang ada yang sange sama toket tupai? Lihat ada yang kemecer liat tupai kemringet? Nah, itulah letak asiknya film ini. Film yang menceritakan sebuah lembaga yang isinya penuh dengan moral dan nilai.
“Genre-nya beda kan sama film Pengkhianatan PKI?” kata saya, Kobis dan kolega menganggukkan kepala dengan kompak. “Puncak ceritanya, lembaga yang paling suci dan—merasa yang paling tanggung jawab—menjaga kualitas tontonan para pemirsa ini malah ndembik dan melakukan kegiatan paling ra mashooook sedunia.”
Ketika film Pengkhianatan PKI menampilkan adegan-adegan gore. Lembaga ini justru mengizinkan predator tampil di acara televisi, untuk tujuan edukasi bahaya menjadi predator. “Film yang penuh dengan twist, kan?” kata saya, mereka kembali manthuk.
Kalau dialog dalam film Pengkhianatan PKI, “Darah itu merah, Jendral!” maka dalam film ini dialognya lebih ngeri, yakni, “Saipul Jamil bisa tampil untuk kepentingan edukasi. Misal, dia hadir (dalam sosialisasi) bahaya predator. Kalau untuk hiburan, belum bisa.” Hiiiiii.
Nggak sampai sana, lembaga yang paling suci nan bersih ini, jebul menyimpan koreng. “Itu ending filmnya, makin ke belakang, makin seru,” kata saya, Kobis pun bertanya gimana bagian ngerinya? Saya menjawab, “Lembaga yang suci nan kudus itu, ternyata malah beberapa anggotanya melakukan pelecehan dan kekerasan seksual. Apalagi terduga pelaku dipaksa untuk berdamai agar nggak dilaporkan balik sebagai pencemaran nama baik.”
“Astagfirullaaaaaah,” begitu kata Kobis dan kolega secara kompak seperti sempak. Mereka pun bertanya, film apa. Kobis pun berpesan, jika film itu sudah ada, harus diputar. Diputarnya jangan tiap akhir September saja, kalau bisa setiap hari, katanya.
Saya pun berbisik-bisik kepada mereka. “Film itu… judulnya….” Kobis dan kolega mendekat kepada saya yang dari tadi duduk di motor. Mata mereka begitu awas walau wajah Kobis masih saja mlotrok. “Judul film itu Pengkhianatan KPI.” Ya, sebuah pengkhianatan yang belakangan isunya menguap begitu saja.