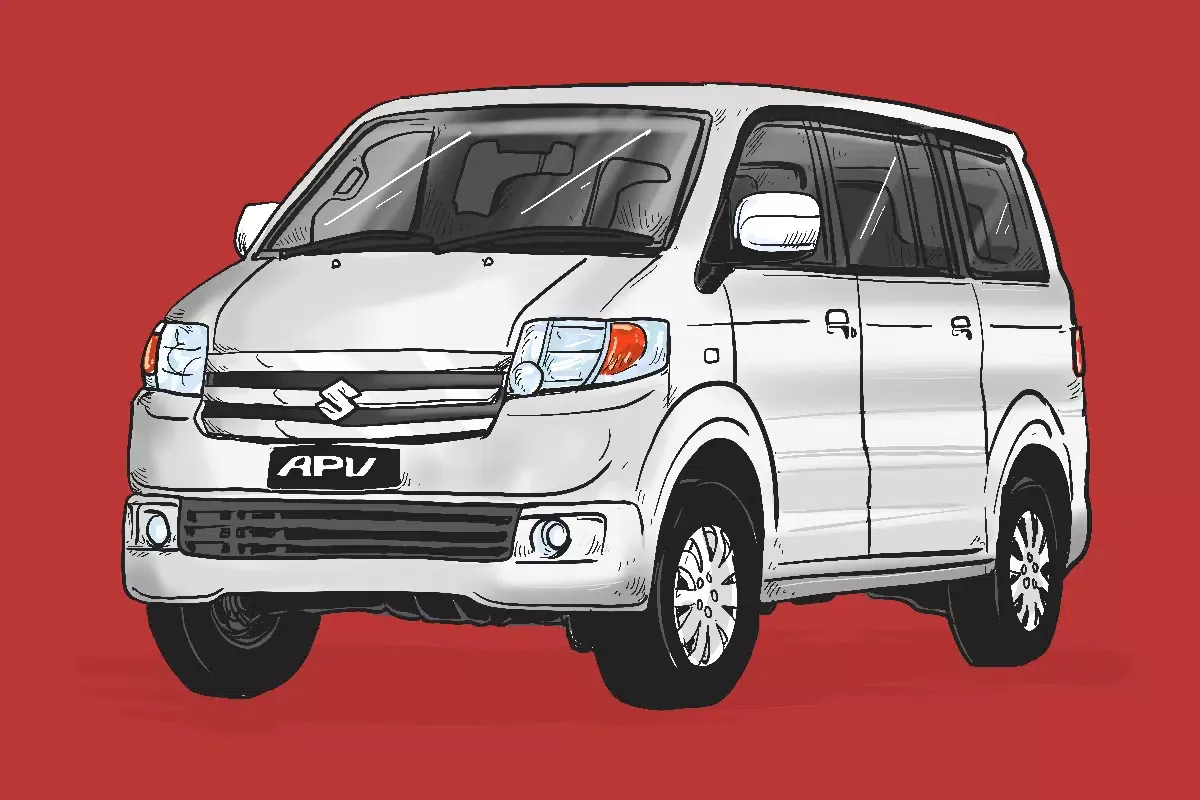Penertiban juru parkir liar kembali menjadi perhatian publik dalam beberapa minggu terakhir. Pemerintah daerah di banyak kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Makassar, dan Surabaya melakukan tindakan terhadap jukir, yang dianggap ilegal atau tidak memiliki izin resmi parkir. Wali kota dan dinas perhubungan berkomitmen untuk membersihkan kota dari pungutan liar (pungli) berkedor parkir yang dinilai meresahkan oleh beberapa masyarakat.
Namun, apakah benar masalah berasal dari jukir liar? Atau korban dari tata kelola kebijakan publik yang tidak adil, birokrasi yang tidak transparan, dan kurangnya kepedulian pada rakyat kecil?
Kebijakan penertiban jukir liar merupakan solusi cepat terhadap keluhan publik. Ada beberapa jukir liar yang tidak menyetor retribusi, mengganggu masyarakat dan bahkan menetapkan tarif seenaknya. Namun coba kita masuk lebih dalam. Kenapa sebagian besar orang memilih untuk menjadi jukir liar? Apakah karena ketidakpatuhan atau kemalasan saja?
Tentu saja tidak.
Banyak dari mereka yang terpaksa bekerja karena tidak memiliki pilihan pekerjaan lain, tidak memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan atau terjebak dalam sistem informal yang berkembang tanpa pengawasan pemerintah. Ketika negara mengambil tindakan represif tanpa menyediakan solusi yang berkelanjutan, maka yang terjadi bukanlah penataan, tetapi peminggiran sosial.
Kebijakan top down dan minim partisipasi
Kita harus bicara dengan data. Menurut jurnal (Dwi Jayanti Lukman, 2012) yang meneliti kebijakan perparkiran Kota Makassar dan menemukan bahwa komunitas akar rumput nyaris tidak dilakukan. Kebijakan dibuat secara top down tanpa mempertimbangkan konteks sosial juru parkir. Fakta ini diperkuat oleh penemuan Grindle (1980) dalam Politics And Policy Implementation In The Third World, yang menyatakan bahwa konteks yang tidak memadai dan kurangnya koordinasi birokrasi menyebabkan implementasi kebijakan di negara berkembang sering gagal.
Pemerintah menganggap bahwa kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) disebabkan oleh jukir liar. Padahal, akar masalahnya terletak di dalam birokrasi. Studi Indonesia Budget Center (2023) menunjukan bahwa hanya tiga puluh hingga empat puluh persen dari potensi pendapatan retribusi parkir akan masuk ke kas daerah. Sisanya hilang karena manajemen yang tidak transparan, perizinan tidak jelas, dan koordinator lapangan yang tidak bersalah yang memungut uang secara ilegal, tetapi tidak dihukum.
Ironisnya, sejumlah besar juru parkir liar bekerja di lokasi yang dikelola oleh pihak ketiga. Uang disetorkan ke koordinator, yang sering berhubungan dengan pegawai atau aparat daerah. Ini adalah jenis maladministrasi di mana negara ikut bertanggung jawab atas masalah. Ombudsman RI (2022) menyatakan bahwa ada pelanggaran tata kelola parkir di Padang dan Surabaya. Termasuk pengelolaan yang tidak sesuai dengan Perda, keterlibatan oknum, dan ketidakjelasan tentang hasil retribusi.
Digitalisasi jukir juga (jelas) bukan solusi
Selain itu, solusi digitalisasi tidak selalu menyelesaikan masalah. Sistem parkir pintar dapat meningkatkan pendapatan dan efisiensi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Zhao et al. (2017) dan Yahya et al. (2022). Tetapi di Indonesia, e-parking biasanya diikuti dengan pungutan tunai oleh jukir atau hanya tersedia di kawasan elit. Artinya, aspek sosial dan struktural masalah ini tidak diatasi oleh teknologi.
Yang lebih memprihatinkan lagi adalah fakta bahwa sejumlah besar pemerintah daerah tidak memiliki arsip yang lengkap tentang jumlah jukir resmi dan lokasi parkir yang tersedia. Hal ini menyebabkan pembinaan tidak teratur. Jurnal (Rizky Maulana Permana. Adi Kurnia, 2024) di Tasikmalaya menemukan bahwa kekurangan data dasar menyebabkan respons kebijakan parkir rendah. Jika tidak ada basis data, pelibatan koperasi jukir hanyalah formalitas.
Rekomendasi kebijakan tentang jukir
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, tindakan koersif harus dihentikan oleh pemerintah dan digantikan dengan tindakan inklusif yang berbasis keadilan sosial. Sebelum melakukan penertiban, periksa dan berbicara dengan para jukir. Mereka harus dimasukkan ke dalam skema koperasi atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akuntabel dan terbuka. Koperasi jukir berhasil membuat sistem parkir berbasis partisipasi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati (2022) di Yogyakarta.
Kedua, birokrasi internal harus menjadi fokus reformasi manajemen parkir. Kontrak pengelolaan parkir, audit retribusi, dan pembentukan organisasi pengawas independen semuanya harus dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai pemerintah hanya menertibkan mereka yang bekerja di lapangan, sementara kebijakan dan struktur masih menyimpang.
Ketiga, kebijakan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan harus mencakup penataan jukir. BLK, Dinas Ketenagakerjaan, dan sektor swasta dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun jalur kerja baru, pelatihan wirausaha, atau integrasi ke sektor informal yang lebih efisien. Negara tidak dapat melarang warganya bekerja tanpa menyediakan pekerjaan alternatif yang cukup.
Penutup
Kebijakan parkir harus berdasarkan transparansi, partisipasi, dan keadilan sebagai bagian dari Good Governance. Penertiban hanyalah bentuk ketidakadilan yang dilembagakan jika sistem yang ada justru memperluas perbedaan sosial. Apalagi jika tindakan tegas hanya berlaku untuk populasi yang lebih kecil, sementara orang-orang penting yang mendapatkan keuntungan dari kekacauan ini tidak diperhatikan.
Tidak ada alasan untuk menilai kebijakan publik hanya berdasarkan retribusi atau jumlah jukir yang ditindak. Sebenarnya, ukurannya adalah seberapa adil, partisipatif, dan memanusiakan kebijakan itu. Jika tidak, negara telah gagal dalam administrasi dan moralnya sebagai pelayan publik.
Penulis: Cintia Karina Butar Butar
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Rusaknya Reputasi Jukir Resmi di Solo Gara-Gara Tukang Parkir Liar
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.