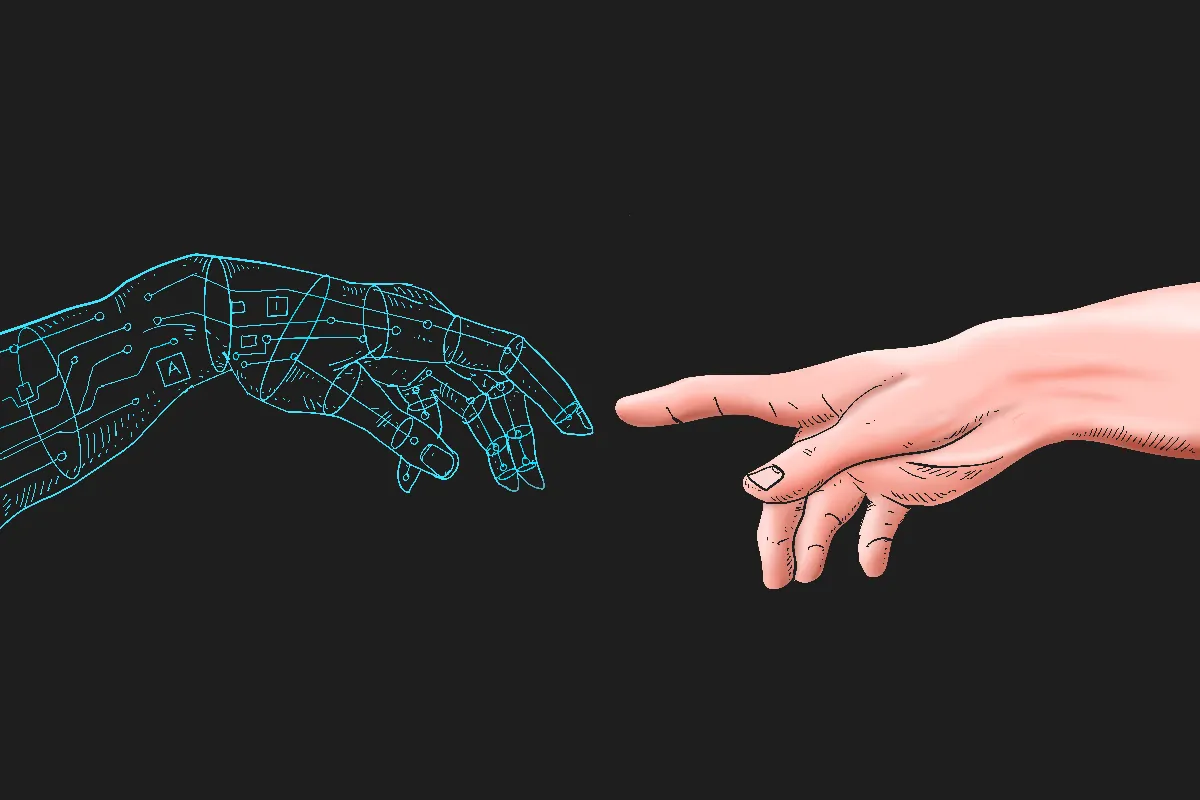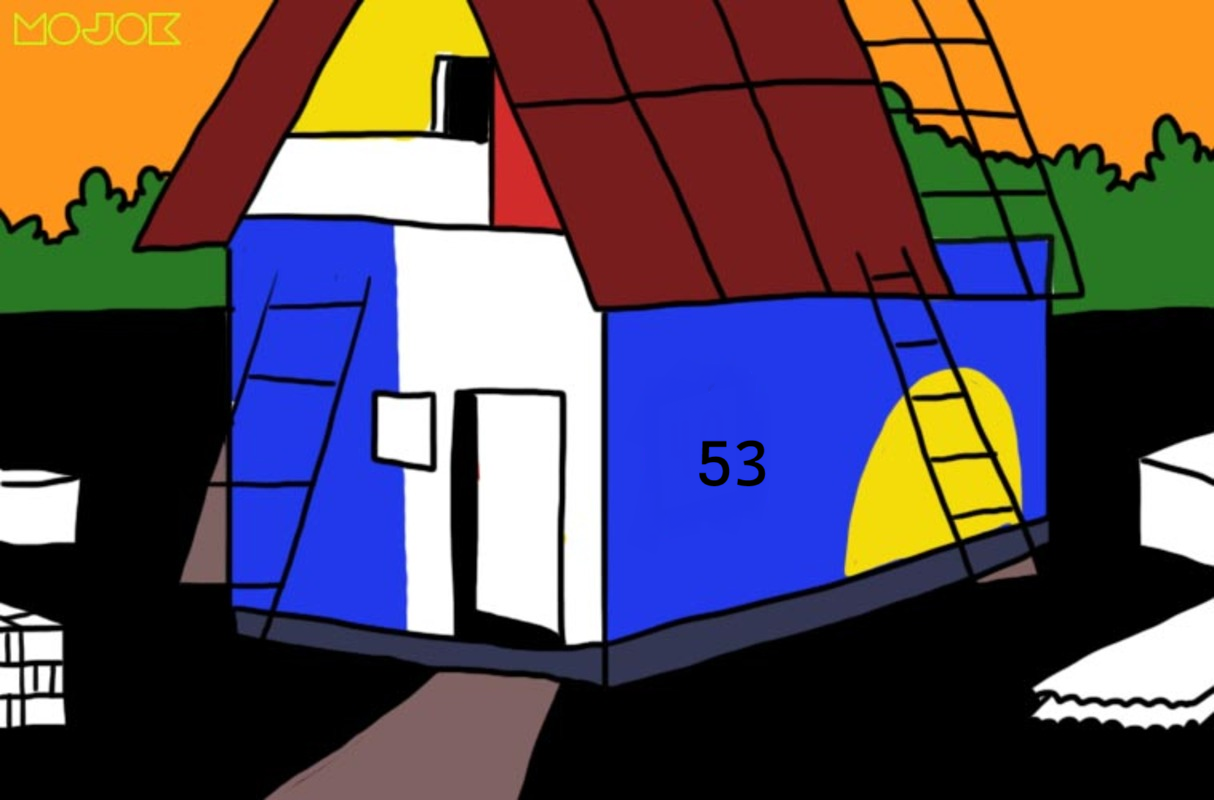Beberapa waktu lalu saya membahas soal asal dan asli daerah saya. Kali ini, saya akan lebih fokus menceritakan daerah asal saya, Sumatera Selatan. Tepatnya di sebuah desa bernama Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Desa yang tidak pernah muncul di permukaan selain cerita soal konflik tanah yang tidak berkesudahan.
Saya tidak akan membahas konflik-konfliknya di sini. Melainkan derita hidup di daerah pelosok yang apa-apa susah. Saya paham ketika menulis ini pasti beberapa pembaca akan ada yang berkomentar, “Banyak kok di daerah lain yang lebih parah,” atau “Nggak bersyukur! Di daerah A dan B lebih parah lagi!”, dll.
Mari kita sama-sama mengesampingkan ego membandingkan satu dengan lainnya. Ini hanyalah keluh kesah saya sebagai warga biasa. Beruntung kalau pemerintah daerah membaca tulisan ini dan memberikan aksi nyata.
Yah, setidaknya cuma ini yang bisa saya coba lakukan. Masalahnya, sejak lahir sampai sekarang, permasalahan di Sumatera Selatan masih berputar di lingkaran yang sama. Maksud saya, ayolah, masa iya mau begini terus? Hadeh.
Hidup di tengah perkebunan karet dan sawit Sumatera Selatan
Sebagian jamaah Mojok mungkin nggak kebayang ya hidup di tengah perkebunan karet dan sawit? Gambarannya begini. Buka pintu depan, pemandangannya jalan tanah liat merah. Balik buka pintu belakang, pemandangannya kebun karet. Buka jendela sebelah rumah, lihatnya kebun sawit.
Meski begitu, tetap ada yang menarik dari tinggal di tengah perkebunan karet dan sawit. Mau tahu? Tengah malam datang lebih cepat dari seharusnya. Coba bayangkan, jam 8 malam di sini rasanya kayak sudah jam 10 malam. Nggak ada lagi aktivitas di luar rumah. Serem.
Ketika saya menceritakan soal ini, yang paling sering ditanyakan orang selanjutnya adalah soal jarak. Misalnya, “Lha, terus jarak ke kota berapa lama?” atau “Kalau kamu ke sekolah berapa lama?” Jawaban saya biasanya bikin para penanya ini kaget.
Jadi begini. Namanya saja tinggal di pelosok Sumatera Selatan, tentu jauh dari mana-mana, ya. Naik mobil dari desa saya menuju kabupaten kota, Kayu Agung, saja butuh waktu sekitar 3 jam. Kalau ke Palembang? Biasanya butuh waktu sekitar 6 jam, kecuali lewat tol. Kalau lewat tol bisa dipangkas jadi 4 jam saja. Waktu segitu kalau di Jawa sih sudah bisa lintas provinsi.
Selama perjalanan itu, pemandangan yang bisa saya nikmati hanya seragam. Maksudnya, kalau nggak perkebunan karet ya perkebunan sawit. Jangan harap melihat pemandangan lain, ya.
Jalan tanah merah masih jadi teman abadi
Selama 22 tahun saya hidup, ada satu hal yang tidak pernah berubah dari desa saya di Sumatera Selatan sana. Jalan desa yang setia dengan tanah merah. Melihat desa sebelah yang bolak-balik menambal jalan aspalnya cuma bisa bikin saya dan kawan-kawan menelan ludah.
Saya dan kawan-kawan pernah menaruh harapan kepada perangkat desa. Setiap kali ada perbaikan jalan, biasanya kami bakal bersemangat. “Wah, jalannya dibenerin, nih!” atau ‘Otw aspal nggak sih ini?” Sampai akhirnya kami menyerah dan jadi trust issue.
Soalnya tiap kali ada janji perbaikan jalan desa, ujung-ujungnya cuma ditimbun pakai tanah merah lagi. Apalagi kalau setelah ditimbun, terus hujan turun. Bukannya jadi bener, jalan makin hancur. Kalau kalian mengenal istilah “nasi sudah jadi bubur”, kami warga Sukamukti Sumatera Selatan punya istilah “jalan sudah jadi bubur” ketika hujan turun.
Bayangkan, kalian harus berangkat ke sekolah tapi jalanan yang harus dilewati rusak parah. Jalannya berlubang, lengket, dan banyak genangan yang bikin jalan semakin parah. Kalau melintas dengan motor siap-siap nyangkut, sih.
Belum lagi kalau hujan berhari-hari dan warga mau ke kota. Duh, sudah pasti bingung mau lewat mana. Soalnya ibarat kata “maju kena, mundur juga kena.” Mau lewat mana-mana juga nggak bisa menghindari jalan bubur itu. Nasib.
Mati listrik itu hal sepele, tapi bikin repot
Selain jalan tanah merah yang nggak pernah berubah. Ada satu hal lagi yang sudah jadi sahabat dekat warga Sukamukti, Sumatera Selatan. Apa lagi kalau bukan mati listrik. Terlebih lagi waktu puasa, sebuah keniscayaan kalau nggak mati listrik.
Sebetulnya warga sini sudah terbiasa dengan yang namanya mati listrik. Coba tanya deh, pasti hampir di setiap rumah warga ada mesin generator set. Kami sudah siap siaga mengantisipasi kegelapan malam kalau PLN lagi jahil.
Malahan di rumah saya dulu ada mesin diesel yang sanggup menerangi beberapa rumah di sekitar. Ya mau gimana lagi. Saat itu listrik belum masuk desa. Listrik baru masuk ke desa kami sekitar tahun 2008.
Masalah penerangan sudah aman. Tetapi yang bikin repot kalau mati listrik itu sinyal beserta jaringan internetnya ikut mati. Kalau kalian dulu sekolah angkatan Covid lalu ada teman yang tiba-tiba nggak bisa ikut kelas dengan alasan mati listrik, percayalah itu memang benar terjadi. Mau sampai menangis pun sinyal dan jaringan internet nggak akan muncul kalau sudah mati listrik di desa saya.
Merantau jadi solusi ketika tidak ada perubahan yang terjadi di Sumatera Selatan
Nah, dari semua masalah yang terjadi di pelosok Sumatera Selatan tersebut, cukuplah untuk membuat warga memilih merantau ke kota. Termasuk saya. Bahkan banyak pemuda desa yang awalnya merantau untuk melanjutkan studi tapi nggak mau balik lagi. Ya mungkin karena sudah telanjur nyaman menikmati fasilitas yang serba ada di kota.
Saya nggak menyalahkan hal ini, kok, saya paham betul gimana kenyamanan dunia kota. Saya pun terpaksa mencari kenyamanan dan pelayanan yang lebih baik di kota atau daerah lain. Bukan karena saya nggak cinta rumah, tapi karena nggak ada perubahan di sana. Saya jadi berpikir perlu keluar dari sana untuk melihat apa saja yang harusnya desa saya bisa lakukan. Apalagi saya merantau ke Jogja, tempat yang memang nyaman untuk segalanya.
Kalau kalian bertanya, “Terus, kamu mau menetap di Jogja dan nggak kembali ke desa?”. Saya pikir ini pertanyaan aneh, ya. Kalaupun nantinya saya akan menetap di Jogja atau di kota mana pun, bukan berarti saya nggak akan kembali ke desa.
Saya juga punya banyak mimpi untuk desa saya. Menjadi desa yang lebih ramah pendidikan, aman, dan nyaman. Satu lagi, setidaknya saya ingin melihat desa di pelosok Sumatera Selatan ini punya jalan aspal. Hehehe.
Penulis: Karisma Nur Fitria
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Pengalaman Saya Tinggal di Pedalaman Sumatera Selatan Sebagai Masyarakat Transmigran.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.