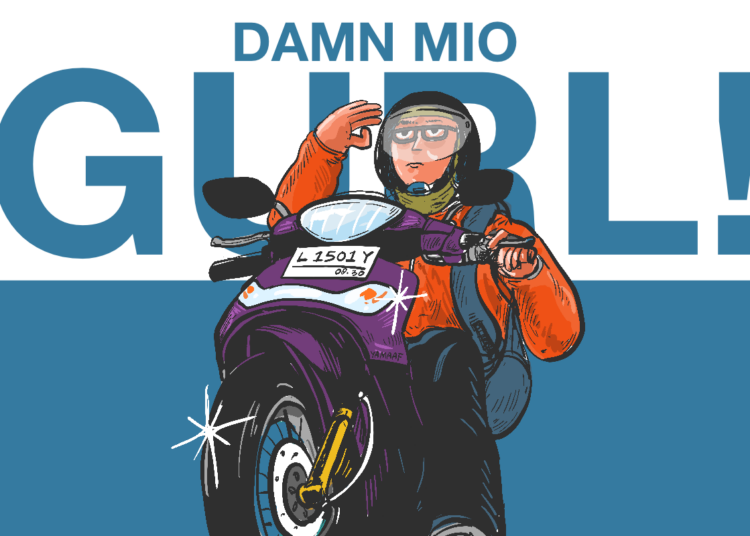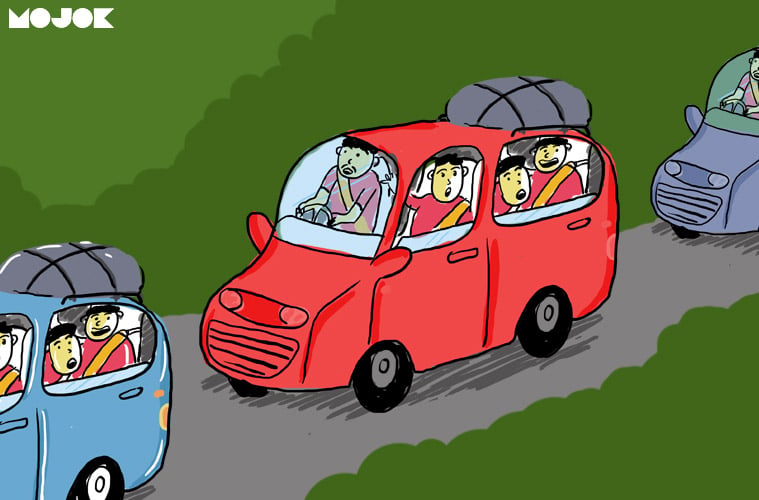Seorang kawan pernah mendatangi saya untuk konsultasi perihal kedai kopinya yang baru berumur satu bulan kurang. Ia berencana memperindah kedainya dengan fasilitas panggung dan live musik. Ia melakukan itu dengan prinsip “ben padha kancane” atau biar seperti orang lain. Yang ia maksud adalah, ia ingin kedainya punya fasilitas yang sama dengan kedai-kedai lain yang lebih dahulu ada. Ia malu, kedainya dianggap cupu oleh pemilik kedai lain karena tak punya live music.
Masalahnya, ia tak punya modal yang cukup, dan meminta saya untuk manggung gratis selama satu atau dua bulan di kedainya. Meski saya orang baik, tetap keluar semprotan khas mas-mas Magelang, “Matamu, Leh!“ Saya menolak dengan keras.
Peristiwa lain yang disebabkan prinsip “ben padha kancane” yang lain adalah perihal acara pernikahan. Tak perlu mencari contoh yang jauh-jauh, dari kerabat sendiri pun ada. Mereka mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya. Uang ratusan juta habis untuk memenuhi prinsip “ben padha kancane” itu. Selesai acara pernikahan itu, kerabat saya ini punya utang berlimpah ruah nan aduhai. Semua dijual, dan mereka terlihat kalang kabut. Baik tetangga maupun saudara banyak yang menghujat dan memberi stigma macam-macam. Mulai dari keluarga menang gengsi doang, hingga dianggap tak bisa menahan dan mengukur kemampuan diri.
Di sebuah kampung yang pernah saya tinggali, ada budaya adu otomotif. Kalau tetangga beli motor baru, tetangga sebelahnya juga ikut-ikutan beli. Begitu terus, sampai semua punya motor yang sama. Hal ini kerap memunculkan masalah, terutama saat para penagih kreditan mendatangi rumah warga.
Nah, orang yang nunggak ini akan jadi bulan-bulanan. Apalagi kalau motornya ditarik, bakalan jadi bahan hibah seantero kampung. Banyak juga yang tetap bisa bayar lunas, tapi harus hemat banget, sampai-sampai anaknya nunggak bayar buku. Ada juga yang lancar bayar kredit, tapi sawahnya hilang. Pokoknya yang penting punya motor keluaran terbaru yang mahal itu.
Prinsip “hidup ben padha kancane” memang berbahaya saat dipahami hanya sebatas punya harta benda yang mirip seperti punya orang lain. Seolah hidup orang lain adalah standar hidup yang benar dan tepat. Padahal, tak harus seperti itu juga. Walau tak saya mungkiri, kadang saya pun begitu. Melihat teman lulus pascasarjana, membuat saya pengin sekolah lagi. Melihat teman beli gitar baru, bikin saya pengin juga. Tapi, sekedar pengin tak harus membuat kita jadi insecure dan menganggap itu semua sebagai sesuatu yang harus dicapai. Apalagi hanya demi gengsi karena tak mau kalah dengan orang lain.
Banyak contoh orang yang hidupnya tak tenang karena menganut prinsip itu dengan ugal-ugalan. Sehingga pada akhirnya mereka hidup dengan rasa yang tak aman dan nyaman. Hidup dipenuhi rasa tersaingi, yang mengakibatkan perasaan tak mau kalah pada orang lain. Sehingga masa hidupnya hanya digunakan untuk memenuhi ego dan gengsi yang membabi buta. Yang bahaya adalah, saat penganut prinsip hidup ini menganggap cara hidup mereka adalah yang terbaik.
Saat ada yang hidupnya santai, apa adanya, tak harus punya rumah begini, mobil begitu, punya kolam koi, pokoknya yang penting senang dan nyaman, malah dianggap malas. Ya, seperti motivator-motivator aneh itu, yang masih senang membuat standar hidup ala mereka, yang kadang nggak mashoook babar blas. Sudah saatnya prinsip hidup “ben padha kancane” yang kita anut ditinjau ulang. Kalau hanya terinspirasi untuk berbuat lebih baik tentu tak masalah, yang pasti ada batasan. Kalau ternyata hanya karena ego, tentu bisa jadi masalah.
Nah, masalahnya adalah, prinsip hidup ini seperti buah simalakama. Seperti kerabat yang memaksakan acara pernikahan, kalau mereka bikin pesta kecil atau sederhana, bukan tidak mungkin bacot tetangga dan saudara akan baik-baik saja. Mungkin mereka tetap akan diomongin sebagai keluarga pelit dan memperburuk citra keluarga besar. Pokoknya digibahin hingga bertahun-tahun ke depan.
Mungkin sebelum kita menilai mereka yang hidup dengan prinsip ini, kita harus sadar. Jangan-jangan kita juga yang menyebabkan hal ini terjadi. Kita ini akar masalahnya, kita yang selalu bacot pada hidup orang lain. Memang, hidup dengan manusia lain itu bikin dilema dan pusing.
Kayaknya lebih enak jadi Tarzan, atau mungkin sekalian jadi pemimpin yang bisa membungkam mulut siapa pun yang nggak disukai.
Penulis: Bayu Kharisma Putra
Editor: Rizky Prasetya